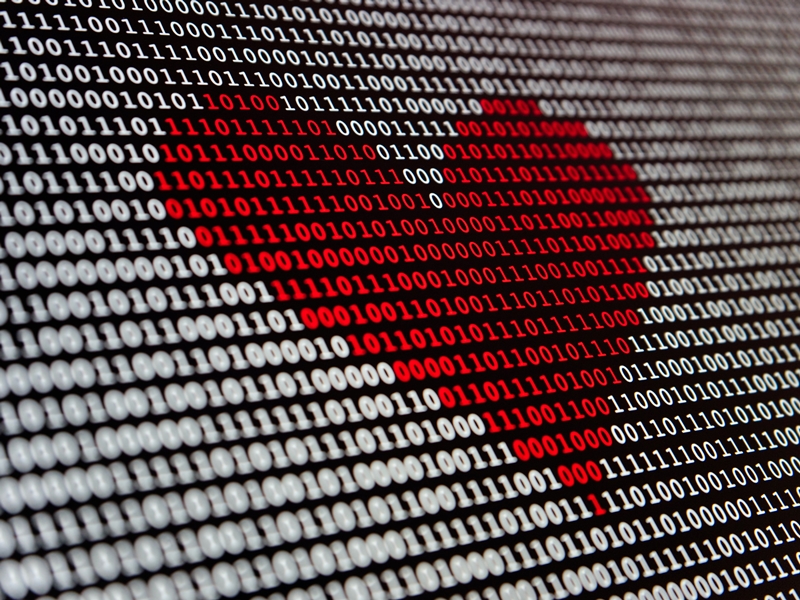Perserikatan Bangsa-Bangsa menerbitkan Annual Repport of Happines untuk meranking tingkat kebahagiaan di 156 negara. Tahun 2018, Finlandia berhasil menduduki peringkat pertama yang dinobatkan sebagai negara dengan tingkat kebahagiaan tertinggi.
Indonesia beruntung dan berhasil berada di urutan ke 96 tepat di bawah Vietnam diperingkat 95 dalam daftar tersebut. Sementara Singapura menduduki petingkat ke 34, dan Malaysia ada di petingkat ke 35. Nggak perlu ngiri, yang namanya rumput tetangga, katanya memang terlihat lebih menggoda—tapi itu kata kambing ya, jadi jangan telalu dipikirkan.
Ternyata tidak hanya PBB yang mengukur kebahagiaan, di level nasional BPS (Badan Pusat Statistik) juga mengukur tingkat kebahagiaan setiap provinsi yang ada di Indonesia. Melalui SPTK (Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan) tahun 2017, tingkat kebahagian tiap provinsi berhasil diranking.
Berbeda dengan PBB yang selalu update, BPS tampaknya tidak mengadakan survei setiap tahun. Tercatat, survei serupa pernah dilakukan pada tahun 2014, namun tidak menggunakan parameter yang sama dengan survei di tahun 2017.
Dari survei BPS, Provinsi Maluku Utara menduduki tingkat kebahagiaan tertinggi. Terus provinsi yang ada di Pulau Jawa dapat petingkat ke berapa? Prestasi terbaik adalah DI Yogyakarta yang menduduki peringkat ke 8 dari daftar yang ada. Sementara itu, Jakarta menduduki peringkat ke 19—lumayan.
Ukuran dalam mengukur kebahagiaan antara lain kepuasan hidup, perasaan, dan makna hidup. Emangnya kalau yang begituan bisa diukur? Meskipun terkesan baper—masa kebahagiaan kok diukur—tentu saja ini penting, apalagi kebahagiaan ini diukur dengan cara yang (kayaknya) ilmiah.
Paling menarik—setidaknya bagi saya—temuan bahwa orang lajang menjadi golongan paling bahagia. Di sinilah mungkin para jomblo bisa berbangga diri. Biar jomblo yang penting happy—begitulah kira-kira. Dan kalau ada yang nanya kapan nikah, Anda bisa menyodorkan data BPS untuk mereka yang terkadang sedikit rewel dan usil.
Survei yang dilakukan BPS tentu—harusnya—bisa dipertanggungjawabkan dibandingkan dengan survei “pesanan”. Survei pesanan udah survei sendiri, terus menang sendiri, hore-hore sendiri, tidak melihat kenyataan.
Terus begitu hasilnya berbeda dengan yang lain, ntar yang lain dianggap nggak valid dan curang. Pingin tak cakot ndase sebetulnya kalau ketemu dengan model survei yang begituan, dibayar buat survei malah ngarang cerita fiksi, biar genrenya fiksi ilmiah tapi ya tetap fiksi.
Orang yang (ngakunya) pinter akan punya daftar panjang untuk meragukan survei BPS. Apalagi orang yang ngeyelan terus ditambah suka baperan, yang macam ini paling susah dikasih tahu, apalagi dikasih pengertian. Eh, tapi begitu dikasih hati terus minta jantung, repot banget hidupmu, Ndes.
Parameter survei BPS dalam mengukur kebahagiaan bisa digunakan untuk menilai kebahagiaan diri sendiri. Bukankah kalau memang valid, ukuran bisa dipakai di mana saja selama keadaan ceteris paribus? Begitulah kira-kira kata guru Sosiologi saya waktu SMA belasan tahun silam.
Tapi tentu saja untuk mengukur menggunakan standar yang digunakan BPS anda harus bisa menjawab dengan jujur. Kalau kemampuan berbohong anda sangat tinggi, terutama dalam menipu diri, tentu tidak ada parameter yang mampu mengukur diri Anda.
Kalau kamu “merasa” kehidupan personal dan sosial baik-baik saja, kamu harus tahu, kalau “rasa” juga bisa diukur. Setelah diukur maka akan ditemukan apa yang sesungguhnya terjadi, mungkin juga hasilnya sama atau mungkin juga berbeda. Yah gimana lagi, perasaan memang biasanya sering menipu.
Kehidupan personal bisa dinilai dari pendidikan, pekerjaan, pendapatan rumah tangga, kesahatan, serta kondisi rumah dan aset. Sementara itu, kehidupan sosial dilihat dari hubungan sosial, kendali lingkungan, keamanan, keharmonisan keluarga, ketersediaan waktu luang.
Ukuran yang tidak kalah seru adalah “perasaan” atau dalam hal ini adalah tingkat afeksi. Untuk parameter jenis ini, akan diukur : perasaan senang (riang/gembira), perasaan tidak khawatir (cemas), dan perasaan tidak tertekan. Kalau yang kayak begini mungkin hanya Anda sendiri yang tahu, namanya juga perasaan.
Dan parameter yang bisa dikatakan luar bisa adalah “makna hidup”. Untuk mengukur makna hidup, kita mesti bisa menilai penerimaan diri, kemandirian, penguasaan lingkungan, pengembangan diri, hubungan positif dengan orang lain, dan tujuan hidup. Disini saya merasa yang membuat parameter sungguh luar biasa.
Tidak sedikit orang yang akan meremehkan parameter-parameter yang ditetapkan untuk mengukur kebahagiaan ini. Orang yang berpendidikan tinggi, otomatis akan sukses dan akhinya hidup bahagia, dan semua ukuran yang dibuat tentu akan masuk dalam level memuaskan. Tapi pada kenyataanya tidak semudah itu, Sarno.
Saya pernah menemukan orang berpendidikan tinggi (S2) yang punya pekerjaan di Jakarta. Namun setelah menemukan tujuan hidup, dia resign pulang kampung untuk jualan kue. Mana yang lebih bahagia, melanjutkan kerja di Jakarta atau jualan kue di kampung? Mungkin akan ada yang mencibir, mau jualan kue aja meski S2, situ waras? Nggak waras itu yang suka repot ngurusin urusan orang, emang urusan situ udah kelar?
Jadi kesimpulannya, untuk urusan survei, semakin panjang, lebar, dan luas parameter yang digunakan tentu akan semakin menarik hasil yang didapat. Termasuk parameter jomblo dalam survei yang diadakan oleh BPS.
Jomblo yang dimaksud dalam BPS adalah tidak menikah alias single KTP. Kalau kamu jomblonya sudah kronis, bahkan nggak pernah punya pacar padahal usia udah “terlalu matang”, mungkin kamu butuh survei lain sebagai senjata.
Kamu mungkin butuh mengumpulkan suara untuk mengajukan petisi pada BPS agar membuat survei tingkat kebahagiaan sesudah dan sebelum menikah. Tapi bila ternyata nanti hasilnya lain dari yang diharapkan, yah mungkin nasib jomblo memang terlalu berat, jadi yah terima saja apa adanya.