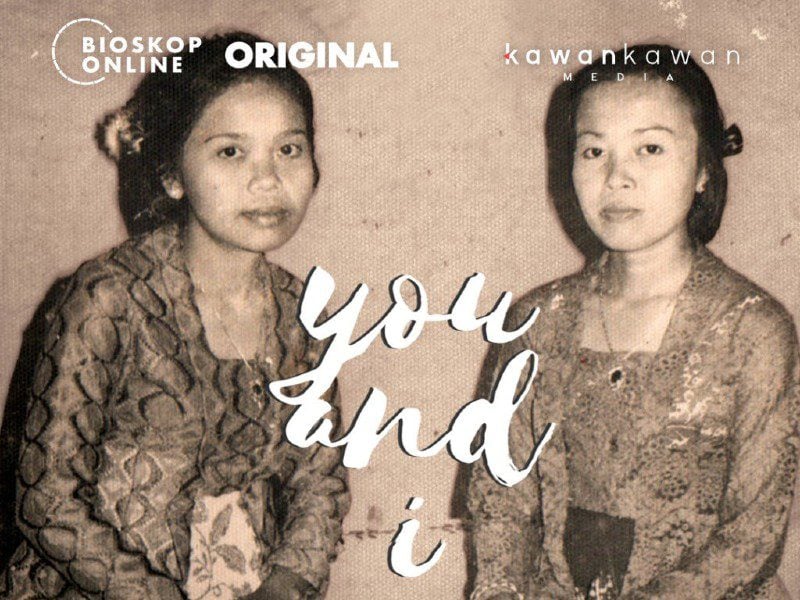“Stay hungry. Stay foolish.”
Rasanya hampir semua orang pernah dengar quote legendaris dari Steve Jobs ini. Kalimat tersebut pertama kali diucapkan Steve di acara Stanford Commenments tahun 2005. Sebagian orang menafsirkannya sebagai ungkapan rasa ketidakpuasan terhadap hasil yang telah kita capai, sehingga kita terpacu untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi dengan cara improvisasi. Ungkapan ini sangat terkenal di kalangan usaha atau bisnis, apalagi kalau bukan karena ulah motivator yang mempopulerkannya.
Improvisasi atau mati, sesederhana itu. Filosofi sederhana tersebut yang meluluhlantakkan Nokia. Pabrikan asal Finlandia itu betul-betul dibuat bertekuk lutut oleh ponsel pintar lain dengan OS Androidnya.
Improvisasi dan kreativitas jelas sangat dibutuhkan dalam industri hiburan, salah satunya di dunia perfilman. Pada 2017 silam, saat duduk di bangku bioskop menanti film King Arthur : Legend of The Sword dimulai, saya menebak film ini akan se-epic saga kolosal Lord of the Ring. Plot cerita yang terbayang juga tidak macam-macam; Arthur muncul sebagai sosok yang sanggup mencabut pedang Excalibur, kemudian maju sebagai Raja lalu memimpin para ksatria dalam memerangi musuh-musuhnya. Tapi saya segera mengenyahkan jauh-jauh pikiran tersebut ketika layar mencantumkan nama Guy Ritchie, mantan suami Madonna sebagai sutradara.
Batin saya, “wow sepertinya akan ada sesuatu yang menarik disini” dan benar saja. Dalam film Arthur ini, Anda akan menemukan perpaduan dua film Ritchie sebelumnya : Lock Stock & Two Smoking Barrels (1998) dan Snatch (2000). Persis seperti paduan rujak dan soto sehingga menjadikan hidangan tersebut sebagai menu andalan kuliner Banyuwangi. Gaya tutur cerita flashback yang unik ala Sherlock Holmes, lengkap dengan guyonan ala-ala british-mate juga diboyong mantan suami Madonna ke dalam film ini.
Andai saja Vinnie Jones ikut terlibat, purna sudah racikan dan ramuan mujarab Ritchie.
Citra seorang Raja yang kaku, sopan santun dengan perilaku kebangsawanan yang rapi, menjaga jarak dengan rakyat akan sulit ditemukan dalam Arthur versi Ritchie. Sebaliknya, figur raja yang berani, urakan, berjiwa pemberontak sekaligus kepala batu namun mau merangkul siapa saja akan mudah anda temukan dalam sosok Charlie Hunnam, sang pemeran Arthur.
Tengok pada adegan terakhir ketika Arthur dengan elegan mengingatkan salah seorang jenderal Viking kalau ia adalah orang yang sama yang pernah bertarung 1v1 dengan dirinya. Teringat dengan bogem mentah Arthur yang pernah mendarat di mukanya, si Viking memilih untuk berdamai. Surprisingly, Arthur malah tak ragu-ragu mengajak si Viking untuk makan bersama dengannya di meja bundar.
“Why have enemies, when you can have friends?” ujar Arthur.
Nampaknya Arthur sangat piawai menerapkan kode etik dunia laki-laki sejati : “Lo asik, gw santai. Lo jual gw beli.”
Kita perlu memaafkan Hunnam yang telah dengan apik menampilkan sosok Arthur yang lain dari biasanya – anti mainstrim. Hal ini tak lepas dari peran sang sutradara. Guy Ritchie juga berhasil mentransformasi sosok Tony Stark yang terlanjur melekat erat dalam diri Robert Downey Jr menjadi detektif Inggris yang smart, Sherlock Holmes. Peduli setan kalau ternyata film tersebut dibilang merugi ratusan juta dollar.
Faktanya, King Arthur-nya Ritchie berhasil mencapai rating 7,2 versi IMDB, lebih tinggi dibandingkan Batman vs Superman yang hanya diganjar rating 6,7. Lho kok bisa? Ya iya lah! Selain karena Ben Affleck memiliki postur badan yang terlalu sterek sebagai suksesor Christian Bale, film Dawn of Justice cenderung membosankan. Karena kita hanya akan disuguhi konflik konyol antara Batman dan Superman yang bertarung mati-matian hanya karena ibu mereka memiliki nama yang sama, Martha. Eerrr …
Menyajikan jalan cerita yang sama sekali berbeda dengan persepsi umum setiap orang adalah salah satu bentuk improvisasi, buah dari kreativitas tinggi. Hal ini juga dengan gampang kita temukan dalam film Spider-Man : Homecoming (2017).
Lupakan sosok Peter Parker ala Tobey Maguire yang menye-menye nan melankolis karena seisi kepalanya hanya berisi soal Mary Jane melulu. Tom Holland berhasil mengembalikan citra Spiderman sebagai superhero idola anak-anak. Ia tampil sebagai Parker yang humanis, Parker yang kerap berbuat salah (maklum saja usianya masih SMA), Parker yang sok tahu dan kelewat pede bahwa dirinya punya peranan penting untuk Avengers.
Lupakan juga salah satu jargon yang selalu terngiang-ngiang dalam film Spiderman terdahulu, “with the great power, comes the great responsibility”.
Kejutan tak berhenti sampai disitu. Jangan berharap kita menjumpai sosok Bibi May yang lanjut usia dan hanya bercakap soal nasihat kehidupan dan petuah bijak pada keponakannya. Oh tidak. Yang akan kita temukan adalah Marisa Tomei sebagai bibi May yang masih muda, cantik, menarik, suka mengenakan tank-top di rumah, pokoknya MILF seksi banget. Tak heran kalau waiter di restoran masakan Thailand sempat flirting genit kepadanya.
Tom Holland dan Marisa Tomei adalah dua orang yang perlu kita maafkan dengan ikhlas karena sudah merusak jalan cerita Spiderman yang mainstream. Tom Holland juga perlu kita maafkan karena berhasil menggeser Andrew Garfield yang belakangan tampak lebih nyaman berakting sebagai manusia religius. Tengok saja perannya sebagai serdadu Desmond Doss yang ngotot tidak mau memegang senapan dalam Hacksaw Ridge. Atau ketika ia bermain sebagai pendeta yang memegang teguh keimanannya sampai mati dalam Silence.
Ingat, DC pun tak kalah kreatifnya dalam hal improvisasi merusak patron jalan cerita. Alih-alih mempertahankan konsep seragam biru merah lengkap dengan celana-dalam-tapi-di luar hasil jahitan Martha Kent, Henry Cavill tampil gagah dengan kostum ala millenial warisan dari Jor-El ayah kandungnya.
Jadi, siap berimprovisasi?