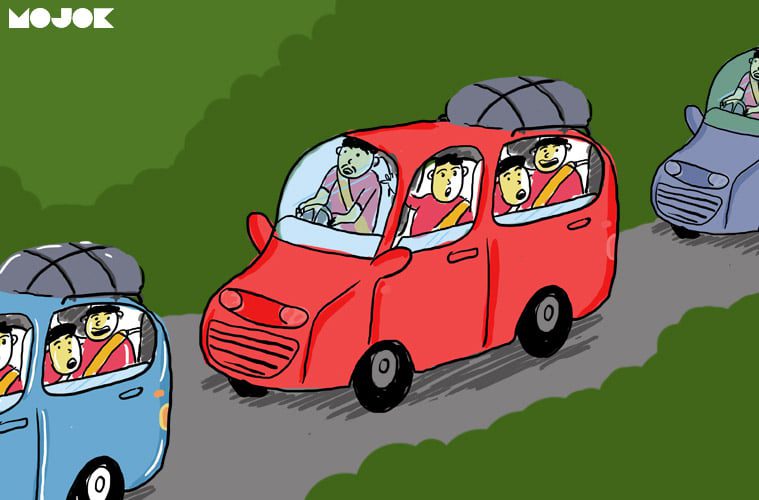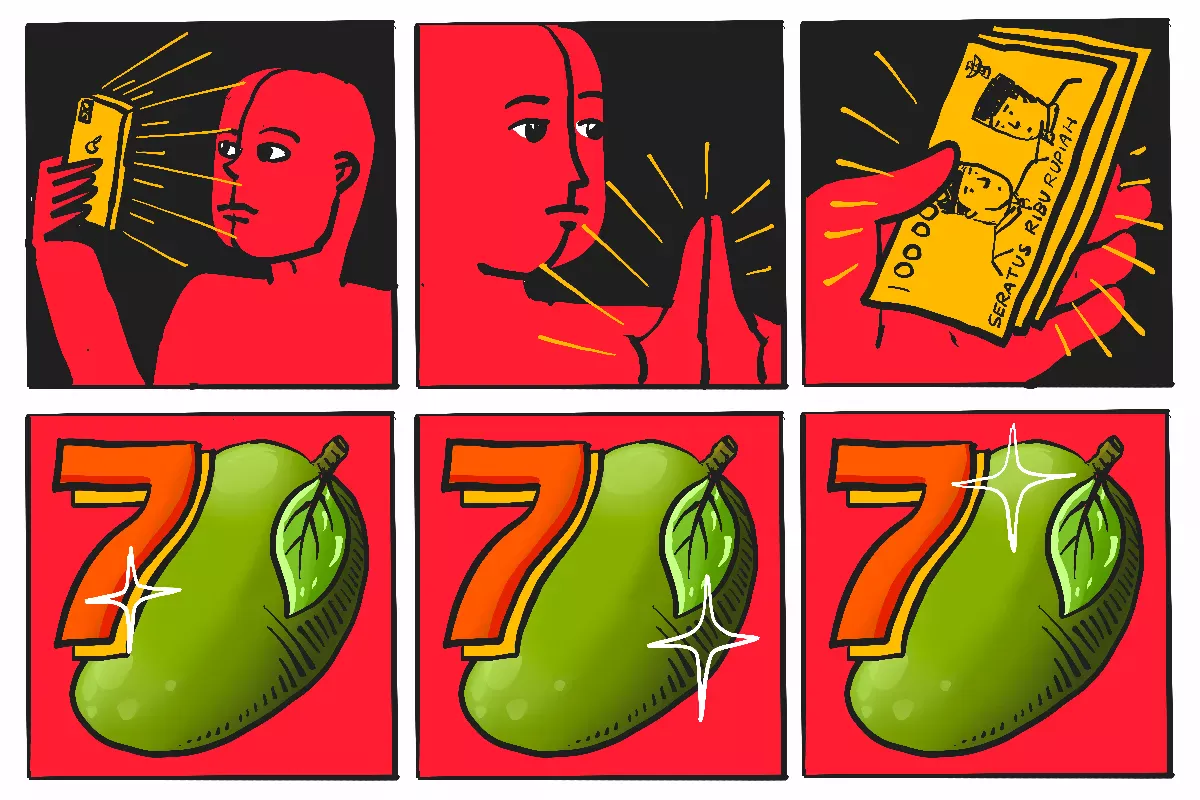Sebentar lagi musim tahun ajaran baru. Mahasiswa baru mulai berdatangan. Spanduk-spanduk ucapan, seperti “Selamat Datang Generasi Cerdas”, bakal dipasang besar-besar. Tapi, di balik wajah ramah brosur kampus dan foto-foto senyum panitia ospek di media sosial, ada satu tradisi yang masih saja menghantui: bentak-bentakan, perpeloncoan, dan kekerasan verbal yang dibungkus dengan dalih “pembentukan karakter”.
Saya tahu, akan ada senior yang bilang, “Kami dulu juga digituin, dan itu bikin kami jadi tangguh.” Tapi, kalau yang kamu wariskan cuma trauma yang dilestarikan demi melampiaskan kuasa, itu bukan tradisi—itu siklus penindasan. Dan siklus ini, alih-alih bikin mahasiswa baru tangguh, justru bikin mereka belajar satu hal: untuk takut duluan sebelum bisa berpikir.
Lucunya, banyak dari mereka yang dulu dibentak dan dibenturkan harga dirinya, sekarang justru jadi pelaku utama. Kalau ditanya, jawabannya macam-macam: mulai dari “biar kompak”, “biar disiplin”, sampai “biar ngerasain perjuangan jadi mahasiswa.” Tapi, kalau disiplin harus disertai teriakan dan ancaman, itu bukan pendidikan. Itu copy-paste metode, euy.
Ospek kok sampah
Ospek—yang katanya kegiatan orientasi mahasiswa baru—lama-lama lebih mirip ajang unjuk kekuasaan. Alih-alih mengenalkan lingkungan kampus dan membangun suasana inklusif, yang terjadi malah parade suara keras, perintah absurd, dan adik tingkat yang disuruh nurut tanpa nalar. Panitia ospek mendadak jadi manusia setengah dewa: bisa nyuruh, bisa bentak, bisa ngatur-atur hidup orang, padahal semester kemarin masih ngulang mata kuliah Etika Profesi.
Dalih yang dipakai juga selalu itu-itu saja: biar mental mahasiswa baru jadi kuat. Tapi kuat yang seperti apa? Kalau kuat itu harus dimulai dengan direndahkan, dihina, bahkan dipermalukan di depan umum, maka yang sedang dibentuk bukan karakter, tapi trauma. Beda tipis antara “pembentukan karakter” dengan pembenaran kekerasan.
Yang lebih ironis, praktik ini punya jejak sejarah yang jelas: warisan kolonial. Dulu, Belanda pakai ontgroening buat nunjukin siapa yang punya kuasa. Setelah merdeka, alih-alih ditinggalkan, justru dilestarikan dan diganti nama jadi ospek. Isinya? Masih sama: hierarki yang timpang, senioritas buta, dan kekuasaan kecil-kecilan yang dijalankan oleh mahasiswa yang merasa dirinya lebih penting dari yang sebenarnya.
Dan bayangkan, sudah otw 80 tahun kita merdeka, tapi cara kita menyambut mahasiswa baru masih mirip zaman penjajahan. Bukannya diajak berdiskusi atau dikenalkan dengan kebebasan berpikir, mereka malah dihadapkan dengan muka sangar, suara lantang, dan tugas-tugas absurd yang kalau ditanya manfaatnya—panitianya pun bingung menjawab. Ada memang semacam diskusi, perkenalan, dan sebagainya. Tapi, adanya bentak-bentakan justru menjadi sampah penghalang yang menghilangkan substansi.
Ospek semacam ini bukan orientasi. Ini sampah. Dan sampah, seperti biasa, tempatnya ya di tong sampah. Bukan di kalender akademik.
Kekerasan dalam ospek itu bukan tradisi, itu ketololan yang diulang-ulang
Kekerasan saat ospek tak hanya soal teriakan atau bentak-bentakan (meskipun cuma gimik) dan hukuman fisik. Ada juga kekerasan verbal, pelecehan psikologis, hingga body shaming yang dibungkus sebagai “materi pembentukan karakter.” Padahal jelas-jelas, studi dan laporan sudah banyak yang membuktikan dampaknya: stres, kecemasan, bahkan trauma yang membekas hingga bertahun-tahun. Tapi, ya itu tadi, yang penting katanya “tradisi.”
Tradisi apa yang pantas dibanggakan kalau hasilnya adalah luka mental dan rasa takut terhadap institusi yang seharusnya melindungi? Kampus bukan barak militer. Pendidikan bukan ajang seleksi siapa yang paling kuat menahan makian. Dan solidaritas bukan dibangun dari siapa yang paling patuh saat dibentak, tapi dari siapa yang bisa saling menghormati tanpa harus merasa lebih tinggi dari yang lain.
Kalau para senior masih merasa perlu bentak-bentakan untuk menegaskan otoritasnya, saya sarankan satu hal sederhana: mending terapi dulu. Karena yang senang berteriak itu bukan tanda wibawa, tapi bisa jadi tanda trauma yang belum sembuh—atau justru egonya yang butuh perhatian.
Waktunya Kampus berbenah
BEM, DPM, rektorat, dan kementerian, semuanya punya andil dan tanggung jawab. Jangan cuma sibuk bikin slogan anti-kekerasan kalau praktiknya masih dibiarkan dengan dalih “biar seru” atau “biar terasa suasana kampus.” Birokrat kampus tak bisa terus menutup mata. Dan organisasi mahasiswa tidak bisa terus bangga dengan titel “panitia” kalau isinya cuma pamer suara lantang dan muka galak.
Reformasi ospek itu wajib. Ospek harus jadi tempat belajar mengenal kampus, mengenal diri, mengenal teman-teman lintas jurusan, mengenal nilai, mengenal semangat kolaborasi. Kalau yang dikenal justru rasa takut dan malu, itu bukan ospek. itu abuse yang dikemas dengan name tag panitia.
Jika masih ada yang keukeuh bilang, “Namanya juga ospek, wajar lah bentak-bentak dikit, ini juga cuma gimik.” mungkin yang perlu bukan pelatihan kepemimpinan, tapi konsultasi ke psikiater. Kalau lidah gatal nggak bentak orang, mungkin itu tanda batin haus kuasa yang belum sempat terlayani.
Serius deh, kalau cita-cita muliamu sebagai mahasiswa cuma jadi manusia paling galak selama tiga hari ospek, lalu kembali jadi budak tugas seperti biasa, itu bukan wibawa, itu krisis eksistensial. Lagian, masa iya kampus bangga punya generasi baru yang hafal yel-yel, tapi trauma lihat senior?
Berhenti mewariskan ketololan pada generasi selanjutnya
Sudah lah. Bentak-bentakan, meskipun cuma gimik, itu bukan metode. Itu ketololan berjamaah yang diwariskan dari generasi malas berpikir. Kalau tradisi itu masih dipertahankan, ya siap-siap aja generasi penerusmu jadi sama tololnya. Atau lebih buruk: bangga jadi penindas kecil-kecilan dengan jaket almamater sebagai tameng.
Jadi, buat para senior yang masih bercita-cita bentak adik tingkat sambil pegang clipboard dan pake headset: sadar, tobat, lalu diam. Tradisi usang ini tak perlu dipertahankan. Sudah saatnya kita buang ke tong sampah, lalu kita bikin ulang ospek yang manusiawi. Yang pakai empati, bukan intimidasi. Yang melatih nalar, bukan mengasah suara paling lantang.
Sebab, mahasiswa sejati itu bukan yang paling keras membentak, tapi yang paling berani berpikir.
Penulis: Rizky Prasetya
Editor: Rizky Prasetya
BACA JUGA Pengalaman Mereka yang Ikut Ospek Tahun 1971, 1995, 1997, dan 2014