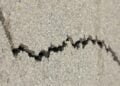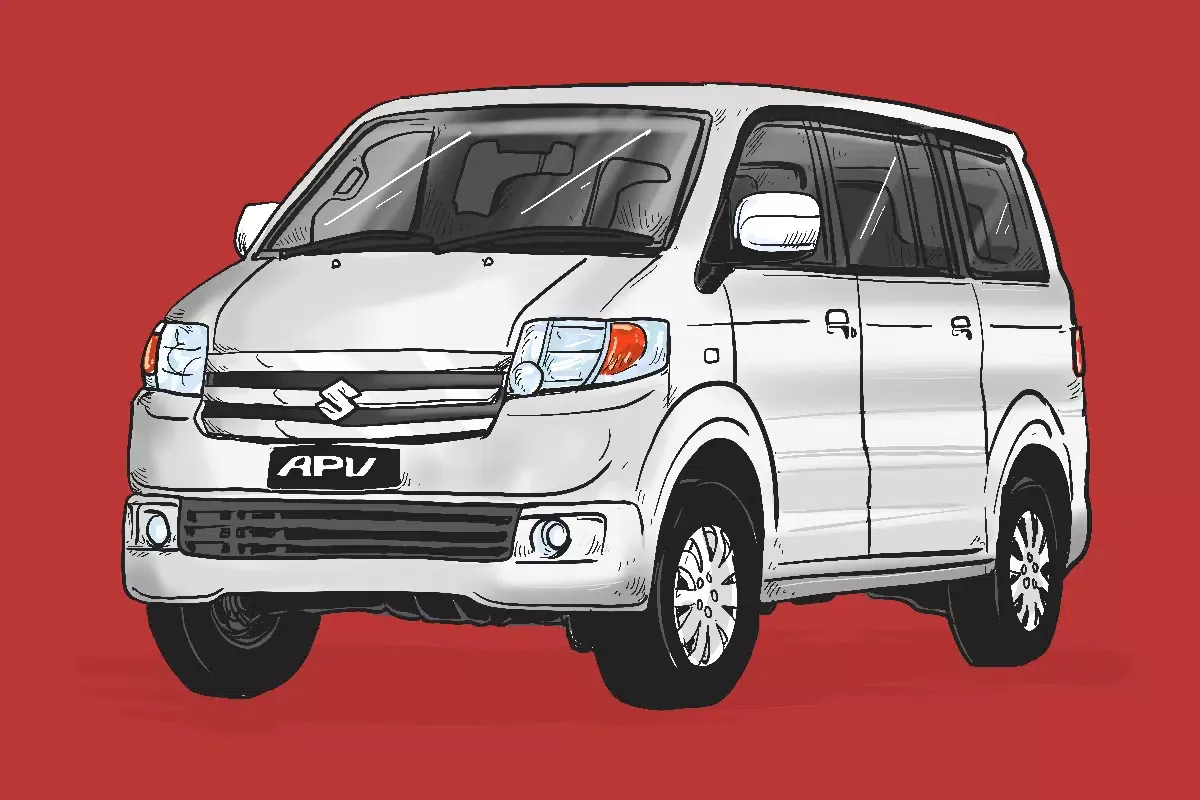Menikah dengan orang beda kota kadang bikin lupa bahwa beda kota itu bisa berarti beda segalanya. Saya orang Lamongan, lahir dan besar di wilayah pantura yang makanan default-nya adalah ikan. Sementara pasangan saya adalah orang Mojokerto yang kebetulan tidak suka ikan laut. Sebenarnya bukan cuma ikan laut saja, dia juga nggak segala bagian dari ikan laut. Entah telur ikan, bau, atau segala olahan ikan laut lainnya.
Tentu soal makanan adalah selera. Masalahnya, di tempat saya ini ikan laut melimpah. Pun bapak saya akan merasa ada yang kurang jika tiga hari saja tidak makan ikan laut. Dan karena dia akhirnya tinggal bersama saya di Lamongan, sering kali saya menyaksikan ia menahan hidung ketika membersihkan ikan laut untuk dimakan saya dan bapak.
Awalnya, saya kira ini cuma fase. Sebab, saya dulu juga sempat demikian. Dulu saya tidak mau makan ikan laut. Tapi lambat laun, apa saja dilahap. Asal memang masih masuk akal. Namun, ternyata istri saya tidak demikian.
Tapi tidak hanya istri saya yang merasakan gegar budaya dan kuliner. Saya pun begitu.
Rujak pakai nasi, siapa pelaku intelektual di balik ide ini?
Di Lamongan, rujak ya rujak. Sebuah makanan sebagaimana umumnya, yang terdiri dari buah dan bumbu pedas. Namun, di Mojokerto ada varian rujak yang menyalahi kodrat, yakni rujak sayur.
Buat yang belum tahu, ini sebenarnya satu genre dengan rujak cingur. Yakni rujak bumbu petis. Hanya saja tanpa cingur. Iya, hanya sayurnya saja. Maka isiannya hanya menyisakan tahu, timun, dan kangkong, yang kemudian disiram bumbu yang gurih pedas, itulah rujak sayur Mojokerto. Rasanya jelas enak, cuma masalahnya adalah, kebiasaan istri saya yang makan rujak ini dengan nasi.
Iya, nasi. Kok bisa gitu lho. Kalau pakai lontong masih oke. Tapi ini nasi. Awalnya, saya kira cuma prank. Ternyata memang default-nya seperti ini. Dan sampai hari ini saya, orang Lamongan asli masih berusaha menerima kenyataan ini.
Menyok vs kaspe
Kami punya akar budaya yang sama, tapi penyebutannya beda. Bahasa dapur kami pun saling melengkapi sekaligus memecah-belah. Saya menyebut singkong itu “menyok”. Sedangkan pasangan saya menyebutnya “kaspe”.
Dua diksi ini cukup asing di telinga kami masing-masing. Kami sama-sama menganggap aneh diksi masing-masing. Alhasil, saling roasting pun sering kami lakukan karena hal sepele, yakni perbedaan penyebutan dan betapa anehnya terdengar di telinga.
Ngoko vs Krama, sebuah perbedaan bahasa keseharian Lamongan dan Mojokerto
Selain soal makanan, satu hal yang sering membuat saya kagok adalah bahasa. Di Lamongan (setidaknya di desa saya), penggunaan bahasa ngoko itu lumrah ke orang tua. Bukan karena tidak sopan, tapi memang begitulah kami berbahasa. Agak egaliter.
Misalnya, ketika saya bertanya ke bapak, “Pak, udah makan?” saya menggunakan bahasa ngoko, yakni, “Pak, wis mangan?” bukan bahasa Kromo: “Pak, sampun dhahar nopo mboten?”
Nah, hal ini berbeda dengan istri saya. ia pernah cerita tentang kekagetannya mendengar obrolan saya dengan bapak yang hanya memakai bahasa Ngoko. Sebab, ia di rumah sangat “disiplin” memakai bahasa Krama. Entah dengan orang yang lebih tua, maupun dengan orang asing. Sedangkan di Lamongan, bahasa krama cuma muncul di ketika ngobrol dengan sesepuh, kyai, atau guru. Itu pun bahasa Krama seadanya, bukan full pakai bahasa krama
Yah pada akhirnya beda budaya itu bukan bencana. Justru dari sana menyimpan banyak cerita. dan bikin hidup jadi lebih ramai. Pun saya juga menyadari bahwa perbedaan antara laut dan gunung pun tetap bisa menikah dan rukun saja asal menyadari bahwa perbedaan memang sebuah keniscayaan. Meski demikian, tiga hal tersebut membuat saya mengalami culture shock pada awal-awal hidup berumahtangga.
Penulis: M. Afiqul Adib
Editor: Rizky Prasetya
BACA JUGA Lamongan Adalah Daerah dengan Pusat Kota Terburuk yang Pernah Saya Tahu
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.