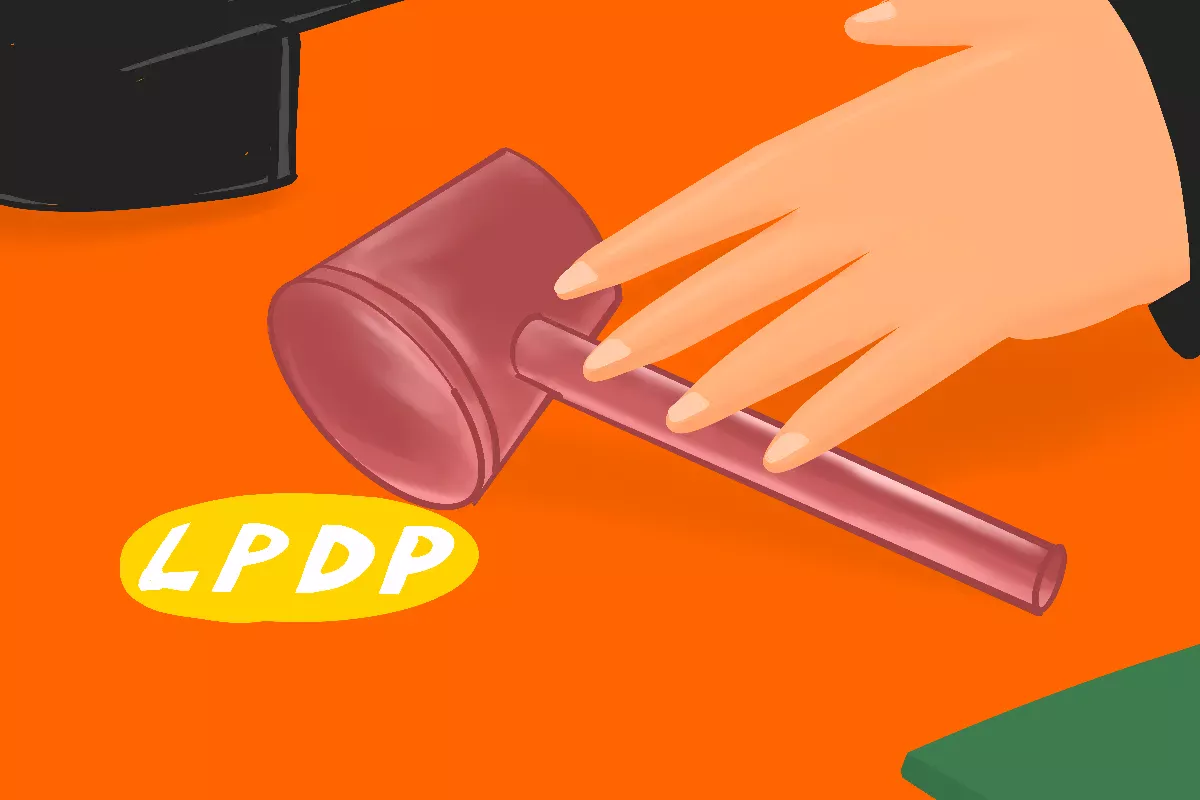Jogja, daerah yang segala sisinya selalu jadi perbincangan banyak kalangan. Sebab, bagi yang pernah mendatanginya, Jogja itu romantis dan ngangenin. Salah satu yang selalu dijadikan objek romantisme adalah angkringan. Tempat makan yang menjual makanan serba mini ini selalu dipandang sebagai identitas dari Jogja.
Bagi banyak orang, angkringan Jogja adalah simbol keberagaman sosial dan penjaga tradisi kearifan lokal. Kemudian tempat paling asyik untuk berdiskusi dan menggali inspirasi, dan menawarkan ketahanan pangan 24 jam dengan harga terjangkau bagi mereka para pengembara rupiah di malam hari.
Ini preferensi, tapi bagi saya, yang beberapa kali bolak-balik Yogyakarta, semua anggapan soal angkringan Jogja terlalu berlebihan alias overrated. Pada kenyataannya, angkringan Jogja (apalagi di kawasan pusat kota dan sekitarnya) tidak selalu menawarkan semua romantisme di atas.
Angkringan Jogja nggak menawarkan keistimewaan
Pertama soal menu dan rasa makanan, bagi saya angkringan Jogja tidak menawarkan keistimewan sebagaimana nama daerahnya. Biasa saja. Artinya begini, apa yang disuguhkan angkringan Jogja, seperti nasi kucing/nasi bungkus, teh, gorengan, sate-satean, dan makanan pendukung lain, juga bisa saya dapatkan di daerah lain seperti Semarang dan Solo.
Bahkan dengan rasa yang lebih enak dan harga yang lebih murah. Apalagi kalau kalian memasuki angkringan di daerah pusat Jogja dan sekitarnya, dijamin menu angkringannya template dan gitu-gitu aja. Kalaupun ada yang beda, paling kopi arang. Yah itu menu yang unik sih, tapi bukan minuman yang bisa dinikmati siapa saja, kan? Status sebagai wisatawan juga bisa membuat seseorang diketok dengan harga tinggi ketika selesai makan di angkringan.
“Oh tapi kan yang dicari suasananya yang hangat, tenang, syahdu, dan membumi?”
Baca halaman selanjutnya: Kedua, romantisme suasananya tidak selalu…