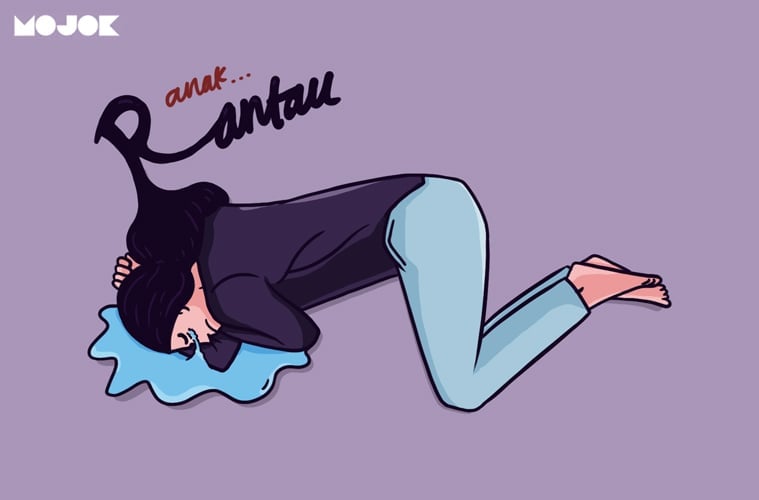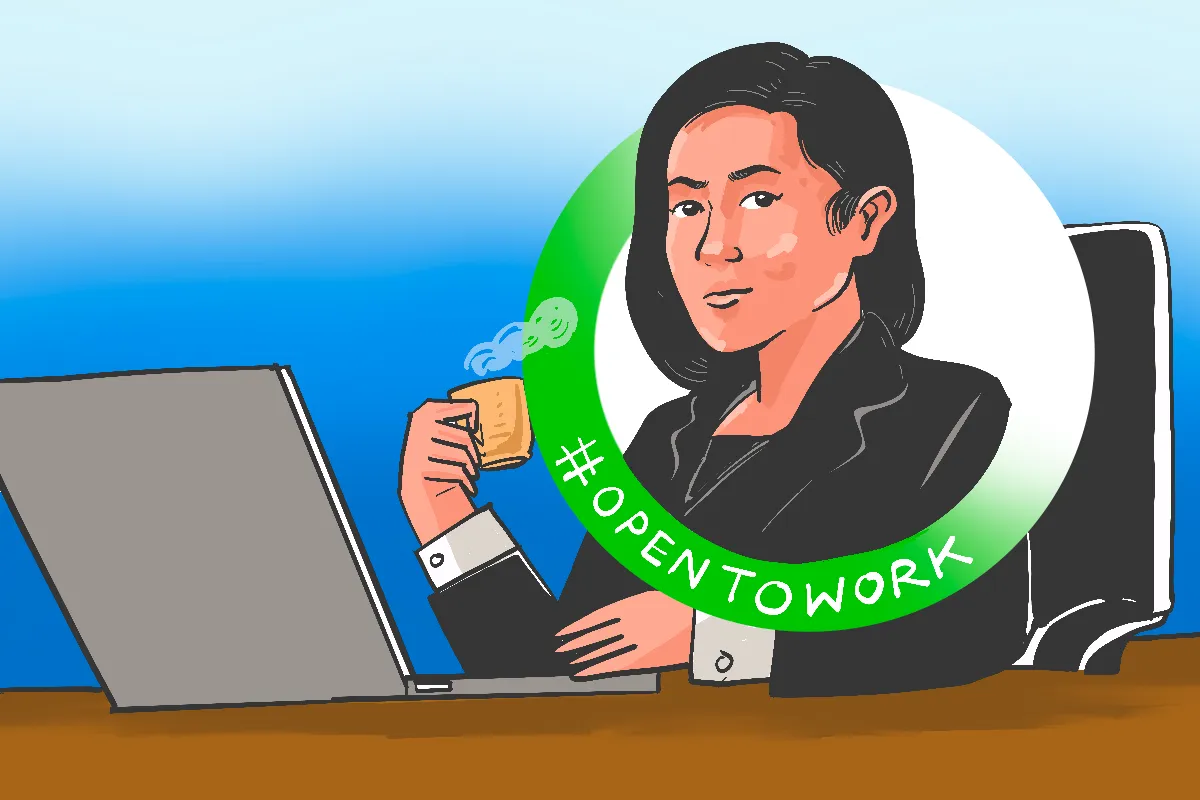Keluarga saya adalah petualang yang gemar merantau sana sini dan hidup nomaden—tapi tenang, pemikiran saya cukup modern untuk kalian sebut mirip manusia purba. Kalau diingat-ingat lagi, setidaknya saya memiliki 7 sekolah selama pendidikan formal saya. Kami berpindah-pindah bukan karena kebanyakan uang sehingga perlu di buang, akan tetapi untuk mencari peruntungan di tanah orang walau masih dalam satu negeri.
Saya sendiri aslinya ‘wong Sleman tulen sing numpang mbrojol ning Ciracas’. Bertahun-tahun saya tinggal di Pulau Sebatik, cukup memahami bahwa negeri ini ternyata memang sangat luas—sampai-sampai membuat Pemerintah pusat mungkin lupa bahwa setiap negara memiliki batas.
Sekitar tahun 2009, ketika konfrontasi militer Indonesia dan Malaysia dalam merebutkan Ambalat berakhir dengan keputusan diplomatis—masyarakat Sebatik dapat bernafas lega meskipun hingga tahun 2015 Malaysia terus melakukan aksi pelanggaran. Pasalnya apabila Indonesia dan Malaysia memutuskan bertindak sebaliknya, maka ancaman terhadap anjloknya kesejahteraan ekonomi masyarakat Sebatik menjadi taruhannya. Tentu saja, mengingat kedekatan sejarah dan budaya kedua negara telah terbangun begitu lama.
Sebelum Pulau Sebatik ramai dibicarakan akibat berita rumah dengan ruang tamu yang berada di garis wilayah Indonesia dan dapur masuk wilayah Malaysia menjadi viral—bukan terbelah lautan loh ya gaes—nggak seluas itu rumahnya. Kalau kalian ingat penampakan rumah dua bocah mirip tuyul di serial Malaysia Upin dan Ipin—tidak terlalu mirip tapi setidaknya begitulah penampakannya.
Masyarakat Sebatik memang sangat bergantung pada Malaysia—bukannya malah Indonesia sebagai negara ibunya. Bukan tanpa alasan—hampir seluruh produk di pasaran, bahasa, hingga kebudayaan cenderung berkiblat ke Malaysia karena kedekatan wilayah strategis dan akses apapun yang lebih mudah. Bahkan diketahui bahwa warga Sebatik yang tinggal di wilayah terdekat dengan patok perbatasan memiliki identitas ganda—bukan transgender—dua KTP.
Tidak hanya itu, masyarakat Sebatik juga bebas menyebarangi dan memasuki wilayah Malaysia dengan identitas seadanya—misalnya KTP atau bahkan Kartu Pelajar bagi pelajar—dan begitu pula sebaliknya.
Kenyataan pahit lainnya, tanpa bantuan tambahan berupa saluran parabola yang waktu itu harganya cukup mahal, channel televisi di Pulau Sebatik hanya berisi channel televisi Malaysia. Tidak heran jika masyarakat Sebatik lebih up to date berita dan sinetron Malaysia dari pada Indonesia.
Setelah Sebatik semakin menarik perhatian dan konflik wilayah perbatasan semakin santer di bicarakan—berbagai peraturan kedua negara menjadi lebih ketat termasuk perihal identitas dan perizinan bahkan untuk warga asli setempat.
Sebatik pun menjelma menjadi zona wisata sekaligus destinasi langganan favorit para politisi dan petinggi negara untuk sekedar melenggang di jalanan rusak dan berlubang khas pulau ini. Lalu pertanyaannya—adakah yang berubah setelah kunjungan para petinggi negara itu? Ada—apalagi kalau bukan headline media massa, kenthir memang.
Menurut hemat Bapak saya, sekarang ini kecepatan pembangunan di Pulau Sebatik termasuk yang paling cepat daripada wilayah perbatasan lainnya. Kemudian menurut hemat saya, pesatnya perkembangan pembangunan ekonomi di Pulau Sebatik tak lepas dari peran besar Malaysia. Hal ini menunjukkan semakin meningkat pula impor barang-barang dagangan dari luar negeri—terutama Malaysia—meskipun tingkat prosedur dan perizinan juga menjadi jauh lebih rumit setelah era klimaks dari kasus wilayah Ambalat.
Mata uang yang digunakan pun masih tetap ada dua—Rupiah dan Ringgit. Secara ekonomi, tentu lebih menguntungkan penggunaan kurs mata uang Ringgit mengingat kurs mata uang Ringgit memang lebih besar dari pada Rupiah, umumnya 1 Ringgit dihargai 3.500 rupiah di pasaran. Biaya distribusi barang-barang asal Malaysia juga jauh lebih murah dari pada biaya distribusi dari pusat produksi di kota-kota besar di Indonesia. Oleh karena itu, masyarakat masih sangat bergantung dengan produk-produk dan penggunaan mata uang Ringgit.
Perihal pendidikan sangat jauh ketinggalan—sampai kehadiran dua universitas besar dari Jogja menjadi pembuka sekaligus universitas pertama asal pulau Jawa yang menyentuh Sebatik 4 tahun yang lalu—yaitu UGM dan UMY melalui program KKN. Di Sebatik pun saat ini telah dibangun sekolah tapal batas dengan kondisi minim fasilitas untuk menampung dan memberikan pendidikan bagi anak-anak TKI yatim piatu dan anak-anak TKI yang kurang mampu. Namun sayangnya, banyak siswa-siswi asal Sebatik kurang disambut baik oleh banyak universitas negeri besar di luar sana.
Mengingat fasilitas pendidikan dan pengajaran yang kurang memadai dan tak sebanding dengan tingkat pendidikan yang berkembang di Pulau Jawa, siswa-siswi Sebatik dituntut untuk memenuhi ekspektasi dan standar pendidikan di kota maju. Mereka justru bagai terjerat kenyataan pahit akibat ketertinggalan ilmu pengetahuan teknologi yang terbentuk akibat sistem pembangunan terpusat di kota-kota besar di Indonesia dan pendidikan yang sangat tidak merata. Jika melihat sejarahnya—tentu saja Malaysia menjadi sangat berjasa bagi masyarakat Sebatik.
Akses yang jauh dari pusat pemerintahan membuat wilayah ini menjadi semakin terbelakang di negeri sendiri. Terlebih lagi permasalahan pendidikan, keterbatasan akses dan pengetahuan serta ketidakfahaman masyarakat menjadi kendala untuk memajukan pendidikan di wilayah Sebatik.
Saya tidak bisa mengatakan bahwa pelajar Sebatik tidak menyadari pentingnya sebuah pendidikan, namun yang membuat saya banyak sedikit miris adalah mereka tidak lebih mengenal negara mereka sendiri dari pada negara sebelah. Saya masih ingat, ketika masa sekolah dasar, setiap upacara kami menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Di luar itu, apa yang lebih sering dinyayikan oleh kawan-kawan saya di luar sekolah? Yup—lagu kebangsaan Malaysia yang mereka hafal mati.
Saya tidak sedang membicarakan masalah nasionalisme, patriotisme, dan segala tetek bengeknya. Namun, pengetahuan yang berkembang, lingkungan, hingga kenyataan hidup di wilayah yang berbatasan langsung dengan negara sebelah, membuat saya terkadang mempertanyakan nasionalisme saya sendiri ketika di sini bahkan sejatinya nasionalisme itu sendiri—ada kalanya konsep tersebut nampak begitu absurd.
Di salah satu daerah dataran tinggi di Pulau Sebatik, ada sebuah Tugu Elang “NKRI Harga Mati”—begitu katanya. Setiap upacara kami menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, membaca UUD, dan Pancasila. Soal nasionalisme sudah ditanamkan sejak lama di hati kami—namun bagaimana jika itu semua hanya sekedar doktrin yang tertanam sebagai formalitas?
“Kami nasionalis kok, kami cinta Indonesia”. Saya pribadi bisa katakan, “Ya, bisa jadi memang benar—siapa saya yang berani menghakimi rasa nasionalisme seseorang”.
Akan tetapi, tahukah kalian bahwa sebagian besar dari mereka saja tidak mengenal UGM atau UI itu apa dan di mana. Kenyataan lainnya—bisa dikatakan hampir seluruh produk yang mereka gunakan sepanjang kehidupan mereka berlabel Made in Malaysia, product of Malaysia, produced and exported by X Malaysia. Tak ketinggalan soal kampung halaman mereka yang katanya di Tawau dikarenakan sebagian keluarga besar mereka justru tinggal di Tawau, Sabah. Hal itu membuat pengetahuan soal Sabah sebagai kota terdekat menjadi lebih akrab di telinga mereka.
Kami memang tinggal dan hidup di Indonesia, tapi separuh kehidupan kami di hidupi oleh Malaysia. Begitulah singkatnya pengalaman yang pernah saya rasakan selama tinggal di Pulau Sebatik.
Hari ini saya sangat bersyukur, distribusi berbagai produk Indonesia mulai banyak menyentuh area Sebatik dan beberapa jenis lembaga pendidikan Indonesia menjadi semakin concern terhadap kemajuan pendidikan dan semangat belajar siswa-siswi Sebatik sehingga pola pikir pemuda Sebatik semakin lama menjadi semakin terbuka terhadap negeri mereka sendiri.
Soal nasionalisme? Jangan ditanya—upacara di Pulau Sebatik sesungguhya lebih sakral loh dengan kehadiran para pasukan militer di perbatasan. Semakin masifnya penjagaan dan banyaknya pos-pos militer yang ada di Sebatik beberapa tahun belakangan ini membuat masyarakat menyadari bahwa tanah ini ternyata masih milik negeri kita sendiri, Indonesia. Selama tinggal di sini, saya saja terkadang bisa lupa. hahaha