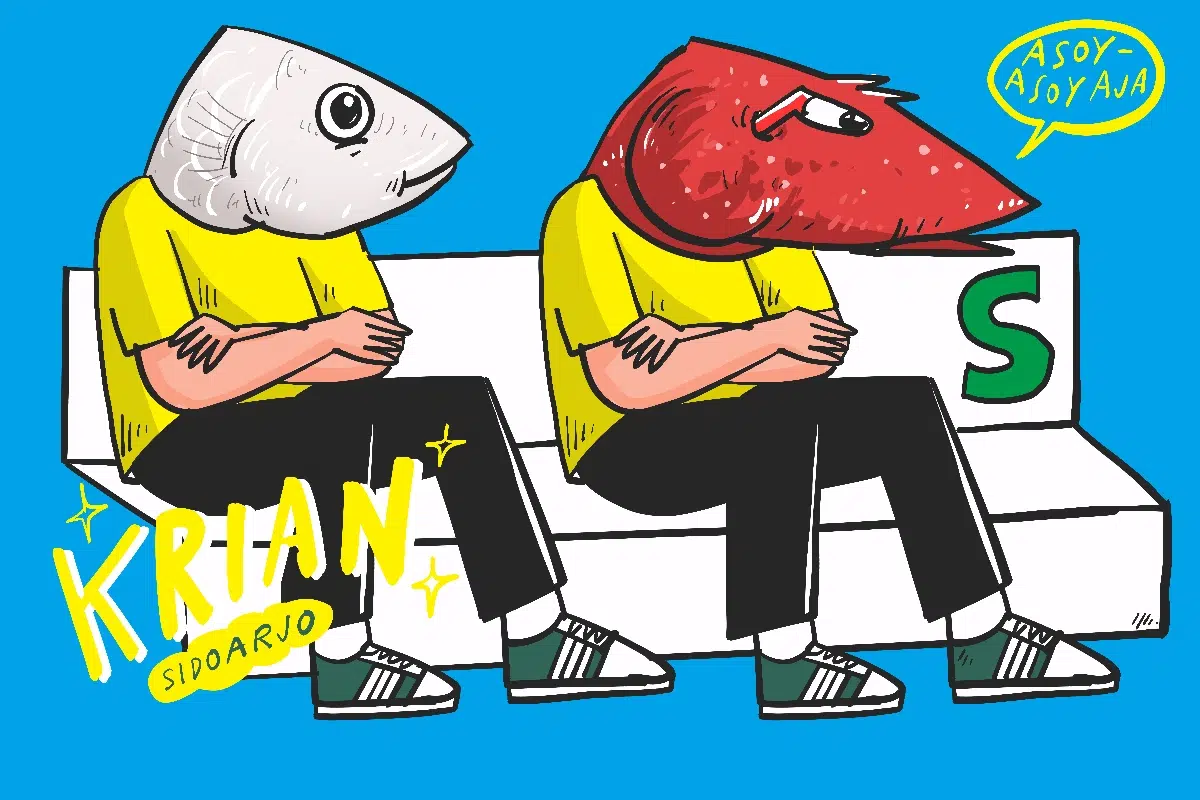Salah satu bahan obrolan saya dan teman-teman kuliah kalau reunian, adalah nostalgia “berburu” beasiswa. Saat itu, 25 tahun yang lalu, program beasiswa di kampus saya itu buanyak banget! Mulai dari program “diangkat anak” (maksudnya semua biaya pendidikan dan biaya hidup ditanggung sampai lulus), “diskonan” (maksudnya yang dibayarin hanya SPP selama empat tahun), sampai “uang kaget” (maksudnya bantuan berupa uang tunai selama periode tertentu).
Saya yakin, dari ABG unyu sampai aki-aki pun paham, kalau beasiswa itu sejatinya ditujukan untuk membantu siswa yang nggak mampu. Tapi, banyak juga penerima beasiswa yang nggak masuk “geng” itu. Dan sepertinya pihak sponsor pun “tutup mata” dengan hal ini. Buktinya, beberapa beasiswa nggak mensyaratkan surat keterangan tidak mampu atau kudu melalui proses wawancara. Jadi kesan saya, program beasiswa saat itu nggak jauh beda dengan proyek kantoran yang sekedar ngabisin dana di akhir tahun.
Tapi, ada satu hal yang ternyata nggak bisa ditolerir dan menjadi syarat mutlak dari pihak sponsor. Apa itu? Bukan cuci tangan, kaki, gosok gigi, pipis lho ya… tapi, syarat nilai akademis. Untuk hal ini, sponsor nggak mau “tutup mata”. Adanya standar nilai akademis ini yang suka bikin saya sentimen. Kok gitu amat?
“Ya iyalah, kan peminatnya bejibun. Siapa sih yang nggak mau gratisan?” Itu jawaban yang sering saya dengar. Jadi, nilai akademislah yang menjadi faktor penentu untuk seleksi berikutnya. Buat saya, pihak sponsor terkesan nggak mau mengambil risiko, cuma mau bayarin pendidikan untuk siswa yang pintar.
Saya geregetan karena menurut saya, kultur ini justru bisa bikin masalah baru. Paling tidak ada dua hal yang perlu diperhatikan.
#1 Bagaimana nasib mahasiswa yang tidak mampu, namun tidak berprestasi?
Saya kuliah di salah satu kampus negeri di Jawa Barat. Dan kampus saya itu bisa dibilang titik temu mahasiswa seantero Nusantara. Ada sekitar 60% mahasiswa yang berasal dari luar Jabar. Banyak banget kan? Nggak sedikit diantara mereka yang berasal dari keluarga tidak mampu dan diterima sebagai “mahasiswa undangan” alias masuk tanpa tes. Mungkin juga hal ini yang akhirnya menjadi daya tarik para sponsor untuk “buka lapak” di kampus.
Di angkatan saya, ada anak nelayan yang orang tuanya harus menjual satu-satunya perahu yang mereka punya sebagai bekal sang anak di perantauan ilmu. Ada juga anak pedagang warung dari sudut kota di Pulau Lombok yang cuma membawa Rp100 ribu rupiah sebagai bekal hidupnya. Belum lagi mahasiswa sebatang kara yang datang hanya modal undangan, nekat dan “gimana nanti”. Banyak deh kisah lainnya yang kalau diceritain semua, dijamin bikin kalian nangis pilu!
Mereka ini jelas masuk golongan tidak mampu yang perlu dibantu. Namun, beberapa dari mereka bahkan sudah jiper duluan buat ngajuin beasiswa karena standar nilai akademisnya masih di bawah persyaratan. Untuk beberapa kasus, saya tahu persis kenapa mereka nggak bisa mempertahankan nilainya. Bukan karena malas belajar, tapi waktu dan tenaga mereka sudah habis buat kerja serabutan.
Saya punya teman yang nguli bangungan selesai jam kuliah atau keliling kos-kosan setiap hari nawarin jasa mencuci baju. Ada juga yang bantu-bantu di warteg, nyuci mobil dosen, bahkan “bekerja rumah tangga” di salah satu rumah staf pengajar. Itu semua mau nggak mau kudu dilakoni cuma untuk bisa hidup sehari-hari.
Kebayang nggak, gimana mereka bisa berprestasi kalau setiap saat mereka harus berpikir, “Besok saya bisa makan apa nggak ya?” Apakah setelah bekerja mereka masih punya waktu dan tenaga untuk belajar? Nggak heran akhirnya mereka malah kalah bersaing dengan siswa lain yang nilainya lebih baik, walaupun belum tentu siswa tersebut lebih membutuhkan beasiswa.
Di kampus lain bahkan ada mahasiswa kurang mampu yang akhirnya drop out karena nggak bisa move on dari kubu “nasakom” alias nasib satu koma. Duh… rasanya seperti membiarkan teman sendiri mati kelaparan!
Sebagai kawan di kampus, sudah pasti saya dan teman-teman nggak tega melihat kondisi mereka. Tapi, seberapa sih bantuan yang bisa kami berikan? Nggak mungkin juga bantuan kami bisa bikin mereka survive selama empat atau lima tahun kuliah kan?
Bukankah dalam UUD 1945 pasal 31 dijelaskan bahwa negara menjamin pendidikan bagi setiap warga negaranya? Artinya, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, tidak terkecuali mahasiswa yang nilainya ngepas kan?
#2 Kesan yang terbentuk bahwa penerima beasiswa adalah mahasiswa pintar
Penerima beasiswa itu identik dengan kaum kurang mampu, namun pintar. Tapi, ternyata hal ini bisa jadi “boomerang” buat sang siswa.
Saya menjadi saksi bagaimana “stempel pintar” ini bikin stress teman satu kamar saya. Ceritanya beliau nggak lulus satu mata kuliah, sementara selama hidupnya ia selalu mendapat predikat terbaik sejak pendidikan dasar. Saya cukup shock melihatnya mewek hanya karena takut laporan ke ortu. Beliau merasa nggak bisa mempertahankan predikat “anak pintar” yang sudah kadung digadang-gadang sang Ibu sejak ia menerima beasiswa. Astaga… kan tinggal ngulang semester depan aja, Munaroooh.
Kesan “pintar” ini nggak cuma bisa “menghantui” sang siswa, tapi juga beberapa orang tua yang maaf, jadi sombong. Belum lama ini saat sedang khusyuk ngantri di sebuah kantor kelurahan, seorang ibu “mengumumkan” ke pengunjung, termasuk saya, bahwa ia datang untuk mengurus perpanjang beasiswa anaknya. Yaaa, lalu kenapa? Kasih taunya ke petugas kelurahan dooong, kenapa mesti ke kita? Kan kita nggak ada yang nanya juga, Bu… pamerin di status aja sanah….
Jadi, buat saya sepertinya persyaratan nilai akademis ini jadi malah menimbulkan masalah baru. Mungkin perlu nyontek slogan Pegadaian “mengatasi masalah tanpa masalah”. Saya sangat berharap suatu saat hal ini tidak lagi menjadi syarat mutlak dalam pengajuan beasiswa. Siapa tahu, nilai akademis ini bisa dipertimbangkan untuk diganti dengan proses wawancara, ujian tertulis, penulisan karya ilmiah, atau naskah yang sukses nembus redaksi mojok.
BACA JUGA Penobatan ‘Hey Look Ma, I Made It!’ sebagai Lagu Rock Terbaik Versi Billboard Itu Sungguh Nggak Masuk Akal dan tulisan Dessy Liestiyani lainnya.
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.
Pernah menulis di Terminal Mojok tapi belum gabung grup WhatsApp khusus penulis Terminal Mojok? Gabung dulu, yuk. Klik link-nya di sini.