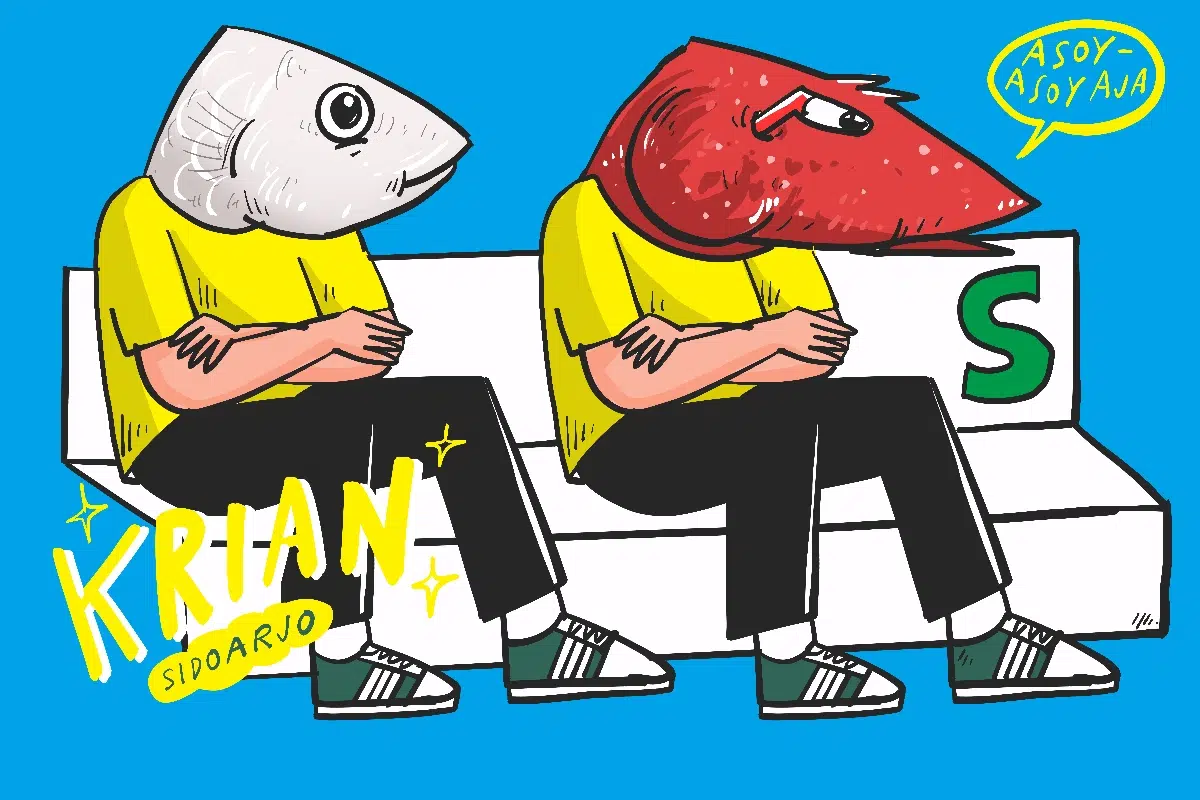Mahasiswa di persimpangan akhir studi selalu dihadapkan pada pilihan yang sebetulnya sama-sama menyiksa: menulis skripsi yang setelah disidangkan hanya akan jadi penghuni rak berdebu di perpustakaan. Atau nekat memilih jalur publikasi artikel jurnal yang prosesnya bisa bikin rambut rontok duluan sebelum lulus.
Keduanya sulit, keduanya punya konsekuensi yang sama sekali tak remeh.
Pasalnya, ini tidak semudah memilih lauk di warteg. Kalau di warteg, tinggal tunjuk: ayam goreng, tempe orek, atau sayur asem, plus es teh satu. Selesai. Sementara skripsi dan publikasi jurnal bukan sekadar soal keberanian menunjuk menu, tapi soal ketahanan mental menghadapi dosen pembimbing, birokrasi kampus, dan sederet aturan akademik yang kadang lebih kaku daripada pagar rumah dinas rektor.
Belum lagi tekanan sosial. Kalau ambil skripsi, siap-siap dibandingkan dengan teman yang lulus lebih cepat. Kalau ambil jalur publikasi, siap-siap ditatap sinis karena dianggap “sok-sokan” atau “nyari ribet sendiri.”
Lebih pelik lagi, pilihan ini sering kali lahir dari “politik akademik” yang dimainkan kampus. Ada fakultas yang terang-terangan mendorong publikasi jurnal demi gengsi akreditasi, seakan mahasiswa hanyalah pion tambahan untuk menaikkan skor BAN-PT.
Ada pula yang masih konservatif. Skripsi dianggap jalan satu-satunya menuju gelar sarjana, meski hasil akhirnya cuma jadi bahan arsip. Mahasiswa pun dipaksa tunduk pada sistem, padahal yang menanggung drama begadang, revisi tanpa ujung, dan dompet menipis akibat fotokopian adalah mereka sendiri.
Tidak ada pilihan lain, selain mengerjakan tugas akhir apa pun bentuknya
Di titik akhir perkuliahan satu hal yang pasti, tidak ada jalan keluar selain mengerjakan tugas akhir apa pun bentuknya. Mau itu skripsi, publikasi artikel jurnal, atau bahkan model lain yang diciptakan kampus demi alasan akreditasi, semuanya tetap bermuara pada satu kata keramat tugas akhir. Jadi jangan berharap ada opsi “skip” atau “jalan pintas” kecuali memang niat tidak ingin lulus.
Inilah kenapa mahasiswa sering merasa terjebak dalam sistem. Mereka tahu tugas akhir itu semacam gerbang terakhir sebelum wisuda, tapi pintunya penuh duri dan dijaga aturan yang sering bikin lelah sebelum benar-benar masuk.
Dan di sinilah letak ironinya. Meski bentuk tugas akhir bisa berbeda-beda, setiap mahasiswa pasti akan merasakan “malam-malam penuh kopi” dan “pagi yang diisi cemas.” Skripsi ataupun bentuk lainnya sama-sama menagih keringat, meski wujud penderitaannya berbeda. Ujung-ujungnya, yang membedakan hanyalah cara kampus menamainya, sementara mahasiswa tetaplah pihak yang harus menanggung getirnya.
Runyamnya mengambil skripsi
Setiap mahasiswa akhir pasti sudah sering mendengar kisah getir dari kakak tingkat soal lika-liku skripsi. Bahkan, sebagian sudah bisa menebak adegan dramanya jauh sebelum mereka sendiri masuk babak itu. Tapi tetap saja, ketika tiba gilirannya, skripsi selalu punya cara membuat kepala pening. Dari memilih judul yang “layak” menurut selera dosen pembimbing, berburu literatur yang sering berakhir dengan tumpukan fotokopi tebal, sampai menghadapi birokrasi kampus yang serba lambat—semuanya menyatu jadi satu jalan terjal.
Belum lagi kalau kebetulan dapat pembimbing yang super sibuk, sulit ditemui, atau sebaliknya, terlalu perfeksionis sampai tiap lembar dikejar revisi. Ada mahasiswa yang baru bisa tidur setelah begadang semalaman demi menambal catatan, hanya untuk besoknya disuruh mengganti total kerangka bab. Dalam situasi itu, wajar kalau banyak mahasiswa merasa skripsi lebih mirip uji ketahanan mental ketimbang uji akademik.
Dan benar saja, setelah segala jerih payah, skripsi akhirnya hanya berakhir di rak perpustakaan. Menjadi koleksi yang jarang sekali disentuh, kecuali oleh mahasiswa lain yang sedang kebingungan mencari contoh format. Ironi paling besar dari jalur skripsi adalah bagaimana sesuatu yang begitu melelahkan dan menyita waktu, akhirnya hanya jadi hiasan katalog kampus.
Meski begitu, skripsi tetap dijadikan “ritual sakral” menuju sarjana. Kampus meyakinkan bahwa skripsi adalah bukti kemampuan mahasiswa meneliti, berpikir ilmiah, dan menulis secara sistematis. Padahal, dalam praktiknya, lebih banyak mahasiswa yang sekadar mengejar revisi dan format ketimbang betul-betul menikmati proses penelitian.
Lelahnya menempuh jalur publikasi jurnal
Kalau skripsi sering dicap runyam, jalur publikasi jurnal jelas tidak kalah melelahkan. Malah, bagi sebagian mahasiswa, beban psikologisnya lebih berat. Bayangkan, bukan hanya harus menulis artikel ilmiah singkat padat jelas, tapi juga harus menyesuaikan diri dengan template jurnal yang ribetnya setengah mati. Margin harus sekian, sitasi harus gaya APA edisi terbaru, tabel dan gambar harus presisi, belum lagi kewajiban melewati proses peer review yang kadang lebih kejam daripada sidang skripsi.
Masalahnya, publikasi bukan sekadar tentang kemampuan menulis. Ada faktor waktu tunggu yang tak menentu—bisa berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan—hanya untuk mendapat kabar, “Artikel Anda direvisi.” Itu pun revisinya sering absurd. Ganti judul, perbaiki metodologi, atau tambahkan referensi yang entah kenapa harus dari jurnal tertentu. Mahasiswa pun harus siap menghadapi kenyataan bahwa perjuangan berbulan-bulan bisa kandas hanya gara-gara reviewer tidak puas dengan satu kalimat.
Dan jangan lupakan biayanya. Ada jurnal yang gratis, tapi banyak juga yang menerapkan biaya publikasi tidak sedikit. Alhasil, mahasiswa dipaksa memilih antara mengorbankan tabungan kos dan makan, atau mengubur ambisi publikasi. Ujung-ujungnya, jalur ini kerap dianggap elitis. Hanya bisa ditempuh oleh mereka yang punya tenaga ekstra, jaringan dosen yang kuat, dan tentu saja dompet yang lumayan tebal.
Jurnal predator
Lebih sial lagi, mahasiswa yang memilih jalur publikasi bisa saja berhadapan dengan jurnal predator. Jurnal macam ini tampilannya rapi, bahkan sering mengaku “internasional bereputasi,” tapi sebenarnya hanya wadah cari duit dengan iming-iming publikasi cepat. Begitu artikel dikirim, mahasiswa diminta bayar biaya ratusan ribu hingga jutaan, lalu dalam hitungan hari artikelnya “terbit.”
Kedengarannya enak, tapi di dunia akademik, publikasi di jurnal predator sama saja dengan menjilat ludah sendiri. Tidak diakui, malah bisa jadi bahan tertawaan.
Kalau lolos dari jurnal predator pun bukan berarti jalan aman. Mahasiswa masih harus menghadapi makhluk lain yang tak kalah menyebalkan: lintah akademik. Mereka ini biasanya datang dengan wajah dosen baik hati, pura-pura memberi bimbingan, lalu tiba-tiba namanya nongol di urutan penulis artikel—padahal sama sekali tidak ikut pusing begadang atau menambal revisi.
Mahasiswa cuma bisa pasrah, karena menolak berarti cari masalah dengan otoritas kampus. Akhirnya, karya yang harusnya jadi bukti perjuangan pribadi malah berubah jadi proyek patungan, di mana yang paling keringatan justru dapat kredit paling sedikit.
Intinya, mau skripsi atau publikasi jurnal, semangat, Dab!
Pada akhirnya, baik jalur skripsi maupun publikasi jurnal sama-sama penuh drama. Bedanya hanya soal jenis penderitaan yang harus ditanggung. Skripsi bikin pusing dengan birokrasi kampus, pembimbing yang sulit ditebak, dan bab-bab yang rasanya tak pernah selesai. Publikasi jurnal bikin lelah dengan template rumit, revisi tak berkesudahan, sampai risiko ketemu jurnal predator dan lintah akademik.
Tapi apa mau dikata, keduanya tetap gerbang wajib menuju toga dan sesi foto bareng keluarga di hari wisuda. Maka yang paling waras dilakukan adalah menyiapkan mental, menguatkan tekad, dan menghibur diri bahwa penderitaan ini cuma sementara. Siapa tahu, kalian justru beruntung dengan pilihan apa pun jalur tugas akhir kalian.
Setidaknya, dari semua runyamnya, akan ada cerita yang kelak bisa ditertawakan—dan tentu, gelar sarjana yang bisa dibanggakan.
Penulis: Sayyid Muhamad
Editor: Rizky Prasetya
BACA JUGA Sama Seperti KKN, Skripsi Sudah Usang dan Tidak Berguna
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.