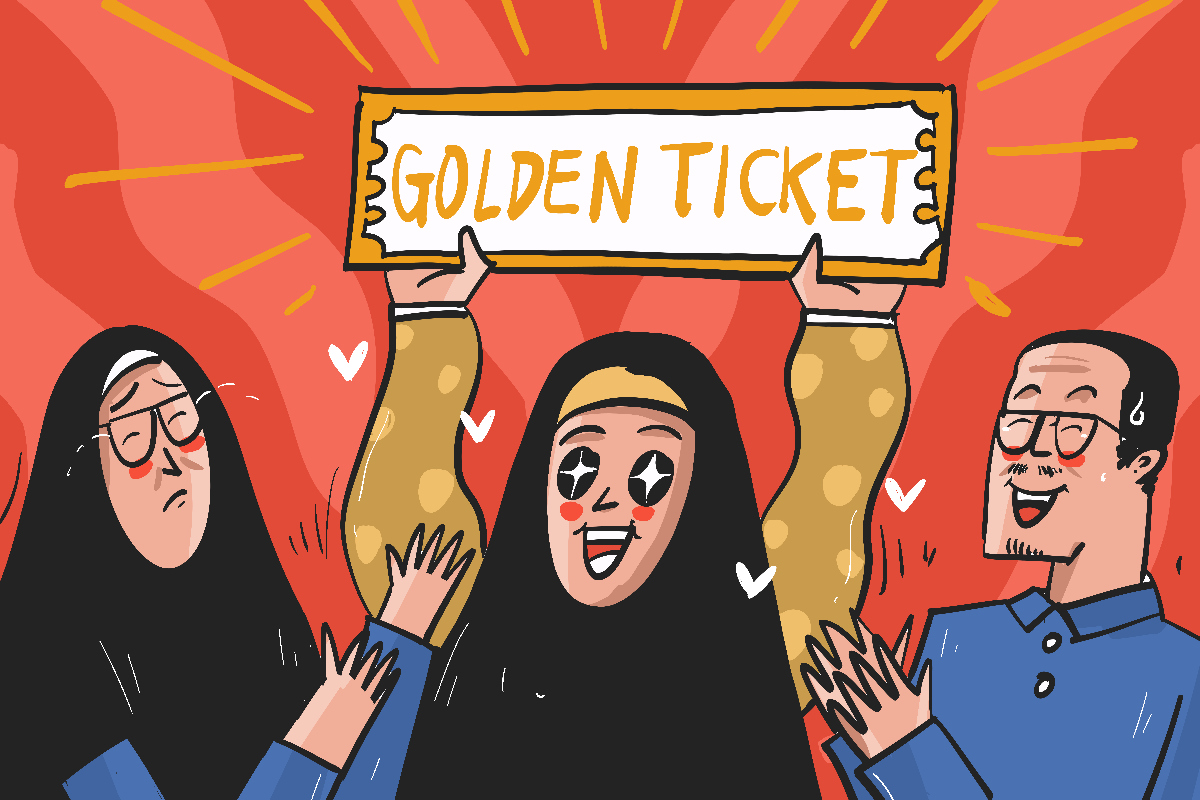Setidaknya butuh waktu satu hari untuk saya berani menulis cerita ini. Trauma atas pertandingan malam itu di Stadion Kanjuruhan masih membekas. Siapa pun tak mengira bahwa selain mengorbankan uang dan waktu, saya dan ribuan suporter Arema lain juga harus siap jika nantinya pulang hanya dengan nama.
Lebih dari setengah umur telah saya habiskan untuk sepak bola, baik itu sebagai pemain atau menjadi suporter. Oleh karena itu saya yakin betul bahwa sepak bola adalah olahraga yang menyenangkan dan layak dinikmati semua kalangan. Rasa tegang karena tim yang saya dukung tak kunjung mencetak gol, panik karena tertinggal, bahkan sorak-sorai ketika bola berhasil menembus jala lawan merupakan perasaan roller coaster yang bisa saya rasakan selama pertandingan berjalan.
Apa yang saya yakini di atas ternyata salah. Malam mencekam 1 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan, membuat saya sadar bahwa sepak bola bisa menjadi bencana dan dengan mudahnya merenggut nyawa siapa saja. Saya menjadi salah satu dari sekitar 42 ribu penonton yang malam itu hadir di Stadion Kanjuruhan.
Awalnya niat kami semua sama: mendukung Arema FC untuk bisa mengalahkan Persebaya Surabaya. Setidaknya, selama 90 menit plus 7 menit tambahan waktu, kami masih satu suara. Hingga sang pengadil lapangan meniupkan peluit panjang, barulah perbedaan keinginan dari kami mulai muncul.
Aremania jelas kecewa, beberapa dari mereka mengumpat. Ada yang memilih keluar stadion lebih dulu, tak sedikit pula yang meluapkannya dengan mengkritik pemain langsung dengan masuk ke dalam lapangan.
Stadion Kanjuruhan seperti medan perang
Saya tak perlu menjelaskan lagi bagaimana chaos-nya di dalam stadion, semua bisa kalian saksikan di berbagai media sosial. Kita harus mengakui bahwa masuk ke dalam lapangan adalah tindakan yang tidak dibenarkan. Pada poin ini, saya yakin Aremania akan satu suara mengatakan bahwa mereka telah melanggar aturan.
Di lapangan, ratusan orang berlari tak karuan. Mereka kejar-kejaran dengan para aparat yang memaksa mereka untuk mundur dan kembali ke tribun. Adanya pukulan, tendangan, bahkan injakan pun saya rasa masih hal yang “lumrah”, toh selama ini kekerasan selalu menjadi bagian ketika terjadi kerusuhan di sepak bola Indonesia, kan? Sudah, jangan denial.
Satu yang disesali oleh Aremania dan bahkan seluruh suporter Indonesia, adanya tembakan gas air mata yang diarahkan ke tribun penonton. Sialnya, Aremania yang berada di tribun adalah mereka yang tidak ikut turun ke lapangan dan mungkin juga sedang antre untuk keluar dari stadion.
Hal ini membuat para Aremania kalang-kabut. Bagaimanapun mereka hanya manusia biasa, insting untuk bertahan hidup mulai berjalan di sini. Laki-laki, perempuan, bahkan anak kecil, berdesak-desakan. Mereka dorong-dorongan dan bahkan terinjak-injak hanya untuk bisa keluar melalui pintu yang kecil itu (Aremania jelas tahu sekecil apa pintu di gate 3 dan 2).
“Ndek njeroh rusuh, Mas, ditembaki gas air mata (Di dalam rusuh, Mas, ditembakin gas air mata),” ujar salah satu dari mereka yang berhasil keluar.
“Woiii, iki arek cilik disikno, ojok surung-surungan, saaken iki. Ayo, seng wedok ambek arek cilik metu sek! (Ini anak kecil didahulukan, jangan dorong-dorongan, kasihan ini. Ayo, yang perempuan sama anak kecil keluar duluan).”
Saya melihat ini dengan mata kepala saya sendiri, beruntung bagi mereka yang “kuat” karena masih bisa berjalan menjauh dari kerumunan. Bagi yang sudah tidak kuat, mereka langsung terkapar sesaat setelah berhasil keluar dari dalam stadion.
Kondisi di luar stadion justru lebih parah
Malam itu saya menonton di utara, atau lebih tepatnya masuk lewat gate 3. Sesaat setelah peluit berakhir, saya memutuskan untuk keluar lewat gate 2 karena pintu di mana saya masuk sudah penuh sesak dengan suporter lain yang juga hendak keluar.
Saya pikir setelah keluar, semunya telah usai dan kericuhan hanya terjadi di dalam. Ternyata saya salah, kondisi di luar jauh lebih menyeramkan dan cukup untuk membuat saya ketakutan.
“Tuhan, saya tidak mau mati hari ini!”
Gate 3 cukup dekat dengan tribun VIP, yang membuat di sini banyak Aremania yang sudah menunggu para pemain Persebaya yang siap-siap untuk keluar dari Kanjuruhan. Mobil rantis yang berisi para pemain Bajul Ijo pun menjadi sasaran amukan mereka yang telah menunggu.
Saya pun cukup lama berdiam di gate 3, hingga akhirnya kami kembali ditembaki gas air mata. Hal ini membuat saya dan puluhan suporter lain berlindung di kios salah satu pedagang di Kanjuruhan dan menutup pintu kios supaya gas tidak masuk ke dalam.
Setelah dipikir semua sudah aman, kios pun kembali dibuka dan banyak dari kami yang sebelumnya berlindung, mulai menjauh dan mencari tempat yang aman. Belum sempat saya menjauh, kami kembali ditembaki, bukan dengan gas air mata, melainkan dengan mercon. Jika kalian tahu kembang api yang biasa dipakai di acara tahun baru yang bisa meledak ketika sampai atas, ya seperti itulah yang saya hadapi.
Saya pun kembali masuk ke kios yang sama, tentu bersama orang-orang lain. Di dalam, kami “buta” terhadap apa-apa saja yang terjadi di luar. Hanya suara teriakan dan ledakan mercon yang datang ke telinga kami. Hingga akhirnya, suara gedoran dari luar itu membuat hati saya tersayat. Bukan gedorannya, melainkan apa yang diucapkan oleh laki-laki itu.
“Tolong bukakno, Mas! Tolong, Mas, iki anakku. Tolong, Mas, iso mati iki areke! (Tolong bukakan, Mas! Tolong, ini anakku. Tolong, Mas, bisa mati nanti dia!)”
Hingga akhirnya pintu dibuka, mereka masuk bersamaan dengan sisa-sisa gas air mata yang ada di luar. Saya sedikit meneteskan air mata karena melihat anak kecil yang kurang lebih berusia 6 atau 7 tahun harus berjuang melawan gas air mata. Matanya merah, napasnya tak teratur, bahkan air matanya sudah kering karena terus-terusan menangis.
Saya merasa gagal menjadi manusia
Hingga akhirnya kami keluar dari kios itu sesaat setelah merasa semuanya sudah aman terkendali. Kali ini saya tak menyia-nyiakan waktu, saya langsung berjalan ke area yang lebih bebas dan tentu jauh lebih aman.
Selama perjalanan mencari tempat itu, saya melihat beberapa orang yang sudah berjatuhan, entah kecapekan, panik, atau sesak karena gas air mata. Bahkan—maaf sekali—saya sulit membedakan, apakah mereka pingsan atau sudah “pergi”.
Pun dengan seorang ibu yang menangis dan panik sambil menggendong balitanya bersama tiga orang TNI, berlari mencari pertolongan. Saya melihat sang anak sudah tak bergerak, tak ada respons atau tangisan. Saya tak mau berasumsi, hanya bisa mendoakan yang terbaik.
Ketika saya rasa sudah sampai di tempat yang aman, saya mendengar kepanikan dari Aremania karena salah satu temannya lemas tak berdaya. Tiga orang itu naik sepeda motor, memaksa membelah kemacetan agar teman mereka bisa sampai ke rumah sakit dengan cepat.
“Mas, amit, Mas. Koncoku gak ambekan. Tolong dalan e bukakno, Mas! (Mas, permisi. Temanku nggak bernapas. Tolong jalannya dibukakan, Mas!)”
Kurang lebih seperti ini yang saya ingat. Mereka panik karena salah satu temannya lemas tak berdaya dan harus segera mendapatkan pertolongan medis. Tak hanya satu kejadian, seingat saya ada tiga momen serupa. Kepanikan itu membuat nyali saya menciut, “Bagaimana jika itu adalah teman saya?”
Di pintu masuk dan keluar area Stadion Kanjuruhan pun sepertinya sudah diblokade. Dari tempat saya berdiri terlihat api yang membara, dan selang beberapa menit terjadi ledakan yang luar biasa dari salah satu truk pihak kepolisian. Kobaran api setinggi kurang lebih 10 atau 15 meter itu membuat para suporter berlari tunggang-langgang. Malam itu, Kanjuruhan semakin mencekam.
Di titik ini saya merasa gagal menjadi manusia. Didikan orang tua bahwa sebagai sesama makhluk ciptaan-Nya haruslah saling tolong-menolong ketika salah satu terkena musibah, tak bisa saya lakukan malam itu. Saya ingin sekali membantu mereka mendapatkan jalan yang enak menuju ke rumah sakit, tapi untuk membelah kerumunan ribuan suporter lainnya, kekuatan saya belum sampai untuk itu.
Terlebih beberapa orang mengatakan, “Ojok nang kono (pintu masuk area Kanjuruhan) sek, Mas. Sek kacau ndek kono. Ndek kene sek ae, aman. (Jangan ke sana dulu, Mas. Masih kacau di sana. Di sini dulu saja, aman).”
Ya, mungkin tragedi kemarin akan membuat saya trauma terhadap Arema dan Kanjuruhan. Terhadap klub dan stadion yang saya impi-impikan mulai kaki ini pertama kali menendang bola. Sudah cukup rasanya untuk salah-salahan. Bagi saya, semua elemen sepak bola Indonesia haruslah introspeksi. Para pemegang jabatan harus dengan rela mundur karena mereka telah gagal. Kejadian 1 Oktober 2022 mungkin adalah ledakan dari bom waktu ketidakseriusan mengurus sepak bola negeri ini.
Jika ratusan nyawa melayang tidak lagi membuka mata hati kalian, butuh berapa nyawa lagi untuk melakukan revolusi? Atau adagium bahwa “tak ada nyawa yang sebanding dengan sepak bola” hanya pemanis bibir belaka?
Penulis: Devandra Abi Prasetyo
Editor: Intan Ekapratiwi
BACA JUGA Tragedi Kanjuruhan: Mari Dukung Sanksi FIFA!