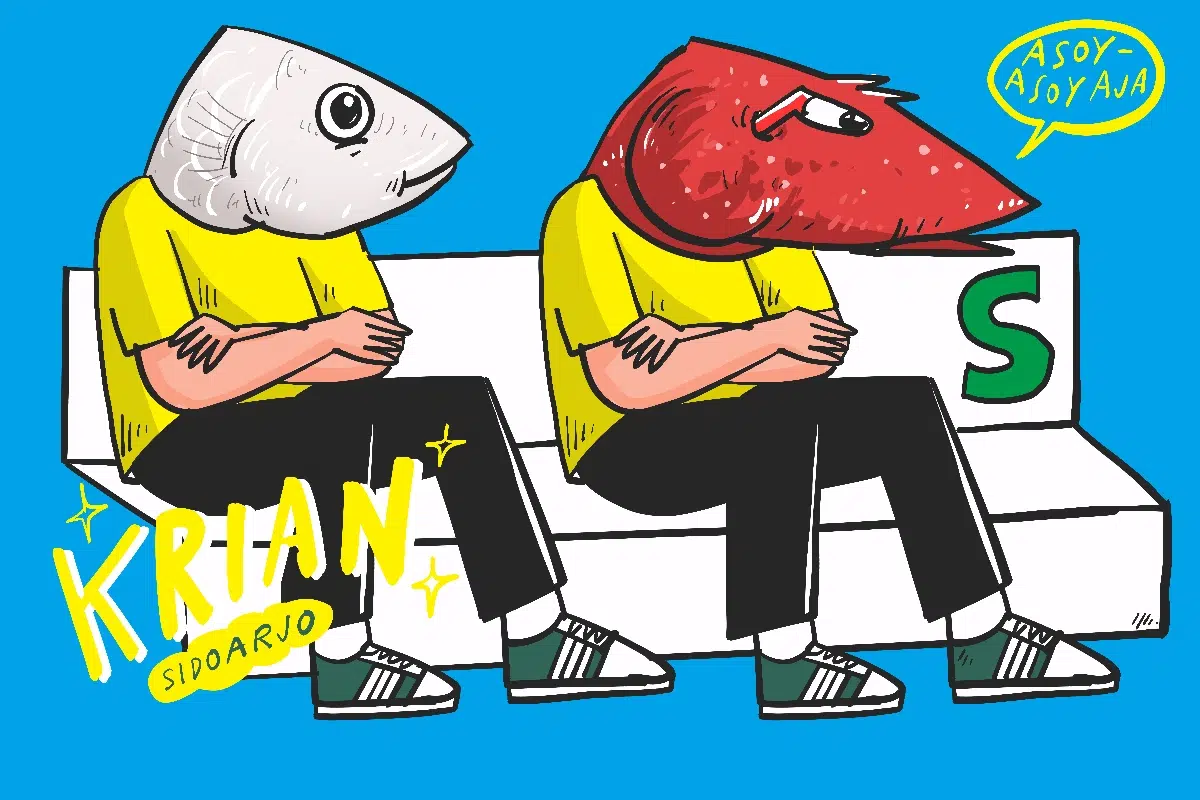Ada apa dengan Malang dan Bojonegoro? Ada kelucuan yang terjadi karena cara pengucapan sebuah kata.
Bicara soal suku di Indonesia, pasti kita mengetahui bahwa suku Jawa adalah salah satu suku dengan jumlah populasi besar di Indonesia. Seperti nama sukunya, bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi sehari-hari adalah Bahasa Jawa. Namun, meskipun sama-sama menggunakan Bahasa Jawa, tidak secara otomatis kosakata di Jawa Tengah dan Jawa Timur sama.
Contohnya ketika menyebut kata “kamu”. Orang Solo menyebut dengan “kowe” sedangkan orang Surabaya menyebut dengan kata “koen”. Itu sama-sama orang Jawa tapi beda provinsi ya..
Nah, sesuatu yang menarik terjadi di dua daerah dalam satu provinsi, yaitu Malang dan Bojonegoro. Penulisan kata di sana bisa saja, bahkan sering, sama. Namun, maknanya bisa berbeda jauh. Pengalaman seperti ini pernah saya alami ketika masih tinggal di Bojonegoro.
Keluarga saya berasal dari Malang, tetapi sudah lama menetap di Bojonegoro. Jadi, dalam komunikasi sehari-hari, saya terbiasa menggunakan dua “bahasa” yang berbeda tergantung siapa lawan bicaranya.
Iya, meskipun Malang dan Bojonegoro satu provinsi, saya mencatat setidaknya ada empat kata dengan penulisan sama tetapi maknanya berbeda. Lucu, tapi sering bikin salah paham.
#1 Kojor
Ada kejadian lucu ketika sepupu saya dari Malang main ke Bojonegoro. Sebut saja namanya Bambang. Sore itu, kami sekeluarga sedang ngobrol-ngobrol sambil makan singkong goreng di teras rumah. Ibu saya memanggil Bambang yang masih di dalam rumah.
“Mbang, ayo mrene jagongan karo maem kojor. Mumpung isih anget. Mau Bulik sing nggoreng”
(Mbang, ayo sini ngobrol bareng-bareng sambil makan kojor. Mumpung masih hangat. Tadi Bulik yang menggoreng).
Bambang keluar kamar sambil garuk-garuk kepala layaknya orang kebingungan.
“Lho, kok aku diutus maem kojor ta, Bulik?“
(Lho, kok saya disuruh makan kojor sih, Bulik?)
“Lha nyapo ta, Mbang? Kowe ora seneng kojor?”
(Lha kenapa sih, Mbang? Kamu nggak suka kojor?”
“Maem sega isih enak kok malah diutus maem kayu bakar ta?
(Makan nasi masih enak kok malah disuruh makan kayu bakar sih?)
Seketika kami semua tertawa. Usut punya usut, ternyata, percakapan antara ibu saya dan keponakannya itu nggak nyambung. Ibu saya yang sudah lama di Bojonegoro terbiasa menyebut singkong goreng sebagai kojor sedangkan di Malang, kata “kojor” artinya ‘kayu bakar’. Jaka sembung lagi minum susu, nggak nyambung bosku.
#2 Tilik
Lagi-lagi terjadi suatu percakapan yang nggak nyambung antara orang Malang dan Bojonegoro. Kali ini si Bambang disuruh ibu saya beli jeruk di pasar. Ibu saya berpesan kepada Bambang agar jangan langsung membeli tapi dicoba dulu apakah rasanya manis atau asam.
“Bu, kula badhe tumbas jeruk. Sekilo pinten, Bu? Legi-legi mboten, Bu?“
(Bu, saya mau beli jeruk. Sekilo berapa, Bu? Manis-manis nggak Bu?” Tanya Bambang kepada ibu penjual buah.
“Sekilo limolas ewu, Mas. Jeruk e legi kabeh, Mas.“
(Sekilo lima belas ribu, Mas. Jeruknya manis semua, Mas)
“ Kula niliki rumiyin nggih, Bu.
(Saya mencicipi dulu ya, Bu?)
“Jeruk e ora lara lho, Mas. Nyapo ditiliki?“
(Jeruknya nggak sakit lho, Mas. Kenapa dijenguk?)
Penjual jeruk keheranan.
Dari percakapan antara Bambang dengan ibu penjual jeruk itu, kita bisa mengetahui adanya kesalahpahaman terhadap suatu kata. Ibu penjual buah yang asli orang Bojonegoro memahami kata “tilik” artinya ‘menjenguk’ sedangkan versi Bambang yang orang Malang, “tilik” berarti mencicipi atau mencoba merasakan. Nah, salah lagi kan si Bambang.
#3 Mari
Cerita ini terjadi pada awal-awal perkuliahan saya di Malang. Suatu sore, saya mengerjakan tugas kelompok di rumah seorang teman yang asli Malang.
“Rud, tugasmu wis mari?”
(Rud, tugasmu sudah selesai?)
Teman saya bertanya.
“Hah, wis mari? Ana sing lara ta?”
(Hah, sudah sembuh? Adakah yang sakit?)
Nah, jadi bingung kan? Kata “mari” yang dimaksud teman saya adalah ‘selesai’ sedangkan kata “mari” yang saya pahami adalah ‘sembuh dari sakit’. Ups, saya keceplosan pakai “bahasa Jonegoroan” padahal posisi saya saat itu di Malang.
Benar kata pepatah “Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung.”
Dari kejadian itu saya berpikir, bukan salah teman saya kalau nggak ngerti apa yang saya maksud tapi saya, sebagai orang Bojonegoro yang harus menyesuaikan diri di mana saya berada.
#4 Ote-ote
Kalau cerita pertama tadi saya membahas tentang keponakan ibu, sekarang yang berkunjung ke Bojonegoro adalah bulik saya datang dari Malang. Dia, yang sehari-hari tinggal di daerah dingin, kali ini nggak betah dengan suhu udara di Bojonegoro yang terasa panas banget. Suatu siang, dia bertanya kepada seorang teman yang kebetulan main ke rumah saya.
“Koen mben dina seneng ote-ote ngene iki tah, Le?”
(Kamu setiap hari suka ote-ote seperti inikah, Nak?)
“Aku gak seneng mangan ote-ote, Bulik. Aku luwih seneng mangan tempe goreng.”
(Aku nggak suka makan ote-ote, Bu Lik. Aku lebih suka makan tempe goreng.)
Bulik berpikir bahwa teman saya tadi mengajak bercanda dia.
“Eeh, arek iki. Ditakoni wong tuwa kok malah ngajak guyon”
(Eeh, anak ini. Ditanya orang tua kok malah bercanda.)
Melihat permasalahan yang muncul, saya berinisiatif menjelaskan kesalahpahaman tadi. Yang dimaksud “ote-ote” oleh teman saya adalah ‘sejenis gorengan’ yang terbuat dari irisan kol dan wortel dicampur dengan adonan tepung. Ote-ote ini di daerah lain lazim disebut bakwan sayur goreng.
Di Malang, jajanan ini disebut dengan weci atau heci sedangkan di Blora (tempat tinggal saya sekarang) disebut dengan pia-pia. Beda lagi dengan ote-ote versi Malang. Yang dimaksud dengan “ote-ote” oleh Bulik saya adalah ‘bertelanjang dada’. Merujuk pada suhu udara yang panas di Bojonegoro saat itu. Dua kata tersebut bedanya telak kan?
Itulah empat kata dari Malang dan Bojonegoro yang penulisannya sama tapi mempunyai arti berbeda. Nah, dengan adanya tulisan ini, saya berharap kalian bisa mengambil manfaatnya. Jadi, pas kalian berada di kedua daerah itu nggak sampai terjadi kesalahpahaman dan ujung-ujungnya diketawain orang.
Penulis: Rudy Tri Hermawan
Editor: Yamadipati Seno
BACA JUGA 7 Tempat yang Sebaiknya Nggak Dikunjungi Saat ke Malang Raya.