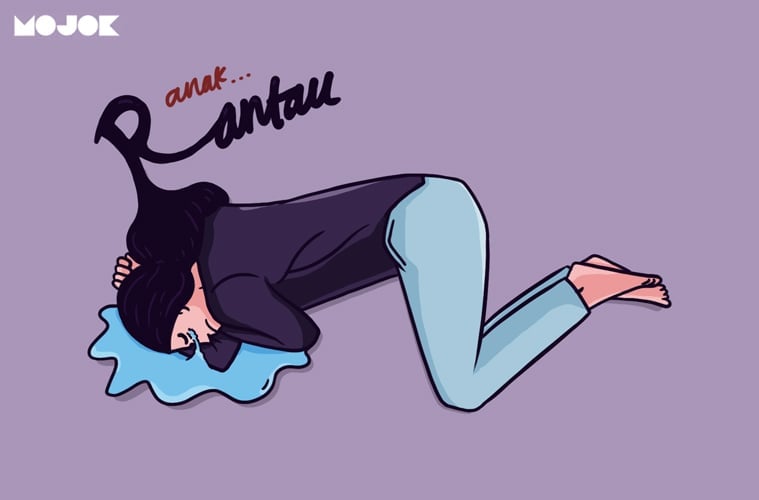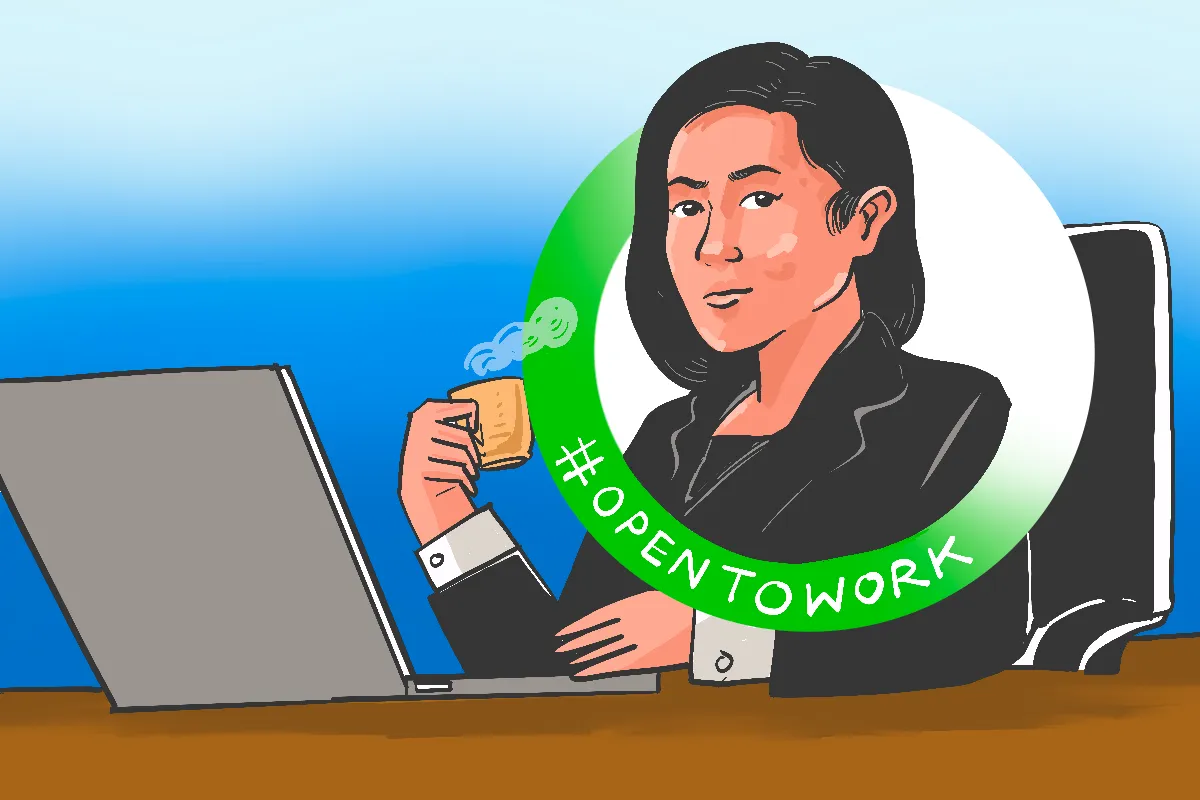Sudah saatnya kita menempatkan polisi dan influencer di tempat seharusnya: sejajar dengan rakyat biasa.
Saya harap, kali ini saya bisa merangkum seluruh geger gedhen media sosial dalam artikel ini. Ngimpi juga sih, lha wong geger gedhen adalah komoditi paling laris di media sosial. Dan saya sendiri termasuk konsumen dari komoditi berbasis tubir ini. Yah, ironi di balik ironi.
Geger gedhen yang saya maksud adalah perkara kepekokan para influencer serta mega blunder para “oknum” polisi. Keduanya silih berganti meramaikan opini warganet, sampai banyak isu terlupakan. Dari potensi ledakan angka positif COVID-19 sampai jeratan utang kereta cepat tersisihkan karena fenomena ra mashok ini.
Tapi, yang seharusnya menggelitik adalah: kenapa sih geger gedhen ini tak kunjung usai? Setiap hari ada saja kasus yang muncul dari kelompok masyarakat influencer dan polisi ini. Apakah negeri kita yang ngeri ini memang sedang tidak baik-baik saja? Andai Almarhum Harmoko masih hidup, pasti negeri ini baik-baik saja seturut petunjuk bapak presiden. Ah, joke lawas sekali ini.
Okelah, kembali ke urusan geger gedhen ini. Sebenarnya bukan salah media sosial dan warganet juga yang membuat geger gedhen ini selalu riuh. Baru satu isu selesai digunjingkan, esoknya ada isu baru lagi. Baru selesai nyinyirin Rachel Vennya, ada polisi merangkap aktor merebut hak privasi warga. Eh perkara polisi ini kelar, tiba-tiba muncul isu Anya Geraldine mandi. Padahal itu juga cuma metode advertising lho.
Tapi, mengapa perilaku mereka menjadi geger gedhen? Dan mengapa mereka berperilaku yang memicu geger gedhen ini? Jawaban dari pertanyaan ini lebih sederhana daripada pertanyaan “kok kamu belum nikah?” Jawabannya ada di bagaimana kita sebagai komunal masyarakat menilai mereka para influencer dan aparat.
Kuncinya adalah pemujaan (dan ketakutan) yang berlebihan. Kita menempatkan kedua kelompok masyarakat itu dalam posisi yang terlampau tinggi. Baik dalam urusan kekaguman, atau dalam urusan ketakutan.
Mari masuk dalam lingkup influencer. Kita menempatkan mereka sebagai agen pemberi pengaruh, kita terjebak dalam sudut pandang berlebihan ini. Kita mengagumi keunggulan mereka yang sebenarnya embuh dari mana. Padahal kerjaan mereka hanyalah jalan-jalan, bersolek, dan pamer kenikmatan. Dan mereka dibayar untuk itu lho!
Tapi, kita menempatkan mereka begitu tinggi. Sehingga segala perilaku mereka menjadi sorotan kita. Dan karena mereka butuh sorotan, mereka memuaskan obsesi kita pada kekaguman berlebihan ini. Akhirnya semua berputar tanpa henti, dan menjadi efek sebab-akibat yang tanpa henti. Kita menyediakan panggung berkarpet merah untuk para influencer. Dan para influencer membutuhkan panggung untuk mengeruk uang dari kantong kita.
Bagaimana dengan polisi? Nah ini juga sama saja sih. Tapi, yang lebih banyak bermain bukan kekaguman. Kecuali Anda bermimpi punya pasangan hidup seorang aparat yang katanya serbamakmur itu sih. Tapi, yang lebih banyak berkuasa dalam benak masyarakat adalah ketakutan pada eksistensi mereka.
Padahal secara fungsional, polisi mendapat mandat dari kita untuk menjaga keamanan. Lha kok malah kita takut berlebih pada mereka. Takut ditilang, takut dikriminalisasi, takut diinterogasi, dan sebagainya. Tapi, mengapa kita bisa setakut ini, sampai ada yang trauma dengan suara sirine mereka?
Ya karena ada pusaran setan yang terjadi. Di satu sisi kita takut, di sisi lain banyak oknum yang memanfaatkan ketakutan ini. Teror yang lahir bahkan dari seragam mereka sudah cukup menjadi bahan bakar pusaran takut-menakuti ini.
Misal dalam kasus paling bajingan: Kapolsek memperkosa (bukan meniduri!) anak seorang tahanan. Di satu sisi, si anak tadi terjebak ketakutan ketika sang ayah menjadi tahanan. Sedangkan terduga pemerkosa ini merasa memiliki “hak” untuk memuaskan nafsu bejat berlandaskan ketakutan ini. Ruwet? Memang ruwet, seperti gaduh di media sosial itu!
Lalu bagaimana ini bisa selesai? Ya hempaskan perasaan berlebihan itu dari benak kita dan komunal. Harus ada yang memotong rantai kekaguman dan ketakutan ini. Dan karena kita yang lebih dulu jadi objek dua kelompok masyarakat ini, ya kita harus mentas duluan. Sebab, yang dua tadi merasakan profit lebih dari fenomena ruwet ini!
Mulailah memandang influencer seperti baliho pinggir jalan. Alias sebagai alat iklan. Pandanglah polisi sebagai fungsi mereka menjaga keamanan dan bukan merenggut hak asasi kita. Gesekan pasti terjadi, tapi mau sampai kapan kita terjebak pusaran ndlogok ini? Sampai Indonesia jadi superpower Asia Tenggara? Bangun, Lur!
Memang benar kata Tuan Patrick Star, “Pemujaan yang berlebihan itu tidak sehat.”