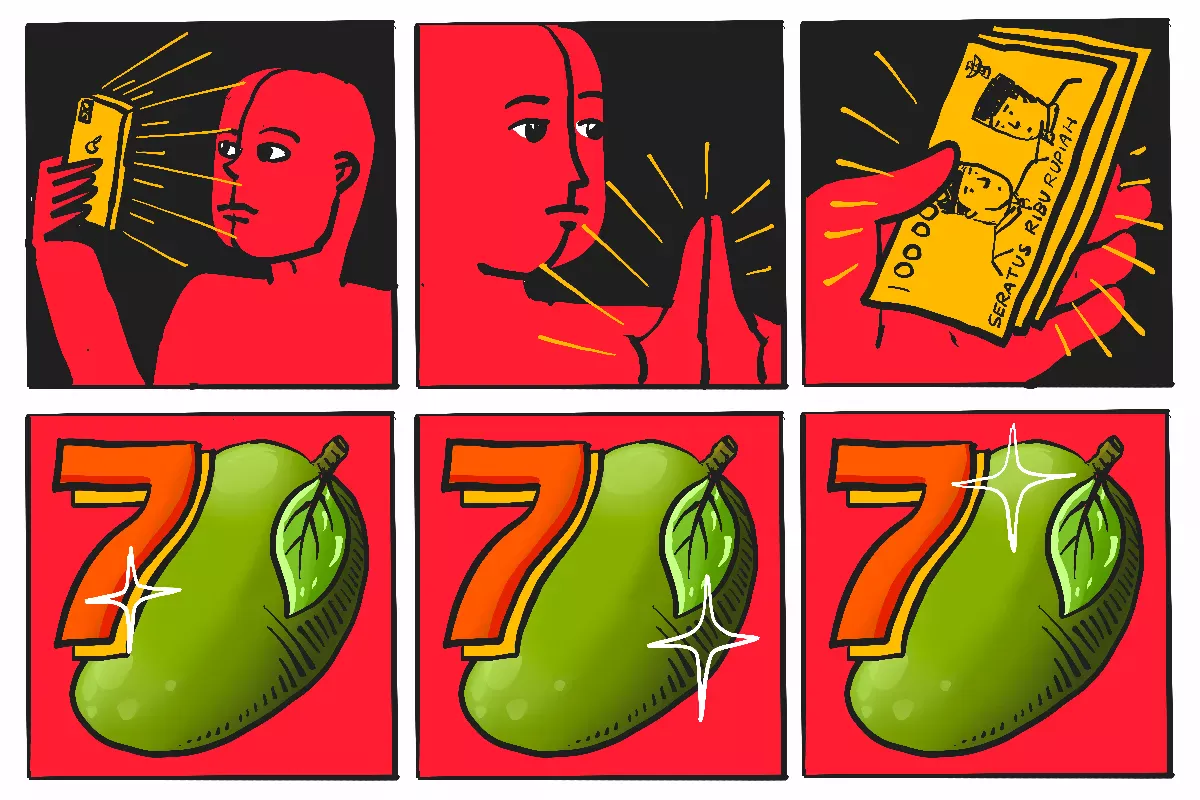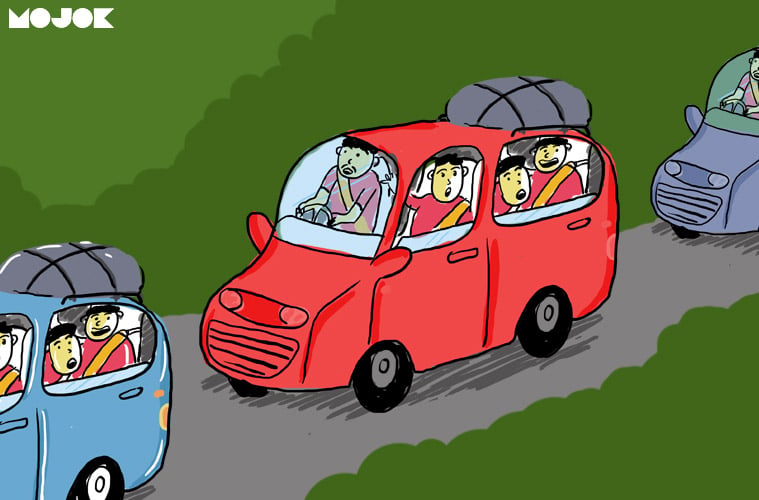Dulu waktu masih SMA, saya hobi banget main ke Solo. Maklum, jaraknya cuma satu jam perjalanan dari Salatiga. Tempat nongkrongnya beragam, event-nya ramai, dan pilihan hiburannya pun jauh lebih lengkap daripada kota saya yang adem itu. Nggak heran kalau dulu saya sempat mikir “Kayaknya enak deh hidup di Solo”
Dan, benar aja, keinginan itu kesampaian. Saya kuliah di Solo, lalu merasa impian saya tercapai. Dalam bayangan saya, hidup di Solo bakal penuh aktivitas keren kayak nonton event budaya, nongkrong di kafe aesthetic, foto ala selebgram, pokoknya hidup Instagramable banget deh. Eh, setelah benar-benar tinggal di sini, saya baru tau, ternyata ada hal-hal yang nggak keliatan ketika saya hanya mampir sebagai pengunjung. Dan jujur aja, ini bikin saya kaget. Apa aja ya hal itu?
Es teh adalah keharusan di Solo
Pertama, soal es teh. Es teh ada kok di Salatiga, tapi nggak sampai level “ada di mana-mana” juga sih. Di Solo, situasinya berbeda. Es teh udah kayak kebutuhan dasar yang harus selalu tersedia. Hampir kemana kaki melangkah, pasti ada pedagang es teh. Jalan beberapa langkah, menjumpai satu penjual. Belok sedikit, eh ada lagi.
Saya rasa orang-orang solo minum es teh tuh nggak semata-mata karena haus deh. Tapi, emang udah jadi kebiasaan yang nancep di hidup mereka. Teman saya yang asli Solo aja, kalau datang ke kos hampir selalu bawa es teh atau minimal bertanya “es teh nggak?”. Kunjungannya seolah-olah nggak lengkap kalau nggak ditemani dua gelas es teh plastik yang mengembun itu.
Baru di Solo saya hampir minum es teh setiap hari, sesuatu yang nggak pernah saya lakukan di Salatiga. Di kota asal, air putih atau wedangan jadi pilihan terbaik untuk menemani hari yang penuh kesibukan. Sekarang? Air putih tetap saya minum, wedangan hilang dari rutinitas, dan es teh bisa masuk ke tubuh saya dua sampai tiga kali sehari. Jadi, apakah ini tanda bahwa saya sudah benar-benar jadi anak solo?
Panasnya Solo benar-benar di luar nalar warga Salatiga
Aduh ini adalah hal yang bikin saya mengeluh tiap hari. Sebagai orang Salatiga, saya terbiasa hidup dalam hawa dingin. Wajar aja, kota ini ada di dataran tinggi lereng Merbabu. Malam hari sering kali masih butuh jaket karena suhu turun cukup rendah. Mandi pun cukup dua kali sehari, karena kita nggak akan berkeringat kalau nggak berkegiatan. Tidur juga selalu nyaman tanpa perlu bantuan kipas angin.
Memasuki Solo? Astaghfirullah hal adzim. Panasnya seperti dendam masa lalu. Baru di sini saya tidur pakai kipas angin nonstop dan tidak memakai selimut. Bahkan, saya mendadak punya hobi baru: mandi. Pagi, siang, sore, bahkan kadang tengah malam, rasanya pengen mandi terus. Gerahnya nggak main-main! Keringat bercucuran bahkan saat saya nggak ngapa-ngapain.
Bagi saya, Solo jam 9 pagi panasnya setara salatiga jam 11 siang. Dan, itu nggak berlebihan, emang gitu kenyataanya. Siang hari, jalan 15 meter buat cari makan aja sudah cukup membuat punggung basah keringat. Sunscreen 50 spf pun tak lupa jadi barang bawaan wajib kemana-mana.
Jalan satu arah yang menguji insting
Nah berikutnya masalah Jalan. Jalanan di Salatiga itu sederhana. Mau ke utara ya tinggal ke utara, mau balik ya tinggal putar balik. Jalan satu arah jumlahnya bisa dihitung jari dan jarang bikin bingung. Navigasi terasa masuk akal, bahkan untuk orang rantau sekalipun. Saya pun tumbuh dengan pola jalan lurus, jelas, dan tanpa aturan buka tutup.
Eh sampai di Solo saya langsung merasa masuk labirin. Contoh paling mudah ya Jalan Slamet Riyadi. Saya tinggal di sekitar Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), jadi berangkat ke pusat kota sangat gampang. Tinggal lurus mengikuti jalan utama. Tapi kalau pulang? Itu lain cerita. Saya harus mutar-mutar menghindari jalan satu arah, masuk gang, keluar gang, dan menghafal jam buka tutup jalan. Rasanya sedang memerankan Ninja Hatori tapi versi Solo.
Nggak hanya itu, saya pun beberapa kali kena omel orang di jalan. Kenapa? Ya karena ternyata saya melewati jalan satu arah. Bukan karena nekat, tapi murni nggak tau. Banyak ruas yang bagi saya keliatanya dua arah, eh tapi ternyata enggak. Belum lagi kalau ada buka tutup jalan di jam tertentu. Orang Solo mungkin sudah hafal ritmenya, tapi bagi saya, setiap perjalanan di Solo adalah ujian mengasah insting.
Membahas perguruan silat adalah topik sensitif
Ya, ini adalah culture shock pertama saya di Solo. Di Salatiga, membahas perguruan silat itu biasa aja. Saya sering kok bahas silat sama teman-teman. Bahkan, dengan mereka yang juga aktif di perguruan. Santai-santai aja tuh. Nggak ada yang tersinggung dan nggak pernah ada masalah berarti. Malah mereka senang kalau di tanya-tanya.
Ternyata kondisi di Solo berbeda. Pernah ada momen, dalam obrolan santai, saya menyebut nama salah satu perguruan silat. Nada saya biasa aja kok, nggak ada maksud menyinggung atau provokasi. Tapi, teman asli Solo langsung menegur “Sst, ojo banter-banter ngomonge”. Obrolannya langsung canggung. Seolah saya baru aja ngucapin nama yang pantang disebut di siang bolong.
Saya pun bertanya-tanya, kenapa hal ini seperti sesuatu yang dihindari? Di Salatiga, ini hal biasa aja kok. Ternyata, kata mereka, konflik perguruan di Solo masih cukup kental, makanya pembahasannya jadi sensitif. Bahkan, stigma terhadap anak silat juga nggak terlalu baik. Nggak jarang juga, kata teman saya ya ini, kalau kamu ketahuan ikut silat, biasanya bakal jadi bahan ledekan di belakang wkwk.
Jadi, udah tau kan apa yang membuat orang Salatiga seperti saya kaget hidup di Solo? Saat ini sudah masuk tahun ketiga saya tinggal di Solo. Hal-hal yang membuat kaget sudah bisa saya terima, kecuali satu hal, panasnya Solo. Itu satu-satunya hal yang sampai sekarang dan sampai kapanpun akan membuat saya mengeluh tiap hari. Solo panas pol cah, sumpah.
Penulis: M. Rafikhansa Dzaky Saputra
Editor: Kenia Intan
BACA JUGA Salatiga, Tempat Slow Living Terbaik di Jawa Tengah.
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.