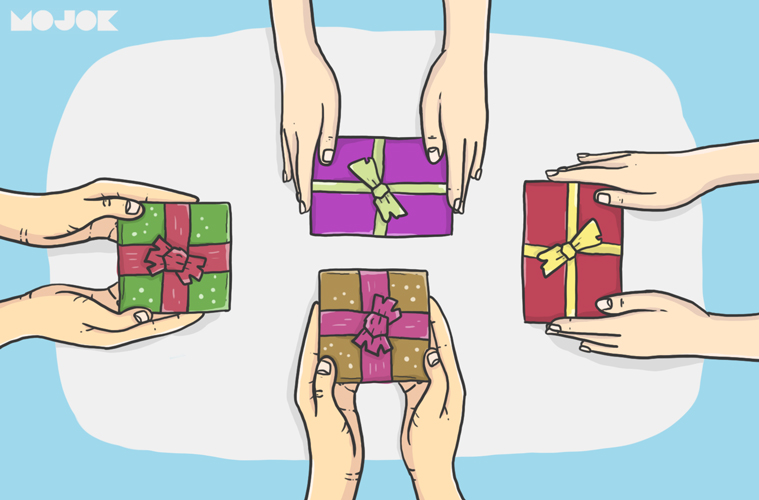MOJOK.CO – Pada titik tertentu, Natal yang orisinal bukan (hanya) di gereja. Natal yang genuine justru berada di antara kotak kado silang keluarga.
Alfonsus No Embu, Penyuluh Agama Katolik di Kantor Kementrian Agama, Kabupaten Merauke dan dosen Sekolah Tinggi Katekisasi Pastoral St. Yakobus, pernah menulis sebuah esai yang begitu menarik, sekaligus menggelitik tentang “ibadah lintas paroki” di jurnal “Retorika” terbitan Program Magister Ilmu Religi dan Budaya Universitas Sanata Dharma.
Alfonsus menjelaskan bahwa di Yogyakarta, terjadi yang namanya ibadah lintas paroki sejak lama. Misalnya, umat dari Paroki St. Yohanes Pringwulung, memilih beribadah di Paroki Santo Antonius Padua Kota Baru. Ada beberapa alasan yang mendasari ibadah lintas territorial paroki, dan hampir semuanya bukan alasan religuisitas dan spiritualitas.
Alasan itu, antara lain soal tata ruang gereja, tempat parkir, dekat dengan tempat wisata, lebih rindang, kotbah yang modern, nonton film pendek ketika kotbah, koor yang seru, dramatisasi, hingga ekaristi khusus untuk kaum muda. Banyak anak muda berbibadah karena ingin sekalian cuci mata “menonton” cewek-cewek yang ke geraja pakai pakaian dugem, bisa duduk-duduk di trotoar sambil mengobrol atau merokok, hingga sambil jajan batagor dan crepes.
Batagor di Gereja Kota Baru memang enak. Saya sudah mencobanya langsung. #ehh
Memang, tak bisa dimungkiri, beberapa brand ibadah misa di gereja tertentu memang lebih menarik ketimbang gereja lainnya. Pastor dan isi kotbah yang lucu, hingga ibadah yang lebih singkat, menjadi contoh. Dan, pada akhirnya, umat akan menjelma menjadi “konsumen” dari produk brand gereja tertentu.
Dalam hermeneutika sosiologis, Zygmunt Bauman, seorang sosiolog dari Polandia menjelaskan bahwa ada dua operasi besar yang mendasar dalam masyarakat (Katolik), yaitu defamiliarisasi dan memahami fenomena dalam konteks struktural besar. Konteks struktural saat ini, menurut Bauman, adalah budaya konsumen dan modernitas cair. Budaya konsumen, melahirkan yang namanya mentalitas belanja.
Dalam konteks ibadah lintas paroki, umat menjadi konsumen yang melakukan aktivitas “belanja”. Ia membanding-bandingkan, membuat berbagai pertimbangan tentang ibadah mana yang lebih asik, dan penjajakan yang berulang-ulang sebelum menentukan produk (baca: gereja) yang akan ia nikmati.
Seperti aktivitas belanja, ada berbagai pertimbangan yang sama ketika “memilih gereja”. Alfonsus menyebutnya dengan “belanja yang kudus”. Gereja tidak lagi menjadi “temple of scarification” tetapi juga sekaligus “temple of consumption”.
Kesamaan antara aktivitas belanja barang dengan “belanja yang kudus” juga terlihat dari cara berpakaian serta sikap umat. Ada umat yang menggunakan “kostum terbaik” mereka ketika dugem atau belanja di mall untuk pergi ke gereja. Dari sisi sikap, ada yang sambil ngemil, menelepon, main game di luar gereja ketika ibadah berlangsung.
Jangan salah, ada anjuran: “pakailah pakaian terbaikmu ketika mengadap Tuhan”. Tapi ya nggak pakai tank top dan rok mini juga. Saya jadi curiga, kalau lagu Malam Kudus di-remix sama Martin Garrix, beliau-beliau ini langsung joget di depan gereja.
Pergi ke gereja menjadi semacam seremonial belaka. Supaya bisa update Instastories “Habis ibadah, gaes!” atau menjawab pertanyaan “Dari mana?” dengan “Ibadah, dong!” sambil tersenyum bangga. Pada kenyataannya, banyak umat yang justru terlalu “menggereja” ketimbang “meng-Kristus”. Gereja menjadi komoditas dan penanda status ketimbang perayaan akan kemurahan hati Tuhan.
Dan, tak terkecuali dengan Natal di gereja.
Natal adalah perayaan akan datangnya Juru Selamat, datangnya sang penebusan dosa manusia. Dengan konteks belanja seperti dijelaskan di atas, ibadah Natal menjadi semacam ajang berburu foto untuk background Instastories. Ketika pulang dari gereja, banyak yang melepaskan segala atribut “kegerejaan” untuk kembali menjadi “manusia biasa”.
Ia akan hidup “menggereja” yang mana artinya “menuju gereja”, tapi tidak “meng-Kristus” yang nama artinya “menjadi Kristus”. Pulang dari gereja, mereka tetap berprasangka buruk kepada sesama, mudah terpelatuk ketika simbol agamanya dirisak, dengki, dan enggan memaafkan orang yang sudah berbuat salah kepada mereka, hingga menghujat pemeluk agama lain.
Oleh sebab itu, Natal yang orisinal bukan (hanya) di gereja. Natal yang justru lebih asli ada di kotak kado silang. Kok bisa? Ini pengalaman pribadi, di keluarga saya yang heterogen.
Ketika Natal datang, semua saudara berkumpul untuk berdoa dan makan bersama. Salah satu aktivitas wajib kami adalah mengadakan tukar kado silang. Bahkan, yang mengusulkan justru saudara saya yang beragama Islam. Nilai kado silang tidak boleh lebih dari 15 ribu dan tidak boleh makanan.
Saudara yang beragama Islam akan menjadi tukang catat nomor kado silang Natal. Bahkan beliau yang memegang kas uang arisan keluarga saya yang mayoritas memeluk Katolik.
Nah, konteks kado silang ketika Natal adalah “kejutan”. Saya tidak akan tahu isi dan dari siapa kado yang saya dapat. Kami tidak membedakan, mana kado yang Islam, mana yang Katolik. Semua membaur, semua menjadi satu.
Kami tertawa bersama-sama ketika mendapatkan kado yang isinya sandal swallow, jepitan jemuran, hingga jas hujan yang harganya lima ribuan. Kami tidak pernah menaruh curiga dengan berkata “mana yang kado dari orang Islam, saya nggak mau menerimanya.”
Penerimaan dan kepercayaan kepada sesama justru diajarkan dan dikhidmati secara paripurna lewat keseruan kado silang, dibanding “belanja yang kudus”. Bukankah membina hubungan yang harmonis dan penuh rasa damai adalah Katolik itu sendiri?
Pada titik tertentu, penerimaan akan keberagaman di tengah keluarga (masyarakat) yang heterogen membuat kita lebih mudah bertemu dengan rahmat Tuhan, ketimbang beribadah di sebuah bangunan setiap akhir pekan.
Gereja punya posisi penting dalam kehidupan Katolik. Gereja menjadi pusat iman, di mana kita mengakui dosa dan berterima kasih kepada Tuhan setiap harinya. Namun, yang paling penting adalah manusia yang menghidupi gereja. Manusia yang di dalamnya penuh kepalsuan dan kecurigaan. Menjadi manusia (Katolik) yang baik hati, justru lebih urgen ketimbang sekadar rajin ke gereja.
Apakah saya terdengar radikal? Mungkin iya, mungkin tidak. Semuanya cuma berdasar kepada hukum tertinggi Katolik, yaitu Hukum Cinta Kasih.
Natal adalah soal berbagi kasih. Keluarga saya melakukannya dengan kado silang. Natal juga bukan hanya perayaan setiap tanggal 25 Desember saja. Natal seharusnya menjadi keseharian Katolik. Ketika kita melahirkan “kabar baik” untuk sesama, setiap waktu, setiap hari, tanpa berkesudahan.
“Yesus” bermakna penyerahan kepada kuasa sang pencipta. Kuasa untuk menebus dosa manusia. Bukankah itu contoh yang luar biasa jelas bahwa hanya ada satu tugas umat Katolik? Betul, jadilah orang baik. Sudah. Itu saja.
Selamat Natal. Semoga semua makhluk berbahagia. Selalu.