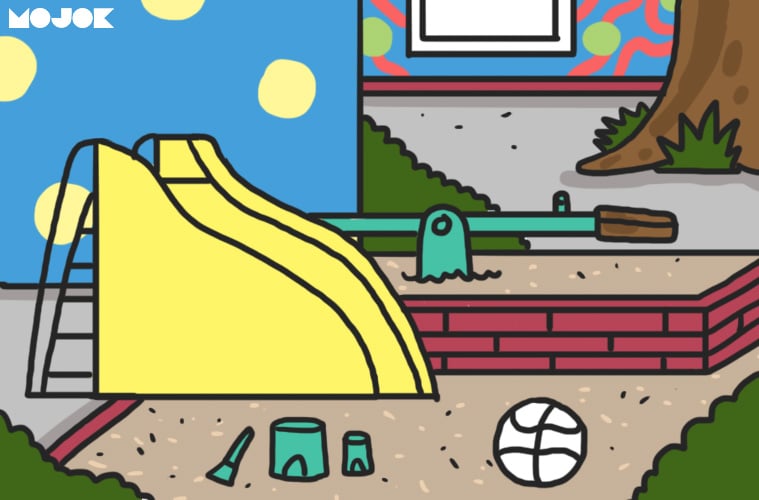MOJOK.CO – Meski kata “goblok” akan sering muncul di tulisan ini, sebenarnya saya tidak membenci orang goblok. Biarkan aja. Toh, mereka juga punya hak untuk goblok.
Orang goblok itu ada di mana-mana. Entah di sekolah, rumah, kantor, bioskop, perumahan atau jalan raya. Meningkatnya jabatan dan usia pun tidak menjamin kadar kegoblokan seseorang akan berkurang.
Saya misalnya, pernah terpaksa (dipaksa sebenarnya) mendengarkan celotehan panjang seorang guru SMA, sudah dewasa tentunya, mengkorelasikan artis korea dengan freemasonry melalui cara-cara yang ajaib. Tak usah saya ceritakan di mana hubungannya, takutnya nanti malah saya yang jadi goblok.
Bagi saya, orang goblok adalah mereka yang tidak bisa menggunakan perkakas logika sederhana dengan baik. Di mana kemudian ketidakmampuan mereka itu terbawa ke dalam cara mencerna informasi, pikiran, dan perilaku sehari-hari.
Saya beri contoh agar persepsi kita soal “goblok” bisa seragam.
Si A, misalnya, punya pemikiran kalau liberal itu sama saja dengan komunis. Dasarnya apa? Komunis dan liberal sama-sama menentang praktik agama.
Hm, mari kita uraikan sama-sama.
Anggaplah liberal itu sebagai mata, komunis sebagai hidung, dan “menentang praktik agama” sebagai muka. Kita semua tahu, mata dan hidung adalah bagian dari muka. Tapi apa mata dan hidung adalah sesuatu yang sama?
Kesalahan di atas pun belum memperhitungkan kebenaran dari anggapan si A, yaitu apakah komunis dan liberal benar-benar menentang praktik agama.
Ada lagi seseorang bernama B. Dalam pikiran B, orang yang berjenggot panjang pastilah memiliki paham radikal. Minimal harus dicurigai atau dijauhi.
Padahal, mungkin ada berjuta-juta orang berjenggot panjang di Indonesia. Bagaimana bisa si B mengetahui alam pikiran berjuta orang berjenggot itu sampai-sampai merasa kalau mereka radikal?
Ketika si A atau si B ditanya dari mana asal pemikiran dan informasi yang mereka dapat, lalu mereka merujuk pada satu situs, ucapan, atau desas-desus yang tidak jelas asal-usul dan pertanggungjawabannya. Lantas kalau tidak jelas, kok bisa dianggap sebagai kebenaran?
“Ya bisa dong, kan ini benar. Info valid! Sumbernya dari si Anu. Si Anu masa bisa salah?”
Kira-kira begitu.
Tapi terlepas dari perkataan “goblok” yang mungkin terdengar kasar dan akan sering muncul di tulisan ini, sebenarnya saya tidak membenci orang goblok—Anda pun sebaiknya jangan.
Bahkan kenalan, teman dan sanak saudara saya pun ada yang goblok. Tapi toh kami tetap baik-baik saja dalam bergaul. Orang goblok kan tidak otomatis jahat atau jelek perilakunya. Yah, kira-kira goblok itu juga masih ada standar mendingnya lah.
Sialnya, sering juga saya menemukan orang goblok yang tidak sadar akan kegoblokannya. Biasanya ini terjadi karena si goblok bukan hanya sekadar goblok. Tapi juga bebal alias keras kepala. Udah tidak tahu, tapi merasa tahu. Ngotot lagi.
Bukannya malu, orang-orang bebal ini malah membicarakan kegoblokan mereka dengan menggebu-gebu. Dipertontonkan seolah itu merupakan penemuan hebat yang bisa ia pecahkan setelah semua ilmuwan gagal melakukannya.
Saya sudah beberapa kali berhadapan dengan jenis semacam ini. Ada yang membicarakan politik, agama, sejarah, sampai fisika. Biasanya saya diam saja sambil mengangguk-anggukkan kepala. Tentu berharap mereka puas lalu mencari telinga lain untuk dibisiki kegoblokannya.
Tapi dulu ada juga satu-dua kejadian ketika saya membantah omongan mereka. Maklum, waktu itu ego saya untuk kelihatan pintar amat besar. Maunya bicara terus, bahkan saat tidak ada yang mau mendengarkan.
Akhirnya karena saya membantah, terjadilah perdebatan. Sekali waktu pernah jadi agak panjang ketika teman saya yang berasal dari kaum bumi datar mengajak berdebat soal bentuk bumi. Tentu di akhir tidak ada yang kalah, kan jurinya saja tidak ada.
Biasanya kalau pendapatnya saya pertanyakan, si bebal membantah dengan jurus klasik: memaparkan informasi yang sama sekali tidak dapat dipertanggungjawabkan asal-usulnya. Diucapkan berulang-ulang, terus-menerus.
“Menurut dokter anu”, “menurut professor anu”, “menurut kisah yang saya baca di blog anu”, “menurut info valid dari facebook si anu.”
Begitulah biasanya mereka menembakkan anggapan-anggapan mereka. Mungkin teman saya ini nggak pede dengan logikanya sendiri, jadi mesti mendompleng pikiran orang lain seperti si dokter anu yang bisa saja ternyata merupakan artis bokep setelah ditelusuri.
Ketika berdebat di sosial media, menanyakan kredibilitas adalah hal mudah. Kita bisa melakukan riset sederhana dengan internet mengenai pernyataan yang kita anggap tidak meyakinkan.
Tapi keadaannya beda lagi di dunia nyata kalau tidak ada internet dan ponsel. Di mana pergumulan dengan lawan bicara terjadi face-to-face. Sudah ngomongnya cepat, ngotot lagi.
Mau membantah pakai apa? Masa dengan mencarikan referensi buku-buku di perpustakaan yang pasti makan waktu puluhan kali lebih lama dari perdebatannya sendiri?
Kalau sudah begitu, jalan terbaik adalah diam. Bilang saja, “Ya sudah deh, kamu keren.” Kekesalan mungkin bertambah karena tidak bisa men-skak si bebal, tapi toh menahan kekesalan bisa dipelajari.
Lagipula setelah saya pikir-pikir lagi, buat apa ya berdebat dengan orang goblok yang bebal? Waktu kita habis. Kepintaran tidak bertambah. Yang bebal pun tidak sadar dari kegoblokannya.
Padahal waktu kita untuk berdebat dengan orang goblok itu kan bisa kita pakai untuk melakukan hal produktif lainnya. Bangun Tembok Cina misalnya.
Namun, situasinya bisa berbeda sih kalau si goblok dan bebal ini adalah teman kita sendiri—atau bahkan mungkin saudara (mampus lah). Lalu kita beranggapan kalau punya teman bebal adalah hal yang percuma bahkan cenderung merugikan.
Hm, saya kira itu adalah pandangan yang tidak sepenuhnya tepat. Justru saya punya banyak sekali pengalaman ketika ditolong oleh orang yang saya anggap bebal dan goblok. Nyatanya kehidupan saya baik-baik saja. Bahkan gara-gara bergaul dengan mereka, saya jadi bisa bikin tulisan ini tuh.
Lagian, masa hanya karena berdebat dan berbeda paham sekali-dua kali, semua hubungan kekerabatan itu hilang? Coba pikirkan lagi, bukankah banyak alternatif selain berdebat untuk menjalin hubungan dengan orang goblok yang bebal?
Buka puasa bareng, main futsal, berenang, main PUBG, dan lain sebagainya. Bukankah kegiatan-kegiatan tersebut akan tetap menyenangkan meski dilakukan dengan orang goblok yang bebal?
Memangnya ketika main futsal Anda masih akan tetap teringat akan kebebalan dan kegoblokan teman/saudara Anda? Ya, tentu tidak dong. Pikiran Anda ya fokus main futsal. Mana ada di saat kayak gitu kepikiran bisa menang debat? Kan nggak?
Lagipula saya curiga dengan Anda-Anda yang waktunya dihabiskan untuk berdebat dengan orang bebal dan semangat sekali dalam urusan menggoblok-goblokkan orang goblok.
Sebegitu banyakkah waktu Anda untuk dihambur-hamburkan? Sebegitu inginkah Anda untuk terlihat tidak goblok?
Biarkanlah orang bebal itu pada dunianya sendiri. Biar bagaimanapun, menjadi bebal dan goblok adalah hak setiap orang.
Kalau karena kebebalan dan kegoblokannya mereka lalu bikin mereka jadi nekat berbuat hal yang merugikan orang lain, kan ada yang namanya hukum. Toh, nggak usah sok parno, kayak Anda sendiri aja yang dirugikan. Teman Anda yang nggak goblok kan lebih banyak.
Lagian, ngapain juga berdiskusi dengan orang goblok plus bebal? Udah deh, diajak temenan biasa aja. Nggak usah bahas yang aneh-aneh.
Lha gimana, kalau Anda berdebat dengan orang goblok itu risiko banyak. Udah penjelasan Anda nggak bakal didengarin, kalau Anda berargumentasi pakai data ilmiah justru Anda yang digoblok-goblokin, kalau Anda setuju—malah Anda yang goblok.
Sudahlah, kalau mau pamer kepintaran itu jangan pada orang goblok dan bebal, pamerlah sama mereka yang tidak bebal dan memang merasa goblok.
Soalnya—percaya deh sama saya—berdebat dengan orang goblok itu hasilnya selalu goblok. Lagian kalau menang debat juga buat apa? Bangga gitu, diakui kepintarannya sama orang goblok?