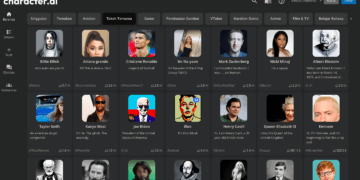Jika saja di masa seperti ini saya adalah seorang pelajar sekolah menengah, mungkin inilah hari-hari paling berat yang mesti saya lewati. Menghadapi keribetan pembelajaran jarak jauh, menyamakan ritme dengan kebanyakan orang (dan lingkungan), mempelajari hal-hal teknis yang hanya saya sendiri yang tidak tahu, alangkah putus asanya. Belum lagi jika membayangkan bahwa mungkin saja gajet saya adalah yang paling buruk di antara yang lain. Saya bisa membaui kecemasan macam apa dan sebesar apa yang akan menggelayuti saya.
Saya ingat betapa mengerikannya pengalaman masuk kelas komputer di kelas 2 SMA. Bukan semata kau sama sekali tidak bisa mempraktikkan kombinasi-kombinasi kunci yang sudah diulang-ulang oleh gurumu di depan kelas untuk mengoperasikannya, tapi terutama karena hanya dirimu satu-satunya orang yang tidak tahu tentang itu—di antara seisi kelas, dan boleh jadi di seluruh sekolahan. Saya merasa saya selalu adalah seorang pejuang untuk banyak sekali hal, tapi untuk hal ini saya menyerah bahkan sebelum betul-betul mengupayakannya: pada usia enam belas, saya sudah membayangkan tak akan bisa menyalakan komputer sepanjang hidup.
Kenangan-kenangan buruk macam itulah yang mengumpul ketika pada akhirnya saya menerima tawaran untuk melakukan wawancara dan diskusi virtual belum lama ini. Saya merasa bukan hanya terlambat nyaris setahun dengan kebanyakan orang, terutama mereka yang menjadi bagian aktif dari booming webinar sepanjang masa wabah, tapi saya bahkan kelihatan tak akan mampu menjadi bagian dari kultur baru itu. Bagaimana kalau ponsel murah saya tak sanggup? Bagaimana kalau layanan data isi ulang saya ndut-ndutan? Bagaimana kalau nanti saya tidak bisa masuk karena tak tahu caranya masuk? Bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begitu, dst.
“Hati-hati dengan yang kau harapkan!” begitu yang orang berbahasa Inggris sering ucapkan. Masalahnya, saya sering merasa tahu akan mengalami masalah dan pada akhirnya benar-benar mengalaminya. Dan memang itulah yang terjadi.
Saya melakukan wawancara lewat Instagram, wawancara virtual pertama saya, dengan kikuk. Sepanjang wawancara, entah berapa kali kata “halo” (dengan nada tanya) yang saya ucapkan, yang mengekspresikan kekhawatiran saya apakah suara saya sampai atau tidak di seberang sana; pertanyaan memastikan “Bisa dengar suara saya?” juga berulang-ulang saya lontarkan. Pada saat yang sama saya berkali-kali memegang ponsel saya yang panas menyengat, khawatir sewaktu-waktu ia akan meledak. Lalu… setelah itu… bagian layar yang memampangkan wajah saya berubah dari buram ke kabur, bergerak lebih lambat, lalu pecah-pecah, dan… begitulah.
Ya, kan! Apa saya bilang!
Pada webinar pertama yang saya lakukan, di hari yang sama ketika pada akhirnya saya punya aplikasi konferensi jarak jauh, saya nyaris ketakutan. Apalagi di seberang, di kotak panel lain, saya menemukan guru-guru saya nongol lebih dulu menunggu saya yang baru bergabung belakangan. Anehnya, atau beruntungnya, selama dua jam semuanya berjalan lancar—meski pertanyaan “Halo, bisa dengar suara saya?” masih saja terlontar otomatis dari mulut saya. Selama dua jam penuh, tak ada hal buruk yang terjadi.
Webinar berikutnya mengalami kelancaran yang sama, bahkan jauh lebih mulus. Dan, ehm, kekikukan dan kekhawatiran yang saya alami di kesempatan-kesempatan sebelumnya mulai menipis—dan memang tak seharusnya. Saya merasa mulai bisa menguasai “salah satu cara survival di masa pandemi” ini lebih cepat dari yang saya bayangkan. Tapi saya lupa bahwa orang berbahasa Inggris (atau entah siapa) juga sering bilang: “Jangan pernah percaya dengan permukaan laut yang tenang.”
Pada webinar ketiga, saya yang mulai menjadi lebih kalem, mulai terbiasa mengoperasikan, dan secara bertahap memahami kenapa wajah saya memenuhi layar sementara wajah yang lain mengecil atau menghilang, tak tahu bahwa ada yang lebih buruk dari gambar buram dan pecah-pecah yang saya alami di kesempatan sebelumnya. Pada satu waktu yang membingungkan, justru ketika saya sedang dengan percaya diri berbicara dengan wajah saya sendiri di layar, layar ponsel saya menggelap, dan memunculkan tanda paling menjengkelkan di era komputer itu: buffer (baca: pusaran angin). Saya panik, memencet apa saja, dan saya keluar dari sidang. Dengan bersusah payah saya kembali ke sidang. Ngomong lagi, meraba-raba sampai mana saya tadi terputus, lalu… gelap lagi. Dan muncullah pusaran angin itu lagi.
Ketika saya dengan susah payah mencoba kembali masuk, saya mendengar suara dari pembawa acara: “Teman-teman, tampaknya Mas Mahfud kembali terpental.” Kata yang tepat. Saya mencoba bangkit dan huyung. Mencoba masuk lagi. Dihantam lagi. Masuk, dihantam lagi. Maka, belum lagi lewat satu jam dari dua jam yang direncanakan, saya harus bilang bahwa ini tak bisa dilanjutkan. Dengan pahit saya pamit: “Saya mundur.”
***
Saya punya sifat bawaan suka berpikir terlalu jauh, nyaris untuk semua hal. Saya tahu saya mewarisinya dari mana.
Saya sering merasa harus menimbang ketika orang lain bisa dengan mudah mengambil keputusan; saya membuat komparasi “bagaimana kalau begini saja” pada saat yang “begitu” sebenarnya tak apa-apa; saya bukan hanya membayangkan akibat ketika saya mengambil keputusan, melainkan akibat dari akibat yang ditimbulkan akibat itu (Anda akan bingung membaca ini jika biasa berpikir lebih taktis dan sederhana). Konsekuensi paling logis, saya jadi mudah merasa khawatir.
Ketika hendak pergi, saya selalu khawatir ada sesuatu yang tertinggal: saya akan membuka-buka kembali tas, memuntir ulang gagang pintu, merogoh saku, atau semacam itu. Ketika akan meninggalkan rumah, saya sering kembali masuk untuk memastikan apakah semua jendela sudah tertutup, keran sudah dimatikan, kompor tak sedang menyala, atau bahkan sekadar membuat kenyamanan saya terpuaskan dengan seluruh kepastian itu. Saat berada di kendaraan umum, terutama jika menuju tempat baru, dan kendaraan tersebut tak memiliki sistem yang meyakinkan kita tiba setepatnya di tempat tujuan kita, saya selalu takut melewatkan titik turun yang saya tuju. Saat memencet nomor yang berurutan (telepon, nomor rekening, dan sejenisnya) saya takut ada angka yang terlewat atau urutannya terkacaukan atau ada tahap yang saya tidak jalani. Saat masih mengirim surat, saya selalu khawatir menulis alamat dengan salah atau tak terbaca, dan surat tak sampai. Saat mengirim email, bahkan dengan alamat yang sudah terang-jelas, saya khawatir ia tersasar.
Apakah dengan bersikap demikian saya kemudian menjadi orang lebih rapi dan waspada? Sayangnya tidak. Atau, lebih buruk dari itu, karena sikap bawaan macam itulah saya justru sering mengalami apa yang saya khawatirkan: pergi keluar ingin menulis tapi lupa bawa laptop; meninggalkan rumah dan kunci masih tergantung di pintu; pergi belanja tapi tak bawa dompet; masak air dan lupa mengentasnya; melewati rute yang sama ribuan kali tapi masih turun di tempat yang salah. Dst.
Saya tahu itu buruk, dan oleh karena itu saya berusaha mengatasinya. Konsekuensi akibat yang tidak terlalu berat jika kesalahan itu terjadi membuat saya bisa lebih santai; pengalaman yang berulang dan pemahaman yang lebih dalam kadang bikin saya tak lagi khawatir. Masalahnya, pada saat-saat seperti itulah saya justru memperoleh pengalaman-pengalaman paling konyol. Misalnya, pada satu malam di Tuban, saya yang hendak ke Semarang justru naik bus ke Surabaya. Atau, suatu ketika di Jakarta, ketika merasa yakin telah menemukan jalur baru dan hanya sekali naik dari Cikini ke Radio Dalam, saya justru terdampar jauh sampai Lebak Bulus, dan membuang tiga jam kebingungan dan tiga kali naik-turun angkutan tambahan untuk bisa pulang ke Fatmawati.
***
Saya membanggakan tradisi pesisir saya yang dinamis, mudah berubah, terus bergerak. Tapi tidak untuk teknologi atau sejenisnya. Saya selalu menyimpan kekhawatiran dengan alat-alat dan temuan baru. Saya ingat gemetarnya badan saat naik kereta. Saya ingat keraguan memencet keyboard komputer yang pertama saya pakai setelah sebelumnya terbiasa dengan mesin ketik. Saya sama berdegupnya ketika awal-awal menelepon atau menerima telepon. Dua tahun lalu, saya menimang ponsel pintar saya yang licin-mulus dengan kengerian bahwa ia bisa jatuh kapan saja dari genggaman saya.
Ya, saya bukan jenis orang yang menyambut kemajuan dengan antusias. Biasanya karena berkait karakternya yang menciptakan kebutuhan baru, konsumsi baru, tapi terutama sifat bawaannya yang ekspansionis. Sebagaimana Columbus membawa petaka bagi daratan yang “ditemukannya”, saya bahkan melihat pendaratan manusia di bulan tak lebih dari sekadar pemuasan ego Amerika karena akhirnya bisa menyamai capaian teknologi luar angkasa Soviet. Jika para orang tua muda di Indonesia hari ini mengarahkan anak-anaknya meneladani semangat inovatif Elon Musk, saya justru tak bisa memikirkan dengan cara lain sosok ini kecuali bahwa ia serupa betul dengan gabungan karakter konglomerat serakah dan ilmuwan gila di komik-komik Amerika. (Apa susahnya ia duduk tenang di beranda rumahnya, ngopi-ngopi, menikmati kekayaannya, menimang anaknya, dan membiarkan Mars tenang tak diganggu di kejauhan sana? Kenapa ia tak memilih mendukung salah satu klub sepak bola terkuat di dunia, dan dengan demikian bisa berbahagia di setiap akhir pekannya?)
Sekitar sebelas tahun lalu, saya membuat sebuah catatan murung untuk memulai blog saya yang murung, Sceptic Tank (yang kini sudah tak ada), tentang keraguan saya dan ketaksukaan saya dengan istilah “kemajuan”. Saya dengan percaya diri bilang bahwa istilah “kemajuan” punya persoalan sejak ia muncul: ia membawa serta sikap penghakiman terhadap apa yang dipandangnya sebagai “ketakmajuan” atau, dengan kata yang lebih populer, “keterbelakangan”; dan, tak bisa tidak, “kemajuan” hanya eksis jika ada “keterbelakangan” sebagai pembanding—baju-kemeja atas koteka, traktor atas bajak, otomotif atas gerobak, mobil balap atas sepeda, negara maju atas negara berkembang, dst. Lebih jauh saya menyimpulkan, apa yang selama ini orang sebut sebagai “kemajuan” tak lebih dari “pergeseran”: kita hanya mengganti masalah lama dengan masalah baru, ketaknyamanan lama dengan ketaknyamanan baru; kekhawatiran lama dengan kekhawatiran baru, kekurangan yang lama dengan kekhawatiran baru.
Mari bayangkan: ketika di satu desa di Lamongan seorang bocah yang baru masuk SMP menginginkan motor baru untuk menggantikan sepeda pancalnya yang usang agar ia tak terlambat sampai di sekolah, tidakkah di saat yang sama seorang insinyur Shinkansen di Jepang sedang berpikir dengan sangat keras bagaimana membuat kereta tercepat di dunia itu menjadi lebih cepat lagi? Artinya, meski yang pertama jauh tertinggal dibanding yang kedua, kedua orang itu toh sama-sama sedang menggelisahkan apa yang tak dipunyainya. Dan, meskipun terpisah waktu berabad-abad, tidakkah jenis kegelisahan yang mendorong semua penjelajah yang dulu mengawali kolonialisme dengan orang-orang yang kini ingin menguasai ruang angkasa terlihat sama? Bahwa Bumi yang dipijaknya dirasa tak mencukupi untuk memenuhi hasratnya.
Saya menuliskan simpulan-simpulan yang muram itu hanya beberapa bulan sebelum memutuskan keluar dari pekerjaan kantoran saya. Itu ketika saya merasa mailing list tak lebih dari tempat pertengkaran yang dipindahkan ke layar monitor, dan internet cepat oleh kebanyakan orang terlihat semata sebagai cara lebih mudah untuk mencari gambar jorok. Dan, tentu saja, ia ditulis oleh seorang karyawan jelang usia 30-an yang tak jelas mau apa dengan kehidupannya. Sayangnya, cara pandang itu tidak terlalu terikat dengan kondisi ketika saya menuliskannya; kekhawatiran asali sayalah yang mendorongnya. Oleh karena itu, kini, ketika saya tak lagi terlalu peduli atas apa yang akan saya hadapi di tahun-tahun ke depan, saya masih memiliki pikiran yang sama.
Tentu saja dengan sedikit menertawakannya. Juga dengan segala ironinya.
Anda tahu, acungan jari tengah terhadap kemajuan itu justru saya upayakan ketika saya mulai merengkuh jenis “kemajuan” yang paling mengubah kehidupan manusia dalam sepuluh tahun terakhir: media sosial. Tulisan tersebut terutama didorong oleh ketaknyamanan baru yang segera terasa begitu saya bergabung dengan Facebook—dan ia adalah salah satu tulisan yang saya unggah begitu tahu ada fitur “Catatan” di situ. Dengan kata lain, saya menyebut kemajuan sebagai konsumsi yang tak perlu, sembari saya dengan lahap mengunyahnya.
Dan saya mengalami semacam déjà vu ketika untuk pertama kalinya mengikuti acara kumpul-kumpul virtual. Kenapa orang begitu ngebet bertemu orang lain ketika kondisi justru membuatnya tak usah melakukannya? Kenapa sebuah aplikasi bernama Zoom bisa lebih mudah digunakan justru ketika gambar dimatikan? Kenapa ia bernama Meet, sementara yang kita lihat di layar ponsel adalah wajah kita sendiri? Kenapa, dan kenapa, dan kenapa lainnya.
Beriringan dengan sekian pertanyaan “kenapa” itu, saya sudah menyatakan setuju untuk menjadi bagian dari beberapa diskusi virtual di minggu-minggu ke depan. Dan setelah beberapa kali melakukannya, dengan pengalaman beberapa kali “terpental”, saya kini merasa lebih siap.
Lagi pula, saya juga bisa segera melihat “sisi baik”-nya. Dengan tetap ada di belakang meja sendiri, di rumah sendiri, saya merasa setidaknya sebagian tubuh saya justru tetap bisa bertahan dengan hal-hal lama yang terbiasa dilakukannya. Bersamaan dengan merengkuh “kemajuan”, berseminar tentang hal-hal hebat di masa depan, tentang sastra, tentang Indonesia, tentang peradaban dunia, pada saat yang sama saya tetap bisa menyimpan dan menikmati “ketertinggalan”. Misalnya, dengan menghirup kopi Kapal Api buatan sendiri, dan bersarung, dan mengudap singkong godog dari Gunungkidul, atau ngemil peyek daun kenikir produksi Bantul.
BACA JUGA Melihat Pengarang Tidak Bekerja dan esai Mahfud Ikhwan lainnya di kolom REBAHAN.