Di pinggir Jalan Raya Solo-Yogyakarta KM 12,5, sekitar 6 km dari Candi Prambanan yang kesohor, teras sebuah toko mebel perlahan berubah menjadi pangkalan para kuli serabutan. Mereka adalah kuli tanpa pekerjaan tetap sehingga tiap hari harus berburu lowongan kerja. Agar lebih terasa akrab, kita juga bisa menyebut mereka kuli freelance, toh artinya sama. Di teras toko mebel tersebut tiap pukul tujuh pagi berkumpullah para pekerja yang tak mengenal gaji, tunjangan hari raya (THR), apalagi asuransi.
Penggalan jalan antarprovinsi tersebut masuk wilayah Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Seperti namanya, jalan ini menghubungkan Kota Yogyakarta dan Kota Solo dengan rute Yogya-Sleman-Klaten-Solo.
Mereka yang berkumpul di tepi jalan antarprovinsi tersebut berasal dari berbagai daerah, tetapi rata-rata dari wilayah sekitar saja. Ada yang dari Klaten (sudah masuk Jawa Tengah serta Berbah dan Kalasan (dua kecamatan di Kabupaten Sleman, Provinsi DIY). Berasal dari tempat-tempat berbeda, persamaan mereka yaitu sama-sama kelas pekerja yang tak terserap sektor formal jenis apa pun.
Teras toko mebel tersebut sudah menjadi pangkalan kuli freelance sejak 40-50 tahun silam. Setidaknya seingat Triyanti (55), seorang penjual lotek―makanan yang masih bersaudara dengan gado-gado dan pecel―di dekat situ, pangkalan kuli ini sudah ada sejak ia masih bocah.
Jika tadi kita sudah punya dua sebutan untuk para pekerja ini, kuli serabutan dan kuli freelance, seorang tukang atur lalu lintas di sekitar situ punya sebutan lain. “(Mereka) pegawai, Bang… pegawai bangunan,” katanya sambil tertawa. Julukan lain yang beredar di pangkalan adalah PU alias pekerja umum. Mungkin ini merujuk ke Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang memang kerjaannya sekitar urusan konstruksi.
Obrolan Kuli Sebelum Memulai Hari
Marsono (51) sudah belasan tahun jadi peserta mangkal setia di teras toko mebel tersebut. Asalnya dari Klaten. Ia mulai jadi kuli serabutan sejak berhenti sebagai buruh pabrik. Alasannya mirip dengan banyak pekerja freelance: agar bisa bebas memilih waktu kerja.
Marsono yang biasa mengerjakan pembangunan membawa sendiri alat-alatnya: paku, meteran, tang, dan seterusnya. Upahnya sekitar Rp100.000 per hari dengan beberapa catatan. Pertama, kerjaan dari pemborong biasanya kurang dari itu. Kedua, kerjaan dari mandor proyek biasanya dibayar Rp100.000, namun sering tanpa ditanggung makan. Ketiga, dan ini paling enak, kerjaan langsung dari pemilik bangunan, seperti renovasi rumah. Bayarannya penuh Rp100.000, masih dapat makan siang dan snack.
Kalau dipikir-pikir, tidak begitu tepat juga perkataan Marsono bahwa jadi kuli serabutan enak karena bisa memilih waktu kerja. Adakalanya ia ingin bekerja, tetapi tidak dapat tawaran. Ia bahkan tak bisa memukul rata, seminggu atau sebulan biasanya dapat berapa pekerjaan.
“Di sini, tuh, adu nasib,” timpal kuli lain yang duduk di sebelah Marsono, saat kami berdua dari tim Magang di Mojok menghampiri mereka, Jumat pagi (24/9).
Marsono dan seorang kuli lain itu yang pertama-tama kami temui saat datang ke sana pagi-pagi. Ketika langit makin terang, makin banyak pula laki-laki dan perempuan yang datang. Menurut Marsono, hari itu tidak seramai biasanya. Hari paling ramai biasanya Senin sampai Rabu.
Mereka duduk di teras toko mebel, menghadap jalan raya. Lalu-lalang di jalan raya makin berisik. Kami harus mengobrol dengan setengah berteriak sambil bergantian menyorongkan kuping. Obrolan itu selesai saat Marsono dihampiri seorang kuli lain, Slamet (39), untuk merenovasi sebuah rumah di Kujonsari, wilayah Kecamatan Kalasan. Sebelum Marsono bersiap-siap menaiki motornya, salah satu dari kami―Sidra―menawarkan diri untuk ikut menguli.
Marsono membolehkan.

Sehari Menjajal Jadi Kuli Serabutan
Saya dan Marsono jongkok di depan pagar rumah bercat hijau dengan sebuah plang biru bertuliskan “RED PLANET Laundry” terpacak di dekat gerbangnya. Pemilik rumah adalah pedagang angkringan cukup besar di dekat kampus UPN Veteran Yogyakarta, kata Marsono. Tugasnya kali ini yaitu membangun taman dan kolam di belakang rumah, lalu mengubah gudang tak terpakai menjadi dapur.
“Tunggu teman sebentar, ya,” ia merujuk kepada Slamet. Kami sementara menunggu di depan pagar. Kata Marsono, Slamet berasal dari Kalasan dan sudah merenovasi rumah tersebut sejak tiga minggu yang lalu.
Sekitar lima belas menit kemudian orang yang dinanti datang. Ia sempat bingung melihat saya mengajaknya bersalaman. Untuk menghindari keruwetan, Marsono menjelaskan bahwa saya adalah mahasiswa yang ingin belajar soal kuli proyek. “Biar Pak Slamet nanti enak jelasin ke pemilik rumahnya,” kata Marsono kepada saya kemudian.
Kami memasuki gerbang dan parkir di halaman. Marsono bersiap-siap. Ia membuka jaketnya, saya mengikuti. Ia mengambil topi dari jok motor, saya pun meraba-raba pet yang sudah sejak awal menempel di kepala, menarik tutupnya ke belakang. Meskipun tak diberi upah dan tanpa pengalaman, praktik menjadi kuli di pagi itu membuat saya bersemangat.
Dengan lagak yakin, saya memasuki bekas gudang dan memeriksa medan yang akan digarap. Ruangan tersebut memanjang, ukurannya 3 x 8 meter, menghubungkan halaman depan dan halaman belakang. Di belakang terdapat dua petak kolam yang terbuat dari semen. Salah satu kolam masih terlihat baru, semennya halus dan warnanya lebih gelap dibandingkan kolam satunya. Kolam baru itu buatan Slamet.
Di halaman belakang itu Slamet mengambil tangga lipat, melebarkan lalu menegakkan kedua kakinya. Ia hendak memasang seng di halaman. “Kamu pegang tangga aja, ya,” ujar Slamet. Rasa gugup saya seketika luntur. Tugas pertama kuli magang ini masih mudah.

Setelah hampir satu jam memegangi tangga, saya dapat tugas yang lebih signifikan. Slamet mengaduk cat dan mencampurnya dengan air. “Bisa ngecat, ‘kan?” tanyanya. Tentu saja. Tinggal oles-oles saja, tho?
Saya mengambil kuas dan menyapu tembok dengan cat yang sudah diracik Slamet. Mengecat bukan pekerjaan yang sulit, justru menimbulkan perasaan nikmat. Namun saya dibayangi kesalahan, mengingat hasilnya akan dibandingkan dengan hasil cat tukang dengan jam terbang tinggi. Akibatnya, saya jadi gusar dan terus-terusan menoleh ke hasil cat Slamet.
Sambil sama-sama mengecat, Slamet bercerita tentang dirinya.
Ia jadi kuli freelance belum lama jika dibandingkan Marsono, baru mulai pada 2014. Kampungnya di Gunungkidul, salah satu kabupaten di Yogyakarta, tapi kini tinggal bersama keluarganya sendiri di daerah Prambanan. Ia punya sebidang sawah di dekat rumahnya, tetapi masih ambil kerja sambilan di restoran.
Di tahun yang sama ia memilih konsisten nyambi sebagai kuli bangunan. Slamet sadar hasilnya tak banyak dan tak pasti kapan akan dapat uang. Di samping upah yang tak menentu (saya teringat cerita Marsono tadi) Slamet bilang proyek konstruksi di Yogyakarta menyerap kuli sampai ke kabupaten-kabupaten jauh, seperti Magelang, Purworejo, hingga Demak. Hukum ekonomi lalu bekerja: banyak tenaga kerja, persaingan makin ketat, upah kuli makin murah. “(Kuli dari luar Jogja) dapat sembilan puluh ribu sudah bagus itu,” ujar Slamet.
Obrolan saat ngecat berlanjut bersama Marsono dan tuan rumah. Dua jam kami berbincang. Menjelang azan salat Jumat, saya berterimakasih banyak dan pamit, namun sebelumnya izin pinjam kamar mandi di rumah tersebut. Seorang penghuni rumah lain heran melihat saya.
“Lah, ini siapa?”
“Anak magang, Bu. Dari UIN, pengin tahu soal proyek,” jawab Slamet, sekali lagi untuk menghindari keruwetan.
“Di UIN ngambil jurusan apa?” tanyanya. “Kok, magangnya jadi kuli proyek?”
Saya cuma cengengesan.
Mangkal di Sor Talok Sudah Jadi Bagian dari Hidup
Selain membuntuti Marsono, kami juga ngobrol dengan kuli lepas lain bernama Rohman (55).
Rohman masih berada di pangkalan hingga pukul sebelas siang, jauh setelah Marsono pergi. Ia menyebut pangkalan ini “Depnaker”, akronim Departemen Ketenagakerjaan. Istilah “departemen” memang masih nempel di lidah orang-orang lama, dipakai puluhan tahun sampai penyebutannya diubah menjadi “kementerian” pada 2009. Selain Depnaker, orang-orang kadang juga menyebut teras toko mebel tersebut sebagai “sor talok“, frasa Jawa yang berarti ‘di bawah pohon tolok (atau gayam)’. Konon si pohon talok sudah ditebang lama dan Rohman menyaksikannya. Kami membenarkan posisi duduk dan mengawali basa-basi dengan menanyakan lamanya ia mangkal.
“Saya belum lama, di sini baru 25 tahun,” kelakarnya. Kami terkekeh.
Kata Rohman, tempat tersebut sudah ada selama puluhan tahun. Dulu sebelum ruko tersebut berganti-ganti pemilik dan direnovasi, hanya ada jalan setapak untuk mereka saat menunggu tawaran kerja. Rohman dan para kuli paruh waktu lain duduk di sana dari pukul enam pagi hingga menjelang tengah hari, mengharap seorang mandor, pemborong, juragan atau siapa saja yang sanggup membayar tenaga mereka. Kerja apa saja mereka lakukan, namun memang biasanya yang dicari khusus kerjaan kasar, seperti halnya tukang atau kuli bangunan untuk sebuah proyek. Mereka bisa bekerja sekali waktu hari itu juga atau borongan selama beberapa hari.
“Kerjaan di sini gak bisa dijagain, kalau gak dapet, ya, pulang,” kata Rohman Rohman sebelum kami sempat menanyakannya. Ia terlihat sedikit pasrah di sela-sela kisahnya.
Tanggungan keluarganya sudah tidak ada. Ia tinggal di rumah hanya bersama istri. Kedua anaknya sudah berkeluarga. Ia di rumah sendirian, sedang istrinya bekerja di tempat laundry. Daripada melamun sendiri, nongkrong dan bertemu teman-teman senasib telah menjadi keseharian kakek bercucu satu itu. Barangkali ada yang hilang dari hari-harinya jika ia sekali saja tak ke Sor Talok. Dapat tak dapat pekerjaan, Rohman akan tetap singgah, bahkan jika ia telah mendapat kerja yang jaraknya terpentang jauh, ia sengaja lewat jalan daerah Dogongan, Kalasan itu.
“Besok ke sini lagi. Nyempetin mampir,” ucapnya.
Baginya, bekerja di kota berbeda dengan di desa. Jika di kota ia bisa fokus bekerja secara penuh hingga proses pembangunan rampung, di desa pembangunan sering kali dilakukan secara bertahap karena alasan dana. Tak jarang ia disuruh untuk berhenti secara tiba-tiba. Kalau sudah demikian, ia akan mangkal lagi.
Hari saat kami datang itu terbilang sepi. Sebelum Rohman, hanya ada belasan orang yang datang lalu pergi. Ketika ramai, katanya bisa sampai tiga puluhan orang berkumpul menunggu kerjaan. Dari lipatan di pelupuk matanya, kami melihat Rohman tersenyum di balik masker yang menutupi wajahnya. Kabar baik. Menurutnya, kalau sepi, tandanya orang-orang sudah mendapat kerja. Sebagian dari mereka sengaja hanya mampir sebelum berangkat ke tempat kerja.
Meski bersedia kerja apapun, mereka memasang standar umum upah per hari, berbeda dengan mandor yang dibayar rangkap. Seorang mandor menerima gajinya sebagai kuli sekaligus sebagai pengawas yang mengarahkan tukang. Untuk pekerja biasa, paling tidak seratus ribu rupiah ditambah uang makan harus mereka peroleh selepas memeras keringat seharian. Kalau mujur, kadang mereka mendapat bingkisan sembako. Saat awal pemberlakuan pembatasan kegiatan karena pandemi pendapatan mereka juga terkena dampaknya: Upah sehari bisa turun menjadi Rp70.000. Itu belum karuan kalau dapat.
Pagi itu panas terik. Kendaraan lalu-lalang. Semua orang terlihat buru-buru, entah akan pergi ke mana. Di seberang jalan sama seperti hari-hari sebelumnya: Beberapa orang berjejer di pinggiran toko mebel. Kami sempat menunggu beberapa saat sendirian di tempat tersebut sebelum Rohman datang. Rasanya sudah seperti menanti mandor yang akan mempekerjakan kami sungguhan.
Saat kami ingin beranjak seorang laki-laki tua datang sembari menuntun sepeda ontelnya. Di tempat parkir motor kami amati jalannya santai, tak seirama dengan bisingnya mesin kendaraan diiringi klakson一yang entah memang perlu selalu dibunyikan atau si sopir saja yang latah. Sejurus kemudian ia duduk. Kami agak gamang menghampirinya, kalau-kalau ia seorang musafir yang sekadar duduk istirahat dari perjalanan yang sangat jauh, namun akhirnya kaki kami tergerak juga ketika ia menyadari keberadaan kami dan menganggukkan kepala sambil menyunggingkan gummy smile-nya.
“Riyanto. Pak Yanto, gitu saja. Orang-orang sudah tahu,” katanya dengan setengah berteriak dan melirik kami yang sibuk mencatat namanya di ponsel.

Dugaan kami keliru: Ia bukan musafir! Pria 61 tahun itu sama seperti orang-orang lain: Bagian dari sekumpulan manusia yang tiap pagi menanti rezeki. Di tengah obrolan kami baru sadar bahwa Riyanto merupakan seorang mandor. Sudah enam bulan ini ia setia bekerja untuk renovasi rumah makan bebek panggang di Jalan Pakem-Kalasan. Letak tempat kerjanya ke arah timur, sedangkan pangkalan PU ini agak ke barat. Dari rumahnya di dekat Pasar Gendeng, ia memilih belok dulu ke pangkalan karena ingin menunggu teman kerjanya berangkat.
Selama setengah tahun upahnya sebagai mandor sebesar Rp120.000 dan upahnya sebagai kuli sebesar Rp100.000. Ia pun kerap memborong tawaran dari beberapa orang. Selain menjadi tenaga untuk pembangunan, ia bertindak sebagai pengawas. Mengarahkan para tukang yang mengecor secara tidak merata, misalnya. Statusnya sebagai mandor membuat upahnya cukup tinggi dibandingkan dengan pekerja lain, bahkan sering kali ia mendapat uang melebihi standar umumnya dan dikasih bonus hingga Rp175.000. “Paling tinggi pas di Condongcatur pernah dikasih 250 sehari. Jadi, gak tentu,” ungkapnya.
Ia menceritakan tempat mana saja yang pernah digarap olehnya selama ini, mulai dari rumah, klinik, hingga toko besi, yang katanya, besar.
“Itu saya yang garap, tapi saya nyepeda terus. Ndak apa.” Cara duduknya berubah menjadi tegap. Kami mengangguk sebagai bentuk apresiasi.
Yanto memang tipikal orang tua yang masih menggunakan cara-cara lama. Ia tak punya ponsel. Tak ada cara untuk berkomunikasi dengannya selain datang langsung menemuinya. Citra “sederhana” ini juga terlihat ketika ia menolak kami sebut mandor. Meski upahnya beda, baik kedudukan mandor, tukang, maupun tenaga biasa terlihat setara baginya.
“Saya ndak mau (disebut mandor) sejak dulu. Yaudah biasa aja, dianggap sama aja seperti teman.”
Gaya bercerita Yanto yang sepotong-sepotong membuat kami seperti sedang bermain lego di kepala… atau apakah mungkin kami juga sedang menjadi pekerja konstruksi di pikiran sendiri? Kemampuannya mengarahkan sesuatu sudah terlatih. Awalnya, Yanto cerita ngalor-ngidul soal pekerjaannya, kemudian tentang bagaimana tukang yang baik, kepercayaan pemilik proyek, hingga soal upah. Semua itu kembali pada alasannya untuk kembali ke Sor Talok. Siapa sangka bahwa ternyata Yanto merupakan seorang seniman patung? Katanya, di depan rumahnya terdapat patung gajah yang ia buat sendiri. Sebelum kerja serabutan ia gemar membuat patung untuk dijual dengan harga yang beragam, namun karena pekerjaan tersebut dianggap tak punya prospek, istrinya melarang.
Percakapan kami terhenti karena kami kehabisan stok pertanyaan di kepala. Di tengah keheningan suara Yanto memelan. Ia mengungkapkan bahwa istrinya telah tiada sejak tahun lalu karena menderita sakit ginjal. Kini ia hidup seorang diri.
Pandangan Yanto menerawang jauh. Ia mengulang ucapannya bahwa ia akan kembali besok pagi pada kami sebelum akhirnya pamit pergi membawa ontel yang telah menemaninya selama empat puluh tahun.
“Sejak dulu saya di sini terus. Gak ada keperluan ke sini pun, saya akan tetap mampir.”
Reporter: Dina Tri Wijayanti dan Sidra Muntaha





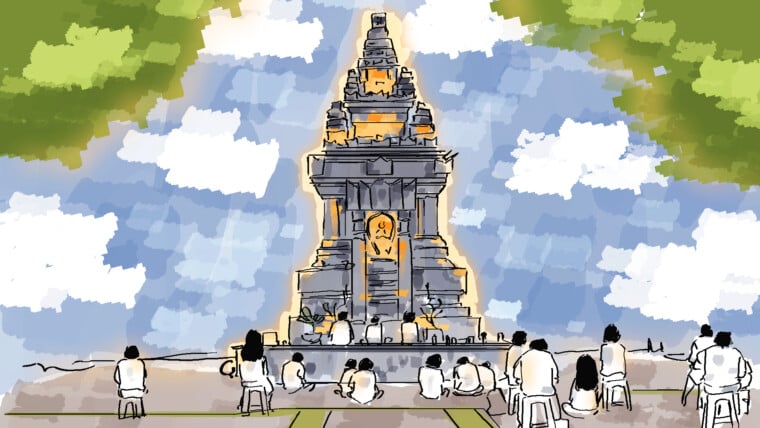



Getirnya Mahasiswa Kedokteran Hewan yang Menghilangkan Peliharaan Klien
Generasi Permen Karet Menyebalkan di Organisasi Kampus
Bukan LSM atau Start-up, Kerja di Pemerintahan yang Paling Enak
Balada Dinda-Dinda yang Punya Resting Bitch Face
Canlı Gambling Establishment Oyunları Oynayın Ve Çevrimiçi Spor Bahisleri Yapın
1xbet Giriş: En Güncel Ve Güvenilir 1xbet Linkleri Burada!
Kasino Mostbet Hrajte Nejlepší On The Web Automaty A Automaty
Best Online Internet Casinos Canada 2024 Best Sites For Canadian Players