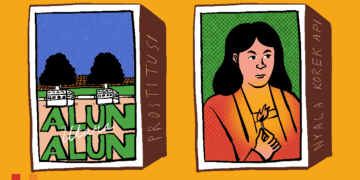Bulan lalu, Bapak pernah datang jauh-jauh dari Semarang ke Yogyakarta untuk potong rambut di bawah beringin atau sor ringin pojokan Alun-alun Utara, katanya ingin nostalgia. Saya yang mengantarkan dan sekaligus berkenalan dengan pencukurnya takjub. Sudah hampir lima tahun lamanya saya tinggal di kota ini dan hampir setiap hari melewati kawasan tersebut, tapi baru kemarin saya tahu jika masih ada profesi pencukur di tempat itu.
***
Sore itu, jalanan di sekitar Alun-alun Utara Yogyakarta tampak ramai. Mobil berplat luar kota melenggang dengan kecepatan rendah untuk menikmati suasana alun-alun di sore hari. Saya berada di belakang mobil-mobil itu, melesat dengan buru-buru sambil sesekali membunyikan klakson ketika ada mobil memarkirkan diri tanpa aba- aba.
Perlahan, saya mengurangi kecepatan motor ketika sampai pada sebuah bangunan lama nan usang. Di sekitarnya masih banyak becak-becak mangkal. Lokasi bangunan ini kira-kira di sebelah barat alun-alun.
Saya memarkirkan motor di pinggir, lalu berjalan menuju seorang pria yang sedang duduk di bawah pohon beringin besar dengan kursi plastik. Di sampingnya terdapat sebuah koper jinjing dan cermin yang telah digantung pada pagar bangunan lawas Persaudaraan Djamaah Haji Indonesia (PDHI).
Aminudin namanya, bisa dibilang ia adalah generasi terakhir jasa potong rambut bawah pohon beringin atau sor ringin di Alun-alun Utara Yogyakarta. “Panggil aja Udin,” ucapnya (14/02/21).
Kalau dulu, Udin sering mangkal di beringin dekat pagar yang kini menjadi rumah makan spesial menu serba bakar. Berjejer mengelilingi sisi barat laut alun-alun bersama 4-5 kawan lainnya. Tapi sekarang, tinggal Udin seorang.
Udin menghisap sebatang rokok di tangan kirinya pelan, matanya ikut terpejam menikmati asap-asap tipis yang memasuki rongga paru. Pria yang telah berumur 53 tahun itu duduk menghadap alun-alun yang mulai macet, maklum jam pulang kerja. Ia biasa mulai beraktivitas pukul 08.00 dan pulang di sekitar pukul 17.00 WIB.
“Dulu kami di sini, berempat. Meninggal satu, terus ada satu orang tukang cukur dari Alun-alun Selatan. Belum lama menetap di sini, meninggal lagi,” ucapnya mengawali obrolan kami.
Saya duduk di sebelah Udin, ikut mengamati mobil dan motor yang tak jarang saling beradu klakson. Beberapa orang juga tampak lalu lalang melintasi trotoar untuk sekadar lari sore.
“Terus yang dua kemana, Pak?” pandangan saya beralih ke Udin yang masih asyik menghembuskan kepulan asap tembakau ke udara.
“Berhenti. Kalau saya nggak salah info, ada yang sakit dan ada yang buka usaha laundry di rumah,” kata Udin.

Berawal dari autodidak
Sebenarnya, Udin sendiri tak menyangka jika jalan hidupnya akan menjadi tukang cukur rambut jalanan. Puluhan tahun lalu, ketika Udin masih remaja, mungkin umur sekitar 15-an tahun, ia bekerja serabutan melalui program padat karya dari pemerintah.
Banyak orang kampung yang belum bekerja diarahkan untuk menjadi sumber tenaga dalam upaya pembangunan. Termasuk Udin. Pada saat itu, ia dan beberapa teman kampungnya dikerahkan untuk membangun gorong-gorong yang sekarang berada di dekat Stasiun Lempuyangan.
Selang beberapa hari bekerja, Udin merenung sambil mengelap buliran keringat di jidat. Teman- teman di hadapannya dengan lahap menyantap nasi sop porsi besar beserta satu kerupuk jatah makan siang. Udin memasukan perlahan suap demi suap. Seketika sebuah pikiran melintas di kepalanya: Manusia tumbuh semakin tua, sementara kehidupan akan tetap sama. Uang masih dibutuhkan untuk mendapat sesuap nasi.
Udin ragu jika hanya mengandalkan kekuatan otot, padahal umurnya akan selalu bertambah. Tubuhnya akan renta dan mungkin tenaga yang dimiliki tak sekuat saat muda. Kalau sudah begitu, bisa apa lagi untuk cari uang?
Pria di sebelah saya menoleh dan tersenyum, menampilkan deretan gigi yang masih rapih.
“Saya coba cari dan cari mau belajar apa. Tiba-tiba saya kepikiran potong rambut, soalnya dulu saya suka ngamatin tukang cukur. Kalau selesai cukur, nggak pernah langsung pulang. Pasti saya amati dulu caranya,” ujar Udin.
Akhirnya, rupiah demi rupiah hasil upah dari program padat karya ia kumpulkan. Sedikit demi sedikit Udin mampu membeli peralatan cukur. “Awalnya saya cuma beli gunting, besoknya kursi plastik. Dapet upah lagi, baru saya belikan cermin, alat cukur manual, sampai kain penutup,” ia terkekeh, walaupun saat itu ia belum bisa apa-apa, tapi yang terpenting punya barangnya dulu.
Beberapa teman dekat Udin diundang ke rumah untuk potong rambut gratis sekaligus jadi percobaan Udin. Temannya senang-senang saja, karena bisa berhemat. Waktu itu, hasilnya lumayan walaupun belum sempurna. Tentu masih banyak kesalahan, tapi tak pernah membuat Udin putus asa.
“Walaupun saya sempat ragu mau melakoni pekerjaan ini. Kalau saya salah cukur, ya udah. Nggak pernah bisa di hapus atau di Tipp-Ex kayak tulisan. Masa mau disambung dan tempel lagi rambutnya?” Udin tertawa kecil. Matanya terus memandang lurus, langit mulai menggelap. Orang-orang yang tadinya lari sore, sudah tak terlihat lagi.
Berpindah dari jalan ke jalan, kios ke kios
Beberapa waktu kemudian, Udin sendiri lupa tahun kapan. Yang jelas, saat tarif parkir masih 100-200 perak, pokoknya sudah lama sekali. Ia pun mulai memberanikan diri membuka lapak cukur untuk mencari pundi-pundi rupiah.
“Lapak pertama saya di sekitaran Mandala Krida. Pinggir jalan,” kata Udin. Berbekal kursi plastik, cermin gantung, dan tas berisi peralatan cukur. Ia membuka lapak di atas selokan yang telah ia beri bambu-bambu sebagai jembatan kecil.
Sebagai orang yang baru belajar alias newbie dalam jasa potong rambut, lapak yang dibuka merupakan hal ternekat sepanjang sejarah hidupnya. Apalagi lapak pinggir jalan, banyak orang lewat yang bisa menonton. Jika ia membuat kesalahan, hancur lah sudah karir barunya sebagai pencukur rambut.
Maka dari itu, Udin selalu mencoba fokus setiap melayani potong rambut para pelanggan yang datang. Tarifnya hanya dipatok sebesar 1.000-1.500 rupiah.
“Waktu itu ya deg-degan, takut salah potong. Sering dilihatin orang-orang lewat, tapi percaya diri aja,” Udin tertawa kecil.
Sampai pada suatu ketika, dirinya didatangi oleh ibu-ibu yang baru saja turun dari bus. Ibu itu menghampiri Udin yang sedang mengobrol dengan tukang becak di lapak kecilnya.
“Ternyata saya ditawari pekerjaan di kios cukur miliknya, tapi sempat saya tolak,” ujarnya. Sebelum saya mengernyit dan mengeluarkan kata mengapa, Udin langsung buru-buru menyelesaikan perkataannya.
“Saya kan nggak pede, Mbak. Baru aja belajar, nanti kalo salah cukur malah bikin jelek nama kios mereka,” ujar Udin lagi.
Tapi, ibu itu ngotot dan selalu membujuk Udin. “Tidak apa-apa. Di sana bisa belajar, daripada kios kami kosong,” ucap Udin sambil menirukan ucapan perempuan itu berpuluh tahun silam

Udin pun menyerah dan mengiyakan, walaupun masih ada rasa takut-takut. Tapi, siapa tahu ini merupakan lapak rezeki baru bagi Udin.
Pria yang sekarang tinggal di Jl. Tukangan itu menoleh ke saya, melirik kanan-kiri seperti mengawasi situasi. Tiba-tiba ia membisikan kalimat dengan nada sangat pelan, “Tapi mereka kayak kompeni, saya gak betah,” ia langsung terkekeh sambil meletakan sisa puntung rokoknya ke meja kecil di sebelah.
Saya ikut tertawa kecil mendengar perkataannya. Banyak kejadian tidak enak yang membuat Udin berulang kali menahan jengkel. Sampai-sampai, ia kena marah karena terlambat datang barang lima menit saja, padahal saat itu Udin harus mengantarkan istrinya ke rumah sakit.
“Saya kena marah cuma karena telat 5 menit. Padahal saya sering pulang molor karena meladeni pelanggan yang datang waktu kios sudah tutup,” ujar Udin. Setelah itu, ia memutuskan untuk keluar dari kios cukur, dan pindah ke kios lainnya.
Beberapa kali Udin pindah dari kios ke kios. Kios terakhir terletak di dekat Terminal Jombor. Pemilik kios tersebut sangat baik, makan pun selalu diberikan pada Udin. Tapi sayangnya, kios cukur tempat Udin bekerja selalu sepi.
“Saya nggak enak hati karena dikasih makan terus tanpa ngasih pendapatan. Saya sendiri pun butuh uang, akhirnya keluar lagi,” ujarnya.
Sampai di rumah, Udin bercerita pada sang istri yang dua tahun lalu baru saja meninggal akibat stroke. Istri Udin lah yang menyarankan untuk ikut buka di jalanan alun-alun saja. Awalnya, sempat ragu karena sudah banyak lapak cukur rambut di sana. Tapi, sebuah kalimat ajaib keluar dari mulut sang istri: “kamu tau pasar nggak? Ada berapa banyak pedagang di sana? Tenang, rejeki ada yang ngatur,” kata Udin menirukan kata-kata istrinya di tahun 2002.
Mendengar itu, Udin langsung yakin membuka lapak kecil di Alun-alun Utara dan bertahan hingga sekarang.
Hanya Udin, tukang cukur yang masih bertahan di Alun-alun Utara
Masih tergambar jelas di benak Udin, suasana alun-alun pada zaman dulu sangat berbeda dengan sekarang. Saat ini, mobil-mobil bergiliran menimbulkan kemacetan serta keriuhan klakson karena jalanan yang cukup sempit. “Kalau zaman dulu boro-boro, lihat mobil mungkin bisa dihitung jari. Paling-paling hanya motor. Sisanya mungkin sepeda, becak, ataupun andong. Damai, tanpa bising,” ujar Udin.
Tahun ini tepat dua puluh tahun lamanya, Udin menelateni pekerjaan sebagai cukur rambut sor ringin di Alun-alun Utara.
Tak pernah disangka Udin, jika dialah yang kini menjadi satu-satunya penerus jasa potong rambut sor ringin. Bagi Udin, profesi ini tidak hanya tentang beringin sebagai simbol. Melainkan, mempertahankan kesederhanaan dan ciri khas bagi para pelanggannya.
Memang, kebanyakan pelanggan Udin berasal dari kalangan berumur, minimal sudah bapak-bapak. Tapi, tak jarang juga anak-anak muda ikut merasakan keterampilan Udin dan sensasi cukur rambut dengan angin sepoi-sepoi.
“Cuma sepuluh ribu, atau kalau dirasa kemahalan bagi beberapa kalangan. Saya nggak masalah kalau dibayar kurang dari itu,” ucap Udin. “Tapi kalau dibayar lebih juga nggak papa,” lanjutnya terkekeh. Udin mengatakan, setiap hari ada saja pelanggan yang datang minta dicukur. Berapa orang persisnya, Udin menggeleng.
“Nggak tentu, tapi ada saja,” katanya. Selain cukur rambut, Udin juga melayani cukur kumis. Harganya tetap sepuluh ribu saja, sudah paket lengkap.

Memberi jasa potong rambut di tempat terbuka, tentu saja ada risikonya. Kalau hujan atau bahkan sekadar gerimis, maka bubar dengan dengan sendirinya. Makanya usahanya sering disebut juga cukur rambut misbar alis gerimis bubar. Lalu bagaimana, kalau sedang mencukur kemudian hujan, maka biasanya akan berteduh dulu.
Namun, ada satu pengalaman yang membuatnya tertawa saat sedang bekerja, hujan turun. Ia sudah siap berteduh, tapi pelanggannya minta ia tetap melanjutkan pekerjaannya. “Alesannya dia belum mandi,” katanya tertawa. Jadilah ia dan pelanggannya basah kuyup. Biasanya begitu hujan, pelanggannya langsung lari berteduh di bangunan PDHI, Udin akan melanjutkan pekerjaanya di gedung itu sampai tuntas.
Pengalaman tak terlupakan dipanggil memotong rambut lansia
Udin tiba-tiba berdeham, pandangannya lurus kepada seorang kakek di hadapan kami. Badannya telah bungkuk, berjalan tertatih-tatih dengan tongkat. Saya ikut memperhatikan dengan saksama sambil mengernyitkan dahi. “Kenapa Pak?”
Rupanya Pak Udin teringat pada sebuah peristiwa. Kata pria lulusan SMP itu, ia juga melayani cukur rambut panggilan, seperti event ataupun untuk mendatangi rumah pelanggan. Yang paling sering ialah diminta datang langsung ke rumah langganan, biasanya lansia yang sudah tak mampu berjalan, takut bonceng, dan hal lain yang menjadi halangan tak bisa datang langsung ke lapak.
“Saya pernah disuruh datang ke rumah Mbah-mbah, dia sudah tua,” ujarnya.
Saat dirinya datang, simbah mempersilahkan Udin untuk masuk. “Eh wis teko yo, Le (eh udah dateng ya)?” ucap simbah waktu itu.
Udin mengangguk sembari mempersiapkan peralatan yang masih tersusun rapi di dalam koper. Simbah masih duduk di atas kasur, ia meminta Udin untuk mempersiapkan segalanya dulu.
“Tak enteni karo turon sik yo, Le (aku tunggu sambil tiduran ya, nak),” awalnya Udin bingung dengan ucapan simbah, tapi akhirnya diiyakan.
“Dalam hatiku ya gakpapa, kan masih ada beberapa menit buat aku nyiapin semua alat,” Udin tersenyum lebar. “Tapi setelah beres. Simbah malah tidur beneran. Kata anaknya suruh datang besok lagi aja atau nanti dipanggil lagi, yasudah aku pulang,” lanjut Udin.
Namun, keesokan harinya. Udin tak kunjung dipanggil kembali oleh anak simbah itu. Ia pun tak mempermasalahkan itu dan kembali beraktivitas seperti biasa di pinggir alun-alun. Barulah beberapa hari kemudian, anak simbah datang.
“Saya kira disuruh ke rumahnya. Ternyata dikabarin, kalau simbah meninggal setelah ia pamit ke saya untuk tidur,” ujar Udin. Senyumannya berubah masam.
Saya diajak Udin untuk beranjak dari kursi kami menuju trotoar tempat Udin meletakan koper alatnya yang belum dibereskan. Jam menunjukan pukul lima sore, dan Udin bergegas menutup kopernya sebelum hari makin gelap.
Reporter: Rahma Ayu Nabila
Editor. : Agung Purwandono
BACA JUGA Jamu Jun Wijoyo, Jamu seperti Bubur, Sumber Vitamin Pejuang Kemerdekaan dan liputan menarik lainnya di Susul.