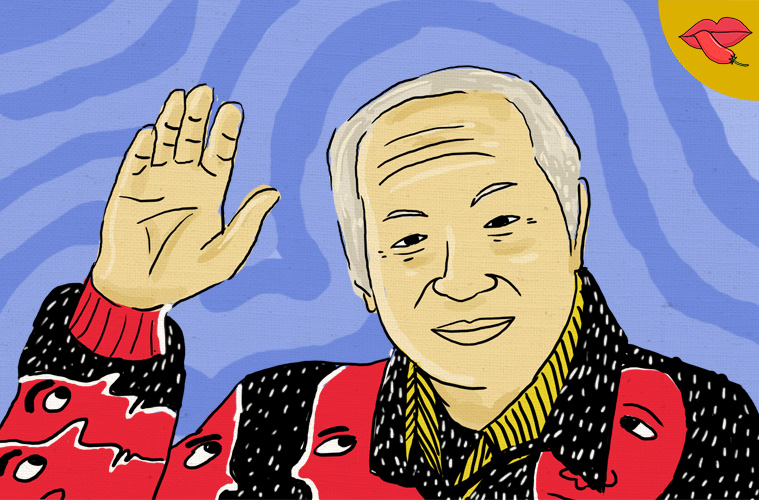Tahun 1990. Saya melakukan riset untuk skripsi saya. Topiknya agak nyentrik untuk ukuran waktu itu. Saya meneliti para jenderal yang tidak puas dengan pemerintahan Soeharto. Perlu diingat, saat itu adalah saat Soeharto berada dalam puncak kejayaannya.
Tentu ini adalah pekerjaan yang sedikit menyerempet bahaya. Jenderal-jenderal ini adalah musuh politik Soeharto. Dan, siapa pun tahu bahwa Soeharto adalah “raja tega” kalau berurusan dengan musuh-musuh politiknya.
Mereka semua berkumpul dalam kelompok yang bernama Petisi 50. Ini adalah kumpulan lima puluh orang elite sipil dan militer (termasuk polisi). Mereka adalah oposisi elitis. Tidak ada akar mereka ke bawah. Bahkan, menurut saya, secara ideologis mereka tidak banyak berbeda dengan Orde Baru.
Para jenderal yang tergabung dalam kelompok ini pada umumnya adalah generasi ‘45. Mereka masih satu generasi dengan Soeharto. Mereka juga mengalami revolusi dan perang kemerdekaan. Itulah sebabnya mereka masih punya ideal. Atau paling tidak mereka masih merasa bahwa mereka ikut mendirikan republik ini.
Orang seperti Ali Sadikin misalnya, ingin sebuah sistem seperti Orde Baru tapi lebih adil dan efisien. Saya tidak bisa menyingkirkan ingatan saya akan Bang Ali kalau saya melihat Ahok. Karakter kedua orang ini sangat mirip: tegas, kasar, efisien, namun pada satu titik punya prinsip moral yang kuat.
Saya pernah dibentak oleh Bang Ali ketika pertanyaan saya dianggapnya melecehkan dirinya. Namun, sesudah interview, dia tahu saya mahasiswa miskin. Dia menawarkan “uang taksi” yang saya terima dengan terpaksa karena tidak ingin menyinggungnya.
Ego Bang Ali sangat kuat. Saya ingat ketika itu dia baru punya bayi. Dia menikah lagi setelah istri pertamanya meninggal dunia. Dia dengan bangga menunjukkan foto bayinya kepada saya seraya menyuruh saya membandingkan dengan tetangganya di seberang Jalan Borobudur, tempat tinggalnya.
Tetangganya itu juga seorang laksamana yang jadi pembantu dekat Soeharto. Dia juga baru kawin dengan seorang yang jauh lebih muda dan jadi sensasi di surat kabar. “Lu bandingin deh ama gue. Apa dia masih bisa ng@#ng …. Jelek-jelek gini, gua masih bisa bikin bayi,” katanya. Memang saat itu Bang Ali masih tegap, sehat, dan badan kekar terpelihara. Kentara kalau dia melakukan olahraga dengan teratur.
Petisi 50 adalah kelompok yang berisi berbagai macam karakter. Di sana ada H.J.C. Princen, seorang pejuang HAM. Ada Chris Siner Keytimu, mantan ketua PMKRI, yang sederhana namun jernih dalam berpikir. Ada Jenderal Polisi Hoegeng yang selalu tampak ceria dengan wajah tanpa dosa. Tetapi, ada pula jenderal yang bergabung hanya karena kecewa proyek-proyeknya tidak jalan.
Semua penanda tangan Petisi 50 mengalami apa yang mereka sebut sebagai “kematian perdata”. Akses mereka terhadap ekonomi ditutup sama sekali. Banyak dari mereka tidak bisa hidup sehingga akhirnya meminta maaf dan menyembah-nyembah kepada Soeharto. Saya masih ingat cerita Bang Ali bagaimana seorang jenderal bahkan tidak bisa memperbaiki giginya karena tidak ada biaya untuk ke dokter gigi.
Salah satu pertemuan yang mengesankan adalah di rumah Jenderal Hoegeng. Dia terkenal sebagai jenderal yang senang musik. Acara Hawaiian Music-nya di TVRI cukup terkenal sebelum dia dilarang tampil karena terlibat dalam Petisi 50.
Di rumah Jenderal Hoegeng itu saya berkenalan dengan beberapa jenderal militer lain. Umumnya mereka sudah berumur. Namun, semangatnya masih membara. Ketika itulah untuk pertama kali saya mendengar lagu “The Impossible Dream (The Quest)”. Lagu inilah yang menyadarkan saya akan perbedaan antara jenderal-jenderal ini dengan jenderal-jenderal yang berada di sekeliling Soeharto.
Jenderal-jenderal oposan ini jelas tampak lebih “westernized” ketimbang jenderal-jenderalnya Soeharto. Banyak di antara mereka yang dididik KNIL. Mereka juga punya akses ke bacaan-bacaan Barat. Juga ke kebudayaan Barat. Mereka memandang rendah orang seperti Soeharto—dan terutama kecenderungan kejawennya. Beberapa dari mereka juga berasal dari kultur santri (seperti Letjen M. Jassin, mantan Pangdam Brawijaya).
Namun, kecenderungan Barat ini sangat kental, setidaknya dari mereka yang berkumpul di rumah Hoegeng. Saat itu mereka bersama-sama menyanyikan lagu, yang kemudian sangat mewakili karakter mereka.
Lagu “The Impossible Dream (The Quest)” digubah oleh Mitch Leigh dan liriknya diciptakan oleh Joe Darion. Lagu ini menjadi sangat populer karena film Man of La Mancha dan sebelumnya ada juga drama musikal dengan judul yang sama dipentaskan di Broadway.
Lagu ini bercerita tentang sikap ksatria. Tekad untuk (seperti liriknya) “mengalahkan musuh yang tak terkalahkan, menanggung derita yang tak tertanggungkan, berlari ke mana si pemberani pun tidak berani pergi, memperbaiki hal tidak bisa diperbaiki”.
Ia bicara tentang integritas sebagai manusia. Ia percaya akan bisa melakukan hal yang muskil untuk dilakukan. “Mengikuti sebuah bintang. Seberapa pun muskilnya. Seberapa pun jauhnya. Berjuang untuk sebuah hak. Tanpa bertanya atau berhenti.”
Puncaknya adalah, saya kira, “Bersedia untuk berbaris ke neraka untuk tujuan-tujuan surgawi” (To be willing to march to hell for heavenly causes).
Saya tiba-tiba teringat akan Petisi 50 dan lagu ini karena saya membaca berita tentang Panglima TNI yang menyebut demokrasi kita sekarang ini tidak sesuai dengan Pancasila. Demokrasi yang diinginkan oleh Jenderal Gatot Nurmantyo itulah yang mematikan secara perdata dan politik jenderal-jenderal senior yang saya temui pada tahun 1990 itu.
Kenyataan ini juga membuat saya tersadar. Ada sesuatu yang hilang dari semua elite politik—baik sipil maupun militer–saat ini. Kita tidak punya elite yang punya integritas, mereka yang punya prinsip, punya keyakinan moral, dan bersedia berkorban untuk keyakinannya tersebut.
Yang kita miliki adalah para elite yang sangat oportunistis. Mereka siap menggadaikan karakternya untuk kekuasaan besar dan kecil. Karena tidak punya karakter itulah mereka memasang foto dirinya di setiap persimpangan jalan. Pajangan yang menjijikkan itu kita lihat di setiap kota di Indonesia.
Kita banyak punya politisi—sipil dan militer—yang rajin menawarkan surga kepada rakyat. Namun, kita tidak punya satu pun politisi sipil atau perwira militer yang bersedia “berbaris ke neraka untuk memperjuangkan tujuan-tujuan surgawi.”