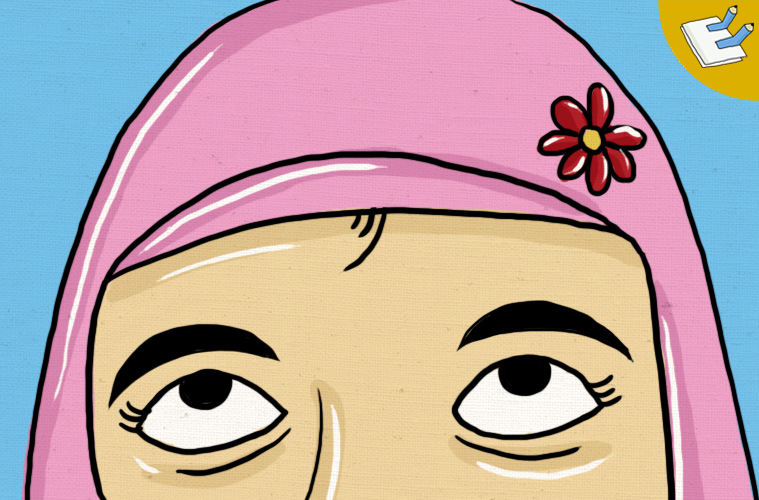Pengantar: esai ini menanggapi esai Azis Anwar Fachrudin berjudul “Mengapa Rambut Perempuan Muslim Dianggap Aurat?”.
Perintah mengulurkan (memanjangkan) jilbab memang benar ada dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab: 59.
“Hai, Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan wanita-wanita orang mukmin agar mereka mengulurkan atas diri mereka jilbab mereka. Itu menjadikan mereka lebih mudah dikenal sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”
Sebelum masuk lebih jauh, mari maklumi bahwa dalam tradisi metodologi tafsir Al-Quran (termasuk berbagai disiplin ilmu yang meliputinya seperti ushul fiqh [ilmu hukum Islam]) dalil-dalil yang tekstualnya terang (syarih) seperti ayat tersebut tidak otomatis hanya punya satu arti. Ia tetap terbuka kepada ragam penafsiran. Contoh lainnya ialah ayat “pencuri hendaklah dipotong tangannya …” yang pada masyarakat kita diwujudkan dalam bentuk hukuman penjara.
Tuturan Azis Anwar Fachrudin menarik untuk “dilengkapi” dalam penalaran yang lebih jauh dengan melihat konteks historisnya (bukan melulu asbabunnuzul ya). Apakah rambut muslimah merupakan aurat yang harus ditutupi karena didasarkan pada Al-Ahzab: 59 tersebut?
Pertama-tama, mari mafhumi bahwa peta metodologis ta’abbudiy (hukum fikih yang tidak bisa dijelaskan alasan rasionalnya) dan dan ma’qulatul-ma’na (hukum fikih yang bisa dijelaskan alasan rasionalnya) sudah sangat problematis pada dirinya sendiri.
Setahu saya, Abdul Wahhab Khallaf (pakar ushul fiqh dari Mesir) tidak menggunakan dikotomi tersebut. Kita bisa bertanya, misal, apa ada hukum fikih yang tidak mengandung filosofi makna untuk dinalar secara rasional? Jangankan urusan rambut dan jilbab, bukankah ‘ibadah mahdhah (ibadah yang murni ritual) macam salat dan puasa pun sangat bisa dijelaskan pretensi-pretensi logis atau illat al-hukmi-nya?
Untuk alasan itu, saya pribadi kurang sependapat dengan penggunaan dikotomi ta’abbudiy dan ma’qulatul-ma’na tersebut.
Urusan wajib tidaknya menutup rambut bagi muslimah bisa dijelaskan alasan-alasan rasionalnya—Aziz menyebutnya berada di wilayah abu-abu antara ta’abbudiy dan ma’qulatul-ma’na. Sangat terang bahwa esensi hukum (maqashid al-syari’ah) keauratan rambut bertalian erat dengan aspek interaksi sosial antar-nonmuhrim. Itu artinya muamalah (hukum yang mengatur urusan kemasyarakatan; perdata).
Oleh karena soal rambut sebagai aurat adalah soal muamalah, muskil memahaminya tanpa memahami nalar historis masing-masing masyarakat yang menerapkannya beserta ruang dan waktu ia diterapkan.
Buktinya bisa dicek pada Surah An-Nur: 31, yakni “… janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak padanya ….”
Kita bisa bertanya, perhiasan yang biasa tampak itu meliputi apa saja? Apakah termasuk suara, rambut, postingan? Lalu menurut siapa? Konteks yang bagaimana? Di masa yang seperti apa? Di tempat yang mana?
Historis di sini bukan melulu sejarah masa lalu, tetapi juga sejarah masa kini. Historisitas adalah kompleksitas masa lalu, masa kini, dan di sini sehingga aspek-aspek kultural, tradisi, adat istiadat, dan tata nilai suatu masyarakat yang khas tak bisa diwafatkan sama sekali.
Secara asbabunnuzul, Al-Ahzab: 59 turun setelah datangnya pengaduan Saudah (salah seorang istri Rasulullah yang berbadan besar sehingga mudah dikenali) bahwa ia baru saja ditegur Umar bin Khattab karena keluar rumah. Rasulullah berkata bahwa ia diperbolehkan keluar rumah untuk suatu keperluan. Lalu turunlah ayat tersebut.
Dalam riwayat lain disebutkan bahwa istri-istri Rasulullah keluar rumah untuk buang hajat, lalu diganggu kaum munafik, kemudian turunlah ayat tersebut.
Ada satu alasan masa lalu lagi yang disebutkan oleh Prof. Quraish Shihab dalam kitab Tafsir Al-Mishbâh (juz 10 halaman 532), yakni ayat tersebut turun setelah turunnya ayat-ayat yang melarang siapa pun mengganggu dan menyakiti Rasulullah beserta kaum mukminin dan mukminat.
Jadi, alasan historis pertamanya: Al-Azhab: 59 tersebut ditujukan sebagai identitas sosial bagi kaum muslimah masa itu agar mereka tidak diganggu.
Menurut Quraish Shihab, muslimah, nonmuslimah, juga kaum budak perempuan sata itu lazim menggunakan jilbab (penutup kepala). Ini tertangkap pada kata tudni (arti asalnya ‘memakai’), yang dalam ayat itu dibahasakan dengan yudnina (‘mengulurkan kepada tubuh perempuan’). Agar menjadi ada ciri tegas untuk membedakan muslimah merdeka dari kaum budak dan non-muslimah, perintah “mengulurkan” jilbab (ingat, penggunaan jilbab sudah lazim) memenuhi kebutuhan riil masa dan keadaan tersebut.
Kedua, ente tahulah betapa orang Arab memiliki parameter tentang sesuatu yang “menggoda” yang berbeda telak dari kita. Bagi kita hari ini, melihat rambut AwKarin bukanlah masalah. Sementara orang Arab, jangankan melihat rambut AwKarin, lihat akunnya saja langsung njengat. Jangankan lihat betis Ken Dedes, dengar suara Kalis Mardiasih saja sudah menuding langit. Sudah pasti Agus Mulyadi tidak memiliki kahanan psikis demikian, sebab Agus orang Magelang, bukan Najd.
Inilah realitas psikososial yang tidak sama antara kita dan orang Arab. Psikososial suatu masyarakat terbentuk oleh habitus yang khas, unik, dan tidak mondial. Lelaki Arab adalah lelaki Arab. Lanang Bantul adalah lanang Bantul.
Maka, bisa dimafhumi pandangan Ibn ‘Asyur bahwa soal model jilbab diserahkan kepada selera masing-masing individu (yang kemudian menyesuaikannya dengan situasi psikososial tempatnya berada). Tidak baku dan saklek sepanjang tujuan Al-Ahzab: 59 (“… sehingga mereka tidak diganggu”) tercapai.
Ketiga, menarik untuk melengkapi kajian tematik (maudhu’i) ini dengan Surah An-Nur: 31 (ayatnya panjang) pada bagian “… janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak padanya …”. Lengkapi pula bagian ini dengan ayat lain tentang menutup dada.
Dalam tatanan psikososial kita kini, penandaan perempuan muslimah dengan hijab dengan tujuan “sehingga mereka tidak diganggu” sudah bukan masalah lagi. Bila orang Arab langsung ngaceng ketika melihat rontokan rambut di antara pasir-pasir sehingga kemudian rambut menjadi bagian dari “perhiasan kecuali yang biasa tampak darinya”, pada masyarakat kita, itu tidak berlaku.
Saya tidak menyatakan rambut bukanlah aurat. Yang saya hendak katakan, ngaceng karena melihat rambut itu sungguh keterlaluan.
Di zaman kita, cakupan psikososial tentang “jangan menampakkan perhiasan” itu bukan lagi perihal rambut atau gemerincing gelang-gelang, melainkan kerapian menutup tubuh dari potensi imaji-imaji sensualitas. Jilboob, misalnya, jika dikembalikan kepada pencapaian “sehingga mereka tidak diganggu” akan menjadi contoh busana syar’i yang tidak syar’i sejak dalam pikiran karena gagal mengemban amanah proteksi atas imaji berahi. Ia berhasil secara formal, tetapi gagal secara psikososial.
Dalam contoh lain, boleh jadi ada seorang muslimah yang berjilbab dengan baik (panjang, menutup dada dan punggung), tetapi gagal mengemban amanah maqashid al-syari’ah itu karena memposting foto-foto selfie dengan bibir nyether, mecucu, sehingga membuatnya “diganggu” dengan cara dijadikan objek imajinasi oleh para jones. Ini pun bagian dari syar’i yang tidak syar’i sejak dalam pikiran. Ia berhasil secara formal, tetapi lagi-lagi gagal secara esensial.
Saya pribadi bisa memafhumi muslimah yang tidak mengenakan jilbab tapi berhasil merawat spirit “sehingga mereka tidak diganggu” dan “janganlah menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa tampak darinya” atas dasar psikososial kita. Memafhumi bukan berarti membenarkan, sebab saya pribadi mengajarkan kepada anak dan istri untuk berjilbab sebagai langkah preventif (tahtit) yang saya yakini lebih mumpuni dalam menggaransi pencapaian “sehingga mereka tidak diganggu” tadi. Bila ada orang lain yang tidak sama langkah dengan saya, niscaya saya akan memafhuminya.
Di atas semua wacana tersebut, jangan lupakan ayat ke-30 dari Surah An-Nur.
“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya ….”
Berhentilah hanya menuntut kaum Hawa menutupi rambutnya berdasar Al-Ahzab: 59 itu, menuding rambut mereka membuatmu ngaceng. Ibda’ binafsik, ‘mulailah dari dirimu sendiri’. Dengan cara mata jangan jelalatan, titit jangan sembrono.
Jika demikian, niscaya semua akan baik-baik saja.