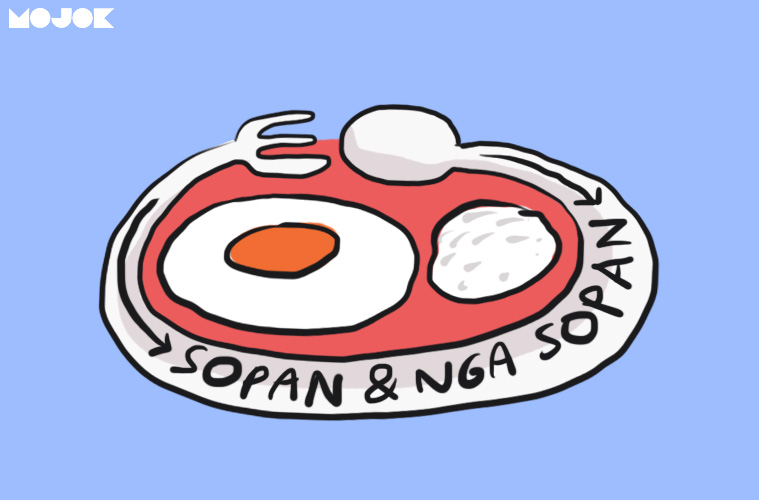Bagaimana cara makan yang (dianggap) baik dan sopan? Apakah makan dengan bersuara berkecap dianggap tidak sopan dan tidak baik? Dan darimanakah asal-usulnya, makan yang dikunyah dengan bibir tertutup kemudian dianggap sopan dan baik? Siapa yang mengukur sopan atau tidak, dan apa pentingnya?
Suatu hari saya menanyakan hal itu kepada Remy Sylado di dalam mobil, sepulang kami dari rumahnya di Darmaga, Bogor. Saya bercerita tentang seorang teman yang punya kebiasaan makan sembari mulutnya berbunyi “cap, cap…” Kadang malah berdahak. Saya tidak menyebut teman itu tidak sopan kecuali saya hanya merasa terganggu. Seperti mendengar sesuatu yang meruntuhkan selera makan.
Saya memang punya pengalaman pahit dengan makan berkecap. Dulu sekali, saya pernah disiram air minum oleh bapak hanya karena saya makan berkecap. Saya kaget. Mungkin juga menangis. Acara makan menjadi tegang. Malam itu, bapak bilang: “Makan sambil berkecap itu tidak sopan. Seperti anjing.”
Bapak memang keras mengajarkan adab. Saya, kakak dan adik saya selalu diajar oleh bapak untuk makan dengan tidak mengeluarkan suara dari mulut setiap kali makan bersama di meja makan sehabis maghrib. Kami juga diajar agar tidak meletakkan siku di atas meja makan dan hanya mengambil makanan yang terdekat dari tempat duduk kami. Kalau hendak mengambil makanan yang tidak terjangkau, bapak mengajarkan untuk menunggu orang yang dekat dengan makanan itu selesai mengambilnya, dan setelah itu baru meminta tolong untuk mendekatkannya ke kita.
Ketika saya punya anak, saya mengajarkan apa yang diajarkan oleh bapak saya kepada anak saya, setiap kali kami makan bersama. Tapi tak pernah saya menyiram air ke muka anak saya. Setiap kali makan, saya hanya bilang, “Bila kamu makan sama papa dan mama, kamu boleh makan dengan cara sesukamu. Tapi kalau makan bersama teman-temanmu dan di tempat umum, tolong katupkan mulutmu agar tidak bersuara, karena bisa mengganggu orang lain.”
Lalu Remy bercerita, dalam konteks Indonesia, makan dengan mengatupkan dua bibir adalah ajaran Belanda. Belanda mengajarkan hal ini kepada kalangan keraton lengkap dengan tata cara makan di meja makan seperti tidak boleh meletakkan dua siku di atas meja makan. Begitulah adab makan yang bescheiden. Itu sebabnya, keraton kemudian menganggap diri mereka adalah kalangan yang menjunjung etiket dan kesopanan, dan di luar mereka adalah golongan yang orang-orang yang tidak beretiket.
Ketika Jepang datang, mereka melakukan sebaliknya: makan dengan berkecap. Orang-orang Jepang makan seperti itu terutama untuk menghormati orang. Hendak memberitahu: makanan yang dimakan sungguhlah enak. Cara itu, tentu saja berkebalikan dengan ajaran Belanda yang menganggap makan sambil berkecap adalah cara makan orang-orang bar-bar. Dianggap tidak met goede manieren.
Dalam perkembangannya, ajaran Belanda itulah yang lebih banyak digunakan sebagai standar cara makan yang baik dan sopan. Masyarakat internasional pun (termasuk Jepang), menyepakati: makan yang tidak mengecap itulah cara makan yang baik dan sopan.
Kesopanan memang relatif. Sopan di suatu tempat, bisa sangat tidak sopan di tempat lain.
Orang Belanda menganggap bersendawa di tempat umum sangat tidak sopan. Di Indonesia, berkentut di tempat umum bisa ditertawakan dan dianggap tidak sopan. Banyak orang menganggap meludah sembarangan sangat tidak sopan, tapi di Cina, orang-orang biasa meludah di warung makan. Di Rusia, tersenyum pada orang yang tidak dikenal bisa dianggap tertarik secara seksual. Tabu melambaikan tangan di Korea Selatan kecuali hendak memanggil anjing. Melangkahi kaki orang yang berselonjor dianggap perilaku sangat buruk di Nepal.
Maka silakan makan dengan cara yang disukai.Silakan berkecap bila itu dianggap tidak menjadi masalah. Silakan makan dengan mengatupkan dua bibir, bila cara itu dianggap yang paling sopan.
Pengalaman saya sebagai wartawan dan sering diundang untuk acara jamuan makan menunjukkan, kesopanan memang tergantung pengalaman masing-masing orang.
Saya sering melihat wajah-wajah orang yang mengundang makan seperti terpengarah sewaktu mereka melihat cara makan beberapa wartawan. Bukan hanya berkecap, tapi para wartawan itu juga menumpuk banyak makanan di piring mereka. Mi goreng digabung dengan nasi. Dicampur capcay, telor rebus dan telor goreng, daging, sup jagung dan sebagainya.
Sebaliknya, saya melihat wajah para wartawan itu seperti biasa-biasa saja. Mereka mungkin menganggap perilaku makan mereka tidak melanggar kesopanan. Lagi pula, siapa yang tahu, kalau mereka sebetulnya benar-benar kelaparan atau tidak pernah memakan makanan yang diperjamukan; meskipun yang sering saya temui kemudian, makanan mereka tidak habis dimakan. Teronggok di piring dan kemudian dibuang begitu saja oleh palayan, ke tempat sampah.