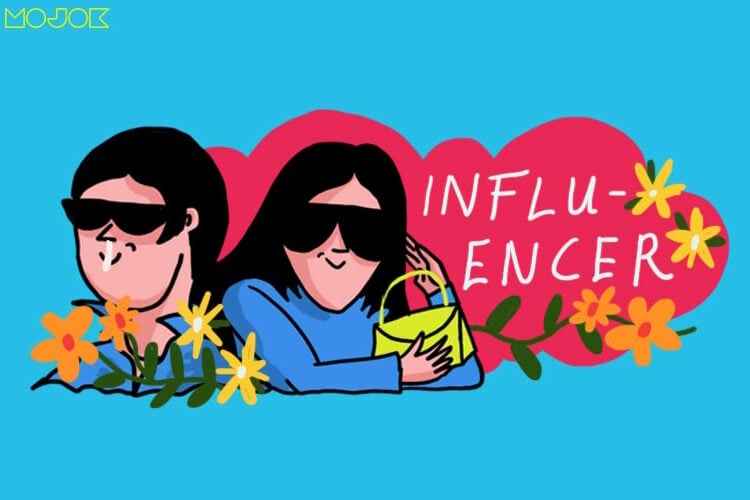MOJOK.CO – Beberapa yang pandir akan melihat konten-konten konten YouTube atau di platform lain dari influencer tadi sebagai ajakan berbuat sesuka hati.
Pernyataan Mgdalenaf atau Magdalena, seorang influencer sekaligus food vlogger beberapa saat yang lalu menjadi polemik. Semua berawal dari cerita pengalamannya mengulas makanan di sebuah resto untuk dijadikan konten YouTube. Mgdalenaf bercerita soal pengalamannya yang kerap dipandang sinis oleh pengusaha kuliner, padahal dia memiliki jutaan followers di media sosial.
“Aku tahun lalu, aku mau datang ke tempat makan. Aku udah nunjukin followers aku berapa, bisa bantu sejauh apa, dia bilang ‘Ini kan bisnis, saya dikasih apa’,” kata Mgdalenaf dalam podcast tersebut. Dia merasa bahwa sebagai food vlogger kerap mengalami pengalaman buruk, misalnya dengan tidak dijamu dengan baik.
Pertanyaan yang seharusnya ditanyakan
Keluhan seorang influencer ini bukannya menarik simpati, Mgdalenaf malah dianggap menggunakan popularitasnya untuk memperoleh kemudahan atau keuntungan. Pada titik ini, saya menilai apa yang dilakukan oleh Mgdalenaf tidak salah. Dia punya platform yang bisa menjadi moda promosi super efisien via konten YouTube-nya. Dengan jutaan penggemar, jika satu persen dari jumlah follower-nya mendatangi sebuah usaha kuliner, dia bisa mendatangkan banyak keuntungan.
Tapi pertanyaannya tentu saja begini: Apakah si pemilik bisnis butuh promosi? Apakah mereka membutuhkan Mgdalenaf untuk meningkatkan volume transaksi? Atau, jangan-jangan, mereka sebenarnya sudah mapan dan cukup. Asumsi kapitalistik yang menganggap semua usaha pasti mengejar untung, membuat keberadaan influencer dan konten YouTube food vlogger jadi penting.
Influencer menawarkan platform untuk promosi, yang diharapkan bisa membawa pelanggan dan akhirnya menambah jumlah pembelian. Tapi, tidak semua bisnis mengejar keuntungan belaka. Benar, ada beberapa orang di kolong langit yang membuka usaha bukan untuk mencari cuan atau keuntungan materi. Beberapa sekadar meneruskan tradisi, warisan, atau mengisi kebosanan.
Mereka yang tidak membutuhkan promosi lewat konten YouTube
Ada satu cerita tentang warung makan legendaris milik keluarga Mbak Tun Ungaran dikelola tiga generasi. Mereka hanya buka di waktu pasaran dalam hitungan kalender Jawa. Tidak hanya itu, warung yang terletak di Semarang ini hanya buka di hari pasaran Wage dan Legi, dari pukul 07.00 hingga 15.00. Tapi mengapa? Bukankah lebih menguntungkan jika buka setiap hari?
Sejak 1970, warung sate Mbak Tun ini awalnya menyesuaikan jadwal buka Pasar Babadan di tahun 1970-an yang memang hanya buka pada Wage dan Legi. Kebiasaan tersebut tetap dipertahankan meski pasar sudah buka tiap hari. Buat banyak orang, terutama hari ini yang tujuan bisnis adalah mencari untung sebesar-besarnya, tentu tidak bisa menerima logika merawat tradisi tadi.
Bagi influencer warung sate Mbak Tun ini tentu punya nilai. Tidak hanya sekadar olahan makanan yang enak, tetapi juga memiliki keunikan cerita. Tapi, jika influencer berpikir mereka perlu promosi, kolaborasi dalam bentuk barter makan gratis agar lebih banyak orang tahu warung ini, ada yang gagap dalam logika influencer dan penjual ini.
Di dunia, ada orang-orang yang ingin hidup sak madya, secukupnya, tidak ingin ngoyo dalam berusaha/bisnis. Membuka usaha setiap hari artinya kita perlu terus-menerus bekerja. Membeli bahan, mengolah, memasak, menjual, dan melayani. Bagi beberapa orang ini adalah realitas keseharian, sementara bagi yang lain hal ini adalah hidup yang mengerikan.
Ada yang malas terkenal
Influencer datang dengan asumsi bahwa dengan konten YouTube yang mereka miliki, sebuah bisnis bisa berkembang lebih besar, lebih baik, dan lebih ramai. Tapi bagaimana jika ada orang yang hanya sekadar ingin berjualan untuk mengisi waktu kosong, atau menjalankan tanggung jawab sehari-hari?
Saya pernah bertemu dengan pemilik Mie Sapi Banteng yang berseloroh bahwa popularitas membuatnya kerepotan. Dia tentu senang bisnis yang dimiliki terkenal dan memiliki banyak penggemar. Namun, dia juga kehilangan momen berharga, seperti mengobrol bersama teman, istirahat, dan juga mengambil jeda.
Dia jelas tak keberatan dan mempersilakan influencer datang ke Mie Sapi Banteng, toh sudah banyak video dan konten YouTube mengenai makanan yang dibuat. Tapi, popularitas memiliki harganya sendiri. Misalnya orang-orang yang datang kerap memiliki ekspektasi tinggi. Saat tahu harus menunggu satu-dua jam untuk satu mangkuk mi, pembeli ini bisa jadi beringas ketika memberikan ulasan.
Di Google Review kita bisa melihat omelan dan kemarahan orang-orang yang memberikan rating buruk. Bukan karena makanan tidak enak, tapi karena waktu antre yang lama. Tentu dalam bisnis kuliner kualitas makanan bukan yang utama, ada kebersihan, suasana, waktu tunggu, dan pelayanan. Namun, menyalahkan penjual karena menunggu lama adalah kebebalan.
Saatnya memikirkan perasaan penjual
Beberapa influencer dengan konten YouTube yang mewah mungkin bisa dengan bangga menepuk dada sendiri dan berpikir dia memiliki dampak pada bisnis orang. Tapi, mereka tak pernah memikirkan bagaimana pelanggan dan penjual merespons popularitas tadi. Warung yang ramai sementara daya dukungnya tak tersedia bisa jadi masalah, sama dengan ulasan yang berlebihan bisa membuat pembeli kecewa karena merasa dibohongi.
Influencer mesti memahami latar belakang dan juga realitas sosial dari sebuah bisnis yang mereka datangi. Misalnya di Warung Bu Spoed, sudah berusia sekitar 100 tahun. Warung ini menyajikan menu-menu sederhana yang bertahan hingga empat generasi. Warung makan di Jogja yang dikenal juga dengan sebutan Warung Mbah Galak, pernah menolak utusan Sultan HB IX yang mau memborong tahu dan tempe bacem dari warung ini.
Jika keluarga Bu Spoed fokus pada kepentingan bisnis, mereka tentu bisa menambah jumlah tahu bacem atau menambah jam operasi. Tapi, hal ini tidak dilakukan karena beberapa hal seperti menjaga kualitas makanan, merawat tradisi, dan yang paling penting adalah fokus pada kualitas layanan. Ini mereka buktikan dari pembatasan transaksi jual beli tahu dan tempe bacem yang dibatasi perorangnya.
Di banyak bisnis, saat sesuatu populer, pemilik modal akan dengan cepat menambah kapasitas produksi, membuat cabang baru, dan jika perlu mencari tambahan kapital. Tapi, bagi banyak penjual makanan legendaris, mencari uang bukan tujuan utama. Mereka memperlakukan makanan sebagai karya seni, yang dibuat dengan hati-hati sembari menjaga kualitas bahan. Tentunya tidak semuanya butuh promosi besar ala-ala konten YouTube.
Pengaruh besar yang belum tentu bermanfaat
Jalan menuju ke neraka dibangun dari niat baik. Sebagian influencer adalah daki peradaban yang sebenarnya nyaris tak punya nilai guna. Mereka berpikir bahwa dengan memiliki ratusan followers, maka pengaruh yang dia miliki akan bermanfaat. Tapi mereka lupa, dari sekian ratus ribu atau jutaan followers yang dimiliki, tidak semuanya memiliki akal yang lengkap.
Beberapa yang pandir akan melihat konten-konten konten YouTube atau di platform lain dari influencer tadi sebagai ajakan berbuat sesuka hati. Berapa banyak suaka alam atau tempat yang rusak karena label hidden gem? Berapa banyak masyarakat yang dirusak nalarnya karena komersialisasi wilayah akibat kedatangan influencer? Atau berapa banyak tanah suci, wilayah sakral, jadi bulan-bulanan konten nir-akal influencer asing yang tak menghormati adat setempat?
Pada satu titik, memang, ada baiknya influencer ini diakhiri dan dihentikan saja keberadaannya. Atau jika memang perlu, masyarakat dan juga bisnis makanan yang sudah mapan, menuliskan papan besar-besaran. “Tidak membutuhkan influencer, apalagi yang tak mampu membayar!”
Penulis: Arman Dhani
Penulis: Yamadipati Seno
BACA JUGA 5 Kebiasaan Food Vlogger yang Sebenarnya Menyebalkan dan analisis menarik lainnya di rubrik ESAI.