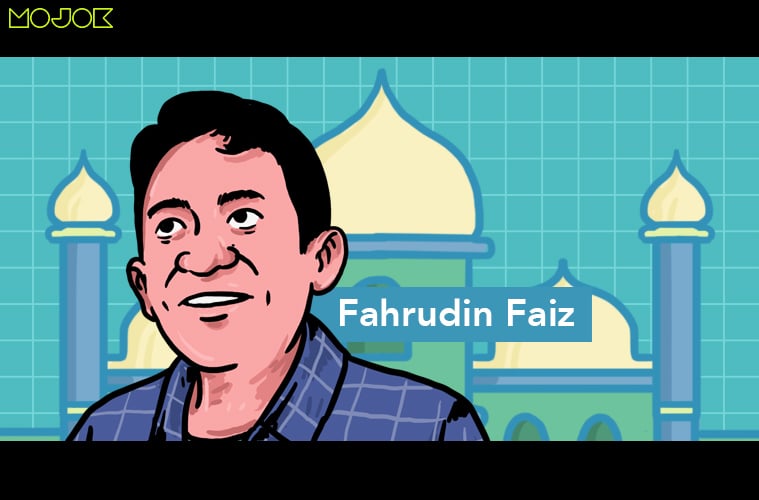Salah satu perilaku mulia yang ditekankan dalam Islam adalah muhasabah, yakni aktivitas yang bertujuan menilai diri sendiri, mengevaluasi, atau introspeksi diri.
Ada sebuah adagium yang sangat terkenal sekali dari Umar bin Khattab r.a. tentang muhasabah ini, yaitu; haasibuu anfusakum qabla an tuhaasabuu (hisablah diri kalian sendiri sebelum kalian nantinya dihisab).
Al-Quraan secara eksplisit dalam Surat Al-Hasyr ayat 18 memerintahkan: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat).”
Banyak Ulama, khususnya dari ranah tasawuf yang memiliki concern terhadap kualitas batin keberagamaan, menekankan pentingnya melakukan muhasabah ini. Imam Hasan al-Basri misalnya, menyatakan bahwa, “Seorang hamba akan berada dalam kebaikan selama dia mampu menasihati dirinya sendiri dan selalu menghisab dirinya sendiri.”
Di kesempatan yang lain beliau juga menyatakan “Seseorang tidak akan mendapatkan predikat ketaqwaan sampai dia melakukan muhasabah kepada dirinya lebih ketat dibandingkan saat menilai temannya sendiri.”
Tekanan untuk melakukan muhasabah ini mengimplikasikan beberapa hal.
Pertama, kesadaran ketidaksempurnaan manusia.
Kesadaran bahwa manusia itu tidak sempurna, lemah dan sering keliru membawa kepada kesimpulan bahwa sebaik dan sebagus apapun hidup yang kita jalani, pasti selalu ada kekurangan dan ketidaktepatannya. Tanpa melakukan muhasabah, maka kita tidak akan menemukan kekurangan dan kekeliruan tersebut untuk diperbaiki.
Kedua, kehati-hatian agar tidak jatuh dalam kesombongan dan rasa sudah pasti benar.
Manusia memiliki kecenderungan egois untuk mendaku kebenarannya sendiri. Dengan kendali muhasabah maka kita akan senantiasa disadarkan untuk tidak mengambil posisi sudah pasti benar, apalagi sempurna.
Ketiga, menghindarkan diri dari kesia-siaan dan kahampaan tindakan karena kekurangtelitian atau kekuranghati-hatian.
Kebenaran dan kebaikan tindakan dalam Islam itu tidak hanya dilihat dari jenis perbuatannya, namun juga dilihat dari niatnya, prosesnya dan juga hasil serta efeknya. Untuk mengukur, menilai dan mengontrol segala aspek tersebut tentunya tidak bisa dilakukan “sambil jalan”, namun diperlukan waktu dan kesempatan yang khusus dalam momen muhasabah.
Tuntutan untuk melakukan muhasabah ini tentunya relate dengan ibadah puasa yang kita jalankan di bulan Ramadan saat ini.
Kalau sekadar mengukur dan mengendalikan diri bahwa kita tidak makan, tidak minum dan tidak melakukan hubungan seksual sepanjang subuh sampai magrib tentunya tidak sukar dilakukan; namun mengukur sejauh mana segala anggota tubuh kita, lahir batin, juga terkendali dari segala perbuatan yang terlarang dan tidak terpuji, tindakan muhasabah yang khusus dan serius harus tetap dilakukan.
Lewat jalan inilah agaknya puasa kita dapat setahap demi setahap semakin “naik kelas” kualitasnya dan tidak sekadar mendapatkan lapar dan haus belaka.
Secara lebih teknis, Imam Haris al-Muhasibi, seorang sufi besar yang dari namanya saja terlihat bahwa beliau ini seorang ahl al-muhasabah, memberi petunjuk bagaimana kita mengevaluasi dan menelaah aktifitas kehambaan kita di hadapan Allah, termasuk tentunya puasa.
Menarik untuk kita ikuti alur muhasabah yang dilakukan oleh Imam Haris al-Muhasibi ini untuk menguji kualitas puasa kita.
Pertama, Imam Haris al Muhasibi mengarahkan kita untuk melihat, sudahkah kita menjaga dan mengendalikan anggota badan kita dari kemaksiatan dan segala perilaku yang dilarang.
Dalam konteks puasa berarti tuntutan bagi kita untuk melihat—selain mulut yang tidak kemasukan makanan dan minuman—adakah lidah, mata, telinga, lidah, tangan, kaki, kemaluan, dan yang lainnya juga terjaga dari kemaksiatan dan segala hal yang tidak utama.
Kedua, apabila sudah dipastikan berhasil dalam tahap pertama di atas, yaitu bersihnya semua anggota badan dari dosa dan kemaksiatan, maka langkah selanjutnya adalah menguji diri kita: apakah tujuan kita dalam menjaga diri dari dosa dan kemaksiatan tersebut hanya karena mencari keridaan Allah saja ataukah ada motif-motif dan pamrih lainnya, misalnya ingin dianggap mulia, ingin lebih tinggi dari yang lain atau ingin mendapat balasan tertentu yang istimewa dari Allah?
Ketiga, seandainya ternyata memang motif segala kebaikan yang kita lakukan itu hanya Allah saja, selanjutnya harus pula ditanyakan: apakah kita merasa takjub kepada diri kita sendiri dan bangga karena sudah melakukan semua yang baik tersebut?
Ataukah kita sadar bahwa semuanya terjadi atas anugerah dan pertolongan Allah belaka? Adakah perasaan bahwa keberhasilan itu karena tekad dan kesungguhan sendiri ataukah muncul kesadaran bahwa semuanya karena bantuan dari Allah belaka?
Keempat, ketika jawaban dari semua proses tersebut ternyata positif, kita sadar bahwa segala macam tindakan kebenaran dan kebaikan kita itu sumbernya dari Allah, tujuannya juga Allah, serta dapat berhasil karena anugerah dan pertolongan Allah belaka, apakah sekarang kita merasa sebagai manusia yang mulia, lebih dari manusia lainnya yang maqamnya masih awam atau biasa?
Tentu saja jika masih memiliki rasa lebih dari yang lain karena keutamaan kita, berarti gugur pula segala keutamaan kita sebelumnya, karena setitik kesombongan yang ada dalam diri kita. Namun jika rasa semacam itu sama sekali tidak ada, dan hanya Allah saja yang menjadi concern kita, berarti kita telah “lulus” dari segala jerat dan godaan nafsu dan hasrat duniawi.
Dalam rumusan Imam Ghazali, mereka yang hanya sukses di level pertama muhasabah adalah kelompok awam. Sementara mereka yang sukses sampai level dua saja adalah kelompok khawas. Sedangkan mereka yang berhasil sampai level empat adalah kelompok khawas al-khawas.
Adapun kita? Tampaknya kita masih berjuang agar setidaknya lulus di level awam saja.
Sepanjang Ramadan, MOJOK menerbitkan KOLOM RAMADAN yang diisi bergiliran oleh Fahruddin Faiz, Muh. Zaid Su’di, dan Husein Ja’far Al-Hadar. Tayang setiap waktu sahur.