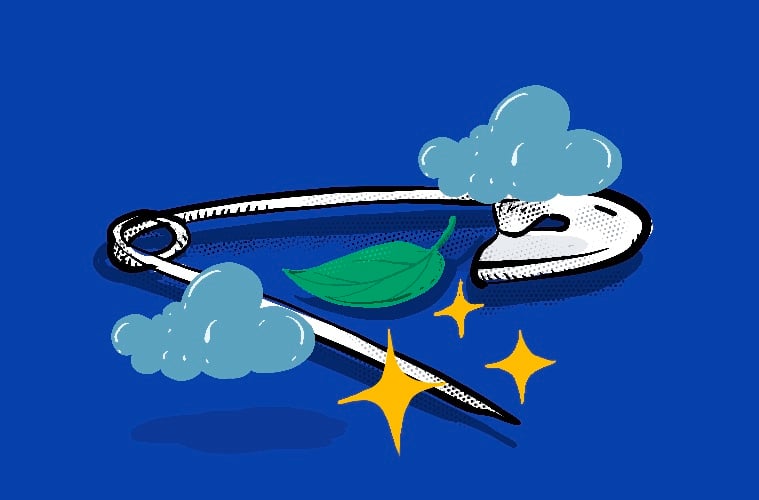Persoalan tentang hadirnya pawang hujan di sirkuit Mandalika, bisa menunjukkan kepada kita sedikit gambaran tentang apa yang ada di balik kepala manusia Indonesia. Sebagian dari mereka menghujat pawang hujan, dan sebagian lagi membelanya.
Sebelum saya melanjutkan tulisan ini, saya berusaha untuk menghindarkan diri dulu dengan persoalan yang lain, karena jika tidak, kita akan terjebak pada kelindan persoalan yang keruh. Sebagian komentar itu memang ada warna ‘politis’-nya. Karena perhelatan itu diselenggarakan di saat pandemi (atau pascapandemi), sehingga dianggap tidak elok. Sehingga ada banyak orang yang menyerang profesi pawang hujan dikaitkan dengan ketidaksetujuan mereka atas agenda olahraga yang menelan anggaran cukup besar tersebut.
Mudahnya, karena mereka tidak setuju dengan perhelatan tersebut, maka apa pun hal yang terjadi di sana, termasuk pawang hujan, adalah pintu masuk untuk menyatakan ketidaksetujuan. Tentu saja, ini ‘jebakan’ menghadapi pohon masalah.
Jebakan seperti itu biasa terjadi dalam berbagai peristiwa politik-sosial di Indonesia. Ketidaksukaan atau rasa tidak setuju, memberi kabut pada kejernihan pikiran. Perhelatan MotoGP yang tidak mereka setujui, pawang hujan yang mereka serang.
Hal lain tentu saja adalah berkembangnya kacamata positivisme yang terlalu tebal dalam melihat profesi pawang hujan. Ini yang menjadi pokok persoalan. Pawang hujan dianggap sebagai profesi yang klenik dan penuh takhayul, karena itu tidak sah untuk eksis dalam kehidupan sehari-hari.
Sebelum masuk lebih jauh untuk melihat kecerobohan pernyataan ini, mari kita lihat kenyataan bahwa profesi itu digeluti oleh banyak orang, eksis, dan setahu saya ada di hampir seluruh wilayah di Indonesia. Mereka yang bilang profesi itu takhayul, mungkin bahkan ketika menikah dan menggelar resepsi pernikahan, orang tua mereka juga menggunakan jasa pawang hujan.
Atau jika mereka bekerja di perusahaan tertentu, yang dekat dengan membuat peristiwa di alam terbuka, misal pergelaran musik, juga menggunakan jasa mereka. Yang jelas, di mana-mana, profesi pawang hujan masih banyak, dan itu tandanya masih dibutuhkan oleh masyarakat. Toh, profesi apa pun itu, tidak akan eksis atau akan lenyap kalau sudah tidak dibutuhkan lagi oleh masyarakat. Sesederhana itu. Seperti hukum ekonomi dasar tentang penawaran dan permintaan (supply and demand).
Kalau hal itu terjadi, berarti ada pengakuan secara sosial bahwa profesi itu punya tingkat keberhasilan yang tinggi. Nah, ini masalahnya. Mereka tidak peduli dengan hal tersebut, yang mereka persoalkan adalah cara kerja pawang hujan yang tidak mereka mengerti, dianggap klenik dan takhayul. Ketidaktahuan sistem operasi pengetahuan tertentu, dengan mudah menggerakkan jari telunjuk mereka dengan mudah untuk bilang takhayul.
Padahal dalam kehidupan sehari-hari pun sebetulnya kita tidak tahu persis apa yang terjadi dalam sistem operasinya. Banyak yang tidak mengerti tentang cara kerja internet, tapi hampir semua dari kita menggunakannya. Mereka kalau sakit pergi ke dokter, bagaimana cara kerja dokter juga tidak mereka ketahui. Mereka tidak tahu isi obat dan bagaimana ia bekerja di tubuh kita, tapi kita tetap menelannya. Iya, tapi kan hal itu masuk akal! Begitu kilah mereka. Oke, mari kita periksa argumen apa yang disebut masuk akal.
Di Indonesia, setidaknya ada beberapa contoh yang bisa kita lihat supaya persoalan ini lebih jernih lagi. Pada tahun 2004 sampai 2005, kebetulan saya terlibat dalam sebuah penelitian tentang dukun bayi di Indonesia. Sebelumnya, dukun bayi dianggap profesi yang juga klenik dan juga takhayul. Tapi lambat laun, dunia medis kita mulai masuk arus baru, semacam pengakuan bahwa metode kerja dukun bayi itu sebetulnya bisa dimengerti secara medis. Tapi itu butuh waktu yang lama. Semua yang dulu tampak tidak masuk akal, perlahan setelah diteliti, akhirnya bisa dimengerti. Sehingga kerap kali, pengakuan itu bersifat post-factum. Distempel dulu dengan takhayul, tapi setelah diperdalam dan diteliti, baru diakui.
Selain dukun bayi, tukang pijat dan ahli tusuk jarum pun mengalami hal yang sama. Kalau di Indonesia yang lebih kontekstual tentu tukang pijat. Butuh waktu lama, metode tukang pijat ini diakui secara medis. Sekarang, di beberapa rumah sakit bahkan mulai merekomendasikan tukang pijat sebagai salah satu metode penyembuhan. Hanya saja supaya keren, disebutnya: akupresur. Padahal ya sama saja.
Bersamaan dengan pengakuan profesi tukang pijat alias akupresur itu, diakui pula profesi ahli tusuk jarum atau akupuntur. China, lebih dulu menyetarakan keahlian ini dengan dokter. Bahkan ada banyak rumah sakit di sana yang menggunakan metode penyembuhan dengan berbasis akupuntur, akupresur, dan obatnya memakai jamu. Sementara kita, membutuhkan waktu yang lama untuk mengakui itu semua.
Profesi pawang hujan, belum pernah diteliti dengan serius, kebanyakan kita hanya tahu tingkat keberhasilannya yang tinggi untuk ‘mengusir’ hujan. Tapi tidak mau mendalami metode di baliknya. Sementara, sebagian dari mereka yang menolak pawang hujan, diam-diam atau dengan terus terang, percaya pada kartu tarot dan zodiak.
Diam-diam, di balik kepala orang ini sebetulnya bersemayam apa yang disebut dalam filsafat sebagai kaum yang menganut positivisme. Sebuah paham yang segala sesuatu harus bisa dijelaskan secara rasional, dan seluruh hal di dunia ini harus bisa dijelaskan dengan cara seperti itu. Paham itu muncul didorong oleh sebuah hasrat untuk menaklukkan dunia.
Saya pernah melakukan penelitian di daerah Tulungagung dan Magetan, bagaimana mengerikannya paham ini yang terjadi di masyarakat. Mungkin ini juga terjadi di kampung halaman Anda. Sekitar sampai tahun 1980an, ada banyak mata air yang mulai hilang, karena belik atau tuk (sumber mata air), yang dulu dianggap ‘sakral’ karena ‘sikap ilmiah’ ini, tempat-tempat seperti itu dianggap lagi bukan tempat yang sakral.
Ikan-ikan di sana yang tidak boleh diambil, lalu diambil dengan cara yang eksploitatif. Pohon-pohon yang dulu dianggap ada ‘penunggunya’, karena terbukti tidak ada penunggunya maka akhirnya ditebangi. Apa yang kemudian terjadi? Banyak sumber mata air yang mati. Kehilangan kesakralan suatu tempat, ternyata punya implikasi terhadap kerusakan ekologis yang serius.
Hal tersebut juga diakui oleh Komunitas Resan Gunungkidul. Komunitas ini berisi anak-anak muda yang punya kesadaran baru untuk menyelamatkan lingkungan, dengan ‘menghidupkan’ lagi mata air yang telah mati. Mereka menanami pohon di sekitar belik atau tuk, membersihkan alirannya, lalu perlahan, tempat-tempat tersebut mulai mengeluarkan air lagi. Alhamdulillah…
Saat saya wawancara (Anda bisa menyimak acara podcast saya di bawah ini), salah satu hal yang membuat mereka menebangi pohon, selain faktor ekonomi, juga karena hilangnya ‘kesakralan’. Padahal, kesakralan itu adalah artikulasi budaya sebuah komunitas masyarakat untuk menjaga alam dan tempat hidup mereka. Tapi karena dianggap tidak ‘rasional’ maka dilanggarlah semua itu. Akhirnya daerah tersebut benar-benar kena tulah alam. Alam tak lagi memberi air. Kesadaran yang terlambat, setidaknya lebih baik, tapi mungkin di banyak tempat lain, tidak ada kesadaran itu. Mata air yang telanjur rusak tidak direkadaya lagi.
Seiring dengan kesadaran menjunjung tinggi sikap ‘rasional’ itu pula, yang kemudian ikut berkontribusi pada bencana ekologis di Indonesia. Belik dan tuk ‘hanya’ sekala kecil (sengaja saya beri tanda ‘..‘ karena dalam kehidupan dan alam ini, sekala seringkali adalah sesuatu yang berbahaya juga, sebab kehidupan ini justru dari kelindan hal-hal kecil yang saling terkait secara organik), sekala yang lebih besar lagi juga dihancurkan: bukit, perbukitan, gunung, hutan, sungai, dan laut.
Kalau belik dan tuk, mungkin ada upaya yang bisa direkadaya untuk mengembalikannya sekalipun butuh waktu panjang, tapi bagaimana mengembalikan perbukitan dan gunung? Bisakah kita menciptakan jajaran bukit dan gunung? Bagaimana kita kembali menyelamatkan laut kalau sudah tercemar?
Dorongan manusia untuk menaklukkan alam, didorong oleh sikap rasionalis dan positivisme, cenderung destruktif dan eksploitatif. Pertama, tentu saja karena kehilangan rasa pada apa yang dianggap sakral. Sebelum mereka bisa menjelaskan kenapa sebuah komunitas itu menyematkan kesakralan pada suatu tempat, mereka sudah terlebih dahulu menghancurkannya. Dan ketika sudah hancur, baru ada kesadaran baru, bahwa sebetulnya hal tersebut juga masuk akal. Sayang, apa yang telah hancur, sebagian besar sudah tidak bisa diperbaiki kembali.
Kita sekarang ini, ada dalam sebuah pacuan dunia yang sangat penting. Di satu sisi, kaum positivisitik dengan hasrat eksploitatif dan destruktif sudah menjadi mekanisme besar yang menopang perekonomian dunia, namun di sisi lain, kesadaran baru tentang ekologi mulai muncul dan menguat. Masalahnya adalah mana yang akan lebih cepat.
Banyak ahli yang pada akhirnya mengakui, kerusakan alam akan lebih cepat terjadi dibanding upaya perbaikan alam. Kita ada di ambang bahaya kehidupan. Tapi sepertinya kita telah terlampau terlambat. Walaupun tentu saja terlambat lebih baik dibanding tidak sama sekali.
Namun sesungguhnya, kesadaran yang terlambat itu juga menghadapi kendala. Karena ternyata apa yang ada di balik batok kepala kita, diam-diam tetap tumbuh dengan pikiran positivisme. Salah satunya adalah apa yang kita saksikan belakangan ini, betapa dengan mudahnya mereka menganggap profesi pawang hujan sebagai sesuatu yang tidak masuk akal, penuh dengan takhayul, hanya karena mereka tidak bisa menjelaskan bagaimana sistem pengetahuan profesi pawang hujan.
Mirip sekali dengan ketika kaum positivistik memandang bahwa tidak ada yang sakral di balik pepohonan yang mengitari belik dan tuk, tidak ada yang perlu ditakuti soal kesakralan yang ada di gunung dan laut, sehingga mereka turut serta andil dalam perusakan. Lalu semua terlambat. Bagaimana mereka akan membuat lagi gunung yang sudah dikeruk dan dihancurkan?
Sesungguhnya, tidak ada yang sepele dalam cara kita memandang dunia. Sebagaimana adagium lama: Kalau Anda bukan bagian dari penyelesaian masalah, jangan-jangan Anda adalah bagian dari masalah itu sendiri. Cuma tidak disadari dan tidak mau menyadari, karena egoisme dan arogansi. Merasa isi kepala yang paling benar sendiri, paling hebat, dan paling suci.
THANK YOU for stopping the rain! 😅#IndonesianGP 🇮🇩 pic.twitter.com/zv7mUB8DPr
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) March 20, 2022