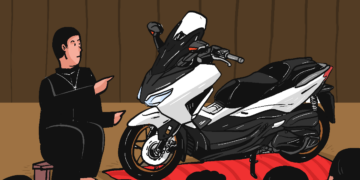MOJOK.CO – Sampai di titik ini, saya masih ragu pada era di mana orang sibuk pamer foto di medsos, kok masih ada saja tuduhan serius ke kami soal masifnya kristenisasi.
Sebagai pembuka, saya ingin jujur bahwa tulisan ini diniatkan agar tak ada rasa curiga di antara kita sebagai umat beragama. Kedua, agar kita sama-sama mencari tahu, siapa yang melakukan kristenisasi di abad ini—di tengah orang-orang di luar sana berlomba memikirkan bagaimana caranya bisa pesan kamar hotel di Planet Mars.
Soal yang pertama—semoga—akan terpenuhi setelah kamu selesai membaca tulisan ini sampai habis. Lalu soal yang kedua, saya akan memulainya.
Begini.
Ketika kuliah, saya aktif di organisasi mahasiswa di bidang keagamaan. Setelah wisuda, saya melanjutkannya di organisasi kepemudaan yang juga bernuansa agama. Dan ketika bergabung di kedua organisasi itu, tak sekali pun kami membicarakan kristenisasi.
Padahal, anak muda adalah ladang subur bagi isasi-isasian karena militan. Kenapa saat itu kami tidak menyusun strategi agar seluruh penduduk negeri ini beragama Kristen? Karena waktu kami habis berdiskusi untuk membantu kawan-kawan yang kesulitan di bidang ekonomi.
Sesekali kami sempatkan juga mencari cara bagaimana membuat Danau Toba agar bersih atau di lain waktu kami berangan-angan melaksanakan pernikahan murah tanpa pesta berlebihan agar tak banyak utang.
Saat itu memang kami sudah berpikir, tak ada gunanya membicarakan agama ketika manusia lain di sekitar kita kelaparan. Belum lagi bicara setiap ayat yang bagi beberapa orang bisa berbeda tafsirannya. Hm, benar-benar melelahkan.
Begitulah kebanyakan kami. Mahasiswa dari kampung yang ingin mengubah hidup dengan jalan lain—soalnya jalan melalui agama sudah dipenuhi para orangtua kami di kampung.
Setelah menikah, beberapa dari kami pun saya ketahui tak sempat memikirkan kristenisasi. Kepala sudah dipenuhi dengan perkara sehari-hari; gaji yang hanya cukup menyicil rumah pas-pasan, susu anak kadang tak terbeli, belum lagi ancaman di-PHK dari perusahaan.
Agya untuk menaikkan gengsi belum terbeli, sudah pengangguran lagi. Boro-boro mengajak orang menjadi seorang Kristen, diri sendiri aja belum terurus.
Kadang-kadang saya berpikir, orang biasa (yang bukan pemuka agama) memang tak perlu memikirkan kristenisasi. Menggunakan energi dan waktu untuk memikirkan cara kristenisasi yang menarik minat orang lain adalah sia-sia.
Lebih baik energi dan waktu itu digunakan untuk memikirkan strategi mendidik anak, mengembangkan karier, atau melestarikan lingkungan sekitar tempat tinggal.
Sampai di titik ini, saya masih ragu di era orang sibuk memamerkan foto di media sosial, masih ada saja tuduhan-tuduhan serius soal adanya kristenisasi.
Oke. Sekarang mari membahas pemuka agama kami dulu.
Saya pernah berdiskusi dengan seorang Pastor. Beliau berkata bahwa mengurusi umat yang sudah ada sekarang pun sudah pusing. Diminta untuk jadi panitia perayaan Natal, jawabannya sibuk nambah penghasilan. Disediakan pelatihan tentang pengembangan ekonomi keluarga, sepi peminat.
Belum lagi materi khotbah harus menarik perhatian semua golongan usia, kata-kata yang sesuai dengan perkembangan zaman, atau sikap yang tak boleh terlalu kaku. Dan yang paling menguras tenaga, menghadapi komentar miring dari umat yang sok tahu. Bisa bayangkan bukan betapa sulitnya menjadi pastor zaman now?
Dari hasil diskusi itu, saya tahu Pastor itu tak perlu repot-repot mengajak orang lain menjadi umatnya. “Susah ngurus orang, Bro!” kira-kira begitu kesimpulannya.
Saya memaklumi kesimpulan seperti itu. Teknologi membuat tantangan menghadapi umat yang sok tahu semakin berat. Pastor tersebut bisa membandingkan khotbah-khotbah atau tafsir dari pastor lain. Bahkan bisa mengutip dari gereja lain hanya untuk membuat malu pastornya atau menunjukkan si umat lebih pintar—kejadian ini banyak saya jumpai.
Di lain waktu, saya berbincang dengan seorang Pendeta. Dengan api semangat yang berkobar-kobar, beliau berkata ingin ber-misi ke negara barat karena di sana sedang terjadi krisis moral. Saya tidak tahu tema apa yang akan dibawakan beliau ketika berkhotbah di Silicon Valley atau di Stadion Old Trafford sesaat setelah Manchester United kalah dari Manchester City—misalnya.
Sampai di titik ini, saya masih ragu di era Revolusi Industri 4.0 ini masih ada kristenisasi.
Oke. Sekarang ke “tersangka” lain yang sering beredar di medsos.
Sependek perjalanan hidup ini, saya banyak melihat Rumah Sakit dan Sekolah Katolik. Umurnya sudah ada yang ratusan tahun. Jika memakai anggapan bahwa sarana itu dipakai untuk kristenisasi, kita cukup melihat sensus untuk mengetahui betapa sedikitnya penganut Katolik di negeri ini dibanding rumah sakit dan sekolahnya.
Mungkin saja dulu, rumah sakit dan sekolah seperti itu digunakan untuk menarik minat masyarakat, tetapi sekarang? Selain pilihan yang tersedia banyak, kita juga tahu fasilitas “Katolik” sangat mahal. Kalau bahasa saya ketika menjadi aktivis dulu: lebih ke arah bisnis alias profesional belaka.
Atau bagaimana kalau diadakan survei untuk mengetahui berapa banyak umat Katolik atau Kristen yang tidak ke gereja di hari Minggu? Agar jelas kita ketahui seberapa banyak orang nggak peduli lagi dengan ibadah rutin di tengah kemajuan teknologi yang bisa menjawab hampir semua pertanyaan manusia.
Itu sedikit gambaran tentang kami. Seperti yang saya tuliskan di awal tadi, bahwa tulisan ini perlu dibuat agar tak ada kecurigaan di antara kita.
Jika masih kurang, mungkin dialog bisa diperbanyak. Apa yang saya tulis ini, bisa juga dipahami dengan membaca berita yang menjelaskan kenapa tidak sedikit gereja-gereja di Barat “dijual” bangunannya—secara harfiah.
Dengan kata lain, agama mungkin saja tak akan menarik lagi—menurut kacamata saya. Peminat teknologi akan berusaha mengembangkan apa saja. Persaingan untuk mempertahankan eksistensi bukan lagi tentang siapa yang paling tahu jalan ke surga, melainkan justru siapa yang paling lama hidup di dunia.
Jadi, untuk saudara sebangsa se-tanah air yang sering menuduh kami kerap melakukan kristenisasi secara terstruktur, sistematis, dan masif, jujur kami sendiri bingung siapa yang melakukan kristenisasi dan untungnya buat kami apa?
Bisa saja itu hanya isu yang sengaja digoreng untuk membangkitkan selera bertengkar kita, agar kita bisa lupa kalau kita sebenarnya sudah sama-sama lapar. Lapar akan kesejahteraan, pengetahuan, pengakuan, sampai lapar akan kebebasan memeluk keyakinan masing-masing.
Hal-hal yang—sayangnya—jadi semakin mahal belakangan ini.