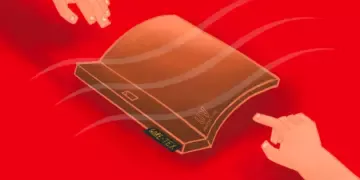MOJOK.CO – Sekolah di mana memang bukan jadi patokan seorang anak sukses atau tidak nantinya, hanya saja kita juga harus ingat tidak semua anak punya mental seperti Bu Susi Pudjiastuti atau Mas Agus Mulyadi.
Membaca tulisan Mbak Nia Perdhani “Masih Percaya Nasib Anak Ditentukan dari Sekolah Favorit atau Bukan?” tanpa pikir panjang saya ingin menjawabnya; iya Mbak Nia, saya percaya.
Enam tahun bersekolah di pelosok kampung dan enam tahun lainnya bersekolah di sekolah favorit di kota memberi saya kepercayaan diri untuk bilang bahwa saya cukup pengalaman bilang “iya” untuk menjawabnya.
Saya sekolah dari kelas satu sampai kelas tiga di SD di kampung, nama kampungnya Mannanti, di Sulawesi Selatan. Di SD saya itu, masih banyak teman-teman saya yang telanjang kaki ke sekolah. Bajunya lusuh kekuningan dan kancingnya dijahit berkali-kali dengan warna benang berbeda-beda. Ada pula yang resleting celananya rusak dan hanya diikat dengan peniti sebagai gantinya. Ada pula yang celananya kelonggaran dan ikat pinggangnya dari tali ala kadarnya.
Naik kelas empat SD, saya pindah ke Kota Watampone, kota kelahiran Wapres Jusuf Kalla. Oh ya, jangan kira saya pindah ke kota karena orang tua saya kaya. Justru sebaliknya, bapak saya yang hanya pembuat gula merah menganggap pendidikan tidak terlalu penting, maka saya ikhlas saja saat orang lain yang cukup kaya mau membiayai sekolah saya. Tentu tidak gratis. Karena setiap subuh, setiap hari, saya harus bangun membersihkan, menyapu, mengepel rumah beserta pekarangannya yang luasnya hampir separuh lapangan sepak bola.
Saya juga harus siap sedia setiap waktu disuruh ke sana ke sini. Suka tidak suka yah harus suka. Yah memang demikianlah harga yang harus dibayar untuk seorang yang lahir dari keluarga miskin seperti saya.
Di kota itu, saya bersekolah di salah satu SD favorit. Dan tebaklah apa yang terjadi. Saya, yang walaupun tak pernah menembus ranking dua besar di kampung, tercecer di peringkat akhir. Saya menjadi bahan ejekan. Di rapor tertulis angka merah untuk nilai sejarah. Wali kelas saya menulis di catatan untuk wali saya alias donatur saya, “Harus lebih giat belajar.”
Sedih sih. Tetapi saya juga sadar. Saya harus bersaing dengan anak-anak orang kaya yang tiap hari minum susu yang bukan susu kental manis dan makan bergizi setiap hari. Untungnya, lingkungan kelas yang kompetitif mendorong saya untuk belajar lebih keras lagi. Sampai akhirnya saya bisa nangkring di ranking kedua di semester terakhir.
Dengan modal inilah, saya diterima di sekolah SMP terfavorit di saat itu. Bahkan saya beruntung bisa masuk kelas unggulan. Siswa-siswa terbaik dari SD seantero kota dikumpulkan dalam satu kelas itu. Setiap kenaikan kelas akan ada beberapa yang terlempar ke kelas lain digantikan dari kelas yang dianggap unggulan kedua.
Lagi dan lagi, teman-teman saya adalah anak-anak orang kaya. Bahkan beberapa di antaranya adalah anak-anak pejabat dan pengusaha kaya. Ketika perkenalan, teman-teman saya menyebut rupa-rupa pekerjaan orang tuanya. Dari Kepala Kejaksaan, Kepala Dinas, Kepala Sekolah, Pengusaha Kain, sampai kemudian giliran saya: Seorang Petani.
Mereka, teman-teman saya yang cerdas, selalu dibanggakan guru ke kelas-kelas lainnya. Langganan juara lomba kabupaten sampai utusan ke tingkat provinsi. Saat itu saya pikir wajar, kami memang memiliki segalanya. Fasilitas belajar yang lengkap, guru-guru terbaik, plus dengan murid-murid bibit unggul.
Persaingan yang ketat memotivasi saya untuk belajar lebih keras lagi. Sebab saya sadar, saya tidak punya modal setara seperti teman-teman saya. Pada akhirnya ini membuat saya harus bekerja lebih keras dibandingkan teman-teman saya. Saya sadar, anak miskin seperti saya memang perlu distimulasi oleh lingkungan sekitarnya agar mau belajar lebih keras. Jadi, saya pikir lingkungan yang sulit itu di sisi lain justru jadi berkah tersendiri untuk saya.
Begitu tamat SMP masalah bukannya selesai, malah semakin jadi masa-masa tersulit. Saya memang berhasil merangsek tiga besar dan pintu sekolah SMA favorit terbuka lebar. Apa daya, saya tidak punya biaya lagi. Di sisi lain, saya juga sudah tidak sanggup tinggal menumpang lagi.
Dengan terpaksa saya harus kembali ke kampung. Saya terpaksa melanjutkan ke sekolah yang baru berdiri dua tahun. Jangankan laboratorium, di sekolah ini perpustakaan pun tak punya. Ruangan kelasnya juga baru tiga. Salah satu kelasnya bahkan separuhnya terpaksa dipakai untuk kantor.
Kondisi ini membuat saya kembali berada di lingkungan dengan teman-teman yang jauh berbeda dengan di kota. Saya tidak lagi memiliki keinginan untuk belajar lebih keras. Lingkungan membuat saya berleha-leha. Tak ada semangat untuk berkompetisi. Informasi-informasi soal lomba yang bisa meningkatkan gengsi sekolah juga sangat terbatas. Bahkan untuk membaca cerpen dan puisi di koran setiap hari minggu pun tak bisa.
Di sekolah itu, saya memang juara sekolah sampai tamat. Sempat juga saya mewakili sekolah olimpiade tingkat kabupaten walau tidak pernah berhasil. Meski begitu, saya masih merasa semakin tertinggal perihal pengetahuan, informasi, dan kesempatan dengan teman-teman SMP saya yang dulu.
Selepas SMA, saya semakin menyadari ketertinggalan saya. Ketika teman-teman SMP dulu dengan lancar dan mudah diterima di jurusan-jurusan favorit di kampus-kampus terbaik, saya tergopoh-gopoh dan susah payah mendaftar sana sini. Barangkali sama seperti susahnya menulis untuk bisa menembus Mojok.
Melihat di depan mata kepala saya sendiri bahwa masa depan teman-teman SMP yang kelihatannya lebih cerah membuat saya enggan untuk kalah. Semangat untuk belajar keras agar bisa seperti mereka mendorong saya untuk belajar lebih keras lagi.
Sudah berhasilkah saya? Saya tidak tahu. Sebab berhasil atau sukses itu kan relatif. Namun, bagi orang udik dan miskin seperti saya, meraih beasiswa dan menikmati pendidikan sampai ke luar negeri adalah keberhasilan tak ternilai harganya. Bahkan melebihi karya-karya Andrea Hirata.
Saya tahu betul, sekolah atau kampus favorit memang bukan penentu nasib. Tak ada garansi kesuksesan di sana. Tetapi sekolah dan kampus favorit menyediakan kesempatan lebih besar. Favorit atau tidaknya sekolah beserta ketersediaan fasilitasnya memang bukan satu-satunya penentu nasib masa depan anak. Itu sebabnya akan ada orang-orang yang berhasil seperti Steve Jobs, Bill Gates, Mark Zuckerberg, atau mungkin Susi Pudjiastuti dan Agus Mulyadi yang cuma sempat sampai bangku SMA.
Pertanyaannya, apa semua orang memiliki sikap mental seperti mereka? Belum tentu. Kalau asal ikut-ikutan dengan langkah-langkah mereka, seorang anak salah-salah bisa dianggap gegabah dan bisa saja berakhir sia-sia. Terkesan heroik di depan, tapi cuma jadi cerita kebanggaan semu untuk dongeng penuh penyesalan di belakang.
Itulah yang membuat saya di satu sisi senang dengan sistem zonasi sekolah sekalipun masih banyak kekurangannya. Hanya karena alasan sederhana, agar anak-anak orang kaya di kampung saya tidak lagi sibuk mengirim anaknya ke kota dan meremehkan sekolah-sekolah di kampung mereka sendiri.
Di sisi lain saya juga khawatir, apakah pemerintah mampu melaksanakan dengan paripurna ide zonasi ini. Seperti misalnya memastikan kualitas lingkungan (dalam hal ini sekolah) guna memberikan akses pendidikan terbaik bagi anak-anak di mana pun mereka berada.
Sebab sependek pengalaman saya selama ini, semuanya adalah tentang seberapa besar kesempatan yang disediakan oleh lingkungan beserta fasilitas sekolah yang memadai. Dibandingkan cerita-cerita berhasil seperti Susi Pudjiastuti atau Agus Mulyadi itu, sebenarnya jauh lebih banyak anak-anak yang gagal karena memang sekolah tidak menyediakan fasilitas yang cukup untuk mereka.
Pada titik tertentu, hal ini bisa saja berpengaruh pada cara pikir keluarga anak-anak tak mampu bahwa sekolah adalah pilihan berisiko tinggi. Dianggap semakin membuat hidup makin sulit, tidak berpengaruh banyak, ya wajar kalau kemudian dianggap tidak penting.
Pada akhirnya, dari tulisan ini saya hanya berharap, semoga sistem zonasi ini bisa semakin mengurangi cerita anak-anak yang harus mengalami kehidupan seperti saya. Sebab saya yakin, setiap anak—di mana pun mereka berada—mereka semua istimewa dan berhak mendapat fasilitas pendidikan yang merata. Karena satu hal yang saya yakini; tidak semua anak di negeri ini bisa seperti Susi Pudjiastuti atau Agus Mulyadi.