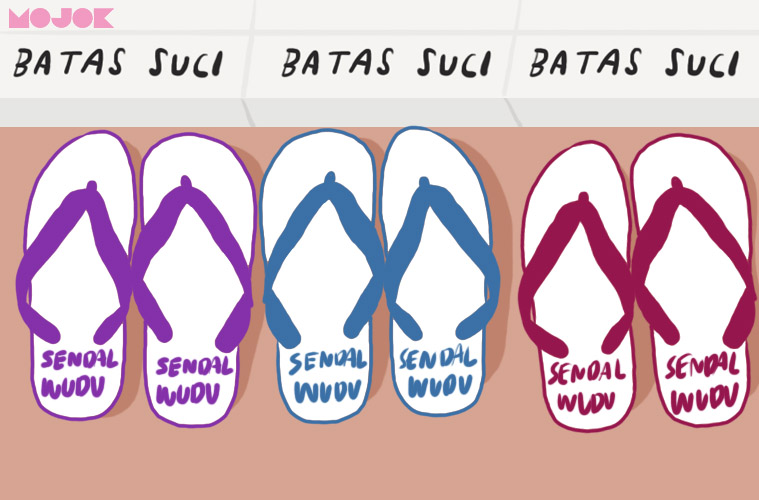MOJOK.CO – Sebuah realitas di daerah Bantul, Yogyakarta. Pembangunan masjid dengan dana dari Timur Tengah sedang masif. Cukup banyak yang anti-bidah. Mau protes tapi kok ya sadar diri, salat di masjid saja jarang-jarang.
Dari sekian provinsi di Indonesia, Yogyakarta adalah salah satu provinsi yang banyak menghadirkan bangunan megah berupa masjid. Setidaknya, dari empat kabupaten dan satu kota, Bantul adalah wilayah yang paling progresif untuk urusan pembangunan masjid.
Mengapa demikian? Selidik bin selidik ada “ikatan” antara penguasa di sana dengan pemberi bantuan dana pembangunan masjid. Memangnya dari mana dana berasal? Hampir sebagian besar berasal dari Timur Tengah. Ada yang dari Arab Saudi, Kuwait, Qatar, UEA, dan lain sebagainya. Ya kalo berasal bukan dari Timur Tengah, bentuknya juga bukan masjid lah, melainkan mall.
Saya berani menulis begini karena dulu pernah terlibat penelitian mengenai masifnya pembangunan masjid di Bantul serta melacak dari mana aliran dana pembangunan tersebut. Penelitian tersebut dilakukan mengingat Dewan Masjid Indonesia (DMI) tidak mempunyai data riil seberapa banyak pembangunan masjid di Indonesia terutama di Bantul. Tambahan lagi, penelitian ini juga digunakan untuk melihat manfaat atau potensi “bahaya” dari bantuan dana dari Timur Tengah tersebut.
Mulanya, saya dan beberapa teman memetakan mana saja masjid yang mendapat dana bantuan dari Timur Tengah. Ada tiga cara sederhana untuk menandainya. Pertama, biasanya masjid yang baru dibangun pintunya berbentuk elips, semacam melengkung kayak es krim Walls. Kedua, di sisi kanan atau kiri terdapat plakat berbahasa Arab. Ketiga, bangunan masjid tidak ada terasnya.
Pada tahap selanjutnya kami juga perlu mengetahui apakah pemberian dana pembangunan disertai permintaan “imbalan” dari pihak penyandang dana. Imbalan di sini bentuknya macam-macam, misalnya, pengurus masjid harus memberi slot jatah penceramah dari Timur Tengah yang perlu dihadirkan pada momen-momen tertentu di masjid tersebut.
Kebetulan, karena waktu penelitian itu masuk bulan Ramadan, saya jadi menemui cukup banyak masjid yang menghadirkan ulama-ulama dari negara penyandang dana pada beberapa momen Ramadan, momen Nuzulul Quran misalnya.
Tidak cuma untuk acara tahunan, beberapa masjid ada juga yang menghadirkan “tamu” penceramah tiap dua minggu sekali. Nggak main-main lho, penceramah ini terbang langsung dari negaranya. Meski begitu, ada juga beberapa masjid yang tidak memiliki ikatan kerja sama seperti ini. Biasanya sih yang model begini pemberi dananya adalah individual. Jadi, ya semacam hibah dana. Kalo soal isi ceramah, bisa beragam. Kebanyakannya sih hanya perkara soal fikih dan akidah. Bukan sesuatu yang patut dicemaskan juga.
Lha kalau penceramahnya dari Timur Tengah begitu terus bahasa yang digunakan apa dong saat ceramah? Ya jelas pakai bahasa Arab. Ada juga yang pakai bahasa Indonesia, cuman tidak banyak. Yang jelas ngga ada yang pakai bahasa Mbantul. Soal apakah pendengarnya paham atau tidak, wah itu bukan urusan saya.
Memangnya berapa dana yang dibutuhkan untuk pembangunan masjid di Bantul? Seingat saya, kisarannya antara 300-400 juta dengan durasi pembangunan yang disyaratkan harus selesai dalam waktu 3-4 bulan saja. Buset, benar-benar kecepatan pembangunan yang luar biasa.
Cara mendapatkan dananya pun tidak ribet-ribet amat. Cukup menyediakan lahan kosong dan mengajukan proposal, lalu tahu koneksi untuk bisa menghubungi pihak sana, selesai urusan. Lain soal kalau kamu ingin renovasi masjid kampung dan membutuhkan dana dari mereka. Nah, yang semacam ini rupa-rupanya belum pernah disetujui untuk didanai.
Saya tahu betul karena hal semacam ini pernah terjadi pada masjid di kampung saya. Waktu itu, tetangga-tetangga saya mengajukan proposal renovasi masjid. Sayang, langsung ditolak begitu saja. Alasan ditolak ya karena mereka menginginkan pembangunan masjid dari awal, bukan merenovasi dari bentuk bangunan sebelumnya.
Demi bisa mendapatkan masjid yang lebih besar dan memadai, masyarakat pun rela merobohkan masjid dulu lalu membangunnya lagi dari awal. Selain agar dapat dana, rupa-rupanya pihak pemberi dana memang menginginkan adanya penyeragaman bentuk-bentuk masjid yang mereka danai. Biar ada signature-nya gitu, jadi semacam ciri khas.
Lalu apakah mereka mengatur jamaah harus berpakaian dan model beribadah di masjid tersebut? Ada yang iya, meski ada juga yang tidak diatur sampai segitunya. Untuk hal itu, saya tahu karena saat meneliti salah satu masjid di Bantul, saya sempat ada diskusi kecil tentang pakaian apa yang harus digunakan. Harus berjubah? Atau cuma pakai sarungan boleh? Atau yang bagaimana?
Nah, dari sekian pengamatan saya, masjid di daerah Bantul sebelah Timur ini yang paling seru. Tempatnya sangat besar. Semacam kompleks yang cukup lengkap. Ada minimarket, rumah sakit, hingga sekolah yang berafiliasi dengan pengurus masjidnya. Begitu masuk ke dalam, saya yang bersama seorang kawan sejenak terpana. Bersih sekali di sana, rasa-rasanya seperti bukan di Indonesia.
Di ruang tunggu, kami melihat ada tiga televisi yang semuanya menyetel acara televisi yang sama. Kebetulan, waktu itu ceramah di sana isinya tentang akidah. Seorang lelaki paruh baya mendatangi kami. Bersalaman lalu mengajak duduk di ruang tengah. Mulanya, saya dan teman saya agak sedikit canggung, bagaimana ya harus memulai percakapan? Tapi, agaknya teman saya punya ide brilian.
Dia hanya perlu mengucapkan pertanyaan sakti:
“Jadi bagaimana ini Ustaz, kok tahlilan merebak di kawasan ini?”
Sesuai dugaan, wajah ustaz di depan kami langsung bungah.
“Iya itu, itu bidah!”
Wah, sukses pancingannya~
Sumpah saya nahan ketawa saat itu. Bukan apa-apa, cuma heran saja, kok pertanyaan awal dari teman saya ini sungguh tepat sasaran. Setelah merasa kami ini juga kelompok anti-bidah diskusi jadi mengalir dengan lancar. Cerita pengembangan masjid, pondok, lini usaha, dan santri-santrinya. Gayeng.
Setelah ngobrol-ngobrol, kami diajak berkeliling ke beberapa kelas di sekolahan dekat masjid anti-bidah tersebut. Entah karena apa, saya tak menemukan foto Presiden dan Wakil Presiden di setiap kelasnya. Belakangan saya tahu kalau foto tersebut baru akan dipasang menjelang penilaian akreditasi saja. Setelah itu ya dicopot lagi. Cerdik juga, batin saya. Ngguatheli saja tapi rasanya. Meski begitu, saya juga nggak berani menduga macam-macam sampai urusan politik mereka. Lha piye? Peneliti je.
Oh iya, peristiwa itu terjadi tiga tahun lalu. Setelah didata, kalau saya tidak salah ingat, jumlah masjid yang didanai Timur Tengah berjumlah 200-an. Angka yang fantastis. Itu cuma di Bantul saja lho, hanya satu kabupaten, belum kalau menghitung satu provinsi.
Kalau mau sedikit jujur, beberapa masjid yang saya teliti memang ada yang anti-bidah. Cukup tertutup dengan beberapa tradisi masyarakat dalam beribadah. Jangankan kenduren atau tujuh harian orang meninggal, tahlilan saja dianggap sebagai penyakit yang mesti disembuhkan kok. Tentu tidak semua masjid berdana Timur Tengah begitu, tapi kalau dibilang cuma sedikit, oh enggak juga.
Saya sendiri awalnya sempat mau protes. Lha kok begitu caranya? Kenapa masyarakat asli malah jadi terjauhkan dengan masjid di kampung mereka sendiri. Kenapa apa-apa yang dilakukan masyarakat mendadak jadi dilarang, dianggap bidah, dianggap mengada-adakan ajaran agama?
Ingin rasanya tidak terima, tapi saya mendadak sadar diri ketika mendengar pertanyaan simpel dari seorang ustaz yang sealiran mereka.
“Kami yang memakmurkan masjid kok kami yang disalah-salahkan? Lha emang situ ke mana aja nggak pernah ke masjid?”
Kalimat tersebut seperti menampar saya. Ya memang sih, harus diakui, mereka ini lebih sering mengunjungi masjid. Tak pernah terlewatkan dalam lima salat fardu. Saya pun merasa tidak berhak untuk protes. Habijimana? Serajin-rajinnya saya, kalau salat ke masjid saja hanya saat magrib dan isya saja. Selebihnya? Ya… kerja-lah, pengangguran po piye?
Dari hal itu saya jadi belajar, bahwa mungkin ada baiknya kita ikut memenuhi masjid-masjid tersebut. Bukannya malah bikin masjid tandingan. Salah-salah malah jadi bikin kubu-kubuan nanti dalam satu kampung. Bisa jadi rasan-rasan sampai memicu ketegangan malahan. Apalagi cuma teriak-teriak di media sosial. Duh, dek, yang begituan ndak ngefek sampai bawah-bawah.
Okelah, kalo kamu atau kadang saya bilang, “Hati-hati mereka suka mengkafirkan.” Tapi apakah benar demikian? Jangan-jangan itu cuma dugaan kita saja. Lha nyatanya, tidak semuanya keras kok walaupun cara pikirnya berbeda dengan Islam kiai-kiai kampung di sekitaran kita.
Bagi saya, boleh setuju atau tidak, lebih baik tindakan seperti ini dilawan dengan sering-sering ikut salat masjid mereka saja. Datang silaturahmi, berbaik sangka, mengajak dialog pelan-pelan. Bukan dengan sumpah serapah bahwa mereka adalah kelompok intoleran dan mengaku-aku benar sendiri. Lha kalau gitu caranya, terus bedanya kita sama mereka apa?