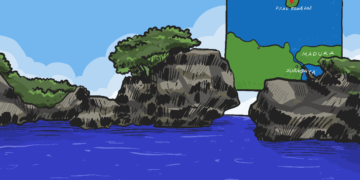Di grup-grup WhatsApp yang saya ikuti, beberapa pekan terakhir bermunculan pesan berantai yang memuat ajakan untuk merobohkan patung paling hits di Tuban saat ini.
Revolusi bermula dari Tuban, mari robohkan patung Dewa Kong Cho Kwan Sing Tee Koen!
“Apa? Merobohkan patung bagian dari revolusi?” tanya teman saya setelah membaca kiriman satu anggota grup WA yang mengajak berdemonstrasi di kantor DPRD Jatim.
Saya tertawa mendengarnya.
Habis, ajakan revolusi-merobohkan-patung itu lebih kayak guyonan. Yang mau dirobohkan kan “kenalan lama” kami.
Waktu saya sekolah di MTs Negeri Tuban, Kelenteng Kwang Sing Bio yang jadi tempat berdirinya patung itu cuma berjarak satu kali lompatan pagar. Bersama sekolah saya, kelenteng itu berada di sebuah pertigaan kecil di jalan Pantura, pinggir pantai Tuban. Nama pertigaan itu Gerdu Laut.
Ada beberapa bangunan yang menjadikan kawasan ini ramai. Di Jalan Diponegoro ada MTs Negeri Tuban, SMP Negeri 2 Tuban, kantor Nahdlatul Ulama, dan Rumah Sakit Muhammadiyah. Di sisi barat, di Jalan R.E. Martadinata, berdiri Kelenteng Kwan Sing Bio.
Bangunan instansi dari agama-agama berbeda dengan lokasi berdekatan bukan hal ajaib di Indonesia. Bisa dibilang sama lumrahnya dengan Alfamart dan Indomaret yang secara misterius suka sekali sebelah-sebelahan. Contoh paling populer ada di Jakarta, Masjid Istiqlal berhadap-hadapan dengan Gereja Katedral.
Di Kelenteng Kwang Sing Bio dulu saya sering keluyuran dengan teman-teman. Karena kami bersekolah di MTs, teman-teman perempuan tentu semua berjilbab, tapi tidak ada yang canggung masuk kelenteng. Selain melihat-lihat, kadang kami meminta lilin yang besarnya selingkaran paha orang dewasa untuk bahan mainan atau bekal kemah.
Namanya saja tempat ibadah, sewajar patung Yesus dan Bunda Maria ada di gereja atau patung Buddha ada di Borobudur, di kelenteng itu ada banyak patung dewa. Kami mengamatinya satu per satu dari jarak dekat. Juga memperhatikan umat Tri Dharma beribadah dan menyalakan dupa.
Ada yang menarik dari cara mereka beribadah? Tentu iya. Tertarik mau ikut beribadah? Tunggu dulu.
Kami orang tetap pulang dan belajar Al-Quran beserta tajwidnya di kiai masing-masing. Besoknya, main lagi ke kelenteng setelah sekolah. Aktivitas kayak begini juga banyak dilakukan siswa-siswa dari sekolah lain.
Akulturasi dengan kultur Tionghoa bukan sebatas main ke kelenteng saja. Teman-teman sekolah saya banyak yang ikut berlatih bela diri Tiongkok dan belajar memainkan barongsai. Saban peringatan ulang tahun Kong Cho yang patungnya dipolemikkan itu, yang memainkan barongsai ya mereka-mereka ini. Biasanya mereka berlatih seminggu tiga kali, dengan malam harinya tetap ngaji diniyah seperti biasa.
Kelenteng Kwang Sing Bio punya halaman belakang luas. Di halaman inilah patung setinggi 30 meter itu berdiri. Di sini pula para pemuda kerap bermain bola, kongkow-kongkow, cari cem-ceman, atau sekadar merokok santai tanpa harus menggadaikan keimanan dan nasionalisme.
Contoh lain hubungan harmonis beda agama di Tuban ada di Kelurahan King King, Kecamatan Tuban, yang mana sebuah masjid berdiri berimpitan dengan gereja. Plek gedek, istilahnya. Bangunan itu hanya dipisahkan pagar semenjak berdiri sampai saat ini.
Suatu saat ada acara keagamaan cukup besar yang digelar di salah sebuah rumah ibadah. Kemudian apa yang terjadi? Ya nggak ada apa-apa. B aja. Biasanya salah satu rumah ibadah malah mempersilakan halaman depan mereka dijadikan tempat parkir selama acara berlangsung.
Intinya, orang Tuban sudah biasa dengan keberagaman. Mau dibakar dengan sentimen agama? Nggak mempan. Buktinya, yang teriak-teriak untuk merobohkan patung itu bukan warga Tuban kok.
Ketika isu agama tidak mempan, dipakailah isu provokatif lain. Misalnya, patung itu sengaja dibuat tinggi sebagai bukti arogansi warga Tionghoa di Indonesia. Apa pula ini? Di Indonesia kan kita sudah biasa dengan fasilitas-fasilitas keagamaan yang dibuat sebagus atau sebesar mungkin. Tujuannya adalah penghormatan kepada agama. Logika congkak ini bahaya sekaligus “nggak masuk”, gampang dibalikkan ke, misalnya, masjid terbesar atau masjid kubah emas.
Ketika demonstrasi menolak patung beneran dilakoni di depan kantor DPRD Jawa Timur dengan massa yang konon ribuan orang, coba cek daftar pesertanya. Sepertinya, tidak ada satu pun lembaga asal Tuban yang ikut berpartisipasi. Apa itu karena orang Tuban takut demo? Bukan. Itu karena mereka melihat tidak ada yang gawat.
Pada akhirnya, debat kusir di media sosial tentang patung Kwan Sing Tee Koen itu sesungguhnya berbanding terbalik dengan keadaan di lapangan. Karena masalah patung itu hanya soal izin.
Dualisme kepengurusan (sejak beberapa tahun terakhir masih belum ada pengurus resmi) itulah yang jadi persoalan antara pengelola kelenteng dengan pemkab Tuban. Penutupan patung dengan kain (bukan dikasih jubah atau kerudung, apalagi pocong) adalah jalan tengah sementara, menunggu sampai perizinan tuntas dan isunya tidak tambah panas. Kedua belah pihak juga menyepakati cara itu.
Jadi, jangan lagi menggoreng isu. Tuban tetap adem ayem tentrem perihal toleransi beragama, walau sedang berperang dengan masuknya industri-industri besar, berbanding terbalik dengan angka kemiskinan yang terus meningkat. Belum lagi penataan lingkungan yang masih amburadul.
Mbok itu saja yang diramaikan dan dijadikan isu nasional. Mbok itu saja yang direvolusi.