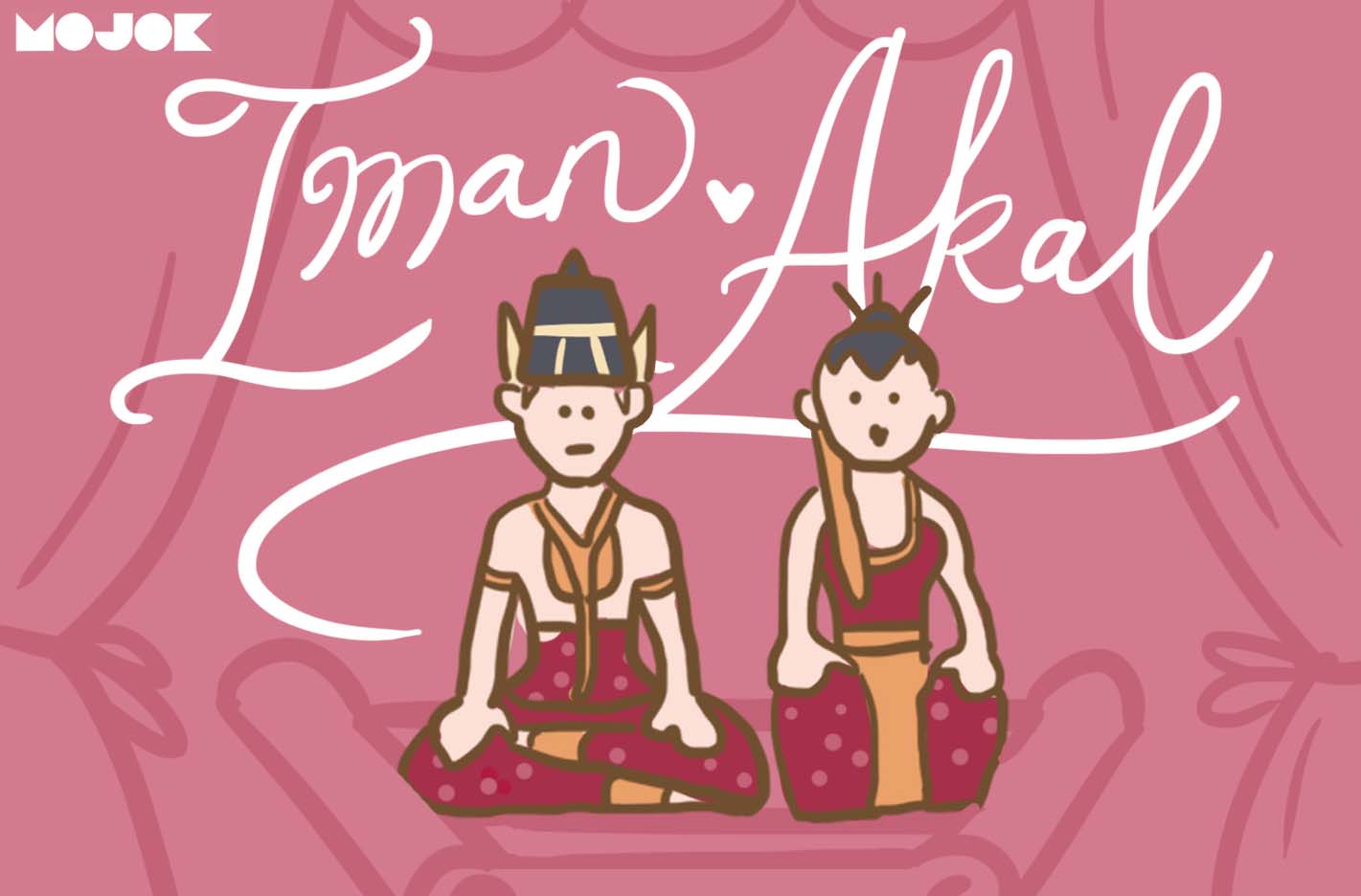MOJOK.CO – Konglomerat sekaligus pemerhati dunia Islam, Edi AH Iyubenu, turun gunung menanggapi tulisan Esty Dyah Imaniar soal kaum hijrah versi nakal.
Saya terkekeh membaca celetukan Dik Ukhti Esty Dyah Imaniar di Mojok yang dengan nakal memplesetkan slogan kondyang Rene Descartes, si Bapak Modernisme yang bikin galau Huston Smith hingga Fritjof Capra, “Aku berpikir maka aku ada,” menjadi, “Aku berislam maka aku berpikir.”
Saya sependapat dengan curhat resah tersebut. Resah, maksud saya begini, karena Dik Ukhti itu kan bagian nyata dari Muhajirin Milenial tapi versi Bakunin. Tak heran kalau sampai muncul kritisismenya.
Soal konsekuensi tak lagi diundang liqa’ dan sejenisnya, saya mendoakan Dik Ukhti bisa menyikapinya sebagai bagian alamiah dari dinamika perjalanan rohani dan intelektual belaka. Siapa tahu, suatu hari, mendadak Dik Ukhti diundang Gus Miftah dan dihadiahi kacamata hitamnya to.
Utang akal, ini fakta “gaya berislam” sebagian kita kini. Buah langsung puritanisme yang melek sebelah mata. Tentu ndak mashok bagi wong NU. Karena wong NU itu progresif yang tradisional atau tradisional yang progresif.
Menjadi pelik benar memang tatkala perkara ilmu yang jelas khittahnya selibat dengan kritisisme-kritisisme dijegal dengan palang kekafahan iman.
Ini problem serius kita kini! Sebuah logical fallacy yang sangat serius!
Membenturkan iman yang esoteris (rohaniah) dengan ilmu pengetahuan yang kognitif (diskursus) sehingga keduanya terpolarisasi bak musuh abadi khas cebong dan kampret yang sama-sama jelek, bau, dan misquen setamsil ini persis ungkapan Imam Ghazali dalam bab ilmu yang ditujukan kepada orang bodoh tapi ngeyelan, “Dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu….”
Nah, lho.
Bahwa iman menuntut secara hakiki “amantu bilLah wa la ilaha illaLah….” dan dimensinya adalah hati, batin, rohani, iya. Bahwa untuk beriman kita mesti meyakini, bahkan termasuk kepada hal-hal yang suprarasional (bukan irrasional), iya.
Tetapi tepat di detik itu juga iman yang hakiki (kata mereka tsiqah) automenisbatkan ilmu pengetahuan, nalar akal, teori dan paradigma, hingga kemudian menjelma sempurna sebagai worldview cum weltanschauung Islam.
Lah, kamu kira Islam bukan worldview cum weltanschauung?
Jika bukan, bagaimana mungkin Islam pantas disebut dan dijadikan way of life, yang artinya juga meliputi urusan mencari rezeki, sedekah, bakulan, berutang-piutang, yang-yangan, meniqa, manak, bikin kafe, nerbitin buku, dan sebagainya?
Jika iya, bagaimana mungkin ia disapih dari ilmu, metodologi, dan analisis ilmiah cum akademik, yang berarti autowajib (bukan hanya autohalal) melibatkan kritisisme-kritisisme?
Hayo, sekarang sampeyan mau milih “bukan” atau “iya”?
Jadi, sampai di sini, dapat dinyatakan dengan terang bahwa ilmu pengetahuan adalah pengukuh iman. Bukan antitesanya.
Kurang banyak gimana lagi ungkapan Al-Quran seputar “afala ta’qilun, liqaumin yatafakkarun, yatafaqqahun, hingga ulul albab” yang mendorong kepada urgensi telaah ilmu?
Bukankah dalam Al-Quran pun bahkan ada ayat yang memerintahkan para sahabat untuk tidak semuanya terjun ke medan perang atas nama jihad, tetapi hendaknya ada sebagian yang berkhusyuk dengan kajian ilmu untuk kepentingan syiar Islam dan itu pun bernilai jihad fi sabililLah?
Kurang terang apa lagi hadis-hadis Rasul Saw semacam “menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim dan mulimah”, “majelis ilmu lebih mulia daripada beribadah banyak-banyak”, hingga “siapa yang mengenal dirinya maka ia telah mengenal Tuhannya” yang menisbatkan mutlak peranan fundamental ilmu pengetahuan?
Dan, kurang terang apa lagi sejarah jenius Sultan Al-Fatih dalam menaklukkan Konstantinopel yang benar-benar disumbangkan oleh strategi hebatnya dalam menjebol benteng kokoh itu?
Baiklah, Bro, sekarang saya akan menawarkan satu fakta pembentukan hukum Islam (Ushul Fiqh) yang niscaya sulit untuk engkau tolak.
Secara umum, para ulama Ushul Fiqh bersepakat bahwa hierarki sumber hukum Islam adalah Al-Quran, sunnah, ijma’, dan qiyash. Lalu, di luar empat itu, masih ada banyak lagi macam qaulus shahabah, ‘urf, hingga mashlahah mursalah.
Kemudian, ada dua pilar utama dalam mekanisme teknis pembentukan (ijtihad, bahtsu) hukum Islam (fiqh) itu, yakni maqashid syariat (hal yang menjadi tujuan syariat) dan ‘illatul hukm (konteks yang melatari pembentukan suatu hukum) dengan relasi hierarkis begitu pula.
Maqashidus syariat itu abadi, berlaku universal, terkandung kekal di dalam dalil-dalil, bisa dzahir (qath’i, terang) dan batin (dzanni, samar). Slogannya adalah shalih likulli zaman wa makan alias selalu relevan dengan setiap zaman dan tempat (lokalitas).
Jika maqashidus syariat bersifat terang dalam suatu dalil, mudahlah ia disimpulkan. Misal, ayat “waqulu qaulan sadidan, ucapkanlah kata-kata yang baik”.
Maqashidus syariat-nya jelas: bicaralah dengan pembicaraan yang baik dan autosebaliknya jangan bicara dengan perkataan yang buruk.
Ajaran ini berlaku selamanya dan universal. Mau di Bantul maupun Jeddah, ya sama begitu prinsipnya.
Kalau begitu, bagaimana dengan pisuhan? Autoharamkah?
Nah, bentar, bentar. Ini sudah masuk ke ranah ‘illatul hukm, suatu konteks yang melatari terbentuknya suatu hukum. Namanya konteks, slogannya sejenis ini: tak ada yang abadi (ala Ariel Noah), tak universal, alias lokal dan kondisional.
Maka, boleh jadi karena saking akrabnya saya dengan Mas Haryo (itu lho, penulis rubrik Celengan Mojok), setiap ketemu, kami berebut nguluk salam begini: “Halo, Cuk, sehat, Cuk? Wes mangan ndomie, Cuk? Njuk piye rasane diblokir Zuckerberg, Cuk?”
Cak-cuk-cak-cuk itu salam akrab kami tanpa secuilpun ada niat di hati untuk menyakiti satu sama lain sebab kami saling menyayangi lahir-batin bagaikan sambal dan teri di dalam bungkus nasi angkringan. Jadi, pisuhan tersebut tidak bisa divonis bagian dari “perkataan buruk”.
Lain cerita jika sampeyan meneriakkannya pada orang asing di jalanan: “Minggir, Cuk, asu bajingan,” jelas di situ ada hati yang tersakiti, maka otomatis terlarang bin haram karena menjadi bagian dari “perkataan buruk” itu.
Sekarang mari ambil contoh dalil jual beli.
Jelas bahwa maqashidus syariat bakulan cum bisnis adalah ta’awun (tolong-menolong) sehingga mesti ‘an taradhin (saling rela alias happy to happy). Dilarang ada gharar (tipu-menipu dan rugi-merugikan) dalam segala bentuknya. Moral-ethic ini abadi dan universal.
Lalu di era digital virtual begini muncul media-media jualan online. Marketplace, misal. Bagaimana hukum jual-beli di marketplace?
Ini ranah ‘illatul hukm, suatu konteks khusus di zaman ini yang tak ada contohnya di zaman para sahabat (btw, boleh jadi lho, 50 tahun lagi cara jual-beli dilakukan ala telepati).
Jika semata berdasar prinsip baku-lawasan “tidak ada tuntunannya dari Rasulullah Saw”, diharamkanlah marketplace. Lalu marketplace hanya diisi dan dikuasai oleh China-Israel-Yahudi-Liberal-Sekuler-Thaghut-lalu-China-Israel-Yahudi-Liberal-Sekuler-Thagut-lagi, apa kalian rela?
Demi kejayaan Islam jangan rela dong, maka masukilah potensi marketplace dengan senantiasa berpegang teguh pada asas-asas maqashidus syariat Islam: ta’awun, ‘an taradhin, dan no gharar!
Tapi kan jual-beli di marketplace tak ada barangnya lho? Bukankah itu diharamkan oleh para ulama Fiqh?
Hadeh.
Esensi dari “tidak boleh melakukan jual-beli barang yang tak ada wujudnya” bukan semata virtualitasnya, tapi ya karena benar-benar riil tak ada wujudnya. Sehingga, ketika ada transaksi, terjadilah gharar itu.
Lha memang barang yang diunggah emang ndak ada wujudnya, lalu apa ente mau maketin giginya Megalondon? Jika ada gharar, musnahlah prinsip ta’awun dan ‘an taradhin.
Perhatikan baik-baik urgensi ilmu, nalar, logika, dan perspektif dalam pelbagai tamsil riil istinbath al-hukm tersebut. Seyogianya ya begitulah hukum Islam berdenyar dinamis sesuai dinamika riil kehidupan umat Islam sendiri dengan berdasar Ushul Fiqh yang ilmiah beneran.
Bandingkan dengan hobi mereka yang membekap kritisisme ilmu karena takut benar iman di hatinya terkoyak, lalu meminta umatnya untuk perbanyak ibadah saja. Atau kasih nasihat, “Ukhti, jangan tanya hal-hal yang syubhat, gimana kabar qiyamul lail-nya, one day one juz-nya gimana, jangan yangyangan ya?”
Memang anomali banget gaya berislam anti kritisisme ilmu begitu. Dan ini yang membuat kita jumud. Satu sisi mendamba ghirah Islam mencahayai peradaban dunia, tetapi di sisi lain berkelakuan menjungkalkan Islam ke masa lalu yang out of date alias ahistoris.
Bukankah ini logical fallacy yang sangat serius?
Sekarang coba jawab: Apa mungkin Dik Ukhti Esty Dyah Imaniar bisa menulis di Mojok jika dia tak punya bekal kritisisme ilmu yang keren gitu?
Mustahil! Dik Ukhti keren karena berilmu, lalu berdialektika, dan tetap baik-baik saja tuh sebagai muslimah. Persis kayak saya, yang juga keren. Kandyani og, koyok karo sopo wae.