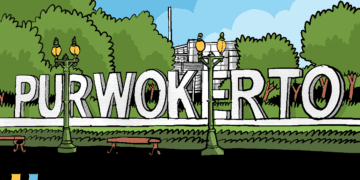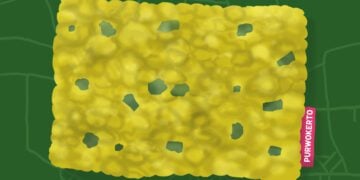Baca cerita sebelumnya di sini.
Saya tak menyukai para selebritas. Ketika Ardyan Erlangga dari Vice Indonesia, yang sering menumpang tidur di kantor kami, menyampaikan temuan koleganya di Amerika Serikat tentang “kemungkinan” pengaruh sebuah novel obskur karangan penulis Indonesia terhadap Freddie Mercury dan David Bowie, saya cuek saja sambil diam-diam, di bawah meja, menggaruk buah-buahan saya buat menghalau bosan, tetapi Sabda Armandio mendengarkan dengan antusias. Ia berulang kali mengatakan, “Terus, terus?” sambil menuangkan anggur merah ke gelas-gelas kami.
“Terus, apa pentingnya?” pikir saya. Kabar kecil tentang orang-orang besar punya kesamaan yang begitu mencolok dengan Tuhan: ada di mana-mana, tetapi tidak berguna. Hanya rekaman tentang orang-orang sepele, yang dilupakan dan terpelanting bahkan dari tempat seremeh catatan-catatan kaki, yang menarik perhatian saya. Barangkali saya merasa sedang bercermin, atau barangkali sekadar bersimpati, kepada mereka. Barangkali saya membenci kebesaran karena tak dapat melihat diri saya dalam setiap gambarnya.
Lahir seorang besar dan tenggelam beratus ribu
Keduanya harus dicatet, keduanya dapat tempat
Bagi Dio, dua baris puisi Catetan Th. 1946 itu tak terpisahkan, tetapi saya selalu berhenti pada “tenggelam beratus ribu.” Tenaga kata-kata itu membuat asam urat saya kambuh. Banyak orang yang membaca buku puisi saya, Pendidikan Jasmani dan Kesunyian, menilai saya sebagai pribadi yang relaks, yang senang melucu-lucukan kesedihan dan penderitaan. Tahu apa mereka? Berjarak betul mereka itu. Asal tahu saja, saya lebih serius ketimbang Marcel Thee dan JRX yang dijadikan satu kemudian dikalikan empat.
Beberapa hari lalu, sehabis sebuah diskusi di toko buku Post, saya menyerang Hikmat Darmawan, orang berambut mullet dari Bandung yang mengatakan, “Beni Satryo lumayan jenaka dan relaks and he’s wow, tetapi sayang sekali tak cukup berani merelaksasi kehidupan beragama masyarakat Indonesia.” Dia mungkin berpikir waktu itu saya sedang coba-coba berlagak akrab, padahal saya mengoleskan misil alias minyak silit ke punggungnya.
Cukup soal itu. Sekarang, saya ingin mengatakan bahwa saya gembira dan sangat menghargai inisiatif Dio dan kawan kami Dea Anugrah—yang kini terbaring di rumah sakit karena demam berdarah dan dengan berat hati mengizinkan saya menggantikannya menulis untuk rubrik ini—buat menggali dan mengabadikan renik-renik kehidupan orang-orang sepele, termasuk Gapi Raja Itam dan Frans Ferdinandus Janurombang dari grup musik Axaxas. Saya tahu mereka melakukan itu karena mengendus pengaruh Arthur Harahap pada lagu-lagu Axaxas, tapi tetap saja. Perhatian kepada kaum kusam, meski dengan alasan berbeda, tetaplah keberpihakan.
Sila baca lebih jauh tentang Axaxas di sini dan dengarkan teaser album-mini mereka di sini.
Gapi dan Frans memang menarik, tetapi musik Axaxas, terus terang saja, buruk sekali. Saya sampai menangis waktu mendengarkannya buat pertama kali. Tetapi keburukan yang menakjubkan itu ampuh. Karena Axaxas, untuk sesaat, saya bisa lebih mencintai diri dan selera saya sendiri. Karena Axaxas, mendoan mbik-mbik, kudapan favorit saya, bahkan terasa lebih nikmat.
“Mendoan mbik-mbik itu apa, Ben?” tanya Dea tak lama setelah ia pulang dari Purwokerto, kota tempat saya tumbuh besar. Dia mendengar istilah itu di sana.
“Itu lho, De. Tempe yang, kalau digigit, bunyinya ‘Mas!’” jawab saya.
Salam,
Beni Satryo, penyair bernapas pendek dan penyelia Radio Cap Ayam
Baca cerita berikutnya di sini.