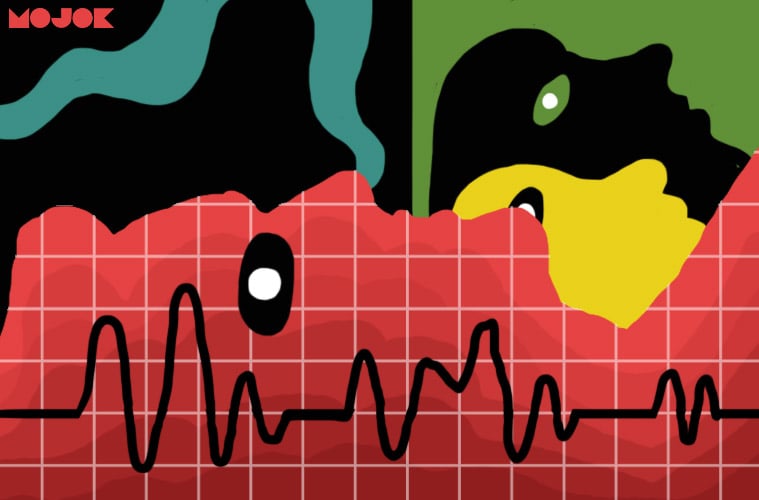Baca cerita sebelumnya di sini.
Jatuh cinta tak ubahnya satu kebebalan yang dikemas dalam kado maha cantik. Pikiran yang sebelumnya terang bisa menjadi temaram hanya lantaran otak tak lagi bisa bekerja sebagaimana mestinya.
Begitulah kiranya yang kurasakan. Aran adalah satu petaka yang menimpa diriku. Mencintainya adalah kebebalan yang tak terkira. Namun, seperti seekor kambing lumpuh yang tak bisa apa-apa, aku masih saja menyimpan iba dan kasih untuknya. Kebebalan seperti apa yang sedang aku lakukan selepas ia menyimpan diriku di lemari pendingin dapur rumah?
Aku ingin membencinya. Ingin rasanya aku melahirkan rasa jijik ketika melihatnya di kantor polisi setelah kegilaannya menghabisiku diganjar hukuman yang setimpal. Ingin juga aku mengutuknya seperti orang-orang yang selama ini menghujatnya. Aku bahkan ingin mendukung Adimas membalaskan dendam.
Namun, meski setiap waktu aku berusaha menumbuhkan pikiran-pikiran seperti itu, tetap saja aku tak kuasa. Aku tak bisa membencinya. Rasa jijikku kepadanya tak bisa bertumbuh. Ada di banyak kesempatan, ketika aku bersua dengannya, perlahan aku masih menyentuh pipi dan jambangnya.
“Satu kali kau harus meminta kepada sipir yang menjagamu itu alat cukur, Mas,” bisikku perlahan sembari membelai pipinya yang mulai dilebati jambang.
Di kesempatan lain, aku akan duduk di sampingnya ketika dia menghadapi sepiring seng berisi nasi, tempe, dan sayur kangkung yang warnanya sama sekali tak mengundang selera.
“Makanlah yang banyak. Kau suka sayur kangkung, kan? Yah, meski kau suka kangkung yang ditumis sebentar saja. Makanlah yang banyak, jangan sampai kau sakit. Kau sekarang kurus sekali,” ucapku di samping telinganya saat ia terlihat tak berselera makan.
Aku masih mengajaknya berbicara, meski kini aku sadar, bahwa ia mungkin tak bisa mendengarku lagi.
Aku paham benar, mungkin selepas 40 hari kepergianku malam itu, portal di langit akan terbuka, dan di masa itulah aku benar-benar akan pergi. Tapi, ada rasa tak rela di dadaku, terlebih ketika melihat Aran seperti saat ini.
Mungkin, pengacara perempuan Aran yang memiliki nama panjang itu—entah siapa namanya, aku kerap lupa mengingatnya—bisa membuat dirinya agak lebih baik. Tapi tetap saja, aku tak kuasa membiarkannya seorang diri di dalam sel yang pengap minim cahaya. Tempat hukuman itu mungkin setimpal untuknya, tapi rasa tak rela selalu menyusup di dadaku ketika melihatnya tidur bergelung memeluk lutut setiap malam.
“Orang-orang mungkin akan mengatakan bahwa aku tolol setelah apa yang kau lakukan kepadaku, tapi aku tetap mencintaimu,” ucapku ketika menemani Aran di dalam selnya.
Aran tak menjawab. Dia hanya menatap dinding putih penjara dengan tatapan kosong yang sedemikian suram.
***
Sudah berhari-hari setelah melihatku dikeluarkan dari lemari pendingin, lelaki muda itu kerap menangis. Matanya sembap, memerah, dan demikian menyedihkan. Rutukan dari bibirnya untuk Aran kerap terdengar di sela rintihannya yang menyesali kematianku.
Adimas Hardoyo terlihat begitu terluka. Aku pergi sebelum sempat mengatakan apa-apa kepadanya. Pertemuan terakhir kami memang tak terlalu berkesan. Seperti biasanya saja; kami bekerja dan membuat program baru untuk satu tahun ke depan.
Bukannya aku tak tahu bahwa Adimas tertarik denganku sejak kuliah, tapi diamnya dia tak bisa kumengerti. Adimas selalu berusaha ada di dekatku. Sebisa mungkin, dia selalu membantuku dalam banyak hal. Ada masa-masa di mana aku benar-benar menjadi ketergantungan akan dirinya. Kehadiran Adimas dan pertolongannya memang candu tersendiri.
Tapi, seolah tak ingin ada kelanjutan dari semua itu, dia hanya memilih diam, menjadi bayang-bayang di belakang punggungku.
Perempuan mungkin bisa bersabar, tapi perempuan bukanlah seseorang yang hanya bisa menunggu sesuatu dalam ketidakpastian. Perempuan juga bukanlah makhluk yang diindahkan untuk menyatakan perasaannya terlebih dahulu. Setidaknya, begitulah bagi diriku.
Maka, dari sekian tahun pertemanan kami, Adimas tetaplah menjadi sahabat dan bayang-bayang untuk diriku. Ia tak bisa mencapai tempat yang lebih tinggi dari itu. Adimas sahabatku yang paling baik dan setia, meski dia juga yang kerap kupatahhatikan berulang kali.
Aku masih mengingat betul waktu itu, saat kukatakan bahwa aku akan menikah.
“Kau serius akan menikah, Sonya?” Matanya sedikit membulat, dia bertanya sembari bibirnya bergetar. Nyata betul dia tak siap ketika mendengar warta berita yang sedang kusampaikan.
“Ya, aku sudah mantap akan menikah, Dim. Kau mendukungku, kan?” Kugenggam tangannya. Terasa begitu dingin dan bergetar.
“Dengan pemuda itu? Kau yakin? Kau tak ingin berpikir ulang? Atau misalnya mencari calon lain?” Adimas tersenyum kecut.
“Calon lain seperti apa?”
Dia terdiam, seolah sulit menjawab.
“Calon yang membuatmu nyaman selama ini. Calon yang baik untukmu, yang ada untukmu dalam banyak waktu.”
“Semisal siapa?”
Aku menanyakan itu dengan dada yang berdebar, bukan lantaran gugup melainkan kesal. Ke mana saja kau selama ini, Dim?!
“Mungkin kawan lamamu,” gumam Adimas.
“Tak ada kawan lamaku yang ingin menikah denganku,” sahutku cepat. Tentu saja selain kau, ucapku dalam hati.
Adimas tak berkata-kata lagi. Ia lebih banyak berdiam. Setelah kabar yang kubawa, di kantor, dia pun lebih sering diam.
Jus alpukat kesukaanku masih dia sediakan di siang hari yang terik. Adimas dan motornya masih sering nongkrong di depan rumah hanya untuk menjemputku. Namun kemudian, dia harus mengalah saat Aran lebih kerap menjemputku. Aku sering kali melihat wajah kesal di mata Adimas saat melihat Aran, tapi siapa yang peduli? Diamnya Adimas selama ini tak bisa lagi kuterka.
Seminggu sebelum aku menikah, Adimas menemuiku di kantor sebelum aku mengambil cuti. Wajahnya muram, bibirnya cemberut. Aku hanya menyimpan senyum saat melihatnya. Entah, meski kadang ada rasa kesal dengan pemuda ini, aku tetap saja tak bisa benar-benar kesal dengannya.
“Jadi kau benar-benar akan menikah dengan ‘gaek’ itu?”
“Gaek?! Dia masih seumur denganmu!” Aku tertawa mendengar Adimas menyebut Aran dengan “gaek”.
“Pikirkanlah lagi, Sonya. Aku melihat dia bukan tipe orang yang baik.” Adimas menatapku dengan sungguh-sungguh.
“Kau tahu apa yang kuinginkan dalam hidupku?” Aku membalas tatapannya.
Adimas menggeleng.
“Aku berharap ingin menemukan seseorang yang bisa mencintaiku apa adanya. Seseorang yang berani mengungkapkan perasaan kepadaku dan mau berkomitmen denganku. Kini aku sudah menemukan itu di diri Aran.”
“Kau mencintainya?”
“Sangat,” jawabku mantap.
Adimas meremas kedua tangannya. Aku melihat patah hati di matanya yang berkaca-kaca.
Setelah melihatnya sepatah hati itu, aku mengira Adimas akan meninggalkanku. Dia mungkin akan menjaga jarak. Tapi ternyata, aku keliru. Bayang-bayang Adimas semakin pekat di belakang punggungku. Bayang-bayang itu kerap hadir, bahkan ketika sinar matahari telah lesap menghilang ditelan malam.
Kini, pemuda yang demikian menyayangiku itu terpuruk dalam duka yang demikian dalam. Seperti malam ini, ia menangis di meja kerjanya yang terletak di sudut kamar tidurnya. Kamar yang biasanya rapi itu terlihat berantakan. Barang-barang terhantar di lantai. Adimas menelungkupkan badan di atas meja.
“Andai aku merebutmu dari bedebah itu, Sonya, aku pasti bisa mempertahankanmu. Bajingan itu tak akan mengakhiri hidupmu,” desah Adimas sembari menelungkupkan kepalanya di atas meja.
“Aku akan berusaha membuatnya membusuk di penjara. Jijik sekali aku dengan manusia laknat itu. Dia telah berani merebut dirimu dari tanganku berulang kali, Sonya. Dia harus merasakan hukuman setimpal!”
Aku seharusnya senang mendengar apa yang diucapkan Adimas, tapi di detik ini aku merasakan rasa nyeri yang lain. Aku tak percaya, bahwa seseorang seperti Adimas bisa sedemikian menyimpan dendam yang demikian besar.
“Relakan aku pergi, Dim. Maafkanlah dia. Dia sama sepertimu, demikian mencintai diriku. Lepaskan amarahmu. Aku ingin kau melanjutkan hidup dengan baik,” bisikku, sembari menyentuh pundak Adimas.
Tak berselang lama, Adimas menegakkan punggungnya. Dia menyentuh pundak kanannya yang baru saja aku pegang.
“Kau di sini, Son? Sonya?!” Adimas berteriak memanggilku, sembari mengedarkan pandangannya ke segala penjuru kamar.
Namun sampai pegal dia mencariku, dia tak akan bisa melihatku. Padahal, aku berdiri tiga jengkal di depannya.
***
Aku masih begitu mencintai Aran. Itu adalah kejujuran yang sangat bodoh. Ketidaksengajaannya menghabisi diriku dengan tulus bisa kuterima, tentu saja ini adalah kebebalan yang melahirkan rutukan banyak orang. Tapi, begitulah adanya; betapa jatuh cinta kepada seseorang bisa melahirkan serangkaian kebebalan-kebebalan.
Namun, sekian hari setelah kepergianku, ada sesuatu yang menimbulkan kegelisahan hati: pengacara Aran yang bernama panjang itu. Aku mengakui bahwa dia mungkin sangat bisa membantu Aran. Tapi, ada waktu aku demikian sebal melihatnya saat menemui Aran.
Di pertemuan pertama, dia bisa membuat Aran bercerita banyak hal sembari menggambar. Di pertemuan kedua, dia mulai leluasa mengumbar senyum untuk Aran. Di pertemuan ketiga, dengan tidak profesionalnya, dia membawa makanan untuk Aran. Bagiku, seorang pengacara tak perlu berlaku seperti itu.
Aran mungkin tak menangkap pesan yang dibawa pengacara itu. Tetapi, sebagai istrinya, meski kini aku telah menjelma menjadi hantu, aku tetap merasakan bahwa pengacara wanita itu sedang menarik perhatian suamiku. Maka, di pertemuan keempat, aku harus waspada turut menemani Aran saat bertemu dengannya.
“Kau tak perlu berbicara bermanis-manis di depan suamiku. Bicara apa perlunya saja. Lagi pula, asal kau tahu, Aran tak menyukai kue-kue manis seperti yang kau bawa itu!” ujarku kesal saat melihat pengacara wanita itu mengeluarkan dua stoples kecil berisi kue-kue.
Tapi sialnya diriku, pengacara wanita itu tak bisa mendengarku. Dia bahkan dengan santainya mengulurkan stoples itu kepada Aran. Kesal, aku menyampar stoples itu. Lalu… Terkejut! Stoples itu terlempar dan pecah membentur lantai. Isinya berhamburan.
Semua orang yang ada di sana terkaget-kaget, begitu pun denganku. Aku tak menyangka aku bisa menampar stoples itu. Hanya Aran saja yang tak terlihat terkejut.
“Sonya tak suka saya diberi hadiah dari wanita lain. Dia selalu cemburu. Kali ini pun sama. Dia tak menyukai Anda memberi saya kue-kue itu,” ucap Aran perlahan. “Sekarang, dia berada di samping Anda.”
Mendengar ucapan Aran, pengacara wanita itu terlihat pucat. Wajahnya mengerut tak percaya.
“Kau cantik hari ini, Sayangku. Terlihat jauh lebih segar dibanding kemarin,” kata Aran sembari menatap ke arahku.
Aku menatapnya tak percaya, sebelum akhirnya tersenyum dan membalas ucapannya, “Kau kelihatan berantakan hari ini. Cukurlah brewokmu itu. Aku malas melihatnya.”
“Nanti akan aku cukur dan rapikan. Biar kau senang,” jawab Aran tersenyum manis.
Aku membalas senyumannya, meski sebenarnya merasa heran: Sejak kapan Aran bisa melihat kehadiranku?
Semua yang ada di ruangan itu terlihat kebingungan, tapi kami seakan tak peduli. Aran berusaha membelai pipi dan daguku seperti dulu. Dengan lembut, aku membalas mencium pipinya, seperti ketika kami saat bermesraan dulu.
Duh, cinta model apa yang sebenarnya sedang kami jalani ini, ya, Tuhan?
Baca cerita berikutnya di sini.