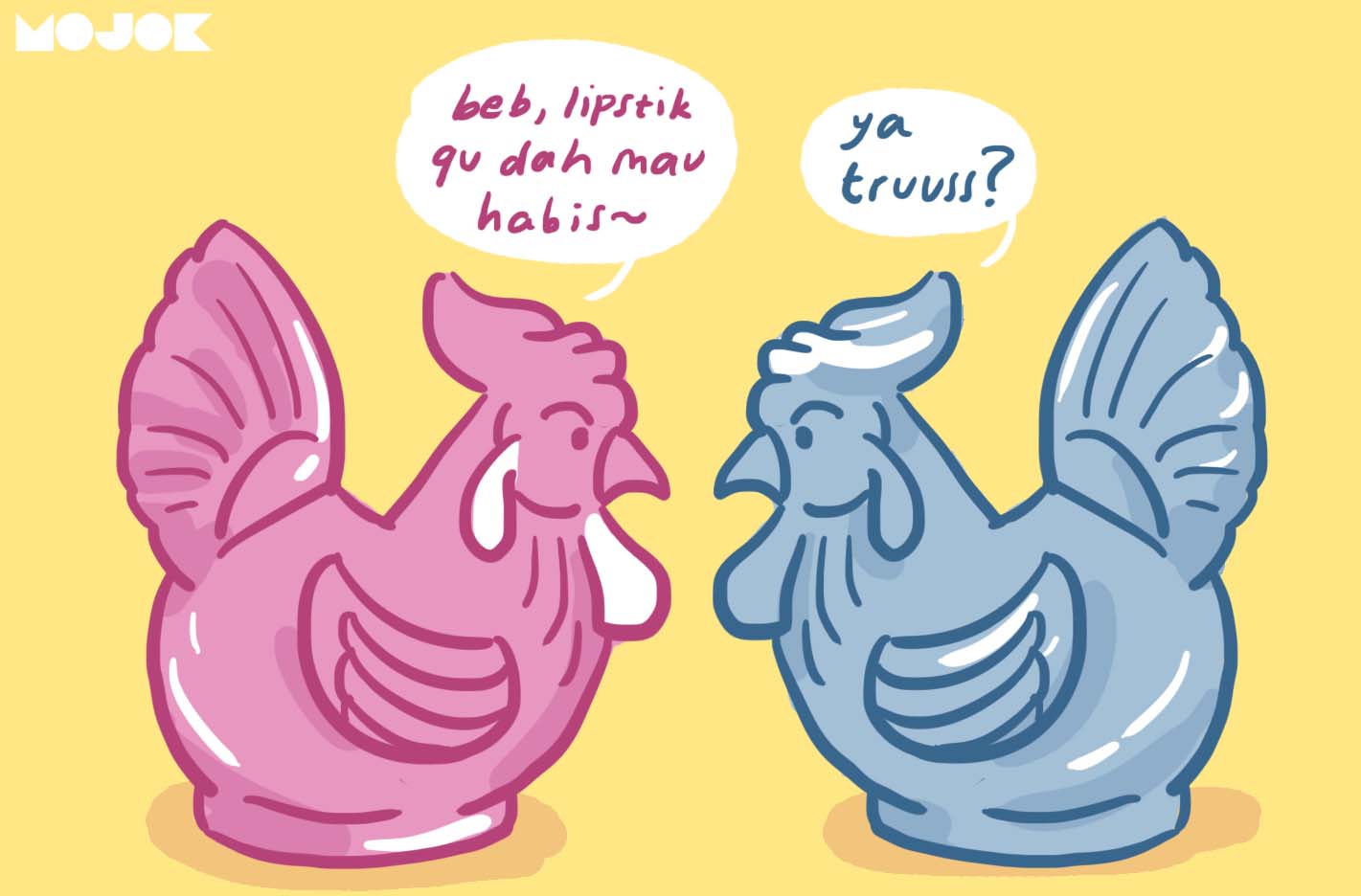MOJOK.CO – Final Liga Europa antara Chelsea melawan Arsenal dikecam banyak pihak. Mulai dari masalah politik, biaya perjalanan, sampai alokasi tiket untuk masing-masing fans.
UEFA punya gawe. Mereka punya kampanye yang diberi tajuk #equalgame. Buat kamu yang nggak tahu, kampanye ini punya arti sebagai berikut: “Semua orang harus bisa menikmati sepak bola. Tak peduli siapa kamu, dari mana kamu berasal, atau cara kamu bermain. Inilah Equal Game.” Sayangnya, kampanye itu berbalik menampar wajah UEFA yang bergurat korup itu.
Sebuah kampanye yang sebetulnya baik adanya. Tanpa memandang latar belakang, perbedaan fisik, sampai keturunan, kamu semua seharusnya bisa menendang bola yang sama. Mau pakai gawang besi, bermain di lapangan standar internasional sampai balbalan dengan gawang sandal jepit dan lapangan di atas tanggul pinggir kali. Semuanya sama.
Sayang, di sepak bola, bahkan di kehidupan nyata, kamu tidak akan bisa memuaskan semua pihak. Bahkan ketika niat sudah baik yang dilambari dengan tajuk yang ndakik-ndakik. Tak bisa disangkal, sepak bola adalah wajah kehidupan itu sendiri. Sepak bola tak usai selama 90 menit. Salah satunya, sepak bola tak lepas dari politik.
Final Liga Europa antara Chelsea vs Arsenal pun tak bisa menghindar dari kenyataan itu. Mulai dari pemilihan tempat laga final digelar, sampai kenyataan bahwa Henrikh Mkhitaryan tak bisa terbang ke Baku, Azerbaijan karena alasan politis.
Kita rembug pelan-pelan. Equal game memungkinkan siapa saja untuk “bermain”, atau kata ini bisa kita ganti menjadi “menikmati” sepak bola. Menikmati bisa diartikan menonton atau menjadi pihak yang menyediakan tempat. Jadi, jika Chelsea vs Arsenal digelar di Baku, Azerbaijan, justru sangat mendukung kampanye itu.
Seperti Piala Dunia, misalnya. FIFA memberi kesempatan negara-negara dari “dunia ketiga” untuk menjadi tuan rumah. Mulai tuan rumah bersama Korea Selatan dan Jepang hingga Afrika Selatan. Piala Dunia di Korea dan Jepang berlangsung mulus, mulai dari persiapan hingga paripurna karena dua negara itu sudah sangat maju dalam hal perencanaan hingga eksekusi.
Piala Dunia di Afrika Selatan adalah Piala Dunia penuh tantangan. Infrastruktur, hingga keamanan. Namun, FIFA tetap memberi kesempatan karena percaya juga dengan kampanye equal game ala EUFA.
Nggak cuma negara-negara mapan di Eropa yang bisa menjadi tuan rumah. UEFA memandang final Piala Europa antara Chelsea melawan Arsenal layak digelar di mana saja. Dan, Baku, sebuah kota di Eropa Timur, mendapat kesempatan. Perlu diingat, pemilihan tempat final ini sudah dilakukan sejak jauh hari, sebelum diketahui bahwa Chelsea akan bermain di final melawan Arsenal.
Atas dasar asas equal game, semuanya menjadi masuk akal. Namun, di sinilah masalah terjadi. Seperti yang saya sebut di atas, sepak bola dan politik seperti dua sisi di sekeping koin. Buat contoh, kita bisa melihat ke sepak bola Indonesia saja.
Ketika APBD masih boleh digunakan sebagai sumber biaya, adalah biasa ketika kepala daerah, bupati, walikota, gubernur, menjabat sebagai ketua umum klub. Bahkan ada yang menjadi manajer. Tujuannya untuk memudahkan aliran dana APBD tersebut.
Kamu tahu, tata cara pemilihan umum di Indonesia mengedepankan aspek popularitas (pemilihan langsung). Fakta itu mendorong para tokoh politik mendekati sepak bola. Sebagai olahraga paling populer, sepak bola menjadi kendaraan politik.
Menunggangi sepak bola, banyak tokoh yang tadinya kurang populer mendadak begitu dikenal. Mereka lebih mudah memperoleh ruang pemberitaan di media massa dan media sosial. Juga lebih mudah untuk menjumpai calon pemilihnya. Cukup dengan datang ke stadion, sudah bisa berjumpa dengan puluhan ribu calon pemilihnya.
Pola seperti ini yang bisa kita lihat dari sepak terjang Edy Rahmayadi. Edy pernah menjadi Pangdam Bukit Barisan dan menjabat Pangkostrad. Namun, Edy Rahmayadi sadar bahwa jabatan militernya itu tidak cukup mengangkat popularitas namanya dan bekal untuk masuk ke politik praktis. Selebihnya, kita tahu bagaimana kisah Bapak Edy.
Kembali ke final Chelsea vs Arsenal, kondisi politik antara Azerbaijan dan Armenia membuat Mkhitaryan tidak mendapat “izin” datang. Bahkan ketika pihak pemerintah Azerbaijan siap menjamin keamanan, nuansa “permusuhan” membuat Arsenal dan Mkhitaryan mengambil langkah paling aman: si pemain menonton final Chelsea vs Arsenal di London.
UEFA dikecam dari dua sisi, pihak Chelsea dan Arsenal. Equal game dianggap tak punya taji, bahkan kampanye kosong belaka. Niat awal mengizinkan kota medioker untuk merasakan euforia sepak bola yang sama dengan “kota kelas satu”, menjadi sebuah bencana sosial yang mencoreng sepak bola itu sendiri.
Namun itulah kenyataan yang harus kita terima. Toh UEFA tak mungkin memindahkan tempat final begitu saja. Ya meskipun (sepertinya) bisa, langkah itu akan semakin memperburuk citra UEFA sebagai badan sepak bola yang seharusnya netral dan mengakomodir semua orang. Apakah Baku dan Azerbaijan akan diam ketika potensi “wisata” mereka dipangkasi begitu saja?
Kompromi harus dicapai, dan sekali lagi, kamu tak bisa memuaskan semua orang. Pun dengan fans Chelsea dan Arsenal yang harus menempuh 2.500 mil dari London menuju Baku, dengan biaya mencapai 1000 paun, dan waktu tempuh perjalanan sampai 20 jam. Fans Chelsea dan Arsenal Mengeluh? Fans sepak bola Indonesia sudah terlatih ketika harus away days ke Stadion Marora, mantan kandang Perseru Serui.
Saya tidak ingin mencoba bijaksana. Saya cuma berusaha menyajikan situasi nyata yang perlu kita pikirkan bersama. Meski protes dan mengeluh, toh Chelsea dan Arsenal tetap mengirim pemainnya ke Baku. Mau walk out? Ini bukan Liga Indonesia di mana walk out cuma dihukum kalah. Walk out di liga profesional bisa berbuntut panjang.
Terlepas dari UEFA yang dipandang korup dan segala keburukan itu, pada titik tertentu dalam hidup, yang bisa kita lakukan adalah berjalan ke depan. Pada titik tertentu juga, yang bisa kita lakukan, pendukung Chelsea dan Arsenal yang akan nonton dari layar kaca Indonesia, adalah memberikan doa dan tulisan penyemangat kepada para pemain lewat media sosial.
UEFA korup? Gusti Allah tidak tidur, my love~