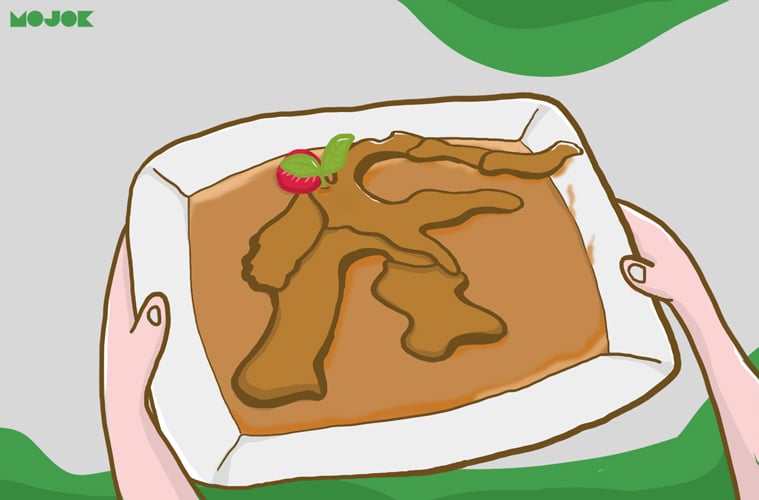MOJOK.CO – Liputan bencana alam di tanah air biasanya adalah soal penggalangan dana dan salat gaib bersama, atau keluarga korban yang menangis histeris.
Seorang sahabat saya yang pernah mukim di Tokyo, Jepang, beberapa tahun lalu mengeluh dengan kondisi media massa nasional dalam soal pemberitaan bencana. “Media di Indonesia terlalu melodramatik (untuk tidak menyebut cengeng),” katanya, “dan cenderung hanya berambisi menguras air mata. Mereka lupa bahwa ada peran edukatif yang diemban media massa.” Begitu kira-kira celotehnya suatu sore di kantin kampus.
Saya mengangguk, meski lebih merasa semacam “pengakuan dosa” pribadi karena cara berpikir demikian sesungguhnya telah mendarah daging dalam praktik jurnalistik sehari-hari.
“Di Jepang,” ia melanjutkan, “media massa memberitakan potensi bencana sebelum bencana tersebut benar-benar datang. Pemerintah dan masyarakat yang membaca berita tadi melakukan upaya antisipasi sebelum bencana datang.”
Ya, maklum saja, Negeri Samurai tersebut banyak belajar dari bencana yang menimpa negeri mereka. Ilmuwan di sana dengan begitu tekun membaca semua gejala alam, membuat hipotesis, mengumpulkan data, dan menyimpulkan “kehendak semesta”. Hasilnya? Bangunan-bangunan didesain agar tahan terhadap gempa bumi, ruang publik siap untuk digunakan sebagai tempat evakuasi, kurikulum sekolah mengajarkan siswa agar tanggap bencana, dan sebagainya.
Mengenai ketahanan bangunan terhadap gempa, masyarakat Kanekes di pedalaman Banten Selatan sesungguhnya punya desain rumah yang baik sebagai contoh. Semua perencanaan berlangsung dalam kalkulasi dingin tanpa selubung mitos dan simplifikasi argumen mengenai tuah dosa manusia.
Di sisi lain, jurnalis punya dasar mengenai wawasan seputar kebencanaan dan memegang kuat etika dalam kerja jurnalisme. Keduanya bekerja dalam hubungan solutif dan memberikan harapan kepada masyarakat, bukannya jatuh pada pesimisme dan duka yang berlarut-larut.
Sebagai contoh nyata, laman www.japan-guide.com menulis peristiwa gempa dan tsunami setinggi 40 meter pada 11 Maret 2011 di Tohoku, Jepang, dalam artikel berjudul Earthquake and Tsunami Update. Media di negeri Matahari Terbit tersebut menulis dampak akibat gempa, tsunami, dan insiden radioaktif akibat pecahnya pembangkit listrik tenaga nuklir di sekitar kawasan PLTN Fukushima, Daichi. Selebihnya, media menampilkan foto dampak kerusakan bangunan akibat gempa dan tsunami, lengkap dengan infografis mengenai titik gempa dan wilayah terdampak.
Di sana, saya nggak nemu, tuh, gambar seperti tim penanggulangan bencana yang tergopoh-gopoh menggotong kantong mayat, korban-korban berjejeran, raut wajah korban yang sedih, keluarga korban yang menangis histeris kehilangan anggota keluarga, atau ucapan bela sungkawa yang disertai suara tercekat dan tangis.
Pada pemberitaan lain, saya juga menemukan berita mengenai topan berkekuatan besar mendekati kawan Okinawa di portal berita www.japantoday.com. Dalam berita berjudul Strong Typhoon Passes Near Okinawa; Set to Hit Mainland, kesan yang saya dapat justru berita tersebut menekankan langkah antisipatif dan pentingnya sikap waspada dibandingkan sekadar teror ketakutan akan datangnya bahaya. Nah, dalam batin saya, justru begitulah seharusnya karya jurnalistik yang berempati terhadap pembaca. Sialnya, saya belum melakukannya!
Benar, reporter seperti saya malah akan lebih tertarik mengejar pengakuan korban di lokasi kejadian tanpa memberi ruang argumentasi ilmiah para pakar dan peneliti yang tekun menyelidik cuaca dan ilmu bumi. Akibatnya, jadilah parade rutin pascabencana sebagai hari berkabung nasional.
Liputan yang ramai setelah bencana di tanah air biasanya adalah soal penggalangan dana, salat gaib bersama, atau kunjungan orang-orang penting ke lokasi bencana. Informasi tambahan pascagempa dan tsunami di Palu pun tak kalah memilukan, yakni kaburnya narapidana akibat runtuhnya rumah tahanan dan penjarahan karena lambannya bantuan untuk korban bencana.
Berita-berita di atas lahir dari adagium klasik yang berbunyi bad news is good news. Sayangnya, hal tersebut masih menjadi acuan para jurnalis—ya, termasuk saya ini. Sementara itu, antitesis gerakan penyajian berita berupa good news is good news ala Shauna Crockett-Burrows (1930-2012) malah tidak banyak berkambang meski sudah digagas sejak 1993 melalui The Positive News (“Shauna Crockett-Burrows 1930-2012” melalui www.positive.news). Pemberitaan positif biasanya hanya akan mudah ditemukan pada advertorial alias berita berbayar.
Pertanyaannya, apakah bad news is good news mesti ditinggalkan? Saya kira tidak. Namun, tidak untuk kasus berita bencana alam.
Begini loh, bad news is good news akan sangat berguna untuk isu-isu hukum, terutama indikasi adanya korupsi yang menyangkut dana publik yang dikelola institusi negara. Namun, titik pijaknya bukan semata kebencian membabi buta untuk menghajar dan menghakimi pihak lain. Penekanannya justru ada pada poin kedua dalam The Elements of Journalism, What Newspeople Should Know and the Public Should Expect (New York: Crown Publishers) karya Bill Kovach dan Tom Rosenstiel (2001). Hmm, apakah itu?
Bahwa loyalitas pertama jurnalisme adalah kepada warga (citizens). Selain itu, poin kedua tersebut berkaitan dengan poin kelima yang menyebutkan bahwa jurnalis harus melayani sebagai pemantau independen terhadap kekuasaan.
Lantas kini, saya mesti kembali bertanya: apakah tugas seorang jurnalis sebenarnya justru selayaknya artis telenovela dalam meliput bencana? Apakah tugas jurnalis akan dianggap sukses besar jika mampu menguras air mata pemirsa?
Saya, sih, ingin menjawab, “Tidak.” Nggak tahu, deh, kalau Mas Anang. Hehe.