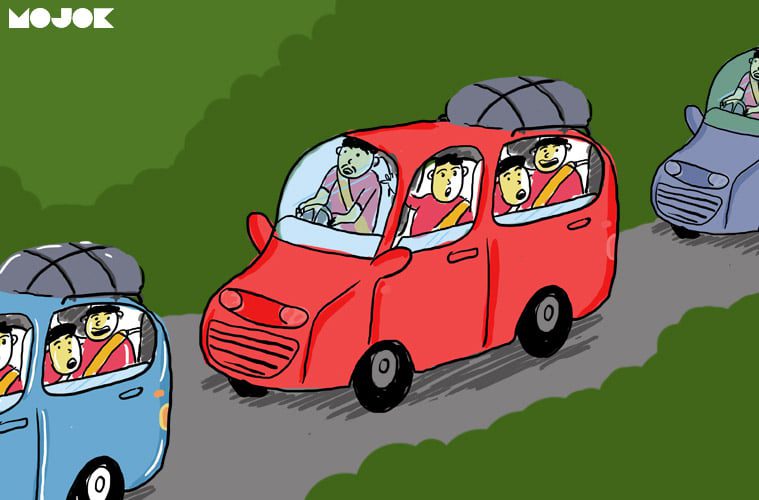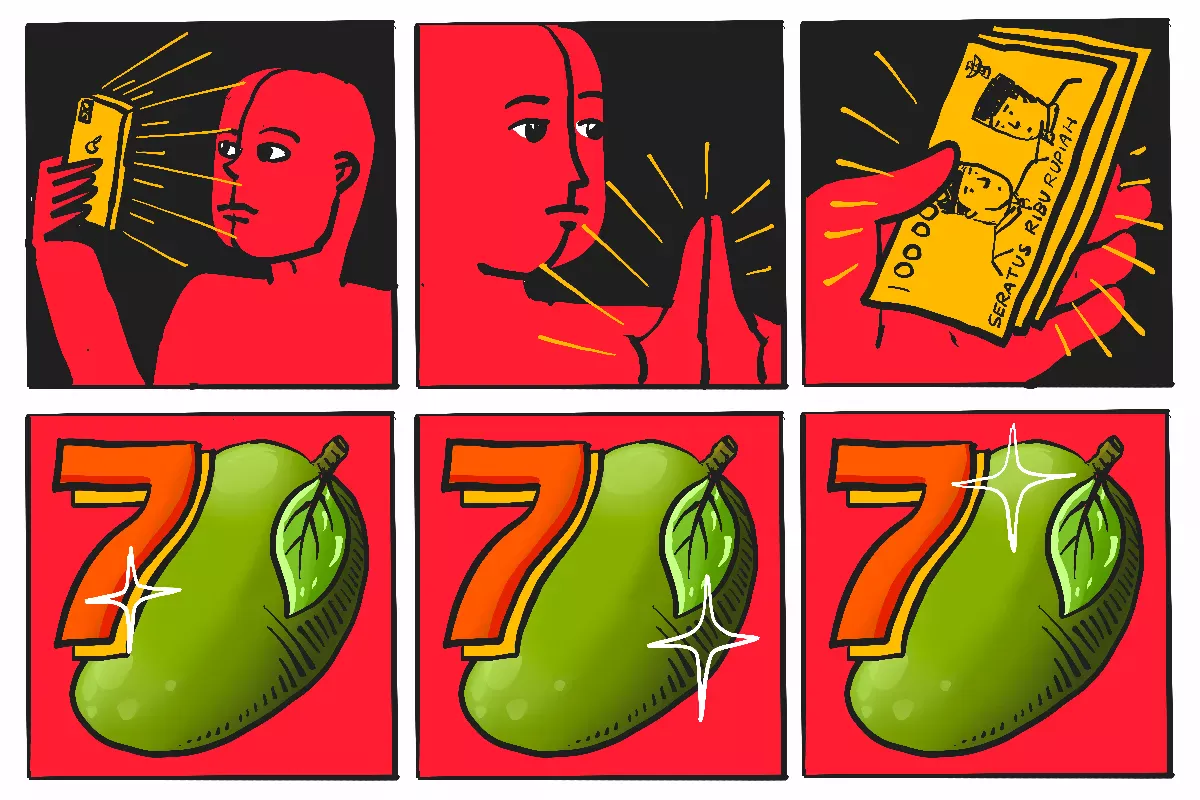Kamis lalu (2/10/2025) saya membaca tulisan Thoha Abil Qasim yang mengkritik tentang wisata di Kota Situbondo dan membandingkannya dengan Banyuwangi. Saya curiga penulisnya cuma orang yang singgah barang seminggu dua minggu, setelah itu pergi. Pasalnya, selama 10 tahun bolak-balik Situbondo, kesan yang saya dapat di kota ini nggak sama seperti yang dituliskan Thoha.
Menyebut Situbondo sekadar tempat isi bensin jelas pendapat yang terburu-buru. Faktanya, ada beberapa destinasi wisata di Situbondo yang nggak pernah sepi setiap akhir pekan. Sebut saja misalnya seperti Utama Raya, atau Pantai Bama.
Jangan-jangan, penulis menyimpulkan demikian karena berkunjung bukan saat weekend? Kalau itu mah, bukan cuma di Situbondo, Moaas!
Sebagai orang yang sudah cukup lama menikmati udara Situbondo, izinkan saya berbagi pemahaman tentang “kota kedua” saya ini, supaya tidak dicap buruk terus.
Membandingkan Situbondo dengan Banyuwangi itu jelas ngawur
Klaim yang menyebut bahwa Situbondo nggak punya magnet wisata adalah hal yang gampang dibantah. Pasir Putih, contohnya, adalah salah satu destinasi wisata yang sudah lama dikenal bahkan di kancah nasional.
Selain itu, penulis mungkin lupa bahwa Situbondo pernah meraih prestasi juara satu kategori Desa Wisata Rintisan. Ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) yang pernah digelar Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) ini menjadikan Kampung Blekok Situbondo sebagai desa wisata terbaik se-Indonesia. Ingat, se-Indonesia, loh!
Masalahnya, mengabaikan fakta ini hanya karena brandingnya nggak sekeras Banyuwangi adalah bentuk yang bias pandang, cacat logika malah.
Justru, masalah utamanya bukan nggak punya potensi, melainkan penulis sudah kadung terjebak membandingkan Situbondo dengan Banyuwangi. Catat, ya, Mas, nggak semua daerah harus punya Kawah Ijen atau event festival internasional. Kalau semua harus disetarakan dengan Banyuwangi, lantas apa gunanya keragaman identitas daerah?
Ekonomi nggak melulu soal wisata
Selain itu, argumen bahwa ekonomi Situbondo stagnan gara-gara pariwisata nggak digarap serius terlalu menyederhanakan realitas.
Begini. Benar memang, ekonomi daerah ini sejak lama ditopang sektor pertanian, perikanan, dan garam. Namun, justru inilah sektor yang menjaga kestabilan rata-rata penghasilan di Situbondo.
Parisiwisata memang bisa jadi bonus, tetapi menyebutnya sebagai mesin utama penggerak ekonomi jelas mengabaikan fakta yang terjadi sebenarnya. Kalau Banyuwangi mau maju dengan sektor wisatanya, ya sudah, jangan samakan dengan Situbondo yang bergerak dengan caranya sendiri yang memang lebih sukses di bidang non-pariwisata.
Klaim kota sepi saat malam hari itu nggak benar
Saya jadi semakin curiga kalau yang membuat tulisan ini nggak bener-bener kenal sama kota ini. Mas ini mengatakan Situbondo sepi saat malam hari mungkin karena singgahnya di pedesaan. Wajar saja.
Tapi, coba saja datang sendiri ke pusat kotanya saat malam hari. Alun-alun kota Situbondo nggak sesepi yang dibilang oleh Mas Thoha. Banyak pedagang-pedagang yang menjajakan makanan di sana. Kalau memang sepi, sudah pasti pada gulung tikar, mah, para pedagang itu.
Saya pernah menulis tentang Alun-alun Situbondo yang punya tiga problem pokok: Sampah, rawan pencurian helm, dan pengamen. Coba, deh, pikirkan, kalau memang jantung kota ini nggak rame, nggak bakal ada problem-problem semacam itu, kan?
Selain itu, nggak jelas dari mana penulis mengatakan bahwa anak mudanya lebih sering lari ke kota tetangga. Memang, tau dari mana kalau anak muda Situbondo singgah ke kota tetangga berarti nggak ada hiburan di kota sendiri?
Mungkin, penulisnya nggak tau bahwa di Situbondo juga ada komunitas kreatif dan tentunya tumbuh perlahan-lahan. Hanya karena nggak viral, bukan berarti mereka nggak eksis, ya.
Cara pandang yang salah tentang julukan Situbondo“Kota Santri”
Kata siapa Situbondo nggak berhasil membranding diri dengan julukan “Kota Santri”? Jangan hanya gara-gara nggak ada festival skala besar, lantas beranggapan brandingnya nggak kuat.
Memang sudah tahu, berapa jumlah santri yang tersebar di kota ini? Asal tahu saja, ya, Mas. Di Situbondo ada salah satu pondok pesantren terbesar di Indonesia yang jumlah santrinya mencapai kurang lebih 24.000-an. Dan santrinya pun juga datang dari penjuru Indonesia. Saya tau 10 tahun terakhir ini memang nyantri di sana.
Kalau bukan karena brandingnya yang sukses sebagai “Kota Santri”, mungkin pesantren-pesantren udah pada tutup. Masih mau bilang julukan “Kota Santri” hampir punah?
Intinya…
Situbondo bukan lagi sekarat, ia hanya memilih jalannya sendiri bertumbuh kembang. Begitu juga dengan daerah-daerah berkembang lainnya.
Membandingkan Situbondo dengan Banyuwangi adalah jebakan logika yang menutup mata dari kekuatan lokal. Daripada terus-menerus menyebut sebagai “Kota Singgah”, mungkin lebih adil jika kita mengakui bahwa daya tarik daerah bukan melulu soal branding wisata. Melainkan keberanian melihat potensi sesuai identitasnya sendiri.
Akan tetapi, yang paling penting sih, sebelum mengkritik suatu daerah, minimal kenal lah sama daerah tersebut (maaf ya, Mas).
Penulis: Ahmad Dani Fauzan
Editor: Rizky Prasetya
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.