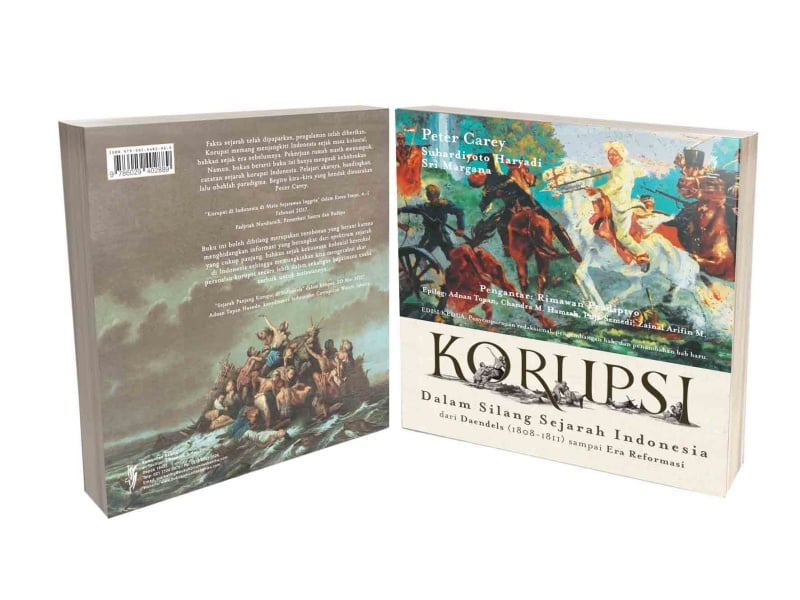Bicara tentang netizen itu seolah tiada habisnya. Di mana ada internet, di situ ada warganet. Kapan ada postingan, di situ ada komentar. Namanya komentar ya macam-macam, tergantung sudut pandang pribadi dan suasana hati. Ada yang pro, ada yang kontra. Ada yang mendukung, ada yang mencela. Ada yang memuji, ada yang menghujat. Ada yang kagum, ada yang nyinyir. Seolah kutub positif dan negatif memang diciptakan berpasangan dan selalu ada.
Apalagi jika ada suatu bahasan yang debat-able, yang ujung-ujungnya jadi ribut. Sebut saja contohnya masalah capres, ribut-ribut antara kubu pendukung 01 dan 02 yang tak kunjung usai. Belum lagi ribut-ribut antara YouTuber, yang sepertinya akan jadi tren baru untuk bikin konten saling sindir selain konten prank-prank yang sudah mulai membosankan.
Lebaran baru beberapa hari sudah mulai ribut lagi. Apakah ini karena kita salah mengartikan ucapan minal aidin—semoga menjadi orang yang kembali— yaitu kembali pada fitrah kita yang suka ribut. Lalu wal faizin—dan orang yang menang—maunya menang sendiri dengan mengalahkan yang lain. Modyaarr~
Membicarakan netizen juga berarti membicarakan diri sendiri. Sebab kita pun pengguna internet dan media sosial—yang otomatis terdaftar sebagai warga net meski status itu tak tercantum di KTP.
Dunia internet itu kompleks—lengkap dengan segala sisi terang dan gelapnya. Sisi positif dan manfaatnya banyak, sisi negatifnya pun tak kalah banyak. Dan sampailah kita pada zaman dimana ketikan jari netizen ini lebih tajam dari lidah yang tak bertulang—bahayanya mereka bisa menggiring opini publik ke hal yang tidak semestinya. Terkadang komentar netizen lebih kejam dari fitnah—padahal fitnah saja sudah lebih kejam dari pembunuhan loh.
Dalam mahfudzat—kata mutiara—sering kita dengar salamatul insan fi hifdzil lisan yang berarti keselamatan manusia terletak pada lisan dan ucapannya. Mungkin pada era kekinian mahfudzat tersebut bisa beralih kalimat menjadi salamatul insan fi hifdzil ‘postingan’—Ya, keselamatan manusia zaman now terletak pada postingannya, tergantung dari apa yang diketiknya di sosial media, tergantung apa yang dishare ke banyak grup, tergantung gambar dan video yang di-upload, dan sebagainya.
Sebatas pengetahuan saya, seseorang di dunia nyata punya kecenderungan menjadi pribadi yang berbeda di dunia maya—tentu tidak semuanya. Atau jangan-jangan, di dunia maya itulah sifat aslinya, sebab kalau di dunia nyata masih ada rasa sungkan berekspresi.
Misalnya saja terhadap suatu isu yang sedang hangat—di dunia maya kita berani berkomentar, mengkritik, bahkan sampai menggoblok-goblokkan. Tapi beda ceritanya kalau kita berhadapan langsung dengan orangnya—jangankan kritik, mau nyapa saja kelihatannya masih mikir-mikir. Cupu memang—lempar batu sembunyi tangan!
Di dunia online orang-orang cenderung lebih berani melakukan suatu hal daripada di kehidupan nyata. Sepertinya ada ilusi kebebasan di dunia maya. Seseorang merasa bebas berbuat apa saja dan tidak punya tanggung jawab atas apa yang ia lakukan karena menganggap perilakunya tidak nyata. Selain itu, adanya peluang untuk menyembunyikan identitas asli (anonymous) semakin menambah alasan seseorang merasa tidak bersalah ketika mencemooh, mem-bully, menghujat, misuh-misuh nggak jelas, share kabar hoax, rasisme, dan lain-lain.
Bisa saya katakan ada kesantunan sosial yang sangat tinggi dalam komunikasi tatap muka. Dalam bersosialisasi di tengah masyarakat, kita banyak dibatasi oleh norma-norma sosial. Sedangkan di dunia maya semuanya ceplas-ceplos dan tak kenal sungkan. Bicara apa adanya sih baik—tapi mbok ya lihat situasi dan kondisi. Alangkah baiknya tabayyun dulu sebelum berkata dan mengomentari sesuatu. Ada orang lagi kena bencana—eh ada yang langsung menghakimi itu azab untuk mereka. Ada orang turun membantu dibilang pencitraan, tak membantu dibilang tak punya perasaan. Hadeeeh~
Internet seperti membebaskan orang-orang untuk mengatakan sesuatu kepada orang asing yang tidak akan pernah kita katakan jika kita bertemu dengan mereka. Lebih parah lagi kalau ada kelompok-kelompok yang beternak akun untuk tujuan tertentu—membuat ratusan akun untuk menyerang kelompok lain. Satu orang tidak puas terlihat menjadi ribuan orang tidak puas. Satu orang memaki, seolah-olah makian dari ribuan orang. Apalagi sasaran ini mengenai mereka para pecandu—pecandu komen dan pecandu share tanpa mau ber-tabayyun. Sudah pasti menggiring opini publik ke hal yang tidak semestinya.
Dari sekian banyak kearifan lokal yang kini semakin dilupakan, salah satunya adalah budaya tepa selira—di dunia maya tidak ada tepa selira. Dalam Bahasa Indonesia, itu antara sifat empati dan tenggang rasa. Sederhananya, kemampuan memperkirakan apa yang kira-kira orang lain pikir dan rasakan. Seseorang harus memandang lawan bicaranya sebagai orang yang pantas untuk dihormati.
Contohnya begini, kalau di dunia nyata kita bisa melihat ekspresi lawan bicara. Jika dia kelihatan sedih, kita bisa pilih bahasa yang lembut dan intonasi yang pelan waktu bicara padanya. Di dunia maya nggak bisa gitu. Kalau di dunia nyata kita terbiasa sopan santun pada orang yang lebih tua meskipun itu orang asing. Di dunia maya juga nggak bisa gitu.
Pemilik akun ataupun media juga harus ber-tepa selira pada pembacanya—paham bahwa nggak semua pembaca itu bijak menyikapi masalah. Bahkan pemilik media abal-abal juga harus paham tentang efek berita yang mereka tulis bisa mengakibatkan perpecahan di masyarakat. Netizen juga begitu—harus saring dulu sebelum sharing, ucapkanlah yang terbaik atau diamlah.
Itu semua baru netizen di dunia internet permukaan (surface). Lain lagi ceritanya jika masuk ke dunia internet yang lebih dalam yang tidak bisa dijangkau mesin pencari biasa—karena butuh akses khusus untuk dapat masuk ke dalamnya. Dunia internet yang dimaksud biasa dikenal dengan sebutan deep net atau dark net—atau ada juga yang menyebut dengan istilah lainnya.
Bisa dibayangkan, di permukaan saja segitu riuhnya, apalagi yang ada jauh di dalam sana. Tapi saya sarankan, jika anda baru bisa berenang di permukaan jangan mencoba menyelami dunia deep net, atau anda akan terdampar di Bikini Bottom.