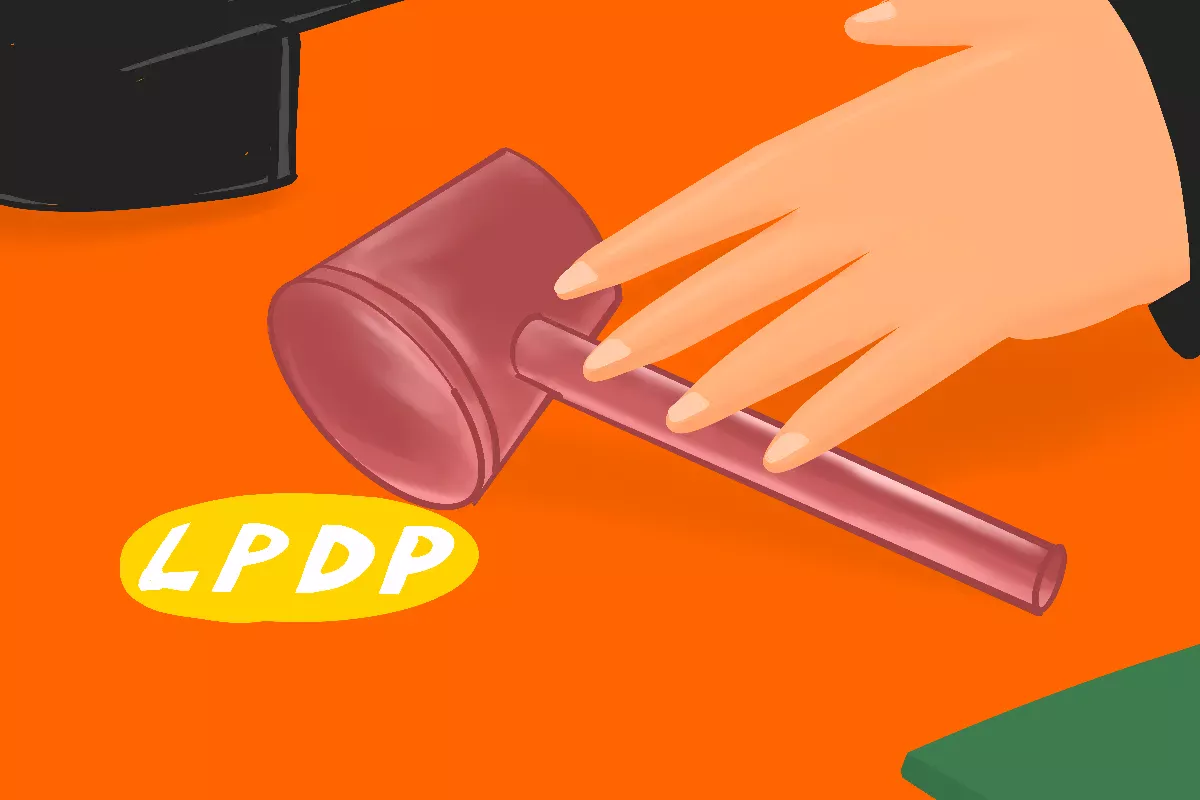Beberapa hari lalu, saya melihat tulisan Fareh Hariyanto di Mojok berjudul “Banyuwangi Kota yang Tak Pernah Ramah bagi Pekerja, Gajinya Rata dengan Tanah!” Tulisan itu kemudian dibagikan ulang di grup Facebook Info BWI 24 Jam, tempat segala berita Banyuwangi berbaur jadi obrolan warung kopi virtual. Seperti biasa, admin grup menulis caption pendek tapi memancing: “Opo yo ngono, lur?”, kalimat khas warga Banyuwangi ketika separuh ingin tahu, separuh pengin nyinyir.
Yang terjadi setelahnya sudah bisa ditebak. Kolom komentar langsung ramai. Ada yang menuduh tulisan itu lebay, ada yang membenarkan dengan emosi, dan ada pula yang menanggapinya dengan kalimat religius seperti, “Gaji besar pun kalau nggak bersyukur ya tetap kurang.” Di antara komentar itu, terselip sindiran getir, “Pejabatnya yang makmur, rakyatnya tambah mlurut.”
Saya membaca semuanya sambil senyum kecut. Karena apa yang ditulis Fareh bukan dongeng. Itu realitas yang, kalau kamu tinggal di Banyuwangi cukup lama, terasa di setiap obrolan, di setiap nadi orang yang hidup dari upah kecil.
Banyuwangi mengilap, tapi…
Banyuwangi hari ini memang tampak gemerlap. Jalan-jalan ke arah wisata ditata rapi, hotel-hotel baru berdiri, dan baliho “Banyuwangi Hebat” bertebaran di mana-mana. Tapi berjalanlah sedikit ke arah selatan, ke Muncar. Di sanalah kamu akan menemukan wajah Banyuwangi yang sesungguhnya: barisan buruh perempuan yang berangkat sebelum matahari terbit dan pulang ketika malam hampir habis. Di antara mereka, banyak yang bekerja sampai 21 jam sehari, berdiri di ruang beku, mengolah ikan untuk ekspor, tapi tak pernah tahu rasanya ikan yang mereka olah sendiri.
Komentar-komentar di grup Facebook itu, kalau dibaca pelan-pelan, sebetulnya menggambarkan satu hal yang sama: penyangkalan. Warga Banyuwangi seperti tak mau benar-benar percaya bahwa daerah yang mereka banggakan ternyata memperlakukan pekerjanya sekejam itu. Mereka menepis kenyataan dengan dalih syukur, dengan pembelaan “hidup di sini murah”, atau dengan logika sederhana: yang penting masih kerja.
Padahal, apa yang ditulis Fareh bukan sekadar opini. Ia menulis kenyataan yang punya bukti ilmiah, dan saya tahu karena saya pernah melihat datanya sendiri.
Sejak 2022, sebuah LSM perburuhan lokal di Banyuwangi melakukan penelitian tentang kondisi sosial-ekonomi dan ketenagakerjaan di industri pengolahan makanan laut. Saya tahu banyak tentang hasil riset tersebut karena kebetulan saya “orang dalam”. Hasil risetnya memang belum dipublikasi secara umum, baru dipublikasi secara terbatas dan dipaparkan di hadapan Kementerian Ketenagakerjaan sebagi rekomendasi kebijakan. Dan hasil riset itu, terus terang, sangat menyedihkan.
Data menunjukkan bahwa lebih dari sembilan puluh persen buruh di sektor ini digaji di bawah UMK. Rata-rata mereka hanya menerima Rp40.000–87.000 per hari, padahal jika merujuk pada UMK Banyuwangi (2024) mestinya Rp105.545 per hari. Mayoritas buruhnya juga perempuan yang bekerja tanpa cuti haid, tanpa cuti melahirkan, bahkan tanpa perlindungan jaminan sosial. Kalau sakit, mereka tak dibayar. Kalau hamil, bisa langsung diganti. Satu-satunya yang tetap dari pekerjaan mereka hanyalah rasa lelah.
Tiap hari mengolah ikan, tapi nggak pernah makan ikan
Di grup Facebook tadi, ada yang menulis, “Banyuwangi itu murah, asal nggak manja. Hidup di sini gampang.” Tapi murah itu relatif, kan? Kalau gajimu sepuluh juta, nasi pecel tujuh ribu memang terasa murah. Tapi kalau penghasilanmu empat puluh ribu sehari, makan pecel dua kali saja sudah hampir separuh gaji. Apalagi ketika harga gas naik, ongkos sekolah anak bertambah, dan cicilan motor menunggu. Dalam penelitian itu, disebutkan pula bahwa seluruh responden mengonsumsi protein dan serat jauh di bawah standar gizi. Mereka makan bukan berdasarkan selera, tapi kemampuan. Seorang ibu bercerita, “Kadang ya makan nasi sama sambal bawang saja, Mas. Yang penting bisa kerja besok.”
Komentar-komentar di Facebook pun memperlihatkan kenyataan sosial yang aneh tapi nyata. Ada yang menasihati dengan kalimat pasrah “sing penting iso mangan”. Ada yang membela diri “kalau rajin, pasti rezeki lancar”. Tapi yang paling jujur, menurut saya, adalah yang menulis: Kerja di Banyuwangi itu tergantung kenal orang dalam. Tukang sapu aja kudu ijazah SMA.
Semua orang tahu, dan memilih untuk pura-pura tidak tahu.
Sementara itu, pemerintah daerah terus bicara soal investasi dan pariwisata. Banyuwangi memang berubah jadi kota festival, tapi sebagian warganya justru hidup seperti figuran di panggung yang tak pernah selesai. Pembangunan terasa seperti cat baru di dinding yang retaknya dibiarkan. Indah dari jauh, tapi keropos di dalam.
Teman saya yang bekerja di pabrik pengalengan ikan bilang, “Mas, saya ini tiap hari mengolah tuna, tapi sudah seminggu nggak makan ikan.” Ia mentertawakannya, tapi tawa itu lebih mirip cara bertahan daripada candaan.
Buruh Banyuwangi hilang harapan
Di riset itu juga disebutkan, banyak buruh Banyuwangi mengalami kelelahan kronis dan gangguan kesehatan akibat kerja berlebihan. Tak sedikit yang kehilangan semangat hidup, sulit berpikir jernih, dan tidak tahu harus memperjuangkan apa. Dalam istilah akademik, mereka kehilangan “daya agen”. Tapi dalam bahasa mereka sendiri, cukup satu kalimat: “Embuh wess.”
Kalau dulu kerja paksa dilakukan dengan borgol dan cambuk, sekarang dilakukan dengan status hubungan kerja yang nggak jelas, upah rendah dan berbagai modus eksploitasi lainnya. Tak ada penjaga yang membawa senjata, tapi ketakutan hadir setiap hari dalam bentuk ancaman “Kalau nggak mau kerja, banyak yang ngantri di luar.”
Dan ironinya, di tengah semua ini, masih ada yang menulis komentar “gaji kecil karena malas”. Entah mereka benar-benar percaya, atau sekadar ingin terlihat paling waras di antara yang menderita. Padahal kalau mau jujur, buruh di Banyuwangi bukan malas, tapi lelah. Lelah bekerja, lelah berharap, tidak ada alternatif pekerjaan lain karena hampir semua perusahaan pengolahan makanan laut di Muncar melanggar aturan ketenagakerjaan.
Saya menulis ini bukan untuk mengeluh, tapi memang mau nyinyir aja ke warga Banyuwangi yang masih denial di tengah fakta seterang itu. Karena fafifuwasweswos soal “bersyukur”, “Banyuwangi baik-baik aja”, dan sebagainya hanya omong kosong yang semakin membuat Banyuwangi menjadi kota yang indah hanya di brosur, tapi rapuh di kenyataan.
Silakan ke Muncar
Banyuwangi boleh punya Ijen yang memesona dan festival yang megah, tapi selama para buruhnya hidup dalam ketakutan dan kelaparan, semua itu cuma dekorasi.
Maka, kalau ada pejabat yang bangga memamerkan keberhasilan daerah ini, datanglah ke Muncar. Lihat bagaimana buruh-buruh yang mengolah ikan ekspor berjalan dengan gontai tiap keluar dari pabrik. Lihat bagaimana “Banyuwangi Hebat” itu sesungguhnya berdiri di atas punggung orang-orang yang bahkan tak tahu apakah besok mereka masih punya pekerjaan.
Mungkin Banyuwangi tidak butuh lebih banyak festival. Mungkin yang dibutuhkan hanyalah keberpihakan—sedikit saja—agar orang-orang yang membuat kota ini hidup juga bisa merasakan hidup yang layak.
Penulis: Ahmad Taufik
Editor: Rizky Prasetya
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.