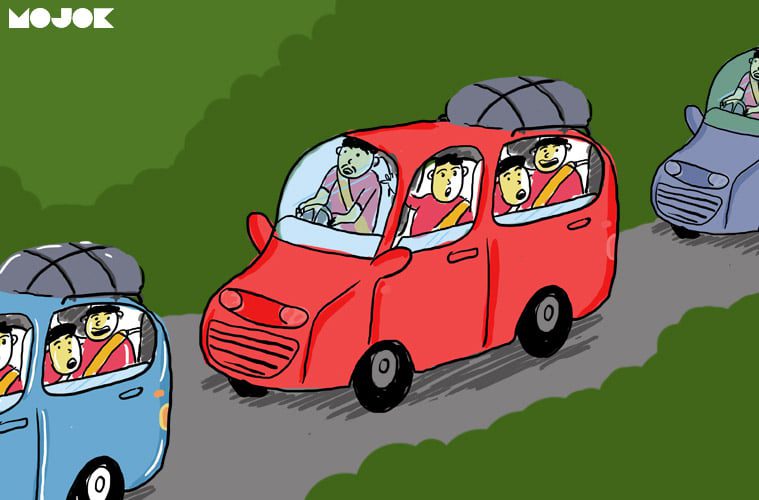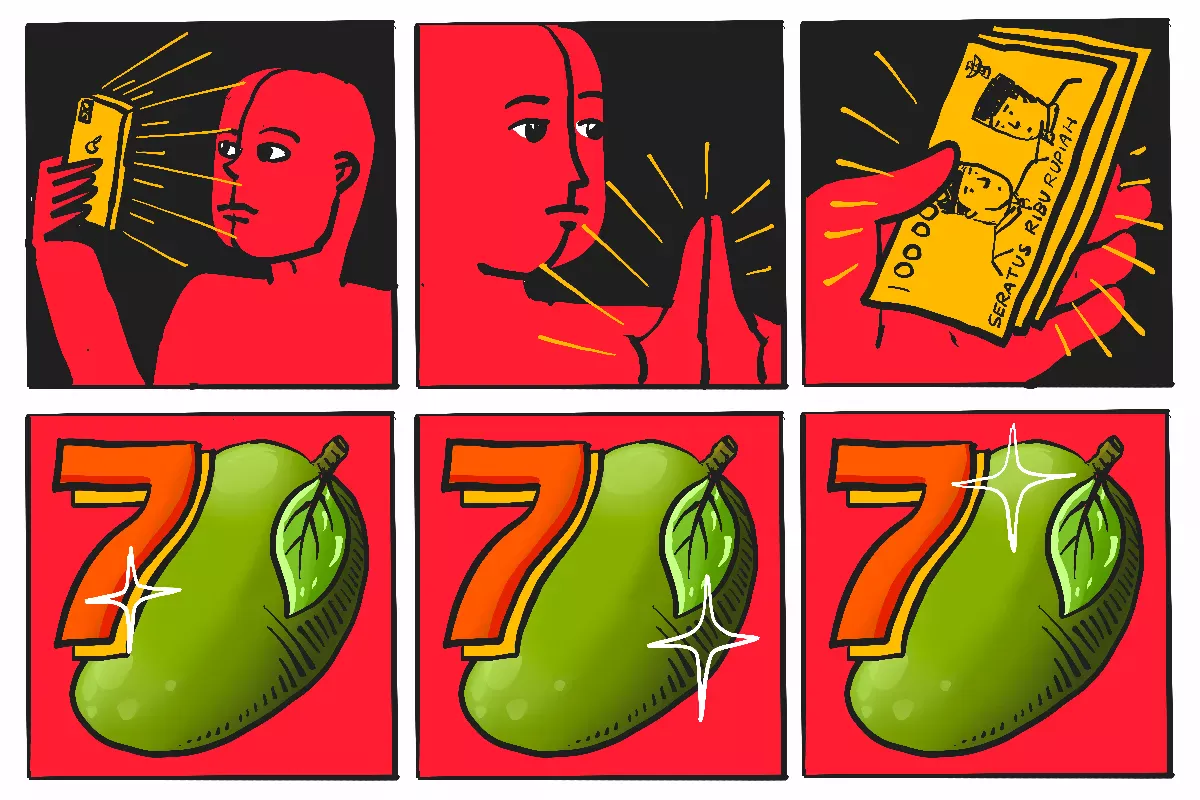Nasi goreng instan memang aneh, tapi kalau dipikir secara tenang, justru sebenarnya amat masuk akal
Minggu kemarin, saya ke swalayan dengan niat beli sabun, kopi, dan sedikit camilan. Tapi seperti biasa, langkah saya nyasar ke lorong makanan instan. Di rak itu, deretan mie instan sudah tampil penuh warna, dengan rasa yang makin lama makin eksperimental sebab saya lumrah menemukan rasa rendang, soto betawi, ayam geprek, singapore laksa bahkan mie rasa sambal matah.
Namun, di antara semua itu, ada satu bungkus yang membuat saya mendadak berhenti, tulisannya Nasindo, nasi goreng instan. Bungkusnya menampilkan gambar nasi berwarna kecoklatan dengan telur mata sapi di atasnya. Jujur, saya agak skeptis. Nasi goreng kok instan? Tapi justru karena skeptis itu, rasa penasaran saya melonjak. Akhirnya, satu bungkus saya masukkan ke keranjang belanja, dengan pikiran, “Ya sudahlah kalau nggak enak paling cuma jadi bahan cerita.”
Review jujur nasi goreng instan: dari nyeduh sampai suapan pertama
Sesampainya di rumah, saya langsung coba. Isi dari bungkus nasi goreng instan ini berupa beras kering bertekstur kecil-kecil, bumbu bubuk, dan minyak sachet. Instruksinya simpel diikuti, tuangkan isi ke mangkuk, seduh dengan air panas, tunggu sekitar 10 menit, aduk rata.
Awalnya saya kira bakal seperti makan bubur instan, tapi setelah 10 menit lebih, teksturnya benar-benar menyerupai nasi. Aromanya lumayan menggoda, meskipun tentu saja tidak seharum bawang putih yang ditumis langsung di wajan.
Saat suapan pertama, rasanya cukup mengejutkan. Tidak buruk, malah cenderung “masuk akal”. Gurihnya pas, bumbunya ringan, dan ada sedikit rasa smokey yang berusaha meniru nasi goreng abang-abangan. Bedanya jelas terasa karena tidak ada tekstur butiran nasi yang pera manja, tidak ada telur gosong tipis yang bikin sedap, dan tentu saja, tidak ada kerupuk yang biasanya jadi teman setia.
Tapi buat ukuran makanan instan, saya harus mengakui bahwa ini lumayan. Kalau dibandingkan dengan mie instan, nasi goreng instan ini memberi sensasi kenyang yang lebih “berat”. Seperti benar-benar makan nasi, bukan sekadar mie yang gampang bikin lapar lagi dua jam kemudian. Setidaknya, nasi goreng instan ini bisa diandalkan sebab cuman butuh duit nggak lebih dari Rp10 ribu untuk menikmatinya.
Budaya instan yang semakin menggurita
Fenomena nasi goreng instan ini terasa sebagai babak baru dari budaya instan di Indonesia. Kita sudah akrab dengan mie instan sejak puluhan tahun lalu. Kopi instan menyelamatkan jutaan pekerja kantoran yang nggak sempat ngopi manual. Teh tarik instan, jus instan, hingga bubur bayi instan, semua ada.
Hadirnya nasi goreng instan seolah jadi klimaks perjalanan panjang itu. Makanan yang biasanya dimasak dengan kelapangan hati, dari menyalakan kompor, memanaskan minyak, mengiris bawang, hingga menumis bumbu—sekarang cukup dengan air mendidih.
Budaya instan ini lahir bukan tanpa alasan. Kehidupan modern menuntut kecepatan. Orang harus kerja dari pagi sampai malam, kadang lembur, lalu masih dikejar aktivitas sosial. Waktu jadi barang mahal. Akibatnya, makanan pun harus menyesuaikan: cepat, ringkas, mengenyangkan.
Ironisnya, kita menikmati instan ini tanpa rasa bersalah. Mie instan bahkan sudah jadi comfort food nasional. Sekarang dengan hadirnya nasi goreng instan, seolah-olah kita bilang, “Kenapa harus repot-repot masak nasi goreng, kalau bisa tinggal seduh?”
Keaslian kuliner yang tergusur
Namun, di balik kepraktisan itu, ada harga yang dibayar: hilangnya ruh kuliner.
Nasi goreng bukan cuma soal nasi yang digoreng dengan bumbu. Ia adalah pengalaman sensorik lengkap. Ada suara spatula beradu dengan wajan, ada aroma bawang putih yang meledak di udara, ada telur yang digoreng hingga gosong tipis di pinggirannya. Bahkan ada interaksi kecil tapi berharga dengan abang gerobak: “Mau pedesnya seberapa, Bang?”
Semua itu lenyap dalam versi instan. Yang tersisa hanyalah semacam “parodi kuliner”: bentuknya mirip, rasanya mendekati, tapi atmosfernya hilang. Kita seperti menonton film lewat sinopsis. Kita tahu inti ceritanya, tapi tidak merasakan detail yang membuatnya hidup.
Industri pangan memang gemar melakukan hal semacam ini. Rendang dikalengkan, bakso dibekukan, soto dijadikan bubuk instan. Semua demi kepraktisan. Tapi kepraktisan itu, kalau dibiarkan, lama-lama akan mengikis tradisi kuliner kita sendiri. Iya nggak sih?
Kalau dipikir-pikir, keberadaan nasi goreng instan juga merefleksikan kondisi ekonomi. Harga bahan pokok yang makin naik bikin banyak orang mencari jalan pintas. Minyak goreng sempat mahal, bawang putih sering melambung, daging ayam bukan lagi pilihan murah. Di tengah kondisi itu, seporsi nasi goreng instan bisa terasa lebih masuk akal: murah, gampang dibuat, mengenyangkan.
Dan di titik inilah, muncul sebuah ironi sekaligus refleksi: nasi goreng instan ternyata lebih “logis” daripada mie instan. Kalau mie instan hanya memberi rasa enak sesaat tapi cepat bikin lapar lagi, nasi goreng instan menawarkan solusi yang lebih dekat dengan kebutuhan orang Indonesia: makan nasi.
Nasi goreng instan: reflektif sekaligus kritik sosial
Pada akhirnya, nasi goreng instan bukan cuma soal rasa atau kepraktisan. Ia adalah cermin kecil dari hidup kita hari ini. Kita makin sibuk, makin pragmatis, makin terbiasa melewatkan proses panjang demi hasil cepat.
Nasi goreng instan memang tidak akan pernah bisa menggantikan nasi goreng abang-abang dengan wajan besar di pinggir jalan. Tapi justru di situlah poin pentingnya: keberadaannya mengingatkan kita bahwa di balik kepraktisan, selalu ada yang hilang. Kita mengorbankan detail, rasa, dan pengalaman.
Namun, mari jujur: nasi goreng instan juga memberi kita sesuatu yang mie instan tidak bisa. Ia lebih mengenyangkan, lebih sesuai dengan budaya makan nasi orang Indonesia, dan lebih masuk akal sebagai pilihan darurat.
Jadi mungkin, dalam dunia yang serba instan ini, nasi goreng instan bukan sekadar eksperimen aneh pabrikan. Ia bisa jadi simbol kompromi: antara tradisi yang perlahan memudar dan kebutuhan praktis yang tak terhindarkan. Dan di tengah hidup yang makin menekan, mungkin kompromi itulah yang membuat kita bisa terus bertahan—meski dengan sepiring nasi goreng yang cuma butuh air panas sepuluh menit.
Penulis: Budi
Editor: Rizky Prasetya
BACA JUGA Tara Nasiku: Nasi Instan Ambigu yang Nggak Laku
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.