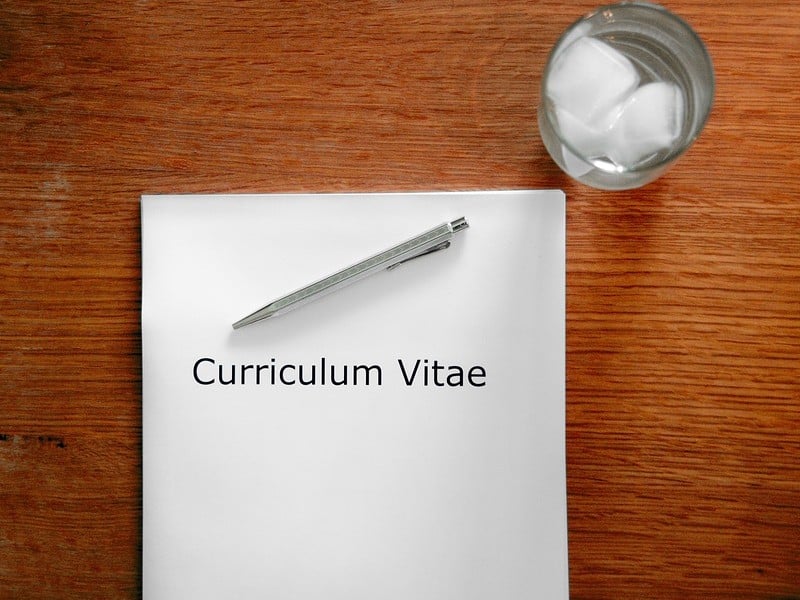Mungkin, banyak di antara para pembaca Terminal Mojok ini banyak yang tidak tidak tahu apa itu wartel. Wartel adalah singkatan dari warung telekomunikasi yang menjamur pada akhir 90-an hingga awal 2000-an. Saat itu, masih sedikit orang yang memiliki telepon seluler sehingga banyak orang yang mengandalkan wartel untuk berkomunikasi dengan orang lain. Kalau sekarang kita bisa melihat banyaknya abang-abang konter pulsa yang menjamur di kota besar hingga pelosok pedesaan, nah, saat itu, yang menjamur bukan konter pulsa, tapi bilik wartel.
Saat itu, jadi pengusaha wartel cukup menjanjikan karena layanan ini banyak dicari orang. Tarif wartel dipatok berdasarkan durasi menelepon, jenis panggilan yang dilakukan, dan waktu menelpon. Paling murah tentu saja panggilan dalam kota atau disebut dengan panggilan lokal, lalu disusul panggilan ke luar kota atau disebut interlokal, dan yang paling mahal tentu saja panggilan SLI atau Sambungan Lintas Internasional ke luar negeri. Waktu untuk menelpon paling murah adalah pukul 10 malam hingga subuh sehingga banyak orang pacaran, atau pasangan suami istri yang menelpon di waktu-waktu tersebut.
Saat itu, tentu saja saya tidak menggunakan wartel untuk pacaran karena saya masih berada di bangku SD. Saya menggunakan wartel hanya untuk berkomunikasi dengan orang tua saya. Antara lain, untuk meminta jemput pada mereka jika saya sudah pulang sekolah. Waktu SD, kadang-kadang saya bisa pulang lebih cepat dari biasanya jika ada rapat guru, atau jika ada demonstrasi besar yang berlangsung di Gedung Sate.
Memasuki bangku SMP, saya pun sering menghubungi nomor telepon seluler orang tua saya untuk meminta jemput jika saya pulang terlambat karena kegiatan ekstrakurikuler atau sekadar main dengan teman-teman. Saya bahkan pernah menelepon orang tua saya untuk meminta bantuan mereka jika topi dan dasi saya tertinggal di rumah menjelang upacara atau ketika ada tugas sekolah yang tertinggal di rumah. Pada saat itu, wartel sering menyelamatkan hidup saya.
Hampir semua sekolah saat itu memiliki satu atau dua bilik wartel yang dikelola oleh koperasi atau kantin sekolah agar peserta didik bisa berkomunikasi dengan orang tuanya untuk meminta jemput atau mengabari orang tua mereka jika ada apa-apa. Saat itu, sebagian orang tua siswa sudah memiliki telepon seluler pribadi.
Wartel pun sering saya gunakan ketika saya sudah tiba di depan pagar rumah, tapi tidak ada siapa-siapa di dalam rumah. Saya pun pergi ke bilik wartel yang berada tidak jauh dari rumah saya untuk menelpon orang tua saya. Mereka pun bilang, “Otw, Gan”, dan saya pun duduk depan pagar sambil menunggu mereka pulang karena saya tidak membawa kunci rumah sama sekali.
Pada 2004 sebetulnya saya sudah memiliki ponsel sendiri, yakni ponsel gaming terkemuka saat itu, Nokia N-Gage. Namun seringkali, saya hanya menggunakan ponsel tersebut untuk menerima panggilan saja karena sengaja tidak mengisi pulsa supaya bisa main game di warnet. Seingat saya, saat itu tarif sekali menelpon ke ponsel orang tua dari wartel saya kurang dari 3000 rupiah saja karena pembicaraannya kurang dari satu menit. Lebih hemat dibandingkan menelepon via ponsel saya saat itu yang tarifnya sedikit lebih mahal daripada tarif wartel.
Saat ini, wartel sudah punah karena harga ponsel dan tarif menelepon yang semakin murah, tapi kenangannya tetap abadi di memori saya. Ada banyak suka dan duka ketika wartel masih menjamur dalam kehidupan kami sebagai generasi milenial yang tumbuh dengan sebuah bilik ajaib bernama wartel. Hal ini tentu nggak akan dirasakan oleh generasi Z, yang bisa mengakses kemudahan hanya dengan ujung jari mereka.
BACA JUGA Suka Duka Membawakan Program Siaran Lagu Nostalgia dan tulisan Raden Muhammad Wisnu lainnya.