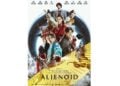Tupperware, merek ikonik idola para ibu yang pernah mendominasi rak dapur di Indonesia kini menghadapi babak akhir yang membagongkan. Pertengahan bulan ini, wadah plastik kenamaan asal negeri Paman Sam tersebut melakukan pengajuan kebangkrutan dengan catatan utang sebesar 818 juta dolar Amerika Serikat atau setara lebih dari 12 triliun rupiah. Fakta ini terdengar menyakitkan mengingat sejumlah upaya penyelamatan telah ditempuh demi keberlangsungan bisnis Tupperware.
Restrukturisasi utang maupun penandatanganan perjanjian investasi pada tahun 2023 lalu nyatanya tak cukup menopang likuiditas perusahaan. Setelah sekitar 78 tahun beroperasi, Tupperware tampaknya harus mengakui kekalahan mereka menghadapi tantangan bisnis di era digitalisasi. Momen keruntuhan digdaya merek raksasa ini jelas mengundang tanya di benak banyak orang terkait biang kerok penyebab terjerumusnya sebuah brand legendaris di tengah kemajuan zaman.
Bengisnya kompetisi memaksa Tupperware berjibaku di red ocean market
Sejak awal kemunculannya, Tupperware dikenal sebagai merek premium. Terlebih, branding ini didukung dengan kualitasnya yang mumpuni. Akibatnya, harga jual yang dipatok di pasaran terbilang cukup tinggi sehingga membuat emak-emak menjerit histeris manakala kehilangan salah satu koleksi mereka.
Sayang, seiring perkembangan zaman, keunggulan posisi tersebut perlahan tak sanggup dipertahankan. Pasalnya, banyak produk alternatif bermunculan dengan menawarkan kualitas serupa. Pembeli yang lebih rasional dan sensitif terhadap harga, cenderung memilih produk dengan harga lebih miring. Kondisi ini mendorong Tupperware harus bersaing di pasar yang lebih berdarah-darah demi memperebutkan konsumen.
Kesusahan akibat menurunnya permintaan di tengah siksaan persaingan
Semakin kompetitif pasar, semakin sulit pula menggaet pelanggan. Perlambatan bisnis Tupperware sejatinya sudah terlihat di kisaran tahun 2000-an. Namun, seperti kalimat “blessing in disguise”, terpaan pandemi justru membawa berkah bagi Tupperware. Sebab, mayoritas orang memilih menyimpan makanan yang diolah sendiri demi alasan kesehatan.
Sialnya, anugerah tersebut tak berlangsung lama. Kesadaran masyarakat tentang dampak penggunaan plastik bagi kesehatan dan lingkungan turut menyeret perusahaan ini ke situasi yang lebih rumit. Konsumen dengan preferensi tersebut condong memilih wadah berbahan kaca atau stainless steel yang lebih tahan suhu. Merosotnya permintaan di satu sisi dan sengitnya kompetisi di sisi lain membuat Tupperware semakin kewalahan.
Tidak ada pesta yang tak usai
Hampir semua orang tahu apa itu Tupperware, tetapi sedikit dari mereka yang mengerti di mana produk tersebut dapat ditemukan. Fenomena ini wajar mengingat Tupperware senantiasa mengandalkan model pemasaran tradisional secara langsung yakni multi-level marketing (MLM). Di masa keemasannya, strategi ini sangat efektif untuk menjaring rekan sekaligus pelanggan.
Bahkan ada kampanye perusahaan bertajuk “Tupperware Parties” sangat diminati kala itu. Dalam acara tersebut, para konsumen berkumpul dan berbagi resep serta memborong sejumlah produk Tupperware. Namun konsep penjualan semacam ini sudah usang dan tidak lagi relevan diterapkan di era digital. Terhitung sejak pandemi, tren belanja masyarakat adalah daring. Pun, mereka menghindari berbagai kesempatan berkumpul bersama orang banyak.
Lambat laun dan terbentuk oleh kebiasaan, orang tak lagi antusias mengikuti “Tupperware Parties”. Selayaknya pesta yang berujung, popularitas Tupperware kian meredup, seolah memberi sinyal menyerah atas gempuran digitalisasi.
Inovasi klise Tupperware kurang menarik minat masyarakat
Tupperware memang melakukan inovasi. Celakanya, inovasi yang ditempuh dirasa kurang ampuh. Pertama, pilihan inovasinya bersifat tradisional yakni sebatas membuat produk ramah lingkungan. Gebrakan ini tak lagi menarik karena sudah banyak brand yang melakukan terobosan sejenis.
Di samping itu, sejatinya Tupperware lebih perlu mengedepankan inovasi model bisnis dan pemasaran mereka. Keterlambatan menumpangi tren e-commerce membuat Tupperware kehilangan kesempatan mencaplok pelanggan baru dengan karakter tech-savvy. Sementara, pelanggan lama mereka juga tak kunjung membeli produk termutakhir karena kemungkinan gagap teknologi atau disebabkan produk lama mereka masih dalam kondisi prima. Ya, ketahanan produk yang terlalu superior terkadang malah menjadi penutup rejeki itu sendiri.
Kebangkrutan Tupperware menjadi gambaran menohok tentang pentingnya adaptasi di dunia bisnis. Kebandelan brand besar ini untuk segera berubah membuatnya tersisih dari persaingan. Meski ketenarannya memudar, kehadirannya di dunia perdapuran akan selalu dikenang dengan segepok cerita lucu di baliknya.
Penulis: Paula Gianita Primasari
Editor: Intan Ekapratiwi
BACA JUGA Membela Ibu-ibu yang Menimbun Tupperware di Rumah.
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.