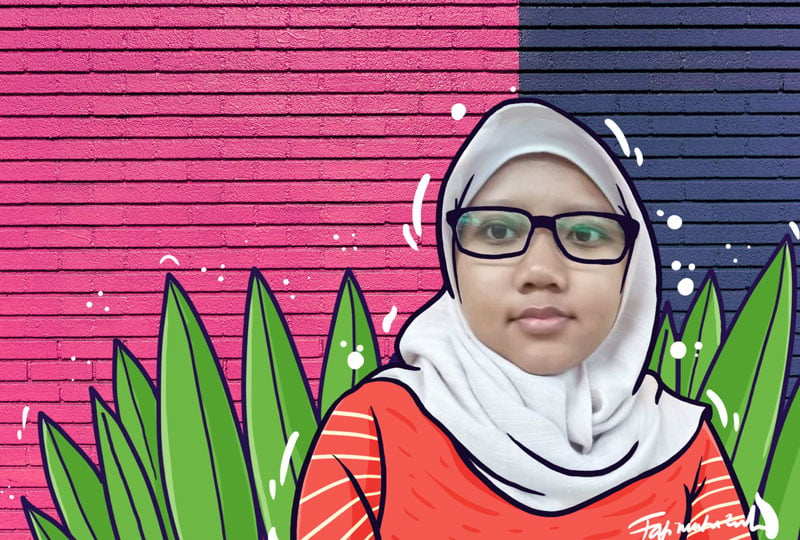Bagaimana bisa guru agama, profesi yang dituntut membentuk akhlak bangsa, justru digaji di bawah standar hidup layak?
Pertanyaan ini terus terngiang di kepala saya sejak pertama kali mengajar pasca-lulus dari jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir. Sebuah jurusan yang di awal begitu membanggakan, namun di ujung jalan seolah tak menawarkan banyak ruang untuk berdiri tegak.
Banyak orang mengira jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir memiliki prospek cerah. Sejak awal, kami dididik untuk menjadi intelektual muslim, pengkaji kitab suci, penjaga tradisi tafsir. Namun kenyataan membatasi pilihan karier hanya pada dua jalur sempit: menjadi guru agama atau berusaha masuk Kementerian Agama.
Tidak salah jika jurusan ini historisnya memang lahir untuk mendukung fungsi-fungsi Departemen Agama di masa lalu: penghulu, penyuluh agama, kepala KUA. Tapi apakah fungsi intelektual lulusan Al-Qur’an dan Tafsir hanya sebatas itu? Atau sistem pendidikan kita memang gagal membuka ruang imajinasi dan peluang?
Di kampus, sosialisasi profesi lain nyaris nihil. Nyaris semua dosen, alumni, dan pembicara tamu datang dari latar yang sama: birokrat Kemenag atau praktisi pendidikan agama. Pilihan-pilihan lain seakan kabur. Akhirnya, banyak mahasiswa—termasuk saya—terjebak dalam arus default: jadi guru agama atau berharap lolos CPNS.
“Ikhlas” yang dipelintir: ketika profesionalisme guru diperas
Mengajar agama adalah profesi mulia. Namun kemuliaan itu sering dijadikan dalih untuk menindas kesejahteraan. Saya pernah mengajar di sekolah Islam swasta dengan gaji tak sampai sejuta rupiah per bulan. Saat itu, sekolah belum terdaftar di Dapodik. Artinya, saya tak punya akses tunjangan. Gaji sekecil itu bahkan tak cukup untuk ongkos ke sekolah, apalagi kebutuhan hidup.
Ironisnya, ketika saya mempertanyakan hak saya, jawaban yang muncul hanya satu: “Mengajar itu ibadah. Ikhlaskan saja.”
Kalimat itu terdengar suci, tetapi juga menusuk. Seolah-olah ikhlas berarti menoleransi ketidakadilan. Seolah-olah profesionalisme guru agama tak perlu diimbangi penghargaan material. Lebih parah, beberapa sekolah malah menjadikan “ikhlas” sebagai dalih menambah beban kerja tanpa kompensasi.
Jadilah guru agama tidak hanya mengajar, tapi merangkap admin, pembina ekstrakurikuler, hingga “satgas” segala acara keagamaan sekolah. Semua tanpa tambahan insentif. Ikhlas menjadi mantra yang memaksa kami terus memberi tanpa diperhitungkan.
Pekerjaan sampingan bukan solusi: fokus guru terkikis, murid dirugikan
Ketika gaji tak cukup, solusinya hanya dua: cari kerja tambahan atau utang. Teman-teman saya banyak yang akhirnya bekerja sampingan: les privat, jualan online, bahkan driver ojek daring. Saya pun nyaris memilih jalur yang sama. Namun realitasnya, pekerjaan tambahan memecah fokus. Waktu dan energi yang seharusnya untuk mempersiapkan materi, memperdalam kompetensi, malah habis untuk bertahan hidup.
Akibatnya? Kualitas pengajaran menurun. Guru kelelahan. Hubungan dengan siswa renggang. Idealnya guru menjadi teladan dan pembimbing. Namun bagaimana bisa menuntut dedikasi penuh jika perut sendiri tak kenyang?
Lebih buruk lagi, sebagian guru terjebak dalam pinjaman online. Awalnya demi menambal kebutuhan mendesak, lama-lama terjerat bunga mencekik. Pesan-pesan penagih utang membanjiri ponsel, menambah beban mental di antara kesibukan mendidik murid.
Kondisi ini bukan hanya menghancurkan guru secara individu, tetapi juga perlahan merusak martabat profesi. Masyarakat mulai melihat guru agama sebagai profesi “kelas dua”, kurang sejahtera, kurang bergengsi. Tak heran, makin sedikit anak muda bercita-cita menjadi guru agama.
Prospek terbatas, persaingan ketat: CPNS Kemenag bukan jalan pasti
Banyak lulusan jurusan saya berharap bisa menjadi ASN di Kemenag. Tetapi harapan ini sering berakhir pahit. Formasi CPNS terbatas, pelamar membludak. Setiap tahun ribuan orang bersaing untuk puluhan kursi. Sementara peluang kerja lain nyaris tak terdengar.
Kini muncul aturan PPPK yang mewajibkan pengalaman dua tahun berturut-turut sebagai honorer. Tapi bagaimana menjadi honorer jika lowongannya tak pernah dipublikasikan terbuka? Banyak yang akhirnya percaya: “Kalau tidak punya kenalan, jangan berharap masuk Kemenag.” Apakah birokrasi kita sudah sebegitu tertutupnya?
Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir seharusnya punya lebih banyak pintu. Lulusan yang menguasai bahasa Arab, tafsir klasik, metode hermeneutika, seharusnya bisa bekerja di ranah riset, penerjemahan, media keislaman, atau lembaga think-tank. Sayangnya, peluang-peluang itu tak pernah terpetakan dalam bimbingan karier kampus. Yang tampak hanya jalur lama: guru agama atau Kemenag.
Saatnya menghentikan romantisasi pengabdian
Sudah saatnya kita berhenti meromantisasi “ikhlas” tanpa memperjuangkan hak guru. Ikhlas bukan berarti rela ditindas. Ikhlas bukan alasan untuk tidak digaji layak. Pendidikan yang berkualitas hanya bisa tercapai jika guru didukung secara profesional, termasuk secara finansial.
Kita perlu mendesak perguruan tinggi membuka wawasan karier lebih luas untuk mahasiswa jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir. Pemerintah perlu memperbaiki sistem rekrutmen yang lebih transparan dan adil. Dan yang terpenting, kita perlu mengubah cara pandang masyarakat: guru agama bukan pekerja sukarela. Mereka profesional yang layak dihormati, didukung, dan dihargai secara proporsional.
Kalau tidak, profesi guru agama akan terus menjadi “penjaga moral” yang ironisnya hidup dalam ketidakadilan. Kita sedang membiarkan generasi pendidik tumbuh dalam kelelahan, kekurangan, dan keputusasaan. Jangan salahkan jika nanti, tak ada lagi yang mau mengajar agama. Jangan kaget jika pendidikan karakter hanya tinggal slogan, karena para pendidiknya sendiri kehilangan martabat.
Mengajar itu memang ibadah. Tapi ibadah pun butuh modal hidup. Dan guru juga manusia.
Penulis: Syauqi Aulade Ghifari
Editor: Rizky Prasetya
BACA JUGA Sebagai Guru Agama, Saya Merasa Nggak Agamis-Agamis Banget