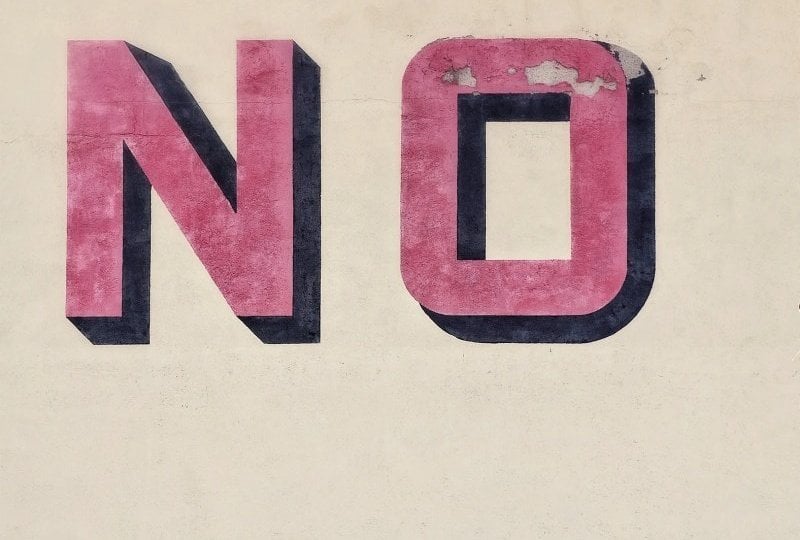Saya kesal belakangan ini, jadi saya banyak menulis tentang hal-hal halu yang berbau wibu seperti kesempatan bikin iklan sirup marjan, bayangan lockdown di desa konoha, sampai wawancara sama truk gandeng yang konon nasibnya jauh lebih baik dari para jomblo karena dia selalu punya gandengan. Yang jelas, saya tidak pernah menulis tentang kekesalan saya secara terang-terangan. Selalu ada media perantara supaya kekesalan saya ini nggak parah-parah amat. Bukan bermaksud narsis, tapi dalam tulisan ini saya ingin mara-mara!
Maaf-maafya pembaca Terminal Mojok, bukannya saya sedang mencari sensasi atau cari muka, bukan juga mencari pembelaan dari orang-orang yang kebetulan satu kepala dengan saya, tapi ini merupakan akumulatif kemuntaban saya. Banyak yang bilang selera saya ini murahan karena banyak serupa dengan arus utama. Mereka bebas menyukai siapa saja, lantas kenapa saya dikata-katai ketika menyukai apa yang menurut saya enak?
Tapi apakah tidak suka Feast lantas membuat saya udik dan tertinggal? Menjadikan saya aneh di mata orang-orang seperti kalian? Apakah ini salah saya? Salah otak saya? Salah lingkungan pergaulan saya? Bedebah!
Suka itu adalah hal yang wajar. Toh datangnya bisa dari mana saja, bisa melalui kelima indera, bisa juga lebih khusyuk melalui perasaan. Menyukai jenis kopi misalnya, biarlah itu menjadi urusan personal, mengungkapkan ke sosial media pun tentu diperbolehkan. Lha wong sosial media itu sebenarnya adalah perwujudan dari keadaan alamiah seperti apa yang dikemukakan oleh Thomas Hobbes. Ya, benar sih, sekarang ada UU ITE yang membuat garis batas antara yang diperbolehkan dalam dunia maya dan yang tidak. Namun, terkadang, garis batas yang dibuatnya itu sangat lentur seperti karet.
Pendapatmu lolos dari sorotan UU ITE, belum tentu lolos dari “aturan” perasaan yang dibuat secara khusus dan istimewa untuk para SJW. Tapi, ada satu teori yang akan disetujui secara universal. Yakni ketika ada yang bilang “apa cuma gue yang….” atau “apa cuma gue yang kalau makan dikunyah?” nih, ya, dari bermiliar-miliar orang di muka bumi ini, jangan menganggap dirimu itu sendirian. Masih banyak orang lain di luar sana. Kecuali cara makan bubur mu itu dengan cara diaduk, emang ada gitu? Nggak ada kan.
Sebenarnya sah-sah saja, sih, mau ngetweet tentang “Anda belum woke kalau belum nge-Feast 5x sehari” atau “nge-Feast itu sama seperti perlawanan sosial”. Mau mengungkapkan orientasi kesukaanmu terhadap apa pun juga, bebas dan boleh-boleh saja. Yang menjadi berlebihan itu ketika apa yang kamu sukai, dalam konsep pikiranmu sudah membentuk asumsi bahwa hal di luar itu adalah sampah.
“Gue berharap cuma gue yang tahu apa itu nge-Feast” lho kumaha tho? Kalau kamu anak sultan, raja minyak atau anaknya Hotman Paris, nggak masalah. Terus kalau yang nge-Feast sudah banyak, terus kenapa? Merasa nggak spesial? Terus kenapa nyalah-nyalahin saya kalau saya nggak suka nge-Feast? Tuh kan, jadi banyak tanda tanyanya. Emang kalau saya sedang mara-mara, jatuhnya malah seperti mahasiswa ambis yang cari muka sama dosen dengan cara nanya-nanya padahal tahu jawabannya.
Nih, ya, saya kasih tahu, Feast juga butuh uang untuk makan, bukan cuma bikin sesuatu buat kamu seorang. Jangan menjadi spesial karena sebuah hal yang membuatmu berbeda dari pandangan orang kebanyakan. Terus pasti pada berkomentar “yang masih nge-Feast di tahun 2023, 2024, 2050…selera kalian bagus”. Hassh, Mas….
Juga ada yang bilang, “Feast saya laporkan ke BNN! Kayaknya mengandung zat aditif berbahaya yang bikin kecanduan, nih. Yang nggak kecanduan seleranya jelek!”. Nih orang pasti belum pernah denger idiomnya Karl Marx yang mengatakan agama adalah candu. Konsep sebuah “selera” yang sempit sekali penjabarannya. Juga sangat ketat, seketat legging ibu-ibu senam. Saya pun tertawa melihat tingkah anak-anak nge-Feast ini.
Memang lebih mudah menyalahkan atau memandang rendah seseorang yang tidak satu aliran. Dalam berbagai perpektif dan keilmuan, sikap ini dinamakan intoleran. Ketika mayoritas menggerus minoritas, namun dalam studi kasus yang satu ini, minor lah yang memandang mayor begitu rendah karena selera mereka seragam. Ya, saya tahu, sesuatu yang seragam itu emang terkadang menyebalkan, banyak aturan dan kolot. Tapi ketika kalian yang merasa eksklusif membangun gagasan sendiri atas apa itu “standar kalian”, ya bagaimana orang-orang ini masuk dalam kategori terntentu dalam otak kalian?
Pernahkah kamu berada dalam sebuah lini masa sosial media, ketika saya share apa yang saya suka, kalian datang mencemooh? Saya sedang asik menikmati apa yang saya suka, lalu kalian berkomentar, “ah, seleranya mainstream, lidah gue nggak welcome”. Heh spatula Spongebob, apa pun yang aku nikmati adalah apa yang aku persembahkan untuk diriku sendiri. Jika kalian sudah memiliki pakem sebuah sifat “keren” menurut pemikiran kalian, ya monggo-monggo saja. Lidah-lidah saya, kuasa saya, bukan?
Biarlah saya menjadi seperti ini. Terjebak dalam arus mainstream yang kalian benci. Saya hanya bisa berdoa kepada semesta alam dan segenap pelindung di dalamnya. Menanti kapan cemoohan ini akan berakhir dan selesai. Dengan menikmati guyuran hujan dan paparan sinar matahari yang perlahan menghilang, saya pun berujar “persetan dengan Feast yang kalian puja! Saya selamanya akan tetap suka dengan Hula-Hula ala Campina” *jilat es krim*.
BACA JUGA Benci Hal Populer Nggak Berarti Pengin Sok Edgy dan Elitis atau tulisan Gusti Aditya lainnya.
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.
Pernah menulis di Terminal Mojok tapi belum gabung grup WhatsApp khusus penulis Terminal Mojok? Gabung dulu, yuk. Klik link-nya di sini.