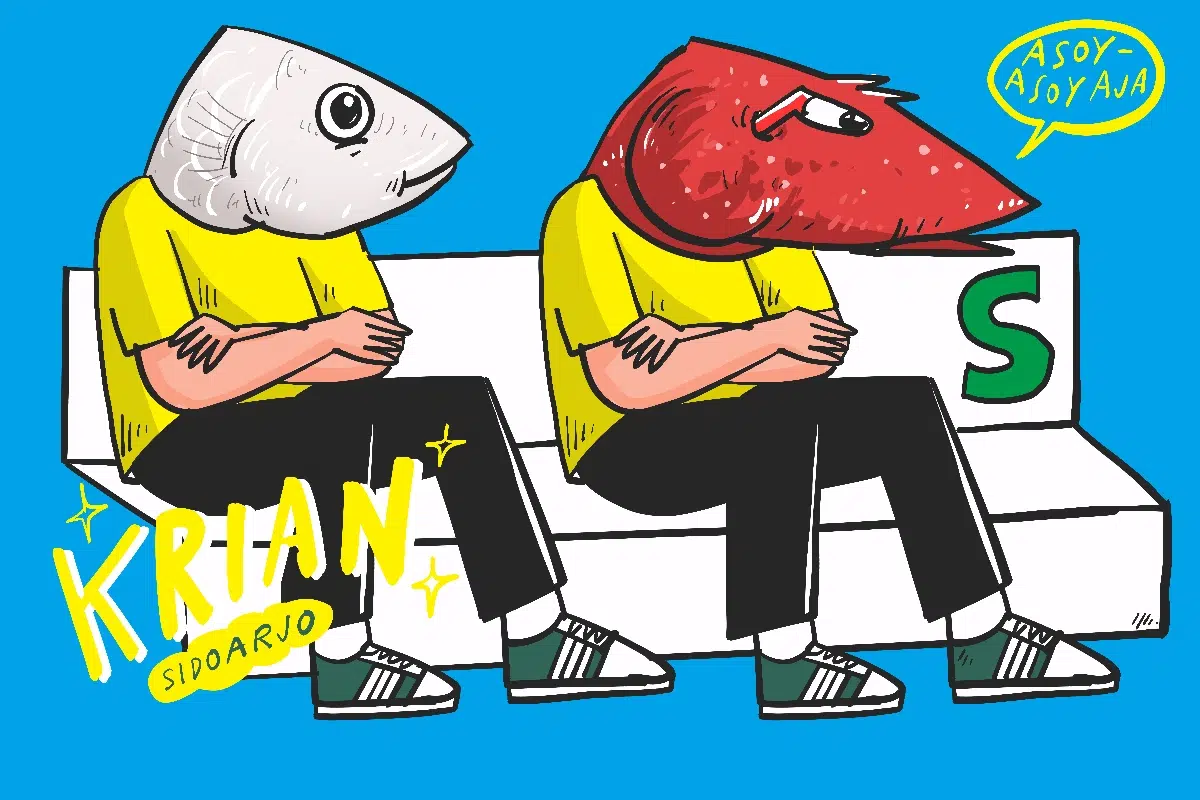Bagi kami yang bekerja di Jakarta, menghadapi kemacetan adalah hal yang biasa. Sekalipun memuakkan, kami seolah dipaksa untuk mencintainya.
Sejak pandemi dinilai sudah mereda, kemacetan di Jakarta terlihat makin menggila. Penyebabnya apalagi kalau bukan karena bertambahnya volume manusia dan kendaraan di jalan raya pasca dicabutnya PKKM dan kembali diberlakukannya WFO.
Berdasarkan data dari BPS tahun 2021, penduduk Jakarta sudah mencapai angka 10 juta jiwa. Yang makin membagongkannya lagi, jumlah kendaraan yang tercatat bahkan dua kali lipat jumlah penduduknya, yakni 21,7 juta unit. Itupun belum menghitung angka para pekerja komuter dan kendaraan yang datang dari luar daerah serta penambahan jumlah keduanya pada 2022.
Dengan luas jalanan yang terbatas dan volume pengguna yang besar, jarak tempuh 2 jam menjadi hal yang biasa. Itu pun hanya menghitung satu kali perjalanan saja, baik itu berangkat atau pulang. Belum kalau saat cuaca sedang hujan yang alih-alih sepi, malah makin macet!
Sebagai pemotor, selain mengatur waktu keberangkatan lebih awal, saya juga perlu memastikan fisik yang prima. Kelenturan pinggul saya selalu diuji saat harus menyalip di antara mobil dan tronton yang berbaris di jalanan Daan Mogot. Belum lagi bokong tepos saya yang nggak berdaya saat menghantam jalanan berlubang.
Sampai saat ini, pilihan menggunakan kendaraan pribadi masih menjadi hal yang paling rasional. Selain akses kereta yang jauh, pilihan transportasi lainnya nggak cukup efisien secara waktu dan ongkos.
Di daerah saya misalnya, yang mendekati standar kota, stasiun terdekat ditempuh dengan 50 menit perjalanan dari rumah alias sudah setengah perjalanan menuju kantor. Pilihan lain yang bisa mengantarkan saya ke Jakarta adalah travel atau bus AKAP yang ongkosnya setara uang makan siang.
Masalah ini pun ternyata nggak hanya menjumpai saya. Beberapa orang lainnya bahkan harus mengeluarkan effort lebih dengan berangkat sebelum subuh untuk bisa sampai ke kantor. Gila!
Kadang saya juga heran, dengan segala keruwetannya, kok ya masih banyak yang mau bekerja di sana. Namun setelah setahun menjadi bagian dari mereka, akhirnya saya paham kenapa Jakarta masih menjadi wilayah paling diminati.
Terlepas dari nominal gaji yang memang oke, saya bisa mengatakan bahwa sektor pekerjaan dan industri di Jakarta lebih luas dan merata. Misalnya saja untuk dunia kreatif dan digital marketing seperti yang saya jalankan saat ini. Nyatanya, ketersediaan lapangan kerja tersebut masih menjadi hal yang terbatas dan sulit ditemui di daerah kabupaten. Setidaknya di tempat asal saya, Kabupaten Tangerang.
Keluwesan pencari kerja dalam mencari sektor pekerjaan yang sesuai dengan skillset mereka pun akhirnya mendorong orang-orang untuk datang ke Jakarta. Ya, argumen mengenai pemerataan yang sudah umum ini nyatanya belum begitu usang untuk menjelaskan pertambahan penduduk dan kaitannya dengan kemacetan.
Namun, apakah pertambahan jumlah manusia di Jakarta menjadi faktor utama kemacetan? Kalau kembali pada pernyataan di paragraf ketiga, ada satu lagi variabel yang perlu diperhatikan dan turut menciptakan kekacauan ini. Apa itu, adik-adik? Yak, betul. Kendaraan!
Sebenarnya isu kendaraan dan transportasi umum ini telah menjadi wacana yang sering digaungkan di mana-mana, termasuk oleh para SJW Twitter dan para kaum komuter lainnya. Sekalipun Jakarta dianggap memiliki sistem transportasi yang baik, namun ternyata hal ini belum cukup untuk mengakomodasi kebutuhan warga Jabodetabek lainnya.
Lihatlah bagaimana Stasiun Manggarai yang selalu dipenuhi oleh lautan manusia tiap harinya. Atau gerbong-gerbong KRL pada jam pulang kerja yang membuat manusia menjadi pepes hidup. Jangan ditanya sumpeknya kayak apa.
Cerita mengenai kaum komuter dan perjalanan kerjanya ini sudah seperti love-hate relationship. Satu sisi kami benci dengan segala keruwetan di jalan, namun di sisi lain ya kami butuh juga untuk mengais rezeki di sana.
Agak naif memang kalau melihat masalah ini dari hilirnya saja tanpa memerhatikan masalah di hulu. Toh pada akhirnya, masalah ini saling berkaitan antar kota satu dengan yang lainnya, apalagi di kota-kota satelit Jakarta.
Kalau bisa berandai-andai, tentunya saya berharap ada angkutan massal yang terintegrasi dan menghubungkan tiap kota. Sekalipun sudah ada KRL, tapi keberadaannya belum bisa mencakup daerah lain yang lokasinya jauh di rel.
Kalau perlu dan memang seharusnya begitu, tiap kota idealnya memiliki transportasi yang memadai. Nggak harus kereta deh, minimal angkutan umum yang nyaman dan saling terhubung dengan harga terjangkau.
Pasalnya, salah satu sebab yang mendorong orang untuk bepergian menggunakan kendaraan pribadi adalah akses transportasi umum yang belum memadai. Nggak perlu bicara jauh-jauh soal kualitas angkutan dulu, bagaimana mungkin untuk mengajak masyarakat menggunakan transportasi umum sedang transportasi umumnya aja bisa dihitung jari.
Tapi apalah saya yang cuma bisa misuh-misuh dan berandai-andai ini. Perkara jalanan rusak dan penerangan jalan yang minim aja nggak ada tindak lanjut, apalagi membangun kota yang ramah pejalan kaki dan mudah diakses oleh siapa pun.
Pada akhirnya, kondisi yang serba terbatas dan cenderung terkesan apa adanya ini harus disikapi dengan pasrah. Atau ini cara mereka yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengajarkan warganya bahwa kita tidak bisa melakukan apa-apa terhadap sesuatu yang di luar kontrol?
Penulis: Muhamad Yoga Prastyo
Editor: Rizky Prasetya
BACA JUGA Apa yang Sebenarnya Perlu Kita Lakukan untuk Mengatasi Kemacetan?