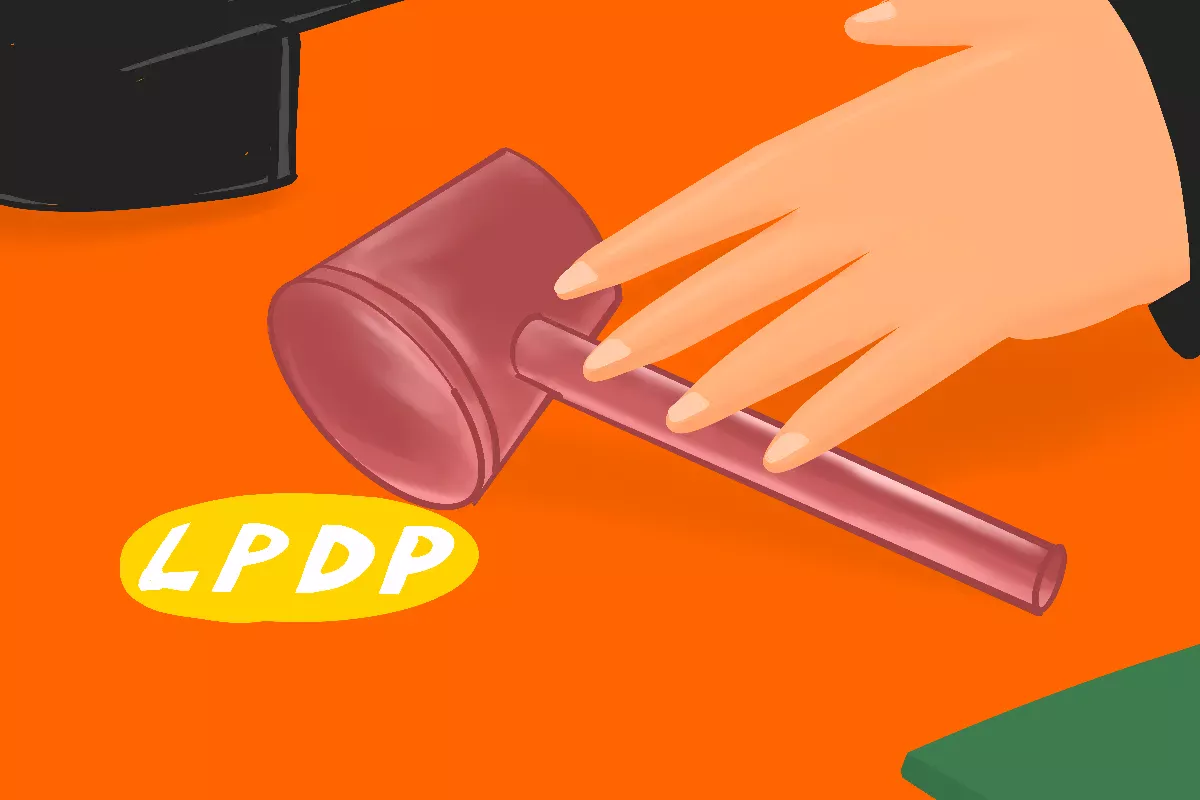Konflik pesilat SH Terate dan Winongo di Madiun sepertinya tak akan berakhir, selama akar masalah tak segera diselesaikan
Bagi masyarakat Madiun, pertikaian perguruan silat bukan lagi tragedi, ia sudah jadi wisata tahunan yang di dalamnya memuat makian, pekik ketakutan, bahkan kematian. Di tanah lahirnya 14 perguruan silat, perdamaian hanyalah khayalan, yang abadi benih pertikaian. Narasi damai hanyalah peluru diplomasi yang kian lama kian basi. Mereka berhasil mengelaborasi olahraga, seni, bela diri, dan kejernihan rohani, yapi lupa dan sering gagal dalam mewujudkan persaudaraan.
Datangnya bulan Suro bukanlah kabar bahagia bagi saya. Bulan yang penuh keberkahan yang menitikberatkan kedamaian malah jadi bulan yang mencekam dan menakutkan. Saat daerah lain merayakan Malam 1 Suro dengan ritual pembacaan doa, Madiun berani tampil beda. Kota ini merayakan suro dengan bisingnya suara knalpot. Keramaian tersebut, bahkan, bikin TPA dibubarkan sementara, agar anak-anak yang mengaji tak kenapa-kenapa.
Pencak silat, bagi warga Madiun adalah cinta, wujud cintanya terpampang oleh tugu kokoh yang ada di tiap perempatan desa, gang kecil rumah warga, serta melekat dengan kain cotton combed 24s dalam wujud kaos. Mencintai pencak silat bagi orang Madiun sama halnya dengan rasa cinta penduduk Surabaya terhadap Persebaya, rasa cinta warga Malang dengan Arema.
Saking cintanya warga Madiun terhadap pencak silat, mereka sampai lupa dengan adagium lama yang sering digembar-gemborkan sesepuhnya, “Bedo guru ojo nesu, tunggal guru ojo padu.” Narasi perdamaian semacam ini hanya bisa diucapkan, mustahil untuk diwujudkan. Karena memang, tidak pernah serius untuk diwujudkan.
Kubu Kuning vs Kubu Putih
Hari yang tidak saya inginkan akhirnya tiba. Tenda-tenda keamanan berdiri kokoh, aparat berjaga sesuai tugasnya, Polisi dan TNI bersiap dengan strategi pengendalian masa terbaik yang telah mereka rencanakan. Warga desa pucat ketakutan, anak kecil hanya bengong dan bertanya-tanya. Dan inilah golongan yang paling membara, pemuda dengan jiwa “pendekar” bersiap dengan segala konsekuensi lapangan. Hari itu benar benar menakutkan, pesilat dari kubu “putih” bersiap di pinggir jalan untuk menunggu dan mengawasi pesilat kubu “kuning” yang rencananya bakal konvoi dengan tujuan akhir nyekar di makam sesepuh.
Sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, pesilat kubu “kuning” bakal melintas di desa yang mayoritas “putih” pada pukul 09.00 WIB. Desa ini tak lain tak bukan ya desa saya tercinta. Beberapa pesilat berlambangkan hati bersinar dan bersiap dengan mindset “mbleyer kepruk” atau dalam bahasa mudahnya, kalau ada pesilat kubu “kuning” yang melintas dan menggeber motornya, itu pertanda genderang perang dimulai. Hal yang tidak saya inginkan akhirnya terjadi. Kira kira 09.12 WIB salah satu dari ratusan pesilat kubu ”kuning” menggeber motornya dengan penuh bangga. Yang jelas tindakan ini memancing emosi kubu “putih” untuk meluapkan kebencian.
“Jancok, lewat yo lewat wae, ora usah mblayer mblayer garai rusuh!”, pekik makian kubu putih. Kondisi makin memanas, beberapa pesilat adu pukul, rombongan konvoi yang masih di atas motor dan tidak bersalah juga ikut ditendang. Ibu-ibu yang berdiam diri di dalam rumah akhirnya keluar dan panik. Polisi sibuk mengamankan beberapa pesilat yang arogan, pengendalian massa gagal, rumah warga rusak, darah berceceran, tangis di mana-mana.
Hal ini terus berulang dengan pola yang sama, mengedepankan ego sektoral di atas semuanya. Cerita kali ini bukan soal kubu “putih” yang kita kenal dengan Persaudaraan Setia Hati Terate melawan kubu “kuning” atau biasa disebut Persaudaraan Setia Hati Tunas Muda Winongo Madiun. Ini cerita pertikaian yang terjadi saat Subuh, saya masih ingat persis kisah ini, sebab saya ikut andil dalam pertempuran ini. Pengalaman masa kelam, bermodalkan ikut-ikutan, biar keren dan diakui tongkrongan.
Oke kita mulai. Cerita berawal saat saya dan kawan kawan desa kumpul jagongan, obrolan yang kami bahas ya obrolan pos ronda pada umumnya, hingga nyeletuklah salah satu dari kami “eh, engko Pandan Alas mudun lo!” Mudun di sini diartikan turun gunung. FYI, Pandan Alas Madiun ini punya Padepokan Pusat di Kecamatan Kare yang terletak pada dataran tinggi. Jadi kalau mereka habis pengesahan dan perjalanan pulang mereka bakal turun untuk kembali ke rumah.
Muncullah narasi untuk begadang sampai Subuh guna menunggu para pesilat Pandan Alas. Ingat, kami tak sekadar menunggu. Kami siap menyergap siapa saja yang mbleyer dan mengganggu tata aturan yang kami ciptakan.
Malam itu kami mengatur pola pengamanan berbalut penyerangan dengan sistematis. Ada yang turun ke tengah jalan untuk menghadapi rombongan pendekar face to face. Ada yang berjaga di gang-gang desa, ada yang bersiap di atas motor, jaga-jaga kalau nanti ada rombongan polisi yang mengejar kami.
“Kalau ada yang mbleyer dan tidak dikawal polisi, sikat! Mengganggu kenyamanan desa itu namanya!”
Komando dari kawan kami pegang dengan teguh. Dan tak lama berselang, rombongan Pandan Alas datang dan tak dikawal. Terbit senyum tanpa kami sadari. Tanpa kawalan polisi, artinya, kami bisa leluasa menghajar mereka.
Yang terjadi selanjutnya adalah pertempuran, tentu saja. Suara erangan karena dihajar, dan teriakan beringas lah yang terdengar malam itu. Namun di antara semua itu, ada satu tindakan kejam yang kami lakukan. Ada “mori” salah satu rombongan yang dibuang kawanku ke sungai. Saya yang menyaksikan peristiwa itu tanpa sadar ikut sedih. Mori bukanlah sembarang kain bagi pendekar, ia adalah hidup dan mati, ia adalah pegangan hidup yang penuh filosofi.
Kenapa mori begitu berarti bagi para pendekar? Karena ia bukan sekadar kain. Ia memuat filosofi kehidupan, tanda perjuangan, dan pengingat kematian. Singkatnya, kain ini, adalah pengingat untuk selalu jadi manusia yang baik.
Dan pengingat akan kebaikan tersebut, dibuang ke sungai, seakan kehidupan tak ada artinya. Sejak itulah, saya tak ingin lagi ikut andil.
Menyelisik akar masalah permusuhan