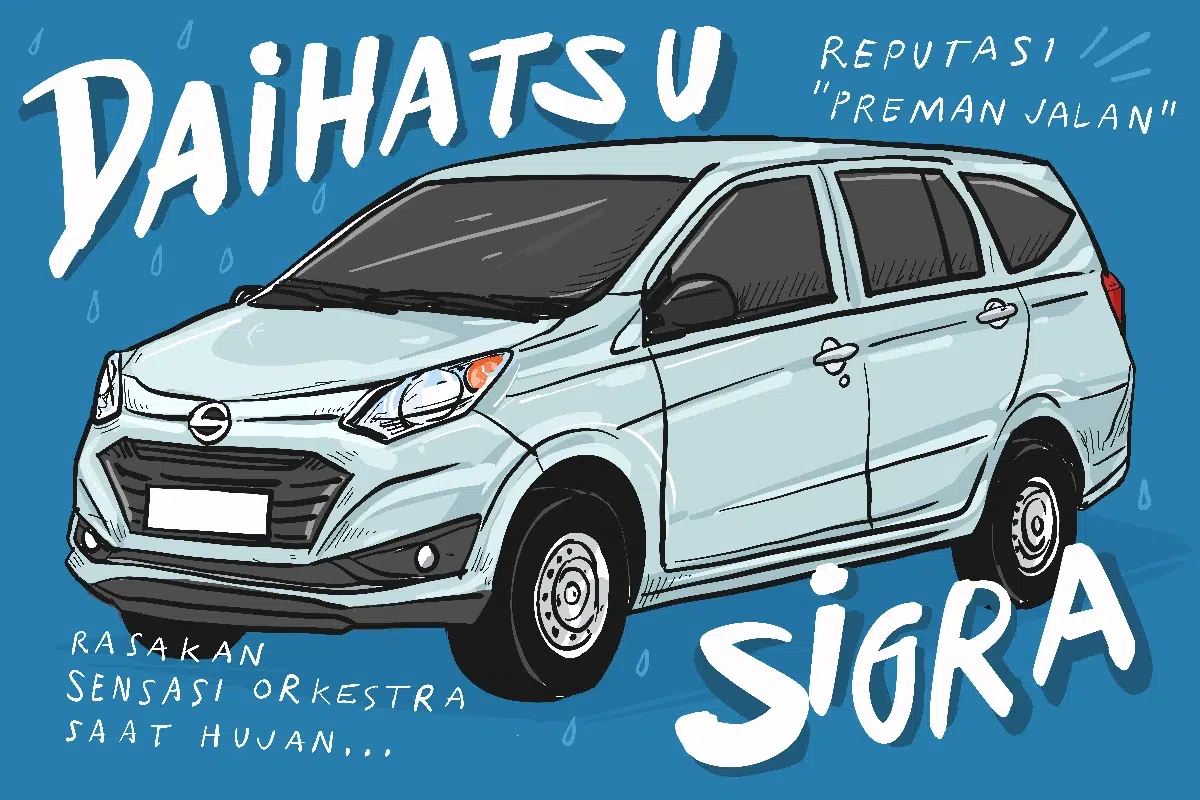Pekan kemarin saya baru sakit. Masuk angin tepatnya. Setelah melakukan terapi kearifan lokal ala kerokan, minum tolak angin dan luluran balsem, saya membaik. Tapi 1×24 jam saya tinggal rebahan, kondisi rumah saya memburuk. Inilah yang bikin saya berpikir kalau istilah “ibu dilarang sakit” itu mungkin menandakan betapa sakitnya ibu rumah tangga.
Selepas saya sakit, pekerjaan rumah tangga menumpuk. Cucian piring segunung dan rumah jadi berantakan. Hasrat ingin beres-beres menjadi motivasi utama kesembuhan saya.
Di hari kedua saat hendak salat, saya sadar tak ada tempat yang memadai. Memang lantai bersih dari najis, tapi rasanya kok acakadut nggak karuan. Sambil menahan migrain, saya menyapu, mengepel, memindah perkakas kotor ke sink, lalu ngomel.
“Kenapa sih nggak bantuin nyapu? Lagi sakit jadi tambah pusing deh liat rumah berantakan.”
Suami memamerkan senyum pepsodent dan angkat bahu. Saya makin kesal. Saat marah, saya lupa kalau minimal ada dua persepsi yang berbeda antara saya sebagai ibu rumah tangga dan suami sebagai pria soal kenyamanan rumah. Setidaknya ini yang saya alami. Bukan berarti semua suami tidak berbakat urusan rumah tangga loh ya.
Pertama, ambang batas kebersihan yang berbeda. Sebagian pria, suami saya merasa baik-baik saja menghabiskan hari dalam kondisi rumah yang berantakan. Fokusnya mungkin hanya pada pekerjaan dan anak-anak.
Suami bukannya tidak membantu. Suami menggantikan saya mengasuh empat anak, masak ala koki kaki lima, dan sesekali jadi juri pertengkaran anak-anak. Itu semua dilakukan di sela dua rapat virtual dan pekerjaannya. Saya tidak bisa memaksanya ketambahan urusan rumah tangga. Desain otak kirinya terbiasa fokus menyelesaikan masalah. Bukan menjlentrehkan semua masalah secara bersamaan seperti saya.
Yang kedua adalah tingkat kepekaan menghadapi rumah yang berantakan. Sebagian pria baik-baik saja duduk di depan laptop dengan kondisi lantai rumah yang berdebu. Mereka yang seperti ini mungkin nggak ngeh bahwa perkakas dan semua yang berhamburan di lantai ini tidak bersayap. Tidak bisa kembali ke tempatnya masing-masing secara mandiri. Harus ada seseorang yang membereskannya.
Ini bukan pertama kali saya sakit, tapi menurut suami, saya sakti. Sun Go Kong kali ah! Saya sakit masih bisa banyak bicara, minta ini itu dan makan dengan baik. Sakit tak sungguh-sungguh melemahkan saya.
Padahal seperti juga suami, istri juga bisa sakit. Posisinya setara sebagai manusia biasa. Hanya level menerima rasa sakit saja yang berbeda. Bisa jadi, istri yang sudah diuji dengan rasa sakit melahirkan mampu menahan sakitnya masuk angin daripada seorang suami.
Tapi, kenapa ada istilah “ibu dilarang sakit”?
Kalimat ini bahkan banyak dicurcolkan para ibu saat kondisi mereka lemah, tapi suami tidak bisa diharapkan urusan beres-beres rumah. Atau, hasil beberes suami tidak sesuai harapan istri. Apa karena ekspektasi istri soal standar pekerjaan rumah tangga amat tinggi? Bisa jadi.
Para suami dulunya juga bujangan yang mandiri. Biasa masak Indomie dan nyuci baju sendiri meski kadang laundry. Tapi, urusan kebersihan dan kerapian memang standarnya di bawah perempuan. Ini rahasia umum bujangan.
Kemampuan basic skill bukannya tidak dikuasai pria. Basic skill bagi pria ya memang sebatas basic. Asal bisa buat bertahan hidup dan wangun saja. Tidak sedetail dan se-advance perempuan. Apalagi estetik segala. Terkadang otak pria dan wanita memang disetel beda pada beberapa sisi. Dan inilah yang saya alami. Kecuali kalau ada suami yang memang punya standar tinggi soal kebersihan dan kerapian, bukan nggak mungkin justru lebih terlatih mengurus pekerjaan rumah tangga.
Yang banyak dikeluhkan para istri, kebanyakan setelah menikah, basic skill pekerjaan rumah tangga pria justru menurun. Pria secara sukarela menyerahkan urusan beres-beres pada orang yang dianggap ahli. Beberapa pria sadar, mereka tidak akan menang melawan urusan rumah tangga dengan wanita. Jadi, mereka memilih medan pertempuran di tempat kerja, bukan fokus di cucian piring.
Hal ini sama sekali tidak meremehkan perempuan dan laki-laki. Kecuali jika ada yang menganggap pekerjaan domestik itu nomor dua. Saya sih nggak ya.
Sebagai makhluk seharusnya setara, wanita bisa berkiprah di luar kerja domestik. Baik sekolah, bekerja, maupun aktiv dalam kegiatan sosial. Segala kesibukannya di luar itu tidak mengurangi kemampuan unggul wanita dalam mengelola rumah tangga. Sakti banget, memang.
Suami dan istri sama-sama memiliki peran dalam rumah tangga. Nggak apa-apa kalau ada pria yang lebih ahli urusan rumah daripada wanita, silakan dioptimalkan. Tapi, bukan berarti menuntut pria dengan kemampuan rumah tangga mininal agar setara dengan kemampuan wanita. Menyerahkan urusan pada ahlinya hasilnya akan lebih efektif dan efisien daripada meributkan suami harus bisa nyapu sebersih istri.
Saya sadar, mengeluhkan suami yang tidak multitasking bab rumah tangga adalah sia-sia. Bukan suami tidak mengambil peran tapi jangkauannya terbatas. Delapan tahun menikah, urusan mengambil baju tanpa mengubah tumpukan yang rapi jali saja belum sempurna bagaimana saya menyerahkan urusan rumah? Fix, saya superior pada urusan rumah tangga dibanding suami saya sendiri. Makanya bagi saya istilah “ibu dilarang sakit” bukan berarti merendahkan peran gender antara perempuan dan laki-laki. Justru istilah ini adalah bukti bahwa para ibu begitu hebat.
Buktinya setelah ngomel soal rumah, suami tetap tidak bergegas membantu. Dia mendengarkan dan mengukur kondisi fisik dan psikis saya setelah seharian tidak nafsu makan. Dia hanya bertanya,
“Mau dibeliin apa?”
Tanpa sungkan saya menjawab nasi padang lauk ayam bakar dan es buah yang mangkal depan Sarangeui Oppa.
“Mau bilang lapar aja urusannya sampai kemana-mana,” cetusnya.
Oke, saya memang superior dalam pekerjaan rumah tangga, tapi urusan ditawarin makan, saya gampang luluh juga. Hehehe. Ibu memang dilarang sakit, tapi bapak dilarang cuek. Kalau seorang suami nggak perhatian, mana mungkin nawarin membelikan makanan. Ya nggak?
BACA JUGA Pekerjaan Rumah Tangga Mengubah Pandangan Saya terhadap Perempuan dan tulisan Yosi Prastiwi lainnya.