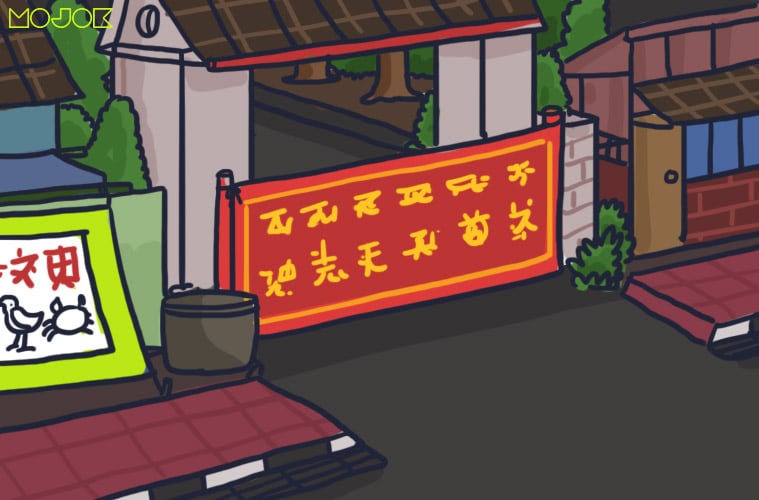MOJOK.CO – Setiap tahun saya mendapat ucapan selamat Imlek dari teman-teman yang bukan Tionghoa. Saya berterima kasih atasnya, tetapi ada kalanya saya merenung lebih jauh….
Pagi ini saya bangun disambut ucapan selamat Imlek di WhatsApp dari lima teman. Mengingat saban tahun ada saja ribut boleh-tidaknya mengucapkan selamat Natal, saya tidak bisa tidak bahagia para sahabat saya begitu welas asih, mau menyelamati saya demi merayakan tahun baru China yang penuh doa-doa baik ini.
Agus Mulyadi, teman sekantor saya itu, bahkan lebih cekatan. Ia sudah mengucapkan “Gong xi fa cai” dua hari lalu.
“Gus,” balas saya dengan penuh pengertian, “Imlek masih lusa.”
Saya memang punya tampang Tionghoa, seturut ciri-ciri yang didefinisikan orang-orang di sini. Mata saya sipit memanjang, dengan kelopak mata yang kurang tegas serta tanpa kantung mata. Kulit saya lumayan terang. Rambut saya lurus hitam.
Ibu saya memang orang Tionghoa. Jadi kalau ada orang tanya, “Ibunya China ya?” saya masih pede menjawab iya. Paling nggak Ibu bisa bahasa Tio Ciu dan Hakka. Keluarganya juga memegang filosofi Tionghoa dan hafal peribahasa-peribahasanya (“Kalau bukan orang beruntung, jadilah orang yang giat bekerja,” katanya suatu ketika. “Dari ayam jadi kambing, dari kambing jadi kerbau,” ucapnya di lain kali, mengingatkan saya untuk bekerja keras memperbaiki kesejahteraan keluarga). Ia berasal dari Pontianak, tapi sudah hampir 20 tahun tinggal di Jawa. Tetap saja, jika marah, kadang umpatan bahasa Tio Ciu-nya yang keluar.
Bapak saya orang Jawa, dan saya merasa lebih menguasai kultur yang satu ini ketimbang tradisi etnisitas ibu saya. Waktu saya kecil, saya dininabobokan dengan lagu-lagu Jawa (“Bebek Adus Kali”, “Lesung Jumengglung”, “Soyang-soyang”, “Menthok-menthok”), juga dengan dongeng-dongeng pewayangan yang hingga kini masih saya hafal. Sewaktu kuliah, saya menemukan lagu “Menthok-menthok” diaransemen dalam irama jazz, dan itu membuat saya senang sekali. Seperti dilemparkan ketika masih dalam buaian orang tua.
Jadi begitulah. Saya tahu beberapa tradisi Tionghoa Kalimantan, Imlek mereka beserta pohon sakura dan jeruk bali dengan tempelan kertas merah bentuk hati. Saya menguasai sedikit resep masakan Tio Ciu yang rata-rata cepat sekali dibikin: semua tumis-tumisan sayur dengan bumbu bawang putih geprek dan garam, atau makanan favorit saya, tumis timun yang diaduk dengan telur (wah, ini enak sekali).
Tapi kalau ditanya, apakah saya seorang Tionghoa, saya tetap keder bilang iya. Seumur hidup, di perayaan Imlek saya hanya berperan sebagai tamu. Saya bisa ngomong Hokkian di sekitar istilah makan-makan doang, seperti ciak cui (minum), bo ciak (nggak mau makan), atau ho ciak (enak). Lagian kulit saya, aduh, kalau dibandingkan teman yang totok, masih kalah bening.
Namun, semua itu tidak mementahkan ucapan selamat Imlek yang saya terima tadi pagi dan di Imlek-Imlek tahun-tahun lampau. Salah alamat memang, karena saya tidak berada dalam pesta dan ritual yang merayakannya. Tapi ada kalanya tho kita dapat paket salah alamat yang bikin kita justru senang?
Saya memutuskan merengkuh ucapan selamat Imlek itu, persis seperti saya merengkuh panggilan “Cik” yang makin hari makin terdengar biasa. Yah, ini memang bagian dari identitas saya.
***
Saya dibesarkan sebagai muslim bertampang Tionghoa yang akrab dengan kultur Jawa tapi tinggal di lingkungan multikultural. Desa saya di Kalimantan dulu, yang sudah saya tinggalkan selama 19 tahun itu, dihuni orang dari banyak suku dan etnis. Teman sekolah saya merentang dari suku Melayu, Tionghoa Hakka, Tionghoa Hokkian, Palembang, Madura, Dayak, Ambon, Sasak, Batak, Jawa, Bugis, Minang, dan Minahasa. Tinggal orang Aceh, Betawi, dan Papua saja yang saya nggak pernah lihat.
Saya juga menyaksikan sendiri agama yang beragam dan pada masanya, pernah menimbulkan kengawuran yang mungkin gawat, tapi bagi anak-anak terasa lucu. Beberapa teman saya yang Konghucu tidak punya kelas agama sendiri. Jadi mereka akan main-main dengan masuk kelas Katolik tahun ini, lalu pindah ke kelas Protestan di tahun depan.
Baru belakangan identitas tersebut jadi agak membingungkan. Begitu pindah ke lingkungan monolitik di Jawa medio 2002, tampang China saya jadi pertanyaan. Biasanya karena identitas saya yang satu dianggap tidak cocok dengan identitas saya yang lain. Misalnya Agus Mulyadi yang pernah berbulan-bulan mengira saya Kristen. Ini sering sekali terjadi. Yah, cukup disenyumin aja sih. Cuma kadang rada nggak percaya juga, 600 tahun setelah Laksamana Cheng Ho datang ke Nusantara, orang masih aja mikir orang Tionghoa pasti nonmuslim. Gus… Gus….
Kerumitan lain menyangkut “asal”. Saya sudah 10 tahun tinggal di Jogja dan, sebagaimana jika Anda ke Jakarta, jika bertemu orang asing kerap ada pertanyaan, “Aslinya mana?” seolah-olah ada asumsi, sebagian besar orang yang tinggal di sini pasti pendatang–sebuah istilah yang problematik.
“Banyumas, Pak,” kata saya berulang kali. Dan ya, sudah bisa ditebak lanjutannya bagaimana.
“Kok nggak ngapak ya?”
Kalau ada waktu dan punya niat, kadang saya cerita panjang bahwa saya lahir di Pontianak, lalu di usia tiga tahun pindah ke Ketapang (300 km dari Pontianak dan punya bahasa sendiri, dekat dengan perbatasan Kalimantan Barat-Kalimantan Tengah), lalu saat SMP pindah ke Banyumas untuk tinggal di sana selama lima tahun, lalu tinggal di Jogja selama 10 tahun. Artinya, pertanyaan “asal mana” itu memang aslik sulit dijawab. Jika sedang ingin menyederhanakan percakapan, saya bilang saja, “Saya orang Jogja,” karena toh, inilah tempat yang paling lama pernah saya huni.
Berbagai pengalaman tersebut membuat saya banyak memikirkan identitas. Kadang sampai terlalu memikirkan hingga hasilnya malah jadi konyol seperti kejadian ini.
Saat baru masuk kuliah, saya mendengar istilah diaspora. Konsep ini saya tangkap simpel saja, orang yang berpindah negara dan karena itu, identitasnya menjadi campur aduk. Lalu kepada beberapa teman saya bilang, saya punya teori bikinan sendiri bahwa orang-orang hasil kawin campur di Indonesia akan saya sebut sebagai “hindiaspora”. Teori itu saya cetuskan sekitar tahun 2009 dan hingga hari ini, kalau sedang reuni teman kampus, saya masih ditertawakan karenanya. Hahaha.
***
Penulis domisili Prancis (sekarang saya lebih lega untuk tidak menulis “asal”) Amin Maalouf yang pernah menulis buku In the Name of Identity (edisi Indonesianya diterjemahkan Ronny Agustinus) suatu kali mengatakan begini.
“Ketika saya cabut dari Lebanon pada 1976 untuk tinggal di Prancis, saya berulang kali ditanya, dengan nada paling ramah di dunia, saya ini merasa lebih Prancis atau lebih Lebanon. Saya selalu ngasih jawaban yang sama: ‘Dua-duanya.’ Bukan mencoba adil atau seimbang ya, tapi kalau saya memberi jawaban lain, itu malah bohong. Karena itulah yang membuat saya menjadi diri saya dan bukan orang lain, dengan posisi saya di antara dua negara, dua atau tiga bahasa, dan sejumlah tradisi budaya. Persis itu juga yang membentuk identitas saya. Masak saya harus memangkas sebagian diri saya biar jadi lebih autentik?
“Kepada orang yang bertanya, saya menjelaskan dengan sabar bahwa saya lahir di Lebanon, tinggal di sana sampai umur 27, bahasa Arab adalah bahasa pertama saya, dan saya pertama tahu Dickens, Dumas, dan Gulliver’s Travel dari terjemahan Arabnya, dan saya pertama kali merasa bahagia ya saat masih kanak-kanak di desa saya di pegunungan itu, desa leluhur saya tempat saya menyimak cerita-cerita yang membantu saya menulis novel-novel saya di kemudian hari. Nggak mungkin kan saya lupain itu semua? Mana bisa saya melepas itu semua dari diri saya? Tapi di sisi lain, saya tinggal di tanah Prancis selama 22 tahun, minum air dan anggurnya, tangan saya mengelus batu-batu tuanya tiap hari, saya nulis buku-buku saya dalam bahasa Prancis, sehingga Prancis nggak mungkin balik jadi negara asing buat saya.
“Terus, separuh Prancis dan separuh Lebanon dong? Nggak lah! Identitas nggak bisa dikotak-kotakin; nggak bisa dibagi jadi separuh atau sepertiga, juga nggak bisa didefinisikan dengan seperangkat batas-batas yang jelas. Saya nggak punya banyak identitas, saya cuma punya satu, terbuat dari banyak elemen-elemen tadi yang membentuknya dalam proporsi yang unik.
“Kadang, ketika saya selesai menjelaskan detil kenapa saya sepenuhnya memiliki semua elemen-elemn saya itu, seseorang bakal datang dan berbisik dengan cara bersahabat: ‘Semua yang kamu omongin bener, tapi jauh di dalam dirimu, kamu ngerasa kamu itu siapa sih?’
“Pertanyaan kayak gini dulu bikin saya tersenyum. Sekarang nggak. Pertanyaan itu menguak kepada saya kelakuan manusia yang lumrah dan berbahaya.”
Maafkan saya sudah membuat omongan Maalouf terasa kayak bocah twenty something yang kebanyakan main Twitter, tapi apa yang dia sampaikan nyampe banget ke saya. Umumnya saya ngerasa santai-santai saja dengan stereotip orang kepada saya. Tapi kadang ngeri ketika ada orang ngotot mendesak kita buat menentukan, sebenarnya ras, suku, etnis, kelompok, pandangan, ideologi kita ini apa. Saya cuma takut dipersekusi.
Rasanya bakal enak sekali jika ada suatu masa ketika orang-orang dengan identitas cair seperti saya bisa diterima ketika menjawab “Saya orang Indonesia saja” kayak lagu Dewa itu. Mungkin itu sebab tanpa sadar kenapa saya pernah getol ngulik bahasa Indonesia. Atau juga akan enak kalau kita bisa kayak tokoh Pi di novel Life of Pi. Dia bisa memeluk tiga agama sekaligus, dan seandainya saya bisa memeluk banyak suku sekaligus. Lebih enak lagi kalau kita bisa bebas memandang semua identitas sama tinggi harkat dan martabatnya sehingga nggak perlu ada anggapan, orang A lebih hina, orang B pantas diusir, orang C keturunan terhormat, dst.
Saya kira saya harus berhenti di sini sebelum perayaan Imlek ini jadi terlalu serius. Terima kasih kepada teman-teman yang memberi ucapan selamat Imlek kepada siapa pun, baik yang “salah alamat” maupun “tepat tujuan”. Gong xi fa cai, sin cia ju ie, kiong hi kiong hi. Segala doa baik diaturkan kepada Yang Maha Kuasa agar kehidupan kita tahun ini jika tidak bisa lebih baik, setidaknya dapat kembali seperti sedia kala.
BACA JUGA Ternyata, Ini Makna 5 Ornamen Imlek yang Muncul Terus Setiap Tahunnya dan esai-esai Prima Sulistya lainnya.