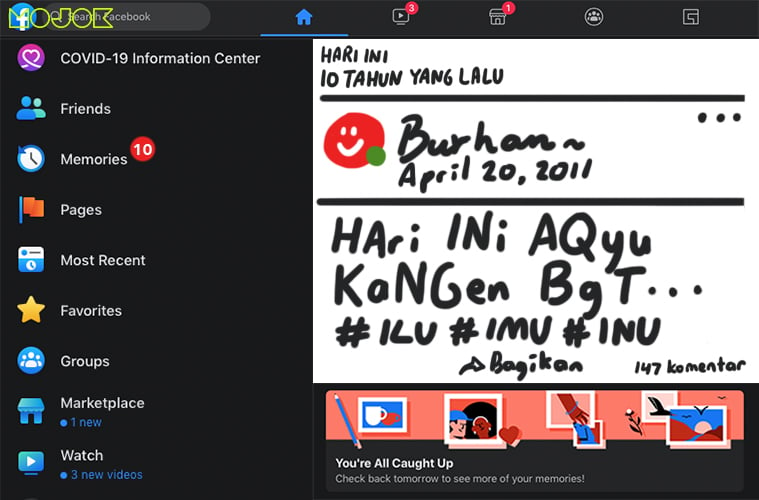MOJOK.CO – Mari belajar dari jejak digital yang buruk di masa lalu.
Di Twitter, sebuah akun mengunggah tangkapan layar status-status Facebook lama Jessica Jane, adik dari Youtuber Tobias Justin atau yang lebih dikenal dengan nama Jess No Limit. “Adiknya Jess No Limit waktu kecilnya bangor juga, ya,” tulis akun tersebut.
Dalam tangkapan layar itu, tampak belaka perangai bermedia sosial Jessica yang tengil, sombong, lagi kasar. Aneka kata-kasar mudah sekali ditemukan dalam status-status Facebook Jessica. Monyet, taik, anjing, homo, najis, dan sebangsanya.
Unggahan tangkapan layar tersebut tentu saja tak butuh lama untuk viral dan diretweet oleh ribuan orang.
Jessica sendiri kemudian ikut menanggapi unggahan tersebut. “Please, jangan ditiru, waktu itu umur 9 tahun hati nuraninya belum bekerja.” Tulis Jessica. “Aduh lupa password facebooknya lagi, maaf guys wkwkkw, gak sadar sekasar itu, jangan di tiru ya.”
PLZ JNGN D TIRU WAKTU ITU UMUR 9 TAHUN HATI NURANINYA BELUM BEKERJA https://t.co/Q2CA9nmIuu
— Jessica Jane (@grcjessicajane) April 19, 2021
Kendati demikian, banyak yang tetap tak habis pikir dengan tangkapan layar tersebut, banyak yang mempertanyakan, bagaimana mungkin anak umur 9 tahun bisa punya banyak sekali kosakata-kosakata umpatan yang kasar dan kejam, bahkan untuk ukuran orang dewasa.
Insiden menyebalkan yang menimpa Jessica tentu saja hanya satu dari sekian banyak penggalian-penggalian jejak digital di masa lalu yang juga menimpa banyak orang.
Di media sosial, tak terhitung berapa banyak orang yang baik, progresif, bernalar, cerdas, bijak, pokoknya adiluhung, yang kemudian agak “terkotori” karena rekam jejak digitalnya yang memperlihatkan bahwa masa lalunya ternyata tak sebaik itu, tak seprogresif itu, tak sebernalar itu, tak secerdas itu, tak sebijak itu, dan tak seadiluhung itu.
Saya yakin, Anda pasti pernah, setidaknya sekali, menemukan fenomena tersebut.
Di lingkaran pertemanan saya, ada semacam tradisi menyebalkan namun menyenangkan, yang kami sepakati untuk diberi nama “tradisi menggali bangkai”. Itu adalah tradisi di mana kami saling meng-up status-status Facebook kami 8-10 tahun yang lalu. Tradisi itu biasa kami lakukan setiap akhir tahun.
Melalui tradisi rutin itulah, kami menertawakan masa lalu kami yang ternyata tidak sedahsyat yang kami bayangkan. Kami menyadari betapa di masa muda, kami cengeng, bodoh, sok progresif, sok bijak, norak, lebay, dan aneka sikap buruk lainnya.
Melalui tradisi itulah, saya harus selalu bersiap saat aib-aib masa lalu saya terbuka untuk kemudian dibaca oleh banyak orang.
Tradisi yang seingat saya sudah berjalan setidaknya tiga tahun terakhir ini seolah memang membuat kami sepakat dan belajar akan sesuatu, bahwa menerima dan berdamai dengan masa lalu adalah bagian yang tak terpisahkan dari hidup.
Beberapa dari kami memang kemudian menghapus beberapa status masa silam yang kami anggap terlalu kasar atau berpotensi menyakiti orang lain, namun banyak status-status dan tulisan kami di masa lalu yang tetap kami biarkan, walaupun kami sadar, tulisan itu norak, buruk, dan menjijikkan.
Pada akhirnya, apa yang pernah kita tuliskan di masa lalu memang merupakan rekam jejak hidup yang sudah seharusnya kita pakai sebagai pelajaran.
Kita berubah dari pola berpikir masa lalu, menuju pola berpikir masa sekarang, dan kelak akan berubah lagi menuju pola berpikir masa depan yang, entah akan bagaimana hasilnya.
Dalam salah satu tulisannya, Zainal Arifin Mochtar menuliskan dengan ciamik, bahwa perubahan atau inkonsistensi berpikir itu adalah hal yang penting, sebab perubahan, kata Zainal Arifin, adalah bentuk dari berkembangnya visi pemahaman.
Perubahan itu memperlihatkan cara memandang yang horizonnya bisa berubah seiring dengan perubahan kesadaran dan kematangan. Mirip pergeseran antara pandangan Marx muda yang masih menggebu dengan Marx yang semakin tua dan dipengaruhi keterasingan dirinya. Begitu kata Zainal Arifin.
Kawan saya, Edi Mulyono, penulis yang juga sekaligus juragan cafe itu pernah mengatakan kepada saya, agar saya jangan pernah malu mengakui tulisan-tulisan saya di masa lalu.
“Kalau kamu menulis buku atau tulisan apa pun, jangan pernah sekali pun berpikir untuk menghapus tulisan itu dari laptopmu, simpan saja. Kelak, suatu saat, ia akan menjadi pengingat yang menarik buatmu.” Ujarnya.
Ia kemudian bercerita tentang dirinya yang sampai sekarang masih suka senyum-seyum sendiri saat membaca tulisan-tulisan dirinya di masa lalu.
“Jebul jaman dulu, aku ini juga pernah sangar dan terlalu menggebu-nggebu,” kata dia membahas buku tentang Islam progresif yang pernah ia tulis saat ia masih muda.
Jejak digital, semenyebalkan apa pun itu, pada titik tertentu adalah instrumen bagi kita untuk menjaga sikap. Agar kita menyadari, bahwa dengan teknologi, keburukan-keburukan kita, juga kebodohan-kebodohan berpikir kita di masa lalu, bisa dengan mudah digali dan ditemukan. Hal yang kemudian membuat kita kemudian senantiasa berhati-hati sebelum menuliskan sesuatu.
Saya jadi ingat apa kata Habib Ja’far kepada saya tentang perkara jejak digital ini.
“Alasan aku berhati-hati di media sosial itu karena aku merasa percaya diri, kelak aku akan jadi orang besar, jadi kalau nulis di Twitter, Facebook, atau Instagram, aku selalu hati-hati,” ujarnya. “Kita ini harus pede, dan mempersiapkan diri kalau di masa depan kita bakal jadi orang besar, perkara hal tersebut ternyata nggak kesampaian di masa depan, itu kan lain soal.” Pungkasnya sambil terkekeh.
BACA JUGA Mari Mendukung Jokowi-Prabowo Duet di Pilpres 2024 Melawan Kotak Kosong demi Indonesia yang Lebih Kolosal dan tulisan AGUS MULYADI lainnya.