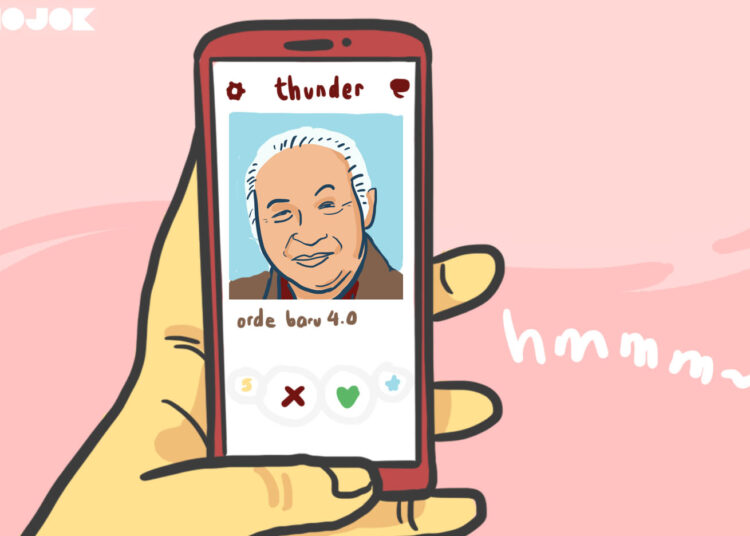Politikus perempuan sekaligus mantan aktris, Rieke Diah Pitaloka, memandang ada kesamaan antara rezim otoritarian Nazi dengan Orde Baru. Pandangan ini ia paparkan dalam salah satu bukunya, Banalitas Kekerasan: Telaah Pemikiran Hannah Arendt tentang Kekerasan Negara (2010), yang mengulas bagaimana negara memfasilitasi kejahatan.
“Banalitas kekerasan” merupakan sebuah pemikiran yang pertama kali dipopulerkan filsuf Hannah Arendt dalam bukunya Eichman in Jerussalem. Buku ini merekam bagaimana Eichman, seorang penjahat perang Nazi yang membantai banyak orang Yahudi, menghadapi peradilan di Israel.
Dalam pandangan Arendt, banalitas kekerasan disebut sebagai situasi di mana kejahatan tidak lagi dirasa sebagai kejahatan, tetapi sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja, alias sesuatu yang wajar atau banal.
Melalui kesimpulannya, yang ia lihat dari Eichman, Arendt memandang bahwa tindakan kekerasan berawal dari ketidakmampuan berpikir secara kritis. Ketidakberpikiran, pada akhirnya bakal membawa seseorang ke dalam kenihilan imajinasi, sehingga membuatnya bias dalam memandang atau memosisikan kejahatan.
Sebagaimana diamati Arendt, Eichmann bukanlah orang bodoh. Yang menjadi “penyakit” utamanya adalah ketidakberpikiran.
“Ketidakberpikiran membuat suatu tindakan menjadi terasa wajar, termasuk tindakan yang mengerikan sekalipun,” kata Arendt, dalam bukunya.
Menurutnya, orang-orang biasa seperti Eichmann bukanlah orang jahat. Ia hanya melakukan tindakan-tindakan brutal karena nihilnya imajinasi soal kekerasan. Sementara banalitas tersebut bukanlah sesuatu yang otonom atau muncul secara tiba-tiba (spontan). Ia lahir karena adanya dogma yang berulang dan masif dari aktor kekuasaan. Dalam kasus Eichman, tentunya doktrin rasial Nazi.
Fenomena inilah yang ingin Rieke bawa ke dalam konteks Indonesia. Seperti halnya Eichman, kekerasan dengan aktor negara, seperti pembantaian 1965-1966, lahir karena adanya banalitas kekerasan itu sendiri.
Banalitas kekerasan rezim Orde Baru
Melalui tesisnya yang akhirnya dibukukan, Banalitas Kekerasan: Telaah Pemikiran Hannah Arendt tentang Kekerasan Negara, Rieke mencoba membaca ulang problem kekerasan Orde Baru, dengan menelaah gagasan Hannah Arendt terkait hubungan antara kekuasaan dan kekerasan.
Dalam kacamata ini, negara—sebagai aktor kekuasaan—ia anggap turut punya andil besar dalam berbagai kekerasan yang dilakukan masyarakat pada masa Orde Baru. Hal ini mengingat kedangkalan berpikir bukanlah sesuatu yang otonom. Ia punya keterikatan dengan kekuasaan.
Menurut Rieke, prakondisi masyarakat dalam melakukan kekerasan antara yang terjadi di Jerman (Nazi) dengan Indonesia (Orde Baru), punya karakteristik yang sama.
Pertama, sebagaimana Nazi dengan karakter totalitarianisme, rezim Orde Baru juga menggunakan mekanisme totaliter dalam menjalankan negara. Ini, misalnya, terlihat dari adanya satu orang sebagai pemimpin tertinggi (absolut), sistem satu partai, polisi rahasia, dan pembersihan berulang-ulang dengan alasan “musuh bersama” (musuh imajiner).
Kedua, sebagaimana di Jerman, kejahatan yang dilakukan negara sepanjang rezim Orde Baru sangat lumrah terjadi. Misalnya, penggusuran paksa dengan melibatkan ormas untuk bentrok, penembak misterius (petrus), dan kekerasan aparat kepada demonstran. Lama kelamaan, kata Rieke, macam-macam kekerasan ini menjadi hal biasa bagi masyarakat.
“Doktrin, propaganda dan teror dari rezim totaliter mengikis kesadaran dan kemampuan berpikir kritis masyarakat sehingga kebaikan dan kejahatan menjadi rancu. Dengan demikian, sangat dimungkinkanlah masyarakat terlibat dalam kekerasan,” jelas Rieke.
Aktor negara dan agama
Sebagaimana Eichman, yang mengalami fenomena ketidakberpikiran akibat dogma militeristik, di Indonesia pada masa Orde Baru pun demikian. Membunuh sebagai sebuah perintah komando, pada akhirnya bikin seseorang merasa benar meski telah melakukan kejahatan.
Di Jerman, jutaan orang dibantai karena perintah pemimpin tertinggi, Adolf Hitler. Orang-orang seperti Eichman, merasa apa yang telah mereka lakukan sudah benar karena menjalankan perintah pimpinan.
Hal serupa juga Rieke temukan di Indonesia. Aktor-aktor militer yang secara proaktif membantai (dalam perkiraan Rieke) hingga 2 juta manusia selama 1965-1966, menculik dan menyiksa aktivis, serta menghilangkannya, merasa posisi mereka benar. Kebenaran ini semata-mata mereka rasakan karena adanya perintah, yang menjadi legitimasi dari kekerasan tersebut.
Lebih lanjut, hal lain yang identik antara kasus Nazi dan Orde Baru adalah tentang dogma ideologi dan agama. Di Jerman, jutaan nyawa orang-orang Yahudi dibunuh dalam peristiwa Holocaust. Pandangan rasial Hitler menganggap “Yahudi tidak diperhitungkan”, yang pada akhirnya mewajarkan pembantaian atas dasar agama.
Di Indonesia pun demikian. Sepanjang 1965-1966, orang-orang akan dibunuh hanya karena ia dianggap komunis atau beretnis Tionghoa. Yang lebih menyesakkan lagi, sebagaimana ditunjukkan banyak penelitian, aktor agama melalui ormasnya punya andil besar dalam “pembersihan” besar-besaran ini.
Namun, yang Rieke garisbawahi, sebenarnya problem utama bukan terletak pada agama itu sendiri, melainkan pada masyarakat yang terkondisikan untuk melakukan kekerasan. Menurutnya, individu yang melakukan kekerasan dalam ormas berlandaskan agama, secara tak sadar sesungguhnya bukan karena agama secara an sich, melainkan kondisi kesepian (loneliness).
Manusia yang kesepian ini akan kehilangan kepercayaan diri, dan kehilangan kepercayaan terhadap nuraninya pada tahap berikutnya. Akibatnya, kemampuan berpikir kritis menghilang. Kejahatan dan kebaikan bertumpang tindih tanpa perbedaan yang jelas.
Maka, tulis Rieke, dalam kondisi demikian, “manusia kesepian” akan sangat mudah termakan propaganda dan percaya pada ideologi yang sifatnya mendikte kepala yang tak kritis. Termasuk dogma kekerasan ala Orde Baru sekalipun.
“Oleh karena itu, kekerasan yang dilakukan warga negara tidak muncul secara sendirinya, tapi sebagai akibat atau produk kekerasan yang dilakukan negara,” tulis Rieke.
Penulis: Ahmad Effendi
Editor: Amanatia Junda