Waktu berjalan amat lambat di akhir bulan. Penyebabnya macam-macam. Sekitar tanggal 20 Oktober, misalnya, pilihan lauk di piring saya semakin terbatas. Merek rokok yang saya hisap juga berubah—awalnya Gudang Garam Surya, lalu jadi Gudang Baru. Merek terakhir, tidak ada. Saya cuma punya template basa-basi buat menjambret rokok teman. Dompet pun semakin tipis, bahkan melompong.
Saya percaya tak ada orang mati karena lapar. Lagipula buat mahasiswa seperti saya, tidak punya uang itu bukan masalah. Ada orang tua, kakak, dan teman baik hati yang siap berbagi apa pun. Bila sedikit rendah diri untuk meminta, mereka mesti siap membantu. Hanya saja saat itu, saya memilih berpangku tangan, berserah diri dan tak cemas. Hingga akhirnya, di hari Minggu (24/10), ada tawaran kerja tak terduga dari seorang kakak tingkat di jurusan.
“Besok mau kerja ndak?”
“Dua hari di BRI Kridosono.”
“Kerjaannya bongkar tembok dan mindahin barang.”
Maksudnya jadi kuli? Saya memang lagi nggak ada uang dan merasa tak khawatir. Tapi di akhir bulan seperti ini, rasanya tidak ada salahnya kalau punya sedikit simpanan. Siapa tahu ada kebutuhan mendadak. Untuk meyakinkan diri, saya minta kisi-kisi lebih lanjut soal tawaran kerja itu buat jadi bahan pertimbangan. “Dari jam berapa sampai jam berapa tuh?” tanya saya.
“Sembilan pagi sampai sepuluh malam, 200 ribu,” jawabnya pendek.
Kepala saya sepintas korslet. Saya menakar untung-rugi tiga belas jam kerja per hari sebagai kuli, yang dibanderol 200 ribu, dibandingkan penderitaan tak punya uang di akhir bulan. Saya dilema.
Pesan itu saya diamkan dan baca ulang terus-terusan selama lima menit. Hingga akhirnya saya membulatkan tekad untuk membalasnya, “Mantap. Gas.”
Dan beginilah ceritanya.
***

Senin (25/10) pagi, sekira setengah sepuluh, saya tiba di BRI Life, Kridosono, Yogyakarta, telat setengah jam dari waktu semestinya.
Mulanya saya berjanji untuk berangkat bersama seorang teman yang enggan disebutkan namanya. Karena itu, kita panggil saja ia Pip (25). Saya mengenalnya sebagai sesama anggota UKM. Dia bergiat di teater, saya di pers mahasiswa.
Sejak jam delapan pagi Pip menelepon, tapi tidak saya angkat sebab masih tidur. Saya baru bangun pukul sembilan dan melewatkan lima panggilan WhatsApp dari Pip. Sedikit panik saya bergegas ke UIN Sunan Kalijaga, tempat kami janjian, tapi batang hidungnya tidak terlihat. Tanpa pikir panjang, saya langsung menuju BRI Life Kridosono.
Kantor BRI Life itu terletak tepat di depan kafe Legend. Posisinya mencolok, memudahkan saya menemukannya dan tidak telat lebih lama lagi. Dari depan gedung, saya mendengar suara besi beradu dan dentuman palu. Saya lantas memasuki gedung.
Di dalam gedung ada tiga ruangan yang hendak direnovasi. Di salah satu ruangan, yang paling besar, beberapa pria berkumpul. Saya lantas menanyakan keberadaan Pip pada sekumpulan pria itu. Salah satu dari mereka lantas menunjuk ke ruangan lain.
Ruangan itulah “kantor” tempat Pip bekerja. Ia kebagian pekerjaan menguliti coran yang menempel di dua sisi tembok berbekal pahat besi dan palu. Ia menyapa saya ramah sambil mengungkit panggilannya yang tidak saya angkat.
“Aku bisa bantu apa ya?” tanya saya lugu pada Pip.
“Tanya itu loh,” ujar Pip sambil menunjuk ke luar ruangannya.
Saya lantas kembali ke ruangan besar dan mencari-cari “itu” yang dimaksud Pip. Saya tanya ke salah satu kuli lain. Dia hanya menjawab, “Tanya mandor,” sambil menunjuk ke arah lain dan melanjutkan pekerjaan.
Siapa sih mandornya?
Saya kaget ketika menyadari bahwa mandor dari proyek itu ternyata juga seorang kenalan dan bergiat di teater yang sama dengan Pip.
Sedari tadi, mandor itu terlihat sibuk mondar-mandir. Saya mendatanginya. Belum sempat saya mengucapkan apapun, ia langsung mengambil pahat besi dan palu lalu berjalan menuju sebuah ruangan. Saya ikuti saja hingga akhirnya kami berdua berdiri di depan sebuah pintu. Dia menguliti tembok di pinggir kusen pintu yang sudah ditandai dengan garis bekas gerinda. Sambil memberi pahat besi dan palu yang ia pakai, si mandor bilang, “Nih. Ini pintunya mau dilepas. Hancurin aja pinggirnya.”
Saya merasa ciut. Pasalnya, pagi itu adalah pengalaman pertama saya menguli. Saya berharap dapat pekerjaan yang sama dengan Pip. Paling tidak, kami bekerja di ruangan yang sama biar saya bisa langsung bertanya padanya kalau bingung akan suatu hal.
Tapi ya sudah, saya jalani saja. Saya pun mulai memahat pinggiran kusen dari garis yang digerinda. Setengah jam pertama, pekerjaan itu saya lakukan secara presisi sampai mandor datang dan menegur dan bilang kalau saya tak perlu memahat dari garis. Belakangan, ketika melihat kuli lain melepas kusen di ruangan lain, saya sadar cara bekerja saya terlalu teliti untuk sebuah “pekerjaan kasar” yang sifatnya hancur-menghancurkan. Konyol.
Pip beberapa kali menghampiri saya. Nampaknya ia khawatir dengan saya yang tak pernah kerja beginian sebelumnya. Tapi sejujurnya, saya tak nyaman kalau bekerja sambil diperhatikan orang lain. Saya gusar ketika merasa dilirik beberapa kuli lain selagi bekerja. Mandor juga berkali-kali mendatangi dan melihat saya bekerja dari belakang.
“Keras?” tanya mandor.
Saya hanya menatapnya, bingung mau jawab apa.
“Pakai drill aja,” kata Mandor lalu mengambil drill di ruangan besar.
Mandor itu mencontohkan cara menggunakan drill tanpa saya minta. Saya berterima kasih atas kepekaannya.
Berbekal drill, pekerjaan jadi lebih ringan. Akhirnya terbentuk lubang di tembok pinggir kusen yang awalnya hanya terkelupas-kelupas. Tapi tangan saya kram karena kelamaan memegang drill yang berat dan bergetar brutal tanpa henti. Memegang drill bikin saya merasa seperti rodeo yang menjinakkan banteng.
Saya berusaha tak mengeluh. Saya berjanji untuk tidak mengeluh selama dua hari menguli. Saya fokus melubangi tembok pintu sambil berusaha mengalihkan pikiran yang terus bertanya, “Ini sudah jam berapa?” dan “Berapa lama lagi saya harus bekerja?”
Tak lama kemudian, jarum jam menunjukkan pukul 12 kurang. Istirahat siang pun tiba. Seorang kuli mendatangi saya dan menawarkan diri untuk membelikan makanan bila saya ingin menitip. Saya iyakan.
Di dompet saya ada uang Rp 15.000,00 hasil meminjam dari teman–saya siapkan sebab kuli proyek non-rumahan, konon tidak mendapatkan jatah makan siang dan kudapan. Semua uang itu saya berikan pada kuli buat makan siang, segelas es teh, dan kopi panas buat menemani saya bekerja.
***
Selama satu jam lebih istirahat saya gunakan buat makan, buang air, dan mengobrol dengan Pip. Pip punya kepribadian yang menyenangkan. Saya jarang berbicara dengannya, meski kami sama-sama anggota UKM. Namun, ia kerap menyapa ketika saya menghampiri sanggar teaternya di kampus.
Kami mengobrol banyak hal. Dari Pip, saya tahu bahwa proyek di BRI Life ini dikerjakan oleh sebuah perusahaan konstruksi yang berpusat di Tangerang dan punya cabang kantor di Jalan Babarsari, Sleman. Kantor itu rencananya hendak direnovasi. Saya tak tahu pasti kantor itu akan direnovasi seperti apa, tapi bersama sekawanan kuli lain, kami berbagi tugas. Ada yang membongkar plafon, mengatur ulang jalur kabel di balik plafon, menghancurkan tembok, memecahkan keramik lantai, melepas kusen pintu, hingga menutup celah tembok bekas kusen pintu dengan batu dan semen.

Semua itu dikerjakan oleh sepuluh orang kuli, termasuk saya dan Pip. Ada pun kuli-kuli itu berasal dari berbagai daerah. Kebanyakan dari mereka asli Yogyakarta, tapi ada juga yang dari luar kota di sekitar Yogyakarta, seperti Boyolali.
Si mandor, menurut penuturan Pip, dulunya sempat menjadi kuli. Tapi setelah bertahun-tahun jadi kuli, ia menaiki tangga karier dan kini menjadi mandor. Pip juga sudah menguli sejak lama, dimulai dari tahun kedua kuliah. Namun, karena tidak menyeriusi pekerjaan, ia tak mengalami nasib serupa si mandor. Pip mengaku bekerja seperlunya, sekadar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, agar punya banyak waktu luang buat berkolektif dan berkesenian.
Pip lantas bercerita alasan dia mulai bekerja sambilan buat bertahan hidup. Di tahun pertama kuliah, Pip mengaku kaya dan hedon. Namun, Pip meminta orang tuanya menyetop kiriman uang bulanan dengan beberapa alasan. Mulai dari situ, ia mencari uang dengan berbagai cara. Misalnya, selain menguli, Pip pernah mengumpulkan botol-botol bekas untuk dijual ke pengepul sampah.
Bertahan hidup tentu tak melulu dengan uang. Pip juga merasa terbantu karena punya banyak teman di teater yang ia anggap seperti keluarga. Dengan teman-teman itu ia berbagi nasib, saling membantu bila salah satu dari mereka tak punya uang. Bila tak seorang pun yang punya uang, barang berharga bisa saja mereka gadaikan. Pip pernah menggadaikan gawainya, yang dihargai Rp 300.000,00, sebab dia dan teman-temannya tak punya lagi uang buat beli makan. “Uang segitu waktu itu masih banyak, tapi cuma habis beberapa hari,” kenang Pip. Kini Pip sudah menyandang status sarjana. Ia baru saja lulus bulan Oktober lalu setelah kuliah tujuh tahun.
Di istirahat kedua, sore menjelang malam, kami mengobrol di trotoar jalan sambil menyesap teh hangat yang dia pesan dari warung penyetan dekat BRI Life. Pip mengaku akan pulang di awal November. Sebetulnya, ia merasa nyaman di Yogyakarta, tapi ia sudah kangen dengan orang tuanya. Ia ingin pulang agar bisa bekerja sambil merawat orang tua.
***
Sekira pukul setengah lima, sebelum istirahat kedua, pekerjaan saya sudah selesai. Saya pun mendatangi ruangan Pip dan membantunya mengangkut pecahan coran yang ia kuliti dan tembok yang saya hancurkan sejak pagi. Mengangkut material itu saya lakukan sampai sore di hari kedua sebab lebih ringan dan tak membutuhkan keahlian apapun.
Dari Pip, saya belajar untuk bekerja lebih santai. Kami mengumpulkan pecahan tembok pelan-pelan, mengangkutnya bersama menggunakan karung yang sudah digunting di kedua sisi agar lebih lebar. Batu yang diangkut di karung pun tidak banyak-banyak agar pekerjaan jadi lebih ringan.
Pekerjaan itu kami lakukan berkali-kali putaran. Di putaran awal, saya bergegas mengumpulkan pecahan tembok sementara Pip, sambil mengisap rokok, berkata, “Santai. Jangan buru-buru.”
Pukul setengah sepuluh, kami pun pulang. Saya, Pip, dan si mandor pulang bersama, bonceng tiga ke UIN. Saat perjalanan pulang, mandor pun bilang hal serupa yang dikatakan Pip. “Kalau kerja begitu jangan terlalu ngotot. Nanti kecapekan,” tegur mandor itu.
Kuli memang tak mengenal kata burn-out–istilah kekinian untuk mental yang ambruk akibat kebanyakan kerja. Namun, dalam keadaan capek, kuli bisa saja mengalami kecelakaan. Oleh karena itu, mengatur ritme saat bekerja menjadi penting.
Sesampainya di UIN, kami berpisah. Saya pulang ke kontrakan dan mengisap beberapa batang rokok sambil melamun.
Usai merokok, saya mandi. Saya meringis ketika tangan saya yang lecet dan kapalan terkena air dan sabun. Saat hendak menggosok punggung, badan saya kaku. Saya kemudian tidur pulas seperti benang basah. Ada ucapan bijak, waktu tidur paling nikmat adalah saat tubuhmu lelah dan punggung mau remuk. Esoknya, selepas tidur pulas, saya meregangkan pinggang dan terdengar bunyi gertak–renyah seperti timun muda.
***

Saya bangun dan bersiap kerja lebih awal di hari kedua. Sesampainya di BRI Life, kusen-kusen pintu dan jendela di ruangan lain sedang dibongkar. Tapi saya tak lagi terlibat dalam pekerjaan jahanam itu. Saya lebih memilih pekerjaan yang lebih ringan, yakni mengangkut pecahan tembok seperti hari sebelumnya.
Saya mulai mengeluh. Waktu istirahat siang, saya tak lagi menitip makanan ke kuli lain. Saya dan Pip malah pelesiran ke sanggar teater dan menghabiskan waktu istirahat di sana. Berbekal utang (lagi-lagi) dari teman, saya beli rokok Surya satu bungkus. Utang saya semakin menumpuk, tapi tak apa, hitung-hitung self-reward setelah bekerja keras.
Saat mengisap rokok, napas saya terasa berat dan kepala saya pusing. Saya tak tahu kenapa. Di benak saya kala itu, penyebabnya barangkali adalah kepulan debu dan suara bising mesin yang saya konsumsi sepanjang hari. Dugaan itu bikin saya cemas sehingga saya berusaha menepisnya berkali-kali. Saya coba membayangkan penyebab-penyebab lain yang lebih sepele. Mungkin cuma capek atau lapar.
Puncak keluhan saya pecah ketika jam istirahat hampir habis. Saya dan Pip makan di Burjo. Tak seperti hari sebelumnya, tak banyak obrolan yang timbul siang itu. Kami makan cepat-cepat. Usai makan, saat hendak kembali ke tempat kerja, saya berteriak, “Ya Tuhan!”
Pip hanya tertawa. “Beginilah hidup,” kata Pip.
***
Lalu, bagaimana saya menghabiskan jam kerja di hari kedua?
Antiklimaks.
Saya mulai terbiasa. Sepanjang pagi sampai sore, pekerjaan saya hanya mengangkut pecahan tembok dengan tempo yang lebih lambat daripada hari sebelumnya. Malamnya, saya dan Pip memecahkan keramik lantai dan coran di bawahnya. Keramik itu amat keras, tak bisa dikelupas dengan pahat besi. Pip lantas menyuruh saya memukul keramik-keramik itu dengan palu godam. “Nggak usah sampai pecah nggak apa-apa. Yang penting keramik sama cornya longgar. Habis itu bisa dikelupas,” jelas Pip. Saya mengikuti instruksinya sampai jam kerja habis lalu pulang bersama ke UIN seperti hari sebelumnya.

Sepanjang perjalanan, saya berpikir cara menghabiskan uang Rp 400.000,00 hasil menguli. Karena merasa sudah bekerja keras, saya jadi banyak keinginan. Saya sempat berpikir buat beli baju baru, tapi saya urungkan. Sebab saya teringat bahwa niat awalnya upah itu akan saya gunakan untuk kebutuhan sehari-hari sampai akhir Oktober dan membayar tumpukan utang yang saya timbun di hari sebelumnya.
Pekerjaan ini sebetulnya tidak buruk-buruk amat kalau dijadikan sambilan. Suatu malam, seorang teman pernah bertanya, “Bagaimana rasanya menjalani profesi yang sama dalam jangka panjang?”
“Senin kemarin, satu hari full aku menguli. Malamnya, bengong doang. Nggak bisa ngapa-ngapain,” jawab saya.
Andai jadi kuli selama 30 tahun, saya melanjutkan, “Aku pasti sudah pelihara burung.”
Saya jadi teringat Slamet, kuli dari Kalasan yang pernah saya wawancarai untuk liputan sebelumnya. Kamis (30/9) pagi, ia menghubungi saya via WhatsApp.
“Malam Jumat kliwon biasanya ngapain, Bro?” tanya Slamet.
“Lagi di perjalanan ke Jogja dari Kebumen, nih, Pak,” jawab saya pendek. Malam itu, saya habis mengangkut 500 kilogram lebih pupuk ke Kebumen bersama Darun, penyedia jasa angkut.
Sehari sebelumnya, Slamet mengajak saya untuk menemaninya kerja, tapi tidak saya sanggupi karena beberapa hal. Saya minta maaf. “Nggak apa-apa,” kata Slamet. Ia cuma pengin bekerja sambil ditemani, tidak sendirian. “Kalau ada teman, kan, nggak suntuk,” balas Slamet.
Selain pertimbangan ekonomi, waktu menerima tawaran menguli, saya menganggap pekerjaan itu bakal jadi pengalaman berharga. Tapi apa? Usai menguli, saya terlampau suntuk buat mencari hikmah di balik dua hari itu.








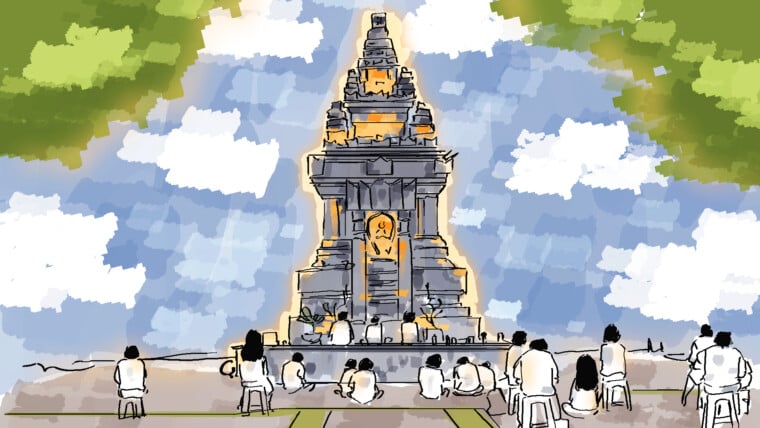
Getirnya Mahasiswa Kedokteran Hewan yang Menghilangkan Peliharaan Klien
Generasi Permen Karet Menyebalkan di Organisasi Kampus
Bukan LSM atau Start-up, Kerja di Pemerintahan yang Paling Enak
Balada Dinda-Dinda yang Punya Resting Bitch Face
Kostenlose Plinko Trial Online Spielen Weniger Risiko
The Basics Of Soft And Difficult Hands
Zakłady Sportowe Watts Polsce The Prawo: Company Musisz Wiedzieć Apa Americ 99ok
Zakłady Sportowe Watts Polsce The Prawo: Company Musisz Wiedzieć Apa Americ 99ok