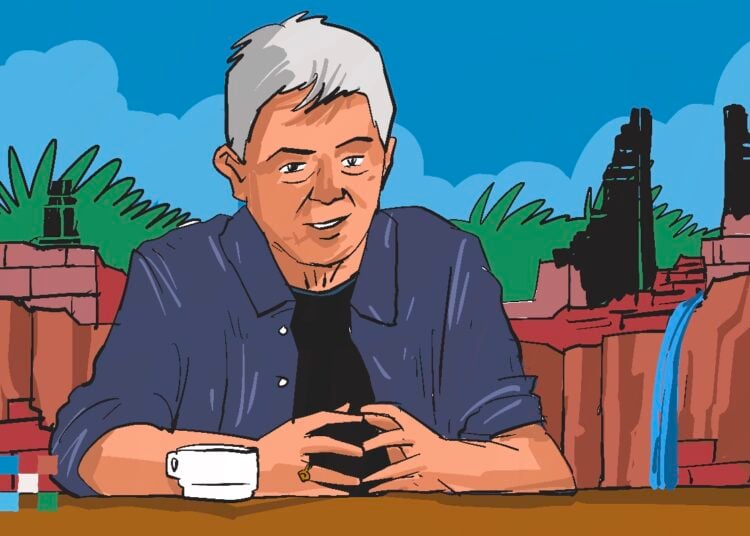Pulau Dewata adalah destinasi wisata favorit para turis. Sayangnya, di balik gemerlap pariwisata Bali, ada banyak hal yang harus dikorbankan. Termasuk budaya dan identitas masyarakat adat yang semakin terlupakan dan tercabut dari akarnya.
***
Tak sulit buat menggeneralisir alasan para wisatawan dalam negeri berlibur ke Bali. Kebanyakan tak jauh-jauh dari pantai atau sekadar “banyak bulenya saja”. Alasan ini jamak didengar.
Padahal, Bali tidak homogen. Ia amat kaya akan tradisi dan budaya. Di pulau ini, terdapat kurang lebih 1.500 desa adat lengkap dengan corak dan ciri khas budayanya masing-masing. Sayangnya, keberagaman ini jarang disorot.
Jangankan wisatawan dari luar daerah, tak sedikit orang Bali yang telah melupakan tradisi leluhurnya. Fenomena ini pun cukup ironis, sebab keberagaman budaya inilah yang–pada awalnya–menjadi daya tarik pariwisata Bali.
Saya pun berbincang dengan Putu Ardana di kediamannya di Desa Munduk, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Dia merupakan seorang pegiat lingkungan dan aktivis masyarakat adat asal Bali.

Pada November lalu, lelaki yang akrab disapa “Kaweng” ini mewakili Indonesia dalam acara Climate Change Conference (COP) #29 di Baku, Azerbaijan. Agenda COP 29 membahas banyak hal, termasuk transisi energi, peran masyarakat adat dalam mengatasi krisis iklim, hingga pengamanan pembiayaan iklim yang berkelanjutan.
Selama kurang lebih satu jam obrolan bersama reporter Mojok, Putu Ardana memberikan pandangannya terkait pariwisata Bali. Baginya, pariwisata Bali kini telah mencabut akar budaya dan identitas masyarakat adat, khususnya anak muda.
Pada dasarnya, masyarakat adat Bali bisa hidup seandainya tanpa pariwisata
Sebagai orang yang lahir, tumbuh, dan besar di Bali, Putu Ardana tahu betul bahwa pada dasarnya masyarakat adat bisa hidup mandiri. Sebelum Bali menjadi tujuan wisata, mereka sudah berdaya; hidup tenang dan swasembada.
Bahkan, Bali mampu melalui berbagai krisis karena semangat kolektivitas masyarakatnya. Misalnya, saat terjadi peristiwa Bom Bali, pariwisata collapse. Banyak wisatawan takut berkunjung. Namun, masyarakat tetap mampu survive karena menurut Putu Ardana, “masyarakat Bali memang bisa hidup tanpa pariwisata”.
Atau, saat pariwisata Bali porak-poranda karena krisis pandemi Covid-19, masyarakat adat di Munduk, tempat tinggalnya, merasa tak ada yang kurang. Hidup tetap berjalan, masyarakat tak kekurangan, bahkan mampu melewati krisis tersebut secara mandiri.

“Karena pariwisata, pada dasarnya, itu memang hanya bonus. Dalam artian, seandainya tanpa pariwisata Bali sekalipun, kami tetap bisa melangsungkan hidup. Tak ada yang berubah,” ujarnya, Kamis (19/12/2024) lalu.
Tradisi sakral dijual demi pariwisata Bali
Putu Ardana juga menjelaskan, pada awalnya, Bali menjadi tujuan wisata karena budayanya. Termasuk perilaku masyarakat, keseharian, maupun adat istiadat yang beragam di 1.500 desa adat yang tersebar.
“Artinya begini: orang-orang itu tertarik dengan keunikan kami, dengan tradisi kami yang beragam. Sederhananya para turis datang untuk menonton keseharian kami saja, yang menurut mereka unik,” jelasnya.
Sayangnya, para stakeholder–aktor negara–melihat fenomena ini dari kacamata yang berbeda. Mereka melihat bahwa keunikan tadi bisa dijual dan menghasilkan profit yang besar. Alhasil, berbagai upaya pun dilakukan, termasuk menggadaikan kesakralan sebuah budaya demi keuntungan para investor dan pemerintah.
“Dulu, sebuah tarian atau upacara tertentu sangat sakral. Ia hanya bisa dilangsungkan di momen-momen tertentu saja. Namun, atas dalih pariwisata Bali, ia kini dijual: dapat dilangsungkan kapan saja asalkan ada wisatawan yang mau membayar,” ungkap Putu Ardana.
“Dari sudut pandang investor dan pemerintah yang membuat regulasi, ini memang menguntungkan. Tapi dari sudut pandang budaya, itu sudah jelas-jelas salah. Hilang sakralnya.”
“Pariwisata itu sama dengan pertambangan”
Fenomena itu pun membawa Putu Ardana sampai pada satu kesimpulan: pariwisata di Bali tak ada bedanya dengan pertambangan. Mereka sama-sama eksploitatif, “menggali” apa saja demi keuntungan, dan yang jelas mengorbankan eksistensi masyarakat adat.
“Bedanya, industri pertambangan itu mengeksploitasi sumber daya mineral seperti emas, nikel, atau batubara,” jelasnya. “Tapi pariwisata Bali menambang peradaban,” imbuhnya.

Dia mencontohkan apa yang terjadi di Desa Jatiluwih, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan. Desa ini terkenal dengan varietas padi lokal yang dihasilkan oleh subak Jatiluwih. Alhasil, pada 2012 lalu, subak Jatiluwih ditetapkan oleh warisan budaya tak benda oleh UNESCO.
Sejak penetapan itu, Desa Jatiluwih menjadi tujuan wisata. Ia makin ramai dikunjungi wisatawan, khususnya mancanegara. Ironisnya, kata Putu Ardana, meski terkenal dengan subaknya, kini tak ada lagi anak muda yang mau menjadi petani.
“Padahal, subak itu ‘kan sistem pertanian. Lantas, kalau tak ada lagi yang mau bertani, bagaimana budaya itu bisa dipertahankan,” ucapnya.
“Makanya, saya bilang, yang ditambang ini peradaban. Masyarakat adat, khususnya anak muda, tercabut dari identitasnya. Bahasanya: ‘anak Bali ilang Baline’,” pungkasnya.
Penulis: Ahmad Effendi
Editor: Muchamad Aly Reza
BACA JUGA: Kiamat Sampah dan Hal-Hal Lain yang Mempercepat Bali Tak Layak Lagi Dikunjungi atau liputan Mojok lainnya di rubrik Liputan