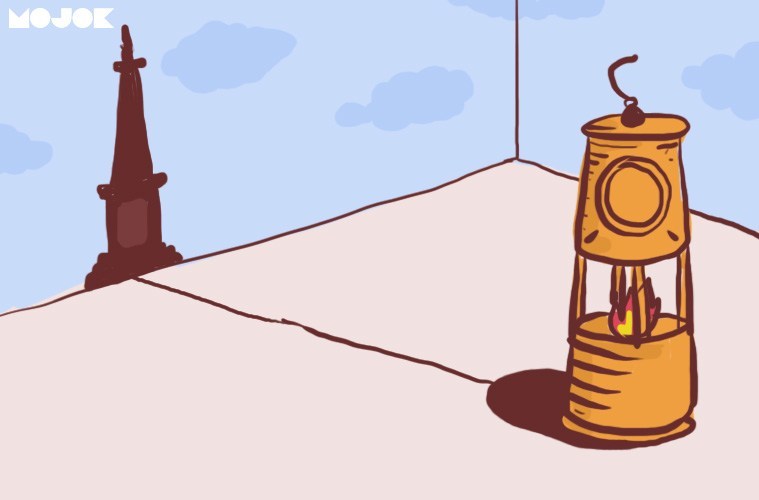MOJOK.CO – Gubernur DIY umumkan UMP Yogyakarta naik sekitar 3,45 persen. Dari Rp1.704.608 jadi Rp1.764.608. Waw, naik 60 ribu. Mantap.
Saya selalu ingat sebuah pitutur Jawa, “Sabda pandita ratu tan kena wola-wali.”
Yang artinya sabda seorang raja/penguasa (dan pendeta/pemuka agama) tidak boleh plin-plan. Apa yang disabdakan seorang raja adalah pegangan hidup bagi rakyatnya. Maka raja harus berhati-hati sebelum berbicara.
Itulah kenapa Sultan perlu menegur Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), karena sang gubernur memberi pernyataan tanpa kehati-hatian.
Lebih buruk lagi, Pak Gub tanpa sikap memahami dan mengayomi rakyatnya. Apalagi ketika berbicara perihal kenaikan upah minimum bagi rakyatnya yang diprotes. Balasan dari beliau yang terucap adalah pernyataan yang tajam dan melukai perasaan.
Kira-kira itulah yang terjadi di Kompleks Kepatihan, 3 November 2020 silam. Sang Gubernur Jogja menanggapi protes buruh terkait kenaikan upah minimum. Para buruh melakukan protes karena menilai upah minimum provinsi (UMP) masih jauh dari kebutuhan hidup layak (KHL) masyarakat Jogja.
Gubernur DIY menyatakan, kenaikan upah hingga 5 juta rupiah akan dirasa tidak cukup jika kebutuhannya mencapai 10 juta rupiah. Menurut blio, kenaikan upah minimum ini telah melalui proses negosiasi terlebih dahulu.
“Ya 5 juta pun belum layak kalau kebutuhannya 10 juta. Tapi bagaimana kita menaikkan kalau dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) kan negosiasinya dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).”
Pernyataan tersebut sangat tajam. Sebab, faktanya tidak seperti itu, dan fakta itu menjadi dasar tuduhan bahwa buruh terlalu berlebihan meminta kenaikan upah. Gubernur juga mengatakan, peran Pemda hanya memfasilitasi kesepakatan yang terjadi antara kedua belah pihak.
“Ya kan, Apindo itu (inginnya) serendah mungkin, kalau karyawan setinggi mungkin, kan gitu? Sedangkan Pemda dalam pengupahan hanya memfasilitasi, kalau sekarang 3 juta lebih suruh nego sendiri sama Apindo coba bisa ndak?” jelas Gubernur DIY.
Gubernur DIY menekankan bahwa blio tidak mau seenaknya dalam menentukan UMP. Semua harus didasari dengan kesepakatan antara Apindo dan karyawan.
Bagi saya, pernyataan Gubernur DIY ini sangat jauh dari apa yang dituntut buruh. Bahkan, terkesan Gubernur DIY ingin menempatkan para penuntut ini sebagai sosok manja yang tidak tahu bersyukur.
Gubernur sendiri menyatakan bahwa upah 5 juta tidak akan cukup kalau butuhnya 10 juta. Ini kalimat yang terkesan kalau Pak Gub memandang para buruh yang menuntut kenaikan upah adalah sosok yang boros dan rakus.
Wah wah, kok jadi gitu?
Padahal, para buruh tidak pernah menuntut setinggi itu. Para buruh menuntut agar UMP DIY disesuaikan dengan hasil survei KHL dari lembaga masyarkat. Para buruh tidak pernah menyampaikan tuntutan yang berlebihan seperti upah 5 juta yang entah didasari dari mana.
Dalam aksi tahun lalu saat penentuan UMP 2020 saja, para buruh merasa upah 1,7 juta rupiah masih jauh dari nilai Kehidupan Hidup Layak (KHL). Sebab hasil dari KHL di wilayah DIY itu sendiri sebesar 2,5 juta rupiah.
Dengan besar UMP dibawah nilai KHL, para buruh merasa defisit karena mendapat hasil kerja yang jauh dari standar hidup layak.
Ini namanya bikin orang kaya makin kaya dan bikin orang miskin makin miskin. Pengusaha kaya untungnya makin banyak, para buruh makin mepet hidupnya. Gap ekonomi pun makin jauh.
Jadi tidak ada itu tuntutan untuk menaikkan UMP sampai 5 juta rupiah. Yang dituntut adalah upah yang memenuhi kebutuhan untuk hidup layak. Bukan hidup foya-foya.
Gubernur juga mengatakan bahwa Pemda menjadi fasilitator dalam negosiasi antara pihak pekerja dengan pelaku usaha. Namun Pak Gub malah meminta yang ingin UMP dinaikkan untuk nego langsung dengan pelaku usaha.
“Bisa ndak?” gitu tadi katanya.
Loh, katanya Pemda DIY adalah fasilitator dari negosiasi ini. Kok malah nyuruh pihak buruh untuk nego langsung? Yang benar itu yang mana: difasilitasi pemda, atau nego sendiri? Pitikih?
Pemerintah itu kan harus bantuin rakyatnya, kalau rakyatnya disuruh gerak sendiri pakai aturan sendiri, lah terus adanya pemerintahan dan peraturan buat apaan coba? Bingung kula, hambokyakin.
Begini lho, Pak Gub.
Jika hanya ada satu dua orang yang merasa kenaikan UMP masih kurang, kita bisa berasumsi bahwa yang bersuara memang kurang bersyukur. Tapi, dalam kasus UMP Jogja memang penuh kecaman serta protes dari banyak pihak buruh dan pekerja kalau naiknya cuma 3,45 persen itu.
Nah, jika protes selalu ada setiap tahun, apakah hasil negosiasi ini tidak bisa dibaca kalau Pak Gub tak pernah mengakomodir tuntutan para pekerja? Atau malah mengabaikan kehidupan layak (yang riil) bagi pekerja?
Mau sejak pandemi, mau sebelum pandemi, kehidupan buruh dan pekerja emang nggak pernah dijadikan prioritas, Pak Gub.
Tentu pandangan semacam ini sangat berbeda dengan cara Sultan Hamengkubowo X yang harapannya pasti akan lebih mengayomi rakyatnya. Tidak seperti Gubernur yang lebih peduli sama kelangsungan hidup pengusaha ketimbang buruh-buruhnya.
Sultan Hamengkubowo X pasti tidak akan plin-plan ketika memberi keputusan, dan memahami bahwa Upah Minimun Provinsi (UMP) DIY itu paling humble se-Indonesia, sehingga protes buruh ini sebenarnya sangat-sangat masuk akal.
Nggak seperti Gubernur DIY yang mungkin memandang buruh itu cuma sekelompok orang kemaruk. Pada akhirnya protes yang ingin disejajarkan upahnya dengan provinsi lain pun dianggap berlebihan. Padahal yang diminta itu upah yang adil.
Salah satu daerah paling kaya di Indonesia kok bisa-bisanya UMP-nya paling rendah se-Indonesia. Dinalar pakai otak paling pas-pasan sekalipun ya tep ramashoook tho? Jadi mau naik sekian persen, kalau UMP Jogja kok kelewat humble sama daerah sekitarnya, hayaaa jelas bakal ada yang protes terooos, Pak Gub.
Oleh sebab itu, hambok Sultan Hamengkubowono X ngasih teguran ke Pak Gubernur DIY, kalau Yogyakarta itu wilayahnya adalah tempat wisata yang ramai dan kaya.
Pendapatan Jogja banyak, tapi yang memanfaatkan hasil dari itu secara maksimal cuma segelintir orang. Sisanya sih cuma dapet recehan dan seringnya disuruh bersyukur sama yang udah ngantongin miliaran.
Di Jogja ini, mahasiswa dan mahasiswi dari luar daerah berdatangan habiskan duit di sini, tanah-tanah dibeli pensiunan-pensiunan Jakarta, perumahan dibangun di-mana-mana lalu orang kaya dari luar pada masuk di sini. Pada akhirnya biaya hidup pun jadi terseret naik dengan harga gila-gilaan.
Belum dengan harga tanah jadi makin nggak masuk akal mahalnya, air jadi sulit di beberapa wilayah karena kesedot hotel-hotel berbintang milik pengusaha ibu kota. PDAM pun jadi pilihan karena hotel dan mal jauh lebih rakus ambil air tanah ketimbang sumur-sumur tradisional warga.
Nah hal beginian nih, Sultan mah pasti paham kegelisahan model-model begini. Mengingat ayahanda beliau (Sultan Hamengkubowono IX) punya pedoman “tahta untuk rakyat”.
Tapi… nggak tahu deh kalau Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, apa beliau ini punya prinsip yang sama nggak ya sama Sri Sultan?
Hm, tapi mohon pertanyaannya diarahkan ke rumput yang bergoyang saja. Anu, ketimbang dikomen, “Ya udah kalau nggak terima, silakan keluar aja dari Jogja!”
Waduh, padahal saya ini asli Jogja e.
BACA JUGA Nggak Usah Terbeli oleh Romantisasi Jogja: Asline Biasa Wae, Lur atau tulisan Dimas Prabu lainnya.