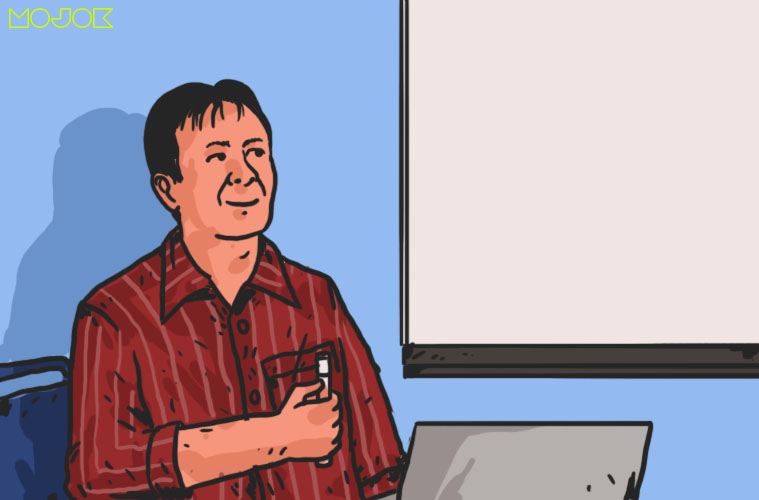MOJOK.CO – Semua orang berubah, tak terkecuali Pak Henry Subiakto.
Saya terpaksa mengingat sosok yang pernah dekat dengan saya di masa lampau, Pak Henry Subiakto, ketika dirinya, melalui akun Twitter miliknya @henrysubiakto menulis cuitan yang mendadak menjadi ramai, amat ramai: “Buruh demo itu logis, karena kekuatan utama mereka memang di situ, bukan di argumentasi. Tapi kalau ngaku intelektual ikut demo seperti buruh, berarti mereka lemah dalam argumentasi dan enggan adu dalil dan konsep di MK. Lebih senang atau menikmati budaya grudak gruduk.”
Saya mengingat beliau sembari terkejut, sebab sikap itu, jika memang benar cuitan tersebut adalah pandangan pribadinya, adalah sikap yang menurut saya sangat tidak Henry Subiakto. Setidaknya, Henry Subiakto yang saya tahu.
Begini, ada beberapa hal yang membuat saya terkejut dan heran. Hal-hal yang mau tak mau harus mengacaukan segala ingatan saya tentang sosok bernama Henry Subiakto itu.
Pertama, saya mahasiswanya. Dulu. Iya, dulu. Karena sekarang saya sudah selesai kuliah dan tinggal di kampung. Itu pula alasannya saya tidak sempat ikut demo yang kemarin itu (halaaah, alasan).
Melihat ada mantan dosen saya berpendapat bahwa demo adalah sebuah aksi ‘grudak-gruduk’, saya tentu saja sedih bukan kepalang. Lebih sedih lagi sebab dosen itu adalah Pak Henry Subiakto.
Saya teringat, betapa dulu, saat Pak Henry Subiakto mengajar, mendadak seseorang mengetuk pintu kelas, ia masuk dan kemudian mengabarkan bahwa sedang ada aksi demonstrasi di Dieng Plaza. Belakangan baru kami ketahui kalau orang yang mengetuk pintu kelas kami tersebut adalah utusan dari KAMUM (Komite Aksi Mahasiswa Unmer Malang).
Lantas, tahukah kalian apa yang dilakukukan oleh Pak Henry Subiakto setelah utusan tersebut menyampaikan informasi itu? Ya, Pak Henry melalukan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang dosen yang baik: mengizinkan siapa saja mahasiswanya yang ingin keluar kelas untuk ikut turun aksi.
Maka, ketika sekarang saya membaca cuitan Pak Henry yang menyebalkan betul itu, sesak juga dada saya, sebab itu artinya, beliau menganggap kami, para mahasiswanya yang saat itu keluar untuk ikut aksi, sebagai kelompok yang lemah argumentasi dan enggan adu dalil.
Air mata saya jatuh. Eh, ini lebay, sih. Tapi, iya. Saya sedih.
Misalkan ingatan pertama itu dianggap sebagai alasan yang terlalu mengada-ada untuk bersedih, mungkin alasan yang kedua berikut ini jauh lebih bisa diterima.
Kedua, Pak Henry adalah dosen yang menyenangkan. Baliau adalah satu dari sedikit dosen yang cara mengajarnya begitu asyik dan ceria. Ia selalu mampu menerangkan materi lengkap dengan contoh-contoh yang relevan dan menyenangkan serupa seorang guru TK saat menerangkan tentang bentuk bulat, kotak, dan segitiga.
Sepanjang yang saya ingat, Pak Henry mengampu mata kuliah komunikasi massa dan kerap membawa contoh media-media yang keliru serta bagaimana dia harus dibenahi. Oh, iya. Dulu Pak Henry aktif di jurnal Media Watch juga. Beliau sosok yang kritis sekali. Dan tentu saja, pemberani. Mungkin akademisi memang harus begitu. Tidak takut membela kepentingan publik, orang kebanyakan, siapa saja yang berhak atas perlakuan jujur dan adil dari media sebagai “penguasa” informasi.
Nah, dengan alasan yang kedua di atas, tak salah bukan kalau saya sedih saat membaca cuitan Pak Henry?
Rasa getir itu timbul sebab dulu, Pak Henry sebagai sosok yang pasti bakal mendukung apa saja yang berkaitan dengan penyampaian pendapat, utamanya jika pendapatnya itu dirasa penting untuk melawan potensi kezaliman penguasa.
Dalam hati, saya benar-benar berharap, dulu ketika Pak Henry mengizinkan para mahasiswanya untuk ikut aksi, itu murni karena beliau menganggap kami para mahasiswanya sebagai pribadi-pribadi dewasa yang punya hak untuk mengemukakan pendapat lewat jalur demokrasi, jalur yang dilindungi undang-undang. Bukan karena ia menganggap kami lemah dalam berpendapat dan enggan beradu dalil.
Ketiga, Pak Henry adalah dosen yang sangat dirindukan. Beliau memang bukan dosen di Universitas Merdeka Malang. Beliau adalah dosen tamu yang biasanya mengajar seminggu sekali. Tiap kali mengajar, beliau nglaju dari Surabaya ke Malang. Hal itulah yang agaknya membuatnya sering dirindukan. Dirindukan kehadirannya, sesekali dirindukan ketidakhadirannya. Maklum, mahasiswa kan tidak semuanya punya iman yang teguh, sesekali juga suka kalau kelas kosong dan bisa nongkrong di warung belakang kampus.
Adalah menyakitkan ketika dosen yang dulu dirindukan sekarang justru mengumbar kalimat yang malah membuat kami malas untuk merindukan sosoknya.
Tentu saja saya masih tidak bisa menutupi kesedihan saya, namun jika mengingat fakta bahwa beliau adalah dosen yang sangat sibuk, maka timbul juga pemakluman saya atas cuitannya di Twitter itu. Orang yang terlampau sibuk memang kadang suka lupa to?
Pada akhirnya, saya memang harus menerima kenyataan, bahwa cuitan Pak Henry tersebut pada akhirnya membulatkan keyakinan saya bahwa waktu memang bisa membuat seseorang berubah. Walau saya masih agak masygul, sebab perubahan yang terjadi pada Pak Henry ternyata se-ekstrem itu.
Saya masih ingat betul itu fragmen tiap kali saya melihat Pak Henry tampil di televisi. Tentu saja sebagai seorang narasumber bermutu, bukan sebagai bintang tamu acara kuis. Tiap kali wajahnya nongol, saya pastilah langsung bersombong ria, kadang kepada kawan-kawan saya, kadang kepada orangtua saya.
“Wah, bagus sekali dia punya omong,” kata ayah saya suatu kali.
“Itu sa pu dosen, Bapa!” kata saya bangga betul. Ayah saya pastilah semakin tulus membiayai ongkos kuliah saya kalau dia tahu bahwa dosen yang mengajar saya adalah sosok yang dia puji dan sering nampang di televisi.
Keparat. Saya tiba-tiba merindukan kembali perasaan semacam itu. Sesuatu yang mungkin akan bertepuk sebelah tangan setelah Pak Henry menyatakan pikiran termutakhirnya di Twitter. Sama halnya dengan merindukan beberapa aktivis reformasi agar tidak perlu mematikan perjuangan adik-adiknya dalam menolak Omnibus Law dengan mengungkit-ungkit perkara fasilitas umum yang rusak.
Ah, kenapa pula saya saya harus sedih dengan perubahan Pak Henry Subiakto. Bukankah perubahan, apalagi kalau sudah menyangkut politik, itu memang niscaya adanya? Jokowi yang dulu pernah kangen dan minta didemo saja sekarang malah mengaku sedih karena didemo melulu, toh?
BACA JUGA Gara-Gara Amien Rais, 3 Lagu Ini Tidak Cocok Dinyanyikan Aktivis ’98 dan tulisan Robertus Bellarminus Nagut lainnya.